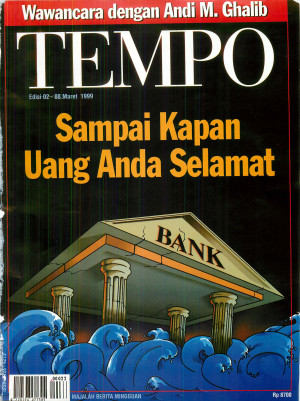Hujan tinggal renyai, menjelang sore. Sisa-sisa kubangan air dan lumpur di jalan tanah yang belum diaspal terlihat di sepanjang jalan sempit di Kampung Meriuk, Desa Ganda Mekar, Kecamatan Cibitung, Bekasi. Jalan selebar dua depa tersebut berujung di jalan utama kawasan industri MM 2100, sebuah kawasan pabrik yang mulai ramai pada awal 1990-an.
Di sepanjang jalan itu, berderet petak-petak rumah kontrakan, 2,5 x 2,5 meter persegi, berdinding tripleks, dan berlantai semen. Yang khas, di depan setiap rumah, bergelantungan jemuran celana biru tua dan kemeja lengan pendek biru muda: seragam pabrik. Dua lelaki muda terlihat duduk di atas pembatas teras rumah kontrakan, sedang membolak-balik isi map berwarna kuning yang dipenuhi surat lamaran pekerjaan. ''Ngelamar pekerjaan susah, Mas. Sekarang harus pakai akta kelahiran segala," kata Mardi, 19 tahun, lelaki asal Klaten, Jawa Tengah, yang lulus SMA pada 1997. Ia sudah dua bulan menumpang di rumah kontrakan kakaknya, yang juga karyawan pabrik di kawasan MM 2100.
Dari arah rumah kontrakan tetangga yang pintunya sedikit terbuka, terdengar lagu-lagu Batak. Seorang lelaki muda asal Flores, sang penghuni, sibuk menyetrika celana pendek. ''Senang mendengarkan lagu Batak. Kakak ipar saya orang Batak, sih" kata Tobyas Hardy, 22 tahun, yang bekerja di PT Inta Pratama Jaya, perusahaan yang memproduksi kampas rem mobil dan motor.
Sewa rumah kontrakan yang ditempati Tobyas dan temannya, yang juga berasal dari Flores, Rp 45 ribu sebulan. Untung bagi Tobyas, ia masih bekerja sehingga masih mampu membayar sewa kamar sumpek, beralas plastik kuning gading yang telah usang, serta berteman dua buah kasur busa tipis yang hanya berlapis tikar plastik, dengan sebuah bantal di atasnya, dan kipas angin kecil yang tak pernah berhenti berputar.
Penghasilan Tobyas hanya Rp 7.775 per hari?jumlah yang tidak seberapa untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta. Mungkin untuk menghibur diri, anak muda ini menghiasi dinding kamarnya dengan poster-poster perempuan dalam pose ''menantang". ''Saya di sini sudah empat bulan," kata Tobyas, yang sebelumnya bekerja di perusahaan yang membuat suku cadang kendaraan di daerah Bantargebang, Bekasi. ''Ya, tapi pendapatan saya tidak cukup, tiga hari saja sudah habis," kata lelaki yang selama krisis cuma makan dua kali sehari itu.
Karena krisis pula, Tobyas dan kawan-kawan sepabrik sudah terbiasa berpanjang akal dan menerapkan kiat-kiat bertahan hidup. Jadwal makan biasanya ditepatkan dengan giliran kerja. Kalau ia mendapat giliran kerja malam, makannya malam dan pagi, sementara siang harinya tidur. Kalau mau lebih ngirit, ia bisa makan bubur ayam atau mi bakso. Pokoknya, isi perut dulu sebelum bekerja.
''Kesibukan baru" Tobyas di masa krisis seperti ini membuat pikirannya hanya terpusat pada upaya bertahan hidup, sekaligus mempertahankan pekerjaan yang masih dimiliki. Jangankan merencanakan demonstrasi, mengulur uang gaji agar bisa cukup untuk hidup sebulan saja sukarnya bukan main. Selain itu, jumlah buruh di kawasan industri menurun drastis?yang dipecat mencapai hampir 50 persen?sehingga tidak mudah lagi untuk mengorganisasikan diri.
Itulah potret buram kaum buruh. Ada beberapa hal yang hilang, yaitu riuh-rendahnya tempat kos mereka. Keadaan bedeng-bedeng tripleks itu jauh lebih sepi setelah krisis moneter melanda Indonesia?sejak pertengahan 1997 lalu. Dari 10 bedeng kontrakan yang dimiliki Nakabutju di Desa Ganda Mekar, sekarang hanya tersewa separuhnya. Dan bedeng dengan 105 pintu di kawasan industri Bantargebang, Bekasi, pun kini tampak lebih sepi.
Dampak krisis makin kentara kalau diamati sektor-sektor lain yang ikut mengais rezeki dari komunitas buruh di kawasan industri tersebut. Rahmat, penjual kain asal Majalaya, Jawa Barat, hanya mampu menjual maksimal 10 potong kain. ''Padahal dulu bisa sampai 20 potong," katanya. Begitu juga nasib Mansur, tukang ojek yang biasa mangkal di ujung jalan Kampung Meruk, di kawasan MM 2100. Sementara dulu bisa mendapat Rp 50 ribu sehari, saat krismon (krisis moneter) ia hanya mengantongi Rp 20 ribu.
Bukan sekadar ''gaya hidup" yang hilang dari kawasan industri, tapi juga ''gaya juang", yaitu demonstrasi buruh. Sebelum krismon, demonstrasi buruh hampir setiap hari terjadi?bahkan mudah menular dari satu pabrik ke pabrik lain?tapi sekarang tidak lagi. Surya Tjandra, S.H., Kepala Divisi Perburuhan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), mengakui bahwa demonstrasi buruh memang berkurang. Semua itu gara-gara krisis moneter, sehingga banyak buruh yang diberhentikan dari pekerjaannya. Menurut data Departemen Tenaga Kerja Bekasi per Desember 1998, hampir 20 ribu buruh yang bekerja di 109 perusahaan sudah diberhentikan.
Penurunan jumlah buruh yang bekerja di sektor manufaktur itu tidak lepas dari ambruknya industri yang menyerap banyak tenaga kerja di wilayah perkotaan ini. Menurut Bomer Pasaribu, Direktur Pusat Kajian Tenaga Kerja dan Pembangunan, tingkat penderitaan buruh sudah mencapai titik kulminasi. Hantaman krisis ekonomi pada sektor manufaktur telah menendang hampir 6 juta tenaga kerja. Angka tersebut baru dihitung dari jumlah karyawan?tanpa memperhitungkan berapa banyak buruh kontrak yang juga harus kehilangan pekerjaan. ''Karena, kalau buruh dikontrak, perusahaan tidak harus membayar pesangon dan itu tidak dihitung sebagai PHK (pemutusan hubungan kerja)," kata Surya. Pokoknya, buruh tidak lagi memiliki posisi tawar seperti dulu, apalagi buruh setengah terampil, yang lowongan kerjanya tiap saat diincar orang.
Mengenai upah, secara nominal, upah minimum regional (UMR) buruh di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) meningkat dari sekitar Rp 6.000 per hari menjadi Rp 7.000 per hari mulai April 1999. Tapi sebenarnya, secara riil, upah buruh justru turun sekitar 50 persen. Sebab, dulu upah buruh, dinilai dengan dolar AS, masih bisa mencapai US$ 2,5, sedangkan sekarang sedolar pun tidak sampai. Menurunnya daya beli itulah yang membuat daya tahan buruh menurun drastis. ''Buruh bisa frustrasi dan kehilangan daya juang," kata Bomer.
Beban berat yang menggelayuti hidup para buruh itulah yang pada akhirnya membuat demonstrasi tidak sesering dulu. ''Karena buruh berada di persimpangan jalan dan merasa terancam," kata Bomer. Perusahaan tempat buruh bekerja rata-rata sudah tidak sehat lagi: kalau tidak bangkrut, paling banter sudah sekarat. Sedangkan buruh tetap membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup.
Di sisi lain, demonstrasi ribuan buruh PT Maspion yang terjadi selama hampir dua minggu, Februari lalu, cukup menjadi pelajaran pahit. Lebih dari 1.000 buruh dipecat karena berunjuk rasa menuntut kelayakan upah di perusahaan yang memproduksi alat-alat rumah tangga itu. Memang kasus Maspion membuka mata kita bahwa buruh masih punya kekuatan yang besar.
Tapi, kalau mereka sudah telanjur dipecat, akan sangat sulit mendapatkan kembali pekerjaan. Soalnya, persaingan mencari kerja sekarang makin ketat saja. ''Sehingga bisa dipahami kalau buruh lebih berkonsentrasi pada upaya menyelamatkan diri," kata Bomer.
Kondisi buruh yang makin tidak punya pilihan ini tampaknya juga ''dimanfaatkan" oleh pihak majikan. Menurut Surya, untuk mengurangi risiko harus memecat buruh dan memberikan pesangon, pihak pemilik pabrik cenderung mengikat buruh dengan sistem kontrak. ''Karyawan yang statusnya karyawan tetap di-PHK-kan dengan alasan menurunnya produksi, dan masuk karyawan baru dengan status kontrak," kata Surya.
Padahal status kontrak semacam itu melanggar hukum. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 tahun 1994, kontrak hanya boleh diterapkan pada jenis pekerjaan yang selesai dalam jangka waktu tertentu, seperti membangun rumah atau jalan. Buruh pabrik dan jasa tidak boleh dikontrak. ''Karena situasinya sekarang begini, pihak pengusaha maunya kontrak," Surya menambahkan.
Menurut Bomer, justru pada zaman reformasi ini buruh dihadapkan pada pilihan yang sulit. Gambaran hidup buruh dalam krisis ekonomi seperti sebuah lingkaran setan. Daya beli yang makin lemah dan ancaman pemecatan menghantui ke mana pun mereka pergi. Akibatnya, potensi untuk melakukan perlawanan terkikis dan nyaris habis. Kalau buruh menuntut macam-macam, toh banyak yang menggantikan. ''Kita surplus buruh luar biasa, hingga pengusaha tidak perlu mempertahankan buruh," kata Surya.
Tobyas dan kawan-kawan sekarang sudah harus puas dengan tinggal dan bertahan di rumah bedeng tripleks yang disewanya. Apa boleh buat, upah tinggi dan demonstrasi harus dilupakan. Saat lepas giliran kerja, mereka langsung tidur pulas ditemani poster-poster perempuan yang berpose menantang yang dipajang sepenuh dinding kamar. Mereka tidak malas, dan kesadarannya sebagai kaum pekerja tidak menyusut sedikit pun. Tobyas dan kawan-kawannya hanya terpaksa tidur karena dengan cara itulah rasa lapar bisa disingkirkan sementara, sebelum waktu makan berikutnya tiba.
Bina Bektiati dan Agus S. Riyanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini