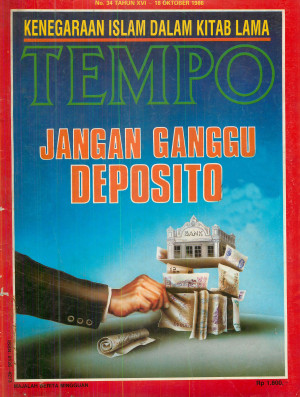EH, tiba-tiba orang jadi ingat dulu ada yang namanya Kantor Biro Lalu Lintas Devisa di Jalan Kebon Sirih. Soalnya, tiba-tiba pula, Dirjen Pajak Salamun A.T. mengharuskan wajib pajak melaporkan semua uang tunai dan utang-piutang dalam valuta asing ke kantor pajak. Utang valuta asing yang sudah di-swap-kan sekalipun termasuk yang harus dilaporkan juga. Karena masih diliputi rasa kaget akibat devaluasi, Surat Edaran Dirjen Pajak 17 September itu oleh kebanyakan orang lalu ditafsirkan sebagai salah satu ikhtiar pemerintah membatasi pemakaian devisa, demi menyehatkan neraca pembayaran. Kalau tidak, untuk apa melaporkan simpanan dan utang-piutang valuta asing segala? Perkiraan semakin berkembang setelah Soeharsono Sagir, dalam sebuah diskusi, menganjurkan agar pemerintah mau menerapkan rezim devisa bebas terbatas. Dan sekonyong-konyong kelihatan adanya gerakan membeli dolar tunai dalam jumlah besar. Secara mencolok pula deposito berjangka dolar, sekalipun belum jatuh tempo, di sana-sini ditarik. Untung, sebelum segalanya runyam, Dirjen Pajak mencabut surat edarannya. Lalu Menteri Keuangan ad interim Prof. Sumarlin, pekan lalu, membantah adanya anggapan seolah pemerintah akan menerapkan rezim devisa terbatas. Pembatasan pemakaian devisa dianggapnya hanya akan mendorong munculnya pasar gelap devisa dan hanya akan membuka kesempatan pelarian devisa ke luar negeri. Untuk mengatur dan memberi jatah alokasi devisa bagi ribuan importir kini juga sulit dilakukan. Karena alasan itu, rezim devisa bebas tetap akan dipertahankan. Pengalaman mahal di tahun 1950-an tampaknya tak ingin diulang. Hanya lantaran cadangan devisa ketika itu sangat terbatas, maka mulai 11 Maret 1950, Lembaga AlatAlat Pembayaran Luar Negeri berusaha mengendalikan pemakaian devisa untuk kepentingan mengimpor barang. Setiap orang yang ingln mengimpor barang, misalnya, selain harus mempunyai izin untuk memperoleh devisa, juga diharuskan memiliki Sertifikat Devisa yang besarnya sama dengan harga barang yang hendak diimpornya. Sertifikat Devisa itu bisa diperoleh di bank devisa tertentu dengan kurs 200%. Jadi kalau orang hendak membeli Sertifikat Devisa US$ 1.000, maka dia harus membayar US$ 2.000. Di pihak lain, pengusaha yang mengekspor suatu barang mendapat perangsang berupa Sertifikat Devisa sebesar separuh dari nilai barang yang diekspornya. Kalau sertifikat tak akan digunakan, eksportir bisa menjualnya ke bank devisa. Menurut Sjafruddin Prawiranegara, yang ketika itu menjabat menteri keuangan, usaha menekan pemakaian devisa dengan cara tadi terpaksa dilakukan mengingat pemerintah hampir bisa dikatakan tak memiliki devisa. Situasi di awal berdirinya Republik saat itu memang benar-benar memprihatinkan. "Bank saja masih sedikit, tabungan dan deposito hampir tidak ada," kata tokoh tua itu. Dalam situasi serba kekurangan itu, tidak sembarang orang bisa jadi importir seperti kini. Menurut Hasjim Ning, untuk menjadi importir seorang pengusaha sedikitnya memerlukan rekomendasi dari dua pengusaha senior. Dengan rekomendasi itulah, si usahawan baru bisa memperoleh jaminan bank. Tapi, kalau pengusaha seperti Hasjim akan mengimpor mobil, maka izin pemasukannya harus terlebih dulu diurus ke Departemen Perhubungan untuk menentukan berapa jumlah mobil yang diperbolehkan diimpor. Dari situ lalu diteruskan ke Departemen Perdagangan, sebelum akhirnya ke Biro Devisa, untuk mendapatkan alokasi devisa. Karena masih dalam suasana perjuangan, dedikasi para pejabat umumnya masih tinggi. Yang nakal, kata Hasjim Ning, jusru para pengusahanya sendiri yang secara diam-diam memperjualbelikan kelebihan devisa impor yang diperolehnya. "Lalu muncul pasar gelap, orang bisik-bisik melakukan transaksi devisa," katanya. Ketika kemudian devisa dari hasil ekspor makin terasa dibatasi pemakaiannya, usaha menyelundupkan devisa terasa bertambah galak. Sebuah barang impor yang di negara penjual hanya berharga US$ 10, misalnya, dalam dokumen L/C bisa disebut US$ 14. Atas kesepakatan importir dengan penjual, kelebihan yang US$ 4 itu untuk sementara ditahan di rekening penjual, sebelum kelak diperjualbelikan di pasar gelap dengan kurs tinggi. Usaha mencegah terjadinya penyelundupan ini sesungguhnya sudah dilakukan atase perdagangan di luar negeri dengan melakukan pengecekan silang terhadap harga barang-barang itu. Tapi karena para pejabat itu hanya mendapat harga dari pihak pabrikan, tanpa mengecek harga pasar, usaha penyelundupan devisa dengan membuat harga barang impor lebih mahal dari harga sebenarnya tetap sulit dicegah. Andai kata ketika itu jasa surveyor seperti SGS sudah dimanfaatkan, ceritanya tentu bakal jadi lain. Menurut cerita Soeroso Patmodihardjo, yang di tahun 1956 menjabat Kepala Bagian Impor Escompto Bank, permohonan impor biasanya cuma memerlukan pemrosesan selama beberapa hari. Bisa tidaknya seorang usahawan melakukan impor diputuskan secara lugas. "Saya belum pernah mendengar ada orang bisa 'nyogok Kantor Lalu Lintas Devisa," katanya. Lazimnya, setelah kantor devisa itu memberikan persetujuan, bank devisa seperti Escompto lalu mengirim telegram pembukaan L/C itu ke negara penjual. Sejarah kemudian mencatat, pembatasan pemakaian devisa yang dilakukan untuk mengerem impor barang itu, ternyata, justru banyak merugikan negara. Cadangan devisa malah terkuras karena permainan harga oleh para importir. Karena alasan itu, Hasjim Ning beranggapan, pemerintah tidak perlu kembali lagi ke rezim devisa terbatas "Kalau perekonomian dlperketat, maka banyak pengusaha akan lari dari sini," kata bekas raja mobil itu. "Kalau rezim devisa dibiarkan longgar seperti sekarang, pemerintah bisa lebih galak mengundang penanam modal asing." Bila kemudahan investasi bagi mereka juga diberikan, para penanam modal itu tentu akan mau menginvestasikan kembali keuntungannya di sini. Repatriasi keuntungan mereka, yang tiga tahun anggaran terakhir pukul rata diduga mencapai sekitar US$ 500 juta, jelas akan bisa dibendung. Dan neraca pembayaran bisa dibikin sehat tidak hanya dengan ikhtiar mengerem impor, melainkan juga oleh upaya menciptakan iklim investasi yang menarik. E.H., Laporan Ahmed Soeriawidjaja & Toriq Hadad (Jakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini