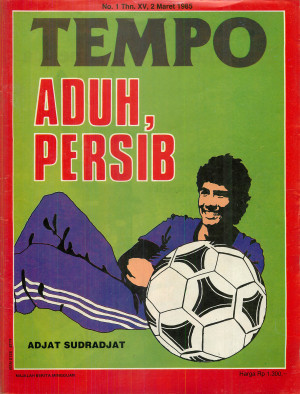SIAPA yang lebih mengancam kemerdekaan pers Indonesia di masa mendatang: pemerintah ataukah pers sendiri? Pertanyaan ini muncul pekan lalu di Solo, tatkala sekitar 50 tokoh pers, cendekiawan, dan pejabat pemerintah bertemu dalam seminar "Upaya Pemantapan Kedudukan dan Peranan Pers Pancasila" pada 18-21 Februari yang diselenggarakan Departemen Penerangan bersama PWI. B.M. Diah, pemimpin redaksi Merdeka, dengan lantang menuding: dalam masa yang akan datang bukanlah pemerintah yang harus ditakuti. "Tetapi konsentrasi pemilikan media pers oleh kaum monopoli merupakan bahaya, tidak saja terhadap pers kecil, tetapi juga terhadap hakikat pers Pancasila." Untuk itu, kata Diah, kekuatan Undang-Undang Pokok Pers harus diarahkan kejurusan itu : memberikan perlindungan terhadap gabungan kekuatan yang menguasai pers dan komunikasi massa tersebut. Kekhawatiran terhadap munculnya gejala konsentrasi pemilikan media massa belakangan ini memang makin santer disuarakan. Dalam seminar "Tanggung Jawab Sosial Wartawan" di Jakarta 6-7 Februari lalu, kecemasan itu muncul juga. Rosihan Anwar, misalnya, yang suaranya mirip B.M. Diah waktu itu melontarkan istilah "pers di atas angin" dan "pers di bawah angin". Di Indonesia, menurut Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Sukarno, saat ini ada 267 penerbitan. "Dari jumlah itu, hanya sekitar 30 persen yang bisa dianggap sudah dapat mandiri, sudah berkembang. Sisanya masih bisa terbit tapi masih dalam taraf berjuang untuk hidup," katanya. Di daerah, katanya, sudah banyak pers yang cukup kuat antara lain Analisa, Banjarmasin Post dan Bali Post. Pers yang dinilainya kuat "Misalnya yang sudah punya percetakan sendiri. Perkembangan pers Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini memang cukup pesat. Bukan cuma koran Ibu Kota yang memiliki mesin cetak offset, tapi juga sejumlah koran di daerah. Beberapa koran daerah malahan telah lama mencapai oplah di atas 100 ribu, antara lain Pikiran Rakyat (Bandung), Suara Merdeka (Semarang), dan Surabaya Post (Surabaya). Di Jakarta sendiri, oplah di atas 100 ribu itu telah lama ditembus harian seperti Sinar Harapan, Pos Kota, dan Suara Karya. Sedangkan oplah tertinggi tetap dipegang Kompas, yang saat ini mencapai sekitar 460 ribu. Seiring dengan perkembangan itu, pendapatan dari iklan juga meningkat pesat. Menurut sebuah sumber, pendapatan kotor Kompas dari iklan setiap bulan saat ini diperkirakan mencapai Rp 1,5 milyar, sedangkan Sinar Harapan Rp 1,2 milyar. Koran-koran daerah juga menyedot cukup banyak penghasilan dari iklan. Pikiran Rakyat, misalnya, bisa memperoleh di atas Rp 400 juta, Suara Merdeka sekitar Rp 350 juta, dan Analisa (Medan) Rp 300 juta. Namun, ada juga koran daerah yang hanya memperoleh Rp 35 juta (Pedoman Rakyat), atau malahan Rp 10 juta (Suara Rakyat). Untuk melindungi pers yang kurang kuat dan untuk pemerataan, pemerintah membatasi jumlah halaman surat kabar harian menjadi hanya 12 halaman. Persentase halaman untuk iklan pada media cetak juga dibatasi 30% -35%. Perkembangan pesat sejumlah penerbitan, diinngl kenaikan pendapatan, mendorong timbulnya pengembangan usaha. Jika semula terbatas pada bidang komunikasi massa, seperti percetakan, penerbitan buku dan majalah, biro iklan, radio siaran niaga, dan pembuatan film, belakangan ini diversifikasi usaha ini makin luas. Beberapa penerbitan Ibu Kota, misalnya, juga menanamkan modalnya pada usaha lain, seperti biro perjalanan, toko buku, bengkel, hotel, atau malahan proyek pembibitan udang. Hingga kemudian muncul istilah grup Gramedia, Sinar Kasih, Femina, dan Grafiti Pers. Apakah tumbuhnya kelompok-kelompok seperti itu yang dikhawatirkan akan menjadi semacam konglomerat dan bisa bertindak monopolistis? Lahirnya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) akhir tahun lalu dipandang merupakan salah satu upaya untuk menahan kecenderungan itu karena membatasi hanya dua SIUPP saja yang bisa diberikan pada tiap penerbit pers. "SIUPP itu untuk pemerataan di bidang penerbitan," tutur Sukarno. SIUPP, menurut dia, memegang asas keseimbangan. "Kita tidak ingin yang kecil mati. Tapi yang besar juga harus dihargai, karena itu hasil kerja keras juga." Pemerintah, menurut Sukarno, belum bisa memastikan adanya gejala monopoli ini. "Harus ada kriteria yang kuat dan alasan substansial." Bekas pemimpin redaksi harian Pedoman, Rosihan Anwar, 63, yang kini menjabat ketua Dewan kehormatan PWI Pusat, melihat tumbuhnya konsentrasi pers itu bisa membahayakan kemerdekaan pers. "Orang kalau sudah kaya akan berhati-hati. Dia akan memperhatikan betul ke mana arah bertiupnya angin. Kasarnya, dia akan menjadi pucuk eru, yaitu ke mana angin bertlup, dia akan ikut," ujarnya. Karena itu, ia beranggapan, banyak penerbitan pers saat ini mengarah menjadi "pers perdagangan", yang tujuannya mencari untung. "Lebih baik kita mengakui terus terang: kita ini sebenarnya pers perdagangan, bukan pers perjuangan." Hal itu, kata Rosihan, merugikan masyarakat. "Pers yang sudah begitu jarang yang sungguh-sungguh mau memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan di negeri kita, tempat ketidakadilan masih banyak, hukum masih harus dibenahi, masih harus dipertanyakan apakah pers yang demikian mau melakukan pembelaan," katanya. Rosihan membagi dua pers Indonesia saat ini. Pertama, pers di atas angin, yaitu yang secara ekonomis sudah mapan dan secara mental politis makin bertanggung jawab. Ia memberi contoh: Kompas. Sinar Harapan. kelompok Kartini dan Femina. Sedangkan yang kedua, pers di bawah angin: yang pengelolaannya tidak baik, tidak dapat menggarap jumlah pembaca yang cukup buat menghidupi surat kabarnya. Masa depan pers di atas angin, menurut Rosihan, bisa dikatakan "yahud" karena tidak ada yang menantangnya. Alasannya: karena tertutupnya kemungkinan diberikannya SIUPP. "Kalau memang mau fair untuk menguji, apakah pers di atas angin ini benar-benar layak dan berhak untuk mendapat, mempunyai, dan mempertahankan posisi yang demiklan itu karena itu mesti dibuka ruang lingkupnya," katanya. Artinya, pengeluaran SIUPP tidak dibatasi jumlahnya. "Jadi, idealnya kasih kesempatan kepada yang lain untuk mencobanya." Koran Pedoman sendiri, sebelum diberangus Januari 1974, konon oplahnya sudah di, atas angin - sekitar 60.000. Jakob Oetama, 54, pemimpin redaksi Kompas, menganggap ' ada absurditas dalam kritik terhadap kelompok-kelompok penerbitan yang berhasil. "Tapi sekaligus ada logika, dan karena itu juga semacam legitimasi," katanya di Solo pekan lalu. Ia berpendapat, duduk perkara yang sebenarnya, dan proporsi permasalahan, belum pernah dikupas secara jernih. Jakob membantah kekhawatiran bahwa beberapa penerbitan akan memonopoli opini masyarakat. "Monopoli itu tidak benar, karena koran itu tidak hanya Kompas, Sinar Harapan, dan TEMPO. Meski jumlah pembaca berbagai koran itu tidak sama, semua mempunyal pembaca, dan semua dibaca oleh mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik." Dl setiap ibu kota provinsi juga ada satu sampai tiga koran daerah yang berkembang, yang mempunyai daerah pembaca sendiri. Koran sekarang berbeda dengan masa lalu. Artinya, sekarang tidak kaku terhadap ideologi dan kepentingan kelompok. Setelah 1966, menurut Jakob, tumbuh kecenderungan koran untuk independen. Mereka mencoba merumuskan visi yang tidak primordial: agama, suku, kelompok kepentingan. "Tapi suatu visi yang bisa diterima masyarakat," katanya. Dari perkembangan visi ini, tiap-tiap penerbit ingin memberi tempat berbicara pada bermacam pendapat. Koran sekarang juga lebih melembaga, tidak lagi mengandalkan kepada kehebatan seseorang. Bila ada yang menganggap kebijaksanaan itu "taktik dagang", Jakob menjawab, "Itu terserah. Tapi kalaupun itu taktik dagang, kenapa pembaca mau?" Diakuinya, Kompas juga menyadari adanya kecemasan bahwa koran yang semakin besar bisa saja makin berhati-hati. "Kami sadar betul adanya masalah itu. Sehingga, kami ekstra hati-hati dan setiap saat menggugat diri." Kompas, kata Jakob, dimulai dengan modal nol. "Kami berusaha secara jujur, baik secara etika maupun undang-undang yang formal," katanya. Ia tampak masygul dengan munculnya tuduhan monopolistis dan istilah pers di atas angin dan di bawah angin. "Semakin besar, kami merasa makin besar juga tanggung jawab. Baik moral, politik, mutu berita - dan semakin profesional."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini