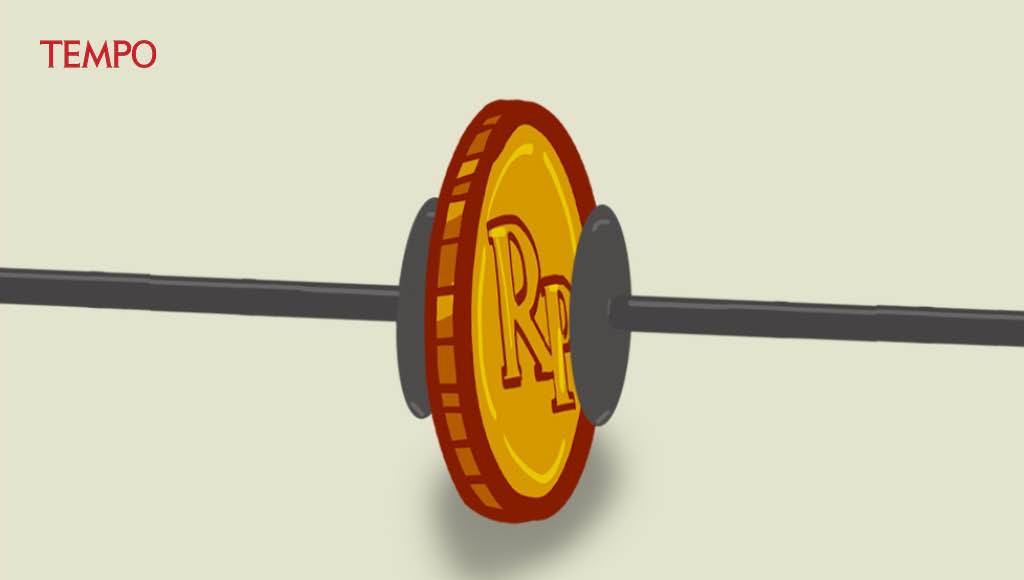PACEKLIK, sebuah kata yang mendirikan bulu roma itu, diramalkan
tidak datang lagi tahuri ini. Ngatiran, petani yang memiliki
sawah 0,5 ha di Pandaan, Ja-Tim, masih punya simpanan 4 kuintal
gabah di senthong-nya.
Menghadapi musim tanam seperti saat ini para petani biasanya
sudah tidak punya apa-apa lagi--kecuali seonggok gabah untuk
bibit. Bulan-bulan berikutnya lebih parah lagi karena harga
kebutuhan pokok mengalami kenaikan. "Menginjak bulan Maret
berarti mengkeret dan bulan April berarti sudah brindil," ujar
Katimun dari Desa Sukosewu (Blitar). Maksudnya: badan sudah
mulai kurus dan harta benda habis terjual.
Masa penantian datangnya panen memang terasa lama. "Sekarang,
dengan adanya padi unggul ini bulan Maret justru sudah panen,"
ujar Katimun. Tiga bulan berikutnya sudah ada panen lagi hingga
jarak antarmusim panen itu dekat sekali.
Karena itulah fluktuasi harga beras tidak begitu berarti.
"Perbedaan harga antarmusim itu dulu m0capai 60%" ujar Mubiarto,
guru besar dari UGM. "Kini tinggal sekitar 10%." Dari sini pula
bermula mengapa lumbung desa tidak lagi populer di kalangan
petani. "Sudah tiga tahun ini tidak ada yang mau pinjam padi
lumbung," ujar seorang kepala desa di Magetan.
Untuk menghilangkan jarak yang kelewat panjang itu ternyata
membutuhkan waktu yang cukup lama. Tahun 1969 sebenarnya sudah
diperkenakan bibit padi jenis unggul bernama PB-5 tapi tidak
segera mendapat tempat di hati petani. "Rasa berasnya seperti
batu. Keras dan hambar," ujar Ngatiran.
Wabah wereng yang melanda Indonesia tahun 1977 kemudian tercatat
sebagai masa peralihan total pada penggunaan bibit padi VU
IW--meskipun di sana-sini dengan jalan paksaan. Di Klaten,
misalnya, berhektar-hektar padi rojolele yang siap panen dibabat
petugas dari kabupaten karena dianggap melanggar perintah
bupati.
Upaya menemukan bibit unggul yang sekaligus enak rasanya
akhirnya memang berhasil dalam wujud IR-36. Jenis inilah yang
sekarang paling disukai para petani. "Hampir 90% tanaman padi
saat ini berupa IR-36," ujar Moeljadi Banoewidjojo, guru besar
di Fak. Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. Moeljadi
melihat kenyataan ini sebagai titik rawan. "Begitu ada wereng
yang punya kekuatan menyerang IR-36 keadaan akan sangat fatal,"
ujarnya. "Perlu jenis padi yang agak heterogen."
"Cara cocok tanam sekarang ini memang sudah lain sama sekali,"
ujar Abdul Rozak dari Rawagempol, Cimalaya (Karawang). Dengan
sistem yang baru ini, seperti diakui Rozak, pendapatan petani
memang naik. "Tapi kebutuhan hidup juga naik. Untuk bisa membeli
sebungkus rokok Gudang Garam ini diperlukan menjual gabah, 2
kg," ujarnya.
Tapi Rozak tidak setuju kalau harga dasar gabah dinaikkan dengan
alasan untuk menaikkan pendapatan petani. "Kenyataannya kalau
harga beras naik rakyat gelisah," ujar petani teladan yang
pernah diwawancarai Presiden Soeharto. "Kalau bisa ya
harga-harga yang lain saja yang diturunkan."
Katimun yang dari Sukosewu juga berpendapat sama. "Membantu
petani dengan jalan menaikkan harga dasar bisa dilakukan kalau
produksi tiap-tiap petani sudah melebihi keperluan untuk dimakan
senduri," katanya. "Kita ini sampai sekarang kan masih saja
hidup untuk makan. Bukan makan unluk hidup," ujar petani yang
jadi ketua kelompok tani termaju di Kabupaten Blitar.
Hidup untuk makan, menurut Katimun berarti seluruh hasil
kerjanya hanya cukup untuk makan. "Kalau masih bisa menjual
beras sedikit-sedikit itu karena di luar musim tanam mencari
penghasilan sampingan," katanya. Kartowiyono, seorang petani di
Magetan yang bertetangga dengan Ngatiran tadi, mengaku bekerja
sebagai kuli bangunan di saat musim tanam sudah lewat. Tiap hari
ia bisa mempaoleh penghasilan Rp 1.000. Sedang pemeliharaan
sawah yang 0,5 ha cukup dilakukan oleh istrinya.
Kalau terjadi peningkatan pendapatan petani sebagian besar
ternyata dari meningkatnya produksi, bukan karena selisih harga
yang besar antara ongkos produksi dan harga jual. "Harga pupuk
diakui murah, tapi ongkos buruh tani besar sekali," ujar
Katimun.
Seorang petani, menurut Katimun baru bisa hidup pas-pasan kalau
memiliki sedikitnya satu hektar sawah. Setelah menunjukkan
hitungan yang njelimet dari sawah satu hektar itu ternyata hanya
diperoleh penghasilan Rp 75.000/bulan.
Rozak yang di Karawang tadi juga menganggap hasil dari pertanian
jauh kalah dibanding dengan usaha lain. Dari tanahnya yang 4
hektar Rozak menghitung secara teliti yang akhirnya diperoleh
kesimpulan: sawah seluas itu hanya memberi penghasilan Rp 200
ribu/bulan. "Karena itu saya tidak heran kalau ada orang yang
menjual sawahnya untuk dibelikan Colt," katanya. Perhitungan
yang dibuat Rozak itu masih belum mencakup kalau terjadi bencana
mendadak seperti serangan wereng atau tikus. Di Indonesia belum
ada asuransi yang menjamin tanaman pangan seperti di banyak
negara lain--meskipun kalau ada juga belum tentu bisa diterima
petani.
Nasib petani dari desa-desa di Kecamatan Undaan, Kudus
(Ja-Teng), lebih jelek lagi. Mereka ini, seperti diceritakan
Subakir pada TEMPo hanya bisa menanam padi sekali setahun. Itu
pun harus pintar-pintar menghitung datangnya hujan. Ada 546 ha
sawah yang posisinya serba sulit: kalau musim hujan terendam
berbulan-bulan sedang musim kemarau kekeringan. "Kami baru
berani tanam padi kalau air sudah surut. Tapi tidak jarang
sebelum padi menguning sudah keburu kekeringan," ujar Subakir.
Padahal jumlah petani yang memiliki tanah di atas 2 ha itu kini
sudah tergolong langka. Rata-rata pemilikan sawah di Jawa hanya
sekitar 0,3 ha. Karena itu tidak heran kalau banyak petani yang
kemudian lebih senang menyewakan tanahnya yang sempit itu
daripada menggarap sendiri. Jumlah mereka ini ternyata cukup
besar sekitar 25%. Mereka ini kemudian memilih kerja serabutan
sebagai buruh.
Buruh tani meski jumlahnya mcncapai sekitar 30% dari "keluarga
besar" petani ternyata punya tarif yang cukup tinggi. Bahkan
kalau dibandingkah dengan harga beras maka perbandingan
tertinggi terjadi sekarang ini. Dengan upah mencangkul Rp 2.000/
setengah hari, bisa untuk membeli beras 10 kg, seperti
diceritakan Gumun, 34 tahun, tetangga Katimun. Tapi harap
maklum, kaum buruh tani itu hanya mendapat pekerjaan tiga bulan
sekali. "Ya hidup pun jadi pas-pasan," katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini