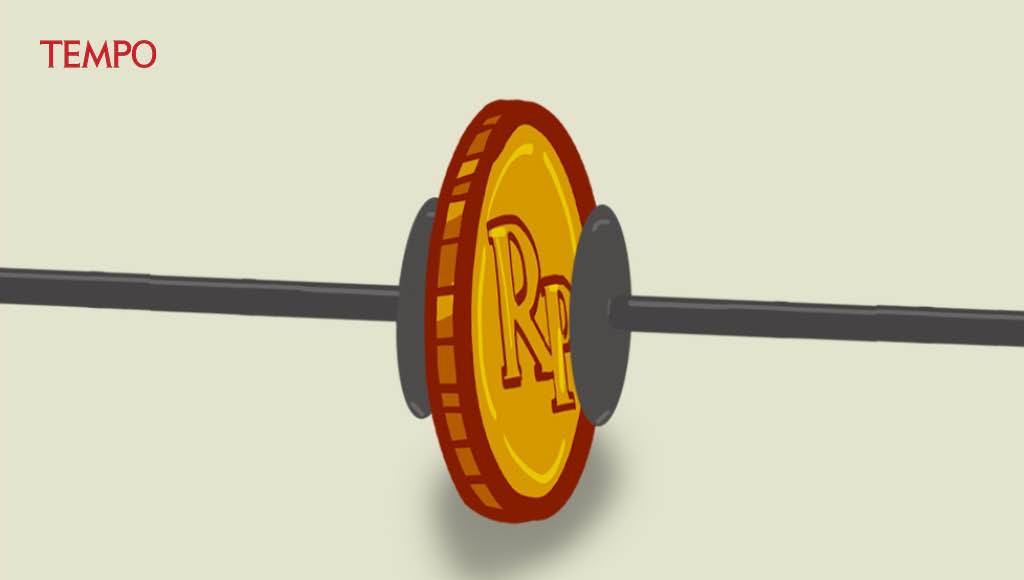Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menuju Dilli Haat, sebuah pusat kerajinan di Delhi, taksi kami terjebak kemacetan. Kawan India itu tampak risi dengan kondisi jalan jalan yang kami lewati: macet simpang siur, polusi, dan sesekali ada pengemis. Padahal saya sesungguhnya tak asing dengan kesemrawutan seperti itu. Jakarta mungkin lebih parah. Seingat saya, untuk urusan logistik, India bahkan lebih unggul ketimbang Indonesia. Sekalipun pendapatan per kapita Indonesia lebih tinggi, India berada di urutan 47 pada Indeks Kinerja Logistik (LPI) 2010, sedangkan Indonesia 75.
Logistik memang bukan sekadar tentang kemacetan. Indeks LPI keluaran Bank Dunia itu berbicara tentang enam dimensi. Selain infrastruktur (termasuk jalan raya), ia memperhatikan efisiensi kepabeanan, kemudahan pengiriman barang, kompetensi petugas jasa logistik, kemudahan pelacakan barang kiriman, dan ketepatan waktu. Ternyata, pada semua dimensi ini, posisi kita di bawah India. Bahkan kita masih di bawah semua negara ASEAN, kecuali Laos, Kamboja, dan Burma. Filipina dan Vietnam yang biasanya ”bersaing” dengan kita dalam hal ketertinggalan berada di urutan 44 dan 53, padahal pada 2007 mereka masih di bawah kita.
Betul, indeks bukanlah segalanya. Peringkat juga bisa berbeda pada indeks yang berbeda. World Economic Forum belum lama ini mengeluarkan Indeks Daya Saing Global (GCI) 2010 2011. Kembali infrastruktur (termasuk jalan dan pelabuhan) menjadi satu dari 12 unsur yang diperhitungkan. Secara umum, Indonesia di peringkat 44 dari 133 negara yang disurvei, masih di atas India (51). Namun, jika hanya melihat infrastruktur, Indonesia berada pada urutan 82 dan India 86.
Terlepas dari berbedanya indeks indeks tersebut, peran infrastruktur atau logistik secara umum dalam pembangunan ekonomi sangat penting. Tingginya biaya logistik dapat menyebabkan tergerusnya daya saing produk di pasar internasional. Pengusaha secara rasional akan menggeser seluruh atau sebagian biaya logistik kepada konsumen lewat kenaikan harga. Sayangnya, untuk kebanyakan komoditas, Indonesia adalah pengikut harga (price taker) di pasar global. Artinya, pengusaha tak bisa terus menaikkan harga, karena itu justru menyebabkan ciutnya pangsa pasar. Bagi mereka yang sudah tak mampu menaikkan harga, satu satunya cara adalah memotong margin keuntungan. Lagi lagi, ini ada batasnya. Maka sebagian yang sudah tak mampu melakukan keduanya terpaksa gulung tikar dan membawa masalah baru: pemutusan hubungan kerja pada para karyawan.
Faktor logistik dan infrastruktur menjadi lebih penting lagi ketika Indonesia semakin masuk ke dalam jaringan produksi regional. Ekspor dan impor di wilayah Asia Timur meningkat dari 23 persen dan 26 persen pada 1985 menjadi 45 persen dan 41 persen pada 2006, sedangkan intensitas perdagangan negara negara Asia Timur dengan Amerika Utara dan Uni Eropa cenderung menurun (Fung et al., 2010). Pada saat yang sama, pertumbuhan perdagangan komponen dan suku cadang meningkat melebihi perdagangan barang jadi. Semua ini menunjukkan sedang terjadinya fragmentasi produksi yang melintasi batas negara, sebagai bagian dari jaringan produksi regional di Asia. Indonesia juga telah masuk ke dalam jejaring rantai nilai raksasa ini. Namun, untuk bisa optimal, banyak hal yang harus dibenahi.
Perbaikan pada infrastruktur secara khusus dan logistik secara umum tidak hanya akan membantu keikutsertaan Indonesia dalam jaringan produksi regional serta integrasi perdagangan global. Ia juga sangat penting untuk meningkatkan ketersambungan atau konektivitas di dalam negeri. Saat ini jamak terdapat perbedaan harga yang sangat besar untuk barang yang sama di tempat yang berbeda karena faktor biaya logistik yang sangat tinggi. Ketika harga beras sekitar Rp 4.000 di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, ia bisa mencapai Rp 10 ribu di Paniai, Papua. Maka perbaikan infrastruktur bukan hanya penting untuk pembangunan, melainkan juga pemerataan.
Untuk dapat mengoptimalkan keuntungan bergabung dengan jaringan produksi regional sembari juga meningkatkan konektivitas domestik—mau tidak mau Indonesia harus meningkatkan daya tarik dan memperbaiki iklim investasinya. Sisi permintaan pada perekonomian kita relatif baik, tapi kendala utama di sisi penawaran adalah faktor logistik dan infrastuktur (Basri dan Patunru, 2008). Ini meliputi biaya logistik input (segmen logistik di antara pasar input dan pabrik), biaya logistik dalam pabrik (in house), ataupun biaya logistik output (segmen antara pabrik dan pasar output). Selain itu, ia mencakup infrastruktur keras (jalan, pelabuhan, listrik), serta infrastruktur lunak (sistem, pengelola).
Studi studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005, 2008, 2010) menemukan bahwa biaya logistik input ataupun output jauh lebih besar daripada biaya logistik in house. Ini berarti sebagian besar dari biaya logistik memang di luar kemampuan perusahaan untuk menguranginya. Ia adalah jalan yang rusak, pelabuhan yang tak memadai, dan pungutan liar. Biaya transportasi barang dengan truk di Indonesia jauh lebih tinggi daripada di negara negara tetangga. Transportasi air dan laut juga tidak banyak membantu mengurangi biaya logistik, karena inefisiensi di pelabuhan dan penyeberangan. Ironis negara kepulauan seperti Indonesia ternyata kurang bisa memanfaatkan keuntungan geografisnya. Dari ribuan pelabuhan di Indonesia, tak satu pun yang memenuhi standar internasional untuk menjadi pusat simpul utama (primary hub port) seperti pelabuhan Singapura.
Prabir De (2009) menunjukkan biaya tambahan di pelabuhan (auxiliary charges, biaya biaya selain tarif yang ditetapkan perusahaan pengiriman) bisa mencapai 40 persen dari total biaya pengiriman barang. Misalnya, biaya pengiriman barang dari Indonesia ke Cina sekitar US$ 850 per kontainer (20 kaki). Dari jumlah ini, 43 persen adalah auxiliary charges yang meliputi pungutan resmi serta biaya penanganan kontainer. Angka itu belum memasukkan pungutan tidak resmi, padahal kalangan bisnis sering mengeluhkan masih adanya pungutan liar yang juga harus mereka tanggung. Studi kasus LPEM mencatat pungutan tidak resmi bervariasi antara Rp 23 ribu untuk sebuah kasus di jalur hijau (green lane) di pelabuhan hingga Rp 1,5 juta untuk kasus lain di jalur merah.
Biaya bukan hanya yang bersifat moneter. Lamanya waktu yang diperlukan untuk proses klarifikasi serta verifikasi dokumen dan fisik untuk ekspor ataupun impor juga merupakan biaya. Studi Ray (2009) menunjukkan dalam banyak ukuran kinerja pelabuhan, termasuk waktu tunggu, waktu tunda, dan waktu kerja, Indonesia masih jauh di belakang standar internasional. Laporan lain (Bank Dunia, 2008) menunjukkan waktu yang dibutuhkan di Indonesia untuk ekspor sekitar 21 hari. Walaupun relatif sama dengan di Cina (21 hari) dan Vietnam (24 hari), ia jelas jauh di bawah Singapura (5) dan rata rata di OECD (9,8 hari).
Tentu tak mudah mengharapkan masalah biaya logistik yang tinggi bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun perbaikan bertahap pun akan membantu sektor sektor yang paling banyak bersinggungan dengan faktor logistik, seperti industri manufaktur (termasuk otomotif, semen, makanan, dan minuman) untuk bisa berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi. Tahun ini pertumbuhan sektor manufaktur diproyeksikan 4,2 4,4 persen dan pada 2011 sebesar 4,6 5 persen. Pertumbuhan ekonomi 2011 secara keseluruhan bisa mencapai 6,4 persen.
Jika ada perbaikan signifikan dalam penurunan biaya logistik, tentu kinerja perekonomian pada tahun tahun berikutnya akan lebih baik lagi, termasuk lewat ekspor yang makin meningkat. Ia juga akan melancarkan impor, tentu saja. Tapi persaingan dari impor akan menciptakan efek disiplin perdagangan (trade discipline effect), ketika perusahaan domestik berusaha bersaing dengan pesaing dari luar sehingga dengan sendirinya mencapai tingkat efisien. Akhirnya, sistem logistik yang lebih lancar juga mempermudah akses pada input serta teknologi.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam jangka relatif pendek adalah realokasi anggaran. Saat ini 13 persen dari total belanja pemerintah digunakan untuk menyubsidi konsumsi energi (bahan bakar minyak dan listrik), sedangkan jatah untuk infrastruktur hanya 8 persen. Kemampuan pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan sistem kemitraan dengan swasta belum berjalan dengan baik. Maka perlu realokasi anggaran dari subsidi yang kurang produktif kepada pembiayaan infrastruktur tanpa harus menambah defisit (Thee dan Negara, 2010). Langkah lain untuk memperbaiki logistik secara umum adalah meningkatkan program program yang sudah dimulai, seperti national single window, sistem operasi pelabuhan 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu (24/7), serta mengoptimalkan pelaksanaan cetak biru logistik nasional dan Undang Undang Pelayaran yang baru.
Dalam konferensi di Delhi itu, kami juga membicarakan isu ”pertumbuhan ekonomi yang inklusif”. Salah satu artinya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi sembari menciptakan lapangan kerja yang cukup. Bahkan dalam dimensi ini pun peran logistik tak mungkin dinafikan. Untuk Indonesia, misalnya, sektor industri manufaktur adalah sektor penyerap tenaga kerja. Namun sektor ini juga yang banyak terbebani biaya logistik yang tinggi. Maka peningkatan kinerja logistik diharapkan bisa membantu pertumbuhan sektor manufaktur dan karena itu, penyerapan tenaga kerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo