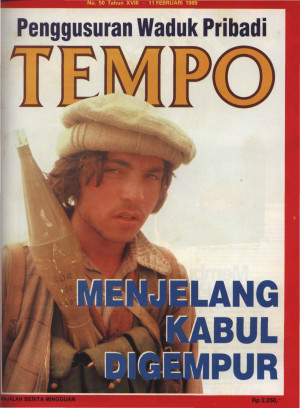HAKIM, layaknya manusia, memang bisa salah. Akibat kekeliruan itulah lahir vonis-vonis yang dikenal dengan vonis "sesat". Senin pekan lalu, pengadilan daerah Shiuoka, sebelah barat daya Tokyo, Jepang, melalui putusan herziening membatalkan vonis mati terhadap terpidana Masao Akahori, 59 tahun, yang semula disangka telah memperkosa dan membunuh seorang anak perempuan berusia 6 tahun, Hisako Sano. Selain meralat vonis, pengadilan juga memutuskan Akahori berhak mendapat ganti rugi 120 juta yen, atau Rp 1,5 milyar lebih karena -- akibat kekeliruan pengadilan -- Akahori mendekam di penjara selama 34 tahun 8 bulan. Keesokan harinya, lelaki yang masuk penjara pada usia 25 tahun itu menghirup udara bebas. "Sungguh, saya terkejut melihat keadaan di luar penjara. Jalan raya dan pertokoannya begitu besar, jumlah mobilnya, wah," kata Akahori, dalam konperensi pers beberapa jam setelah keluar penjara. Berada di dalam kungkungan tembok tebal dan tinggi selama 1268 hari telah mengubah fisik Akahori dari seorang lelaki muda menjadi lelaki gaek dengan beberapa gigi copot dan rambut ubanan. "Terus terang, saya dendam dan benci pada polisi, jaksa, serta hakim," ujarnya. Pada Maret 1954, seorang bocah perempuan, Hisako Sano, diculik seseorang dari pelataran sebuah kuil di Kota Shimada, Provinsi Shizuoka. Murid sekolah taman kanak-kanak itu ditemukan tak bernyawa di sebuah hutan di tepi Sungai Oi, sekitar 2 kilometer dari kuil tadi, tiga hari kemudian. Ia dibunuh setelah diperkosa. Sampai dua setengah bulan kemudian, polisi tak berhasil mengungkapkan pembunuhan keji itu. Pada waktu itulah Masao Akahori, 25 tahun, ditangkap dengan tuduhan mencuri. Tapi di pemeriksaan, kabarnya, pemuda yang sehari-hari bekerja serabutan itu juga mengaku sebagai pembunuh Hisako Sano. "Setelah memperkosa korban, selanjutnya Akahori memukul dada korban dengan batu dan mencekiknya," begitu konon pengakuan Akahori. Di pengadilan, Akahori membantah tuduhan itu. Ia terpaksa mengaku, katanya -- mirip di Indonesia -- karena ditekan dan dipaksa polisi. Tapi Pengadilan Shizuoka tak mempercayainya, dan Mei 1958 memvonis Akahori dengan hukuman mati. Melalui Pengacara Nobuo Suzuki, Akahori pun naik banding. Tapi Pengadilan Tinggi Tokyo dan Mahkamah Agung di sana, Desember 1960, mengukuhkan putusan tersebut. Sampai empat kali, Akahori mencoba upaya peninjauan kembali (herziening). Semua tak membuahkan hasil. Akahori rupanya pantang mundur. Setelah Suzuki meninggal, 1979, ia dibela Pengacara Toshihiko Ohkura. Ajaib, permohonan herziening yang diminta Ohkura dikabulkan. Kasus Akahori diperiksa ulang. Selama proses persidangan ulang itu, Mei 1986, eksekusi hukuman matinya ditangguhkan. Tapi setiap saat, kata Akahori, ia dibayangi ketakutan. "Setiap mendengar bunyi langkah kaki pengawal penjara, saya gemetar karena mengira saat kematian saya sudah tiba," ujarnya. Di proses herziening, jaksa tetap menuduh Akahori membunuh Sano, kendati hanya berpegang pada pengakuan Akahori di pemeriksaan polisi dulu. Pengacara Ohkura meragukan pendapat jaksa yang menyebutkan Akahori memukul dada korban dengan batu. Kalau itu terjadi, menurut Ohkura, seharusnya tulang rusuk Sano patah. Padahal, menurut otopsi, katanya, tulang rusuk korban tak terbukti patah. Majelis hakim yang diketuai Toshinobu Ozaki, Senin pekan lalu, ternyata menerima dalil Ohkura dan membebaskan Akahori dari tuduhan. Akahori pun tercatat sebagai terpidana keempat dalam lima tahun terakhir yang dianggap sebagai korban peradilan "sesat" (enzai) di Jepang. Selain itu, majelis juga memutuskan pemberian ganti rugi maksimum sebesar 120 juta yen bagi Akahori. Akahori, yang hadir di sidang itu, tak bisa membendung kegembiraannya. "Bapak Hakim, saya mengucapkan banyak terima kasih." Pembatalan vonis mati Akahori itu disambut pahit oleh ayah kandung korban, Teruo Sano, 72 tahun. "Saya merasa jengkel. Sampai sekarang, saya percaya Akahorilah pembunuhnya," ujar Teruo Sano. Kendati hakim kini meralat vonis terdahulu, memang tak tertutup kemungkinan bahwa vonis baru ini yang sebenarnya salah. Proses peradilan Akahori juga mengingatkan kita kepada kasus Sengkon dan Karta satu-satunya vonis pidana yang dianggap "sesat" dalam proses herziening setelah terhukum mendekam di penjara. Seperti juga Akahori, Sengkon dan Karta, yang semula dianggap merampok dan membunuh, belakangan dinyatakan "bersih". Bedanya, kedua korban peradilan "sesat" Indonesia itu, sampai mereka meninggal, gagal menuntut ganti rugi.Hp. S. dan Seiichi Okawa (Tokyo)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini