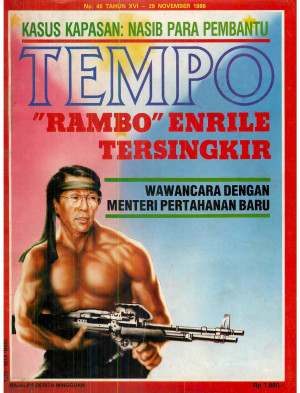BONIRAH, 30, pembantu rumah tangga di Jalan Kapasan Surabaya, pekan-pekan ini menjadi "bintang pengadilan". Ketika sidang yang memeriksa penganiayaan atas dirinya, Sabtu pekan lalu, ribuan pengunjung luber sampai ke halaman pengadilan. Sejak pukul 6 pagi, pengunjung sudah antre untuk mendapatkan tiket masuk yang terbatas -- sebagian besar hanya bisa mengikuti sidang di halaman pengadilan melalui pengeras suara. Selain Bonirah atau Irah, hari itu memang hadir pula di sidang rekan senasibnya, Windarti dan Markamah, yang juga dianiaya majikannya. Pengunjung yang berjubel hanyut dalam luapan emosi. Mereka berteriak, "Irah . .. Irah ...," ketika saksi dibawa meninggalkan pengadilan. Sebab itu, pihak keamanan terpaksa siaga penuh mengamankan sidang -- melebihi acara sidang-sidang subversi: sekitar 300 polisi dan puluhan anjing pelacak dikerahkan. Alat baru di lingkungan peradilan yang selama ini menganggur, metal detector, difungsikan. Ikut pula meramaikan persidangan petugas TVRI Surabaya yang meliput sidang. "Sejak saya menjadi kepala Humas di sini, baru kali ini sidang pengadilan diliput televisi," kata Kepala Humas Pengadilan, Monang Siring-go-ringgo. Begitu penting? Setidaknya kedua kasus itu sempat membangkitkan amarah sebagian penduduk Surabaya. Akhir September itu, beberapa hari toko-toko terpaksa tutup, dan panser tampak bersiaga di berbagai sudut kota. Sementara itu, kerumunan orang terlihat di beberapa tempat. Kegawatan itu bermula dari munculnya Irah, merangkak keluar dari rumah majikannya di Jalan Kapasan, dengan luka sekujur tubuhnya pada 16 September. Sewaktu dibawa tukang becak melapor ke polisi, ia mengaku telah empat tahun disekap di rumah majikannya, Herman Hartanto, persis di sebelah kantor Polres Surabaya Timur. Kecuali mengaku disekap dan diperkosa majikannya, Irah menyatakan sepanjang hari disiksa pula oleh istri Herman, The Hoen Hoen. Ia, misalnya, sempat disetrika, dipukuli jarinya sampai rusak, atau disiram air panas. Belum habis kegemparan soal Irah, di pekan itu juga, penduduk Surabaya dikagetkan lagi oleh kasus Windarti, 15, dan Markamah, 17. Majikan mereka di Jalan Dharmahusada, Suseno Kurniawan, terpaksa melarikan Windarti ke rumah sakit dalam keadaan kritis akibat penganiayaan dan siksaan. Akibatnya, massa benar-benar marah, dan sempat terjadi pelemparan batu ke mobil-mobil. Untunglah, petugas keamanan, yang langsung dipimpin Panglima Brawijaya, Mayjen Saiful Sulun, cepat mengatasi keadaan sehingga kerusuhan yang lebih besar teratasi (TEMPO, Nasional 4 Oktober). Toh, aparat keamanan menempuh kcbijaksanaan untuk menyidangkan perkara itu secara terbuka, bahkan mengundang TVRI segala. Sebuah keberanian yang patut dipuji dan bisa menjadi senjata ampuh untuk menangkal desas-desus yang tidak benar. "Kata Panglima, biar masyarakat tahu dan puas bahwa terdakwa pelaku penganiaya kedua kasus itu diadili," ujar Kepala Pendam Brawijaya, Letkol R. Abdurahman Amang. Saiful Sulun memang sangat memahami kemarahan warganya. "Perbuatan terdakwa benar tidak manusiawi. Semua pihak tidak terkecuali WNI keturunan apa pun-akan trenyuh dan prihatin bila melihat perlakuan tidak manusiawi itu, kata Saiful Sulun. Keadaan tubuh Irah, misalnya, kata Saiful, sampai tidak bisa dipulihkan kembali -- cacat seumur hidup -- kendati dengan operasi plastik sekalipun. "Sekujur tubuhnya rusak dan tidak bisa dibikin mulus karena tidak secuil pun kulitnya yang bisa diangkat untuk menambal yang rusak itu," ujar Panglima. Begitu pula nasib Windarti hampir-hampir membuat Panglima putus asa. Sebab ketika ia dilarikan ke rumah sakit, keadaannya hampir tidak tertolong. Berat badannya hanya tinggal 19 kg dan HB-nya 5,2. "Ketika itu sudah saya siapkan pesawat untuk menerbangkannya ke Jakarta. Sebab, kalau dia mati, saya tidak bisa membayangkan bila massa akan semakin beringas dan liar," katanya. Kendati begitu, Panglima Saiful Sulun tidak lupa mengingatkan masyarakat Jawa Timur agar mampu menahan diri selama persidangan yang direncanakan secara maraton itu berlangsung. Kepada wartawan, Saiful menganjurkan agar perkara itu diliput sejelas-jelasnya. "Tulis sak pol-pol-nya supaya masyarakat melek bahwa keadilan itu benar-benar ditegakkan," kata Saiful Sulun. Cerita Irah di sidang memang lebih memilukan lagi. Bertubuh gemuk pendek, kulit kuning langsat, janda beranak satu itu tampil dengan pakaian sederhana dan sandal jepit di depan majelis hakim yang diketuai Hungudidjojo. Ia kelihatan masih belum bisa melupakan peristiwa selama ia disekap, sehingga banyak pertanyaan hakim yang dijawabnya dengan melenceng. Sementara itu, di tubuhnya, seperti diperlihatkan kepada hakim, terdapat banyak bekas luka bakar yang cukup parah, terutama di bagian selangkangan, paha, punggung, sekitar payudara. Bahkan lengan dan wajahnya pun berkerut akibat siraman minyak goreng dan kena setrika. Penderitaan itu, kata Irah, bermula sejak ia masuk bekerja di keluarga Herman, sekitar 1982, setelah ia gagal dalam perkawinan di desanya di Pacitan. Ternyata, nasib yang menyambutnya di kota besar tidak lebih baik daripada di kampungnya. Hampir setiap hari ia kena siksa dari majikannya, The Hoen Hoen, yang ternyata kejam. Bila suatu hari ia, misalnya, dianggap tidak bersih mencuci piring, katanya, langsung disiksa: matanya diucek-ucek dengan air sabun. Suatu ketika, ceritanya, ia terlambat menyediakan air panas untuk mandi majikannya yang dipanggilnya "yuk-lik" itu. Akibatnya, ketika air itu diantar ke kamar mandi, ia langsung disiram oleh The Hoen Hoen sehingga meninggalkan luka bakar pada bagian dadanya. Pada hari lain, lengannya disetrika nyonya rumah, gara-gara ia dianggap tidak beres menyetrika baju. Dan, yang lebih dahsyat, ke-10 jarinya pernah disuruh jajarkan di lantai. Kemudian, dengan batu untuk mengulek sambal, jari itu ditumbuk nyonya umah sampai remuk. "Saya tidak tega melihat kukunya, darahnya ... sehingga saya memalingkan kepala tidak mau lihat," tutur Irah di sidang, dengan wajah datar, seakan-akan jari dan kuku yang diceritakannya itu milik orang lain. Kesepuluh jari itu kini cacat, bengkok, bengkak, dan tidak bisa digerakkan lagi. Memuncaknya siksaan Irah itu konon karena sang nyonya cemburu suaminya bermain gila dengan pembantunya itu. Menurut Jaksa Fati, suatu hari Herman sempat menyeret Irah ke lantai satu rumahnya, gara-gara pembantu itu menolak ditidurinya. Di situ, kata Jaksa, Irah direbahkan dan diperkosa. "Tentu waktu itu tubuh Irah masih mulus," kata Fati, yang disambut teriakan pengunjung. Irah sendiri tidak banyak cerita tentang perbuatan mesum itu. "Yu De (panggilannya untuk Herman) memang sering mencium saya," katanya, yang membuat The Hoen Hoen di kursi terdakwa menarik napas panjang dengan geram. Sementara itu, Herman sendiri mengaku terus terang. "Memang saya sering menciumnya dan juga menidurinya," kata Herman, yang dilahirkan 36 tahun lalu di Singapura dan kini bekerja di salah satu biro jasa di Surabaya Alasannya, ia sering cekcok dengan istrinya, dan merasa dulunya terpaksa menikah karena si istri hamil duluan. "Sebetulnya saya tidak cinta," katanya, yang membuat si istri duduk kepanasan di ruangan sidang. Kenapa Irah tidak lari atau pulang kampung saja? "Tidak bisa, Pak. Soalnya, dijaga Yu Lik," katanya. Selain tidak dibolehkan keluar, katanya, ia diancam: kalau coba-coba lari atau lapor ke polisi, ia akan dibunuh atau diceburkan ke laut. Ia memang tidak pernah bisa keluar dari rumah itu karena semua pintu keluar selalu dikunci. Neraka itu baru bisa ditinggalkannya, 16 September itu, gara-gara Herman lupa mengunci pintu ketika mengantar anaknya ke sekolah, sementara The Hoen Hoen sudah lebih dulu berangkat mengantar anaknya yang lain. Kelalaian itulah yang kemudian membongkar cerita sehingga, pekan-pekan ini, Herman beserta istri dan kedua anaknya duduk di kursi terdakwa. Tidak berbeda kiranya derita Irah dengan nasib yang dialami Windarti dan Markamah. Dilahirkan di desanya, di Lamongan, Win terpaksa mengadu untung ke Surabaya setamat SD, gara-gara orangtuanya sangat miskin. Di Surabaya, tidak sulit bagi gadis itu mendapatkan pekerjaan, meski hanya sebagai pembantu di rumah keluarga Suseno, yang sekaligus merangkap toko di Jalan Dharmahusada. Ketika ia mulai bekerja, cerita Win di sidang, ternyata sudah ada rekannya yang lebih dulu bekerja di situ, Mar, yang berasal dari sebuah desa dl Blitar. Tapi, baru seminggu bekerja, Win sudah mulai tidak betah. Sebab, ia sudah menangkap gelagat tidak enak: tidak boleh ke luar rumah. Tapi yang paling membuat tidak kerasan adalah soal makan. "Saya hanya diberi makan sekali sehari," tutur Win kepada hakim. Soal gaji? Memang dijanjikan Rp 15.000 sebulan. Tapi ketika ditagih, nyonya rumah, Yuliana, menjawab, "Tidak ada bayaran, wong kerjanya tidak becus." Gara-gara kelaparan itulah, seperti yang diakui Win dan Mar, mereka suka mencuri makanan ketika tuan dan nyonyanya tidak di rumah. Bahkan, suatu kali, mereka berani mencuri makanan dengan mencongkel kulkas yang terkunci. "Habis, saya lapar," kata Win. Tapi, karena itu pula mereka disiksa. Ketika Yuliana memergoki perbuatan mereka, keduanya diperintahkan saling memukul dengan tangkai bulu ayam 150 kali. Hukuman semacam itu kemudian dilaksanakan pula bila mereka dianggap malas. Siksaan-siksaan semacam itu, seperti dituduhkan Jaksa Kussusilohardi, semakin lama semakin memuncak. Suatu kali, lengan Mar sempat disetrika nyonya rumah, gaa-gara pembantu itu merusakkan baju. Pada suatu kali, mereka dipaksa menggigit batu gara-gara mencuri makanan. Dan, yang lebih menusuk hati, ketika kedua pembantu yang masih remaja itu dipaksa makan nasi yang bercampur air WC. Cara begitu pernah pula dilakukan oleh mertua Suseno, Nyonya Lie Aiy Yen, sehingga Win langsung sakit perut, sementara Mar mencret-mencret. Perlakuan yang paling kasar yang diterima dari Suseno. Suatu kali, kata Jaksa Suseno pernah mendorong Win sampai kepalanya membentur lantai. Akibatnya, seperti belakangan diketahui, kepala Win mengalami keretakan kecil. Tapi, di sidang Suseno membantah soal itu. "Itu hanya gara-gara ia terpeleset saja, karena lantai kami porselen," kata Suseno. Tapi untuk soal yang lainnya, baik Suseno, istri, maupun mertuanya mengakui. Majikan Win dan Mar masih berbaik hati membawa pembantunya ke dokter bila sakit. Begitu pula, di akhir September lalu, ketika Win sakit gawat. Tubuhnya yang lemah, akibat kurang makan, menarik perhatian dokter rumah sakit yang, kabarnya melaporkan kasus itu ke polisi. Akibatnya, seperti majikan Irah, pekan-pekan ini Suseno bersama istri dan mertuanya duduk di kursi terdakwa. Irah, Win, dan Mar tampaknya hanyalah contoh yang hangat saja dari banyak rekan senasib mereka. Kecuali mendapat perlakuan sewenang-wenang, dari segi hukum pun nasib para pembantu itu belum banyak mendapat perhatian (lihat Menghukum Pembantu Rumah Tangga Kita). Sebab itu, Panglima Laksusda Jawa Timur Saiful Sulun merencanakan, dalam waktu dekat akan mengadakan razia dari rumah ke rumah. "Bisa saja ditemukan 'Irah-Irah' yang lain," katanya. Irah-Irah yang lain itu tidak hanya di Surabaya dan tidak terbatas pada majikan keturunan Cina saja. Di Medan, misalnya Suliyem, 16, dan Wateni, 19, mengalami nasib yang tidak berbeda dengan rekan-rekan mereka di Jawa Timur. Mereka bekerja di keluarga S.P. Sinurat, perwira seksi Sospol Kodam I Bukit Barisan. Kata Suliyem, "Setiap pagi kami sudah harus mulai bekerja dari pukul setengah empat pagi, dengan perut keroncongan, dan baru bisa sarapan pukul 11 siang." Hampir 20 jam sehari mereka harus bekerja membersihkan rumah dan segala tetek bengek urusan rumah tangga. Toh, nyonya rumah masih menganggap mereka bekerja tidak benar. Nyonya Sinurat, menurut mereka, suka menyiksa. "Dada, rusuk, dan punggung kami dilecut dengan rotan oleh Nyonya. Bapak ikut memukul pakai sapu," kata Wateni. Bukan cuma itu. Mereka mengaku pula pernah dilempar dengan gilingan cabai. Bahkan, Wateni mengaku pernah giginya disikat nyonya rumah dengan sikat pembersih WC -- hingga berdarah. Di hari lain, cerita Wateni, ia disulut dengan rokok. Dan yang sakitnya tidak tertahankan, katanya, ketika alat vitalnya digosok dengan cabai yang dicampur obat gosok. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, cewek kelahiran Deli Serdang itu meminta pulang ke rumahnya. Ia diantar Sinurat menjelang tengah malam -- dengan bekal sepotong roti dan uang Rp 15 ribu. Tapi di tengah jalan ia diturunkan. Dengan merangkak akhirnya ia diselamatkan penjaga malam di perkebunan, dan sempat dirawat di rumah sakit perkebunan PTP V. Setelah Wateni pergi, Suliyem, yang mengaku pernah kepalanya direndam nyonya rumah, memilih kabur. Karena pengaduan Suliyem ke LBH Medan, kasus itu terungkap. "Kami tidak mau berdamai -- harus dituntut sesuai dengan hukum," kata ayah Suliyem, Soman (TEMPO, Kriminalitas, 8 November). Kepala Pendam I Bukit Barisan, Letkol Suyono, menjanjikan perkara Sinurat itu akan diteruskan ke Mahkamah Militer. Sedang istrinya ke pengadilan biasa. "Agar orang tidak bilang oknum tentara kebal hukum," kata Suyono. Keluarga Sinurat membantah semua cerita kedua pembantunya. "Kami bersumpah tidak melakukan itu -- kami bukan barbar," kata Alamsyah Sinurat, keponakan tersangka, kepada TEMPO. Keluarga Sinurat menganggap kasus itu bagaikan cerita semut yang digajahkan. Di Jakarta kasus-kasus seperti ini merupakan cerita ulangan. Korbannya tidak hanya pembantu biasa, tapi juga terjadi pada pcmbantu yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan majikan. Ema Delfrita Sibangariang, contoh -- terbaru. Gadis berusia 12 tahun yang yatim itu tinggal di rumah pamannya, Pahala Sibangariang, di bilangan Kampung Bali di Tanah Abang. Tapi, di rumah itu ia dianggap pembantu dan melakukan pekerjaan sebagai pembantu. Lebih dari itu, hampir semua tetangga Pahala dapat menjadi saksi, anak itu korban siksaan pamannya sendiri. Kendati gadis kecil itu tidak menangis, tetangga menyaksikan tubuh anak itu penuh luka. Akhirnya, cerita itu sampai ke pengurus Paguyuban Batak. Pahala beserta istrinya, pekan lalu, diserahkan ke polisi. Ema dipelihara istri ketua paguyuban itu, Nyonya Pasaribu. "Pertama kali saya melihat anak itu, saya jijik, karena banyak borok," ujarnya. Cerita tentang pembantu-pembantu di atas masih kalah menyedihkannya dibanding berbagai kasus yang pernah membuat sejarah peradilan. Di Pengadilan Negeri Blitar, Jawa Timur, seorang istri pensiunan polisi, Nyonya Hartati alias Nyonya Lik Utik, 50 Mei lalu duduk di kursi pesakitan. Ia dianggap bertanggung jawab atas kematian pembantunya, Sumiati, yang ditemukan mengambang di sumur. Berdasarkan pemeriksaan, korban meninggal akibat penganiayaan berat, karena di leher dan perutnya terdapat luka. Bahkan alat vitalnya rusak berat, seperti ditusuk-tusuk dengan benda tajam. Konon, Hartati mencurigai pembantunya itu "ada main" dengan suaminya. Akibat ulahnya itu, Juni lalu, ia divonis 18 tahun penjara. Pengadilan banding kemudian mengurangi hukumannya menjadi 15 tahun. Kesadisan perlakuan terhadap Sumiati itu kalah menghebohkan dibandingkan pembunuhan Kasinem, yang bekerja di keluarga Sucianto di Sragen. Gadis berusia 18 tahun itu, sebelum menemui ajalnya Agustus 1982, diikat kakinya dan direntangkan antara dua tiang selama tiga hari tiga malam. Sasaran utama siksaan atas dirinya adalah bagian dada, kemaluan, dan kepala. Dua rekan sekerjanya, Sriarti dan Sumadi, mengaku dipaksa Sucianto dan istrinya, memasukkan dua buah jeruk ke kemaluan Kasinem. Jeruk itu, kata mereka, didorong dengan kayu agar bisa masuk. Kedua rekan Kasinem itu tidak berani menolak perintah. Sebab, anak majikannya yang berusia 13, sebut saja Robby, siap menyulutnya dengan rokok bila membangkang. Sriarti dan Sumadi memperlihatkan bekas luka-luka bakar kepada hakim. Akhirnya, setelah tiga hari disiksa dengan posisi tersalib begitu, Kasinem menemui ajalnya. Mayatnya kemudian dibuang ke tempat sampah di Desa Slogohimo di Surakarta. Majelis hakim, yang mengadili kasus itu di tengah emosi massa, memvonis Sucianto dengan hukuman mati, dan 20 tahun penjara bagi Susana, sementara Robby dan seorang adik perempuannya dihukum masing-masing 12 dan 5 tahun penjara. Nyonya Susilowati, ibu Susana, yang mengatur pembuangan mayat, dihukum 10 tahun penjara. Tapi hukuman itu di tingkat kasasi diperbaiki Mahkamah Agung. Sucianto dan Susana masing-masing hanya dikenai hukuman penjara 7 dan 8 tahun. Robby diganjar 4 tahun, sementara adiknya bebas. Nyonya Susilowati kena 9 bulan penjara. Sebagian terhukum sampai kini masih menjalani hukumannya. Tapi cerita tragis itu bagaikan tidak kunjung habis. Setelah Kasinem, menyusul Sumiati, dan kini muncul kasus Irah, Win, dan Mar. Belum lagi kasus yang tidak terungkapkan atau yang tidak jadi berita. Tidak adakah perangkat hukum yang bisa menenteramkan para pembantu sekalipun dalam lindungan maJikan yang hangat dan manis? Karni Ilyas, Laporan Biro-Biro
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini