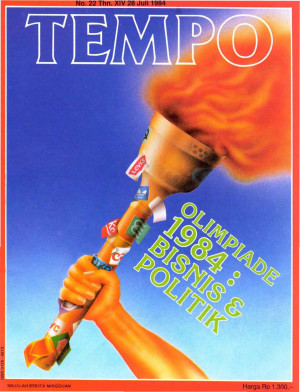ORANG-orang desa melamunkan dunia metropolitan dan menyekolahkan anak-anaknya ke kota. Orang-orang besar di kota merindukan "surga purba" dan menyerahkan putra-putranya ke pesantren di desa. Orang desa seolah-olah haus pembebasan dan menyerbu kota. Orang kota sakan ingin memperoleh kembali sesuatu yang hilang. Seolah-olah di tengah orang yang merindukan kebebasan terdapat yang mendambakan keterikatan. Anak-anak, kata mereka, jangan terlalu disodori kebebasan agar tak menjadi setan. Anak-anak perlu dogma. Perlu agama. Di tengah para guru yang pusing soal kurikulum baru, ada sahutan: pendidikan anak-anak nomor satu adalah agama. Kalau otak direnggangkan dari agama, racun lingkungan akan lebih banyak merasuk. Kenapakah, tampaknya, orang selalu harus memilih antara kebebasan dan keterikatan? Demikian dalam pendidikan, dalam berpolitik, dalam beragama. Kenapa mesti salah satunya, dan tidak, misalnya, kedua-duanya, dengan "persentase" yang mungkin bisa diperhitungkan? Berkat memilih salah satu itu pula feodalisme selalu diganyang. Di Indonesia, Jawa menjadi kambing paling hitam. Orang berpaling ke Barat. Di keraton, abdi dalem mempersembahkan dirinya, melenyapkan pribadinya, menempel di lambang Sumber Hidup tempat ia pasrah dan merasa aman dalam genggaman. Di negeri maju, orang tidak menyerahkan diri kepada raja atau seseorang lain, melainkan kepada suatu bangunan sistem yang dipercayakan kepada mesin-mesin dan komoditi. Keduanya sama-sama mengikatkan diri. Sisi kelam feodalisme ialah permusuhan kelas, baik kelas raja-kawula maupun manusia-mesin. Sisi yang netral mungkin naluri untuk terikat pada sumber, untuk menyerahkan diri kembali kepada "hakikat". Anak-anak muda meminum wiski kebebasan mengigau sepanjang jalan, di kampus, di koran, di panggung sesungguhnya hanya tak sabar menanti datangnya sesuatu ketika ia bisa memasrahkan diri, meraba kebahagiaan dan berhimpun di penjara Tuhan. Anak-anak muda pacaran, kawin, menyodorkan tangan untuk diborgol oleh bayangan kebahagiaan, menuntut suatu lingkungan yang bisa menampung naluri pengembaraannya ke Tuhan, apa pun namanya ia, mengimbau hadirnya pemimpin yang mengatur mereka, tatanan yang membatasi gerak mereka, serta kemutlakan dogma dan iman yang bisa mereka tumpahi ketidakmengertian mereka atas hidup. Jadi, apakah arti memilih salah satu di antara kebebasan dan keterikatan? Orang kecewa pada tirani, lari ke pembebasan. Orang cemas pada kerakusan nyala kebebasan, kepingin rasa aman. Agama, yang dianggap duta dogma, di satu sisi ditinggalkan, di sisi lain kembali dipercaya. "Agama perlu bagi kanak-kanak dan orang tua yang tinggal beli kijing tapi anak-anak muda butuh kebebasan." Tentulah yang dimaksud agama yang pengertiannya sudah direduksi. Pendidikan agama di tengah kita banyak tereduksi menjadi hanya dogma, karena itu agama hanya sukses di kalangan anak-anak dan para jompo. Ketika putra kita sudah menjelang akil balig, agama memaparkan cakrawala yang jauh lebih luas. Cuma karena struktur sosial keumatan agama disifati oleh kelas-kelas feodal juga, pembeberan segi kreativitas beragama bisa mengundang bahaya bagi establishment suatu kelas. Maka, anak-anak muda juga terus hanya dicekoki dogma. Maka, nilai-nilai Tuhan dicari prioritasnya yang aman. Maka, ayat-ayat pun, disengaja atau tidak, dipilih hanya yang menjamin stabilitas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini