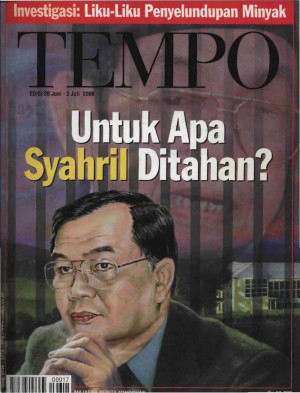Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dunia tidak menjadi Amerika yang lebih luas, dua ratus tahun lebih semenjak 4 Juli 1776.
Dewasa ini kita memang masih mendengar kecaman terhadap ”universalisme palsu”—asumsi yang menganggap bahwa apa yang baik di (atau bagi) Amerika akan baik pula bagi bagian bumi yang lain: baik itu kapitalisme, sistem pemilihan distrik, maupun cacahan kentang goreng. Pierre Bourdieau, pemikir Prancis yang cemerlang itu, pernah menulis dengan meradang apa yang dianggapnya sebagai ”la ruses de la raison imperialiste”; adapun, menurut dia, salah satu buah kecerdikan akal imperialis itu adalah ”McDonaldisasi pemikiran”. Dengan kata lain, sebuah pembentukan cara berpikir yang terjadi lantaran dominasi Amerika di pelbagai sudut: dalam hal dana riset, kemampuan penerbitan buku dan risalah, kekayaan dunia akademik, penyebaran media massa.
Tapi tidakkah di sini kita mencium sebuah purbasangka yang sangat sering dijumpai di Eropa (benua yang tua), yang memandang Amerika (yang lebih muda) hanya sebagai dunia barbar pengunyah permen karet yang menyebalkan?
Imperialisme Amerika, ”McDonaldisasi pemikiran”, dan globalisasi. Barangkali ada cara lain untuk memandang hal-hal itu, cara yang tidak mengikuti Bourdieau. Cara lain itu sebenarnya sudah ditawarkan oleh Marx, ketika ia, bersama Engels, menuliskan Manifesto Komunisnya yang termasyhur itu.
Yang sering dilupakan orang ketika berbicara tentang Marx ialah bahwa pemikirannya menjadi dahsyat karena ia menyaksikan kedahsyatan kaum borjuis, kelas menengah yang mengubah dunia dan ”mencapai keajaiban yang jauh melebihi piramida Mesir, akuaduk Romawi, katedral Gothis”. Kaum borjuis, menurut Marx, ”telah memainkan peran paling revolusioner dalam sejarah”. Dunia lama digantikan yang baru. Keinginan yang lama digantikan keinginan yang baru, yang tak cukup dipenuhi oleh produksi setempat, melainkan oleh hal-hal yang datang dari negeri jauh dan cuaca yang beda. Dalam Manifesto yang ditulis di tahun 1848 itu Marx mengungkapkan apa konsekuensi dari perubahan besar itu: saling ketergantungan. ”Kesatu-sisian nasional dan kesempitan-pandang nasional semakin lama menjadi semakin mustahil.” Marx saat itu hendak berbicara tentang akan munculnya ”sebuah kesusastraan dunia”, tetapi argumennya bisa dipakai untuk membicarakan produksi kerohanian pada umumnya. Ia sesungguhnya telah melihat globalisasi yang kini, 150 tahun semenjak itu, disambut atau dikutuk orang itu.…
Tapi, berbeda dengan banyak analis kini, Marx melihat bahwa yang menjadi sumber dari transformasi itu bukanlah sebuah negeri, Amerika atau Inggris, melainkan sebuah dinamisme yang datang dari kepentingan modal. Setiap pelaku ekonomi berada dalam posisi harus bersaing dengan pelaku ekonomi yang lain, baik yang membuka toko di seberang jalan maupun yang datang dari pantai yang jauh. Perubahan dan inovasi harus djalankan, sebagai salah satu cara menemukan akal selamat. Kaum borjuis, kata Marx, ”tak akan ada tanpa terus-menerus mengubah alat-alat produksinya.”
Memang, Marx tidak hanya memuji peran sejarah kaum borjuis. Ia juga melihat kelemahan dasar dari proses itu. Kaum borjuis pada akhirnya hanya melaksanakan satu dari kemampuan dirinya yang beragam itu—kemampuan yang dibebaskannya dari ikatan-ikatan feodal—dan itu adalah kemampuan menghimpun kapital. Dengan demikian manusia hanya berkembang terbatas dan menjadi bengkok. Akhirnya hanya yang bisa dipasarkan, hanya yang bisa menjadi komoditi, yang bertumbuh. Dalam proses itu, manusia borjuis sendiri akan kehilangan dayanya untuk mengendalikan gerak agresif modal yang dimilikinya. ”Masyarakat modern borjuis,” tulis Marx, ”sebuah masyarakat yang telah menyulap-jadikan alat-alat produksi yang begitu hebat, mirip seorang ahli sihir yang tak bisa lagi mengontrol kekuatan dunia bawah yang telah dipanggilnya sendiri”.
Itu sebabnya Marx meramalkan akan ambruknya borjuasi. Sejauh ini kita belum melihat itu sedang akan terjadi. Yang tampak bahkan arus yang kian deras dari apa yang dikemukakannya di tahun 1848 itu: makin mustahilnya ”kesatu-sisian nasional”. Yang kini terjadi ialah bahwa sebagian kecil manusia hidup dan bekerja dalam sebuah ruang global yang satu—tak peduli apa yang tertulis di paspornya—sementara sebagian besar yang lain terpaku di antara perbatasan-perbatasan lama, bahkan perbatasan yang lebih tua ketimbang ”nasion”. Seorang eksekutif di New York akan lebih merasa satu tempat dengan seorang ahli teknologi di Jakarta, seorang pendesain industri di Osaka, seorang konsultan pemasaran di Capetown. Pada 4 Juli ada orang-orang yang akan menyanyi ”God Bless America” tapi saham berkelit dari pelbagai penjuru, lari ke pelbagai penjuru, tenaga-tenaga pakar melintas benua dan tinggal di hotel-hotel interkontinental dengan CNN di televisi di kamar mereka. Kita mungkin tidak bisa lagi menggunakan kata ”kecerdikan akal imperialis”, karena kita tidak lagi melihat sebuah negeri menjajah negeri lain. Kita bahkan agak bingung apa yang kini bisa disebut sebagai ”negeri”, juga ”negeri Amerika”.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo