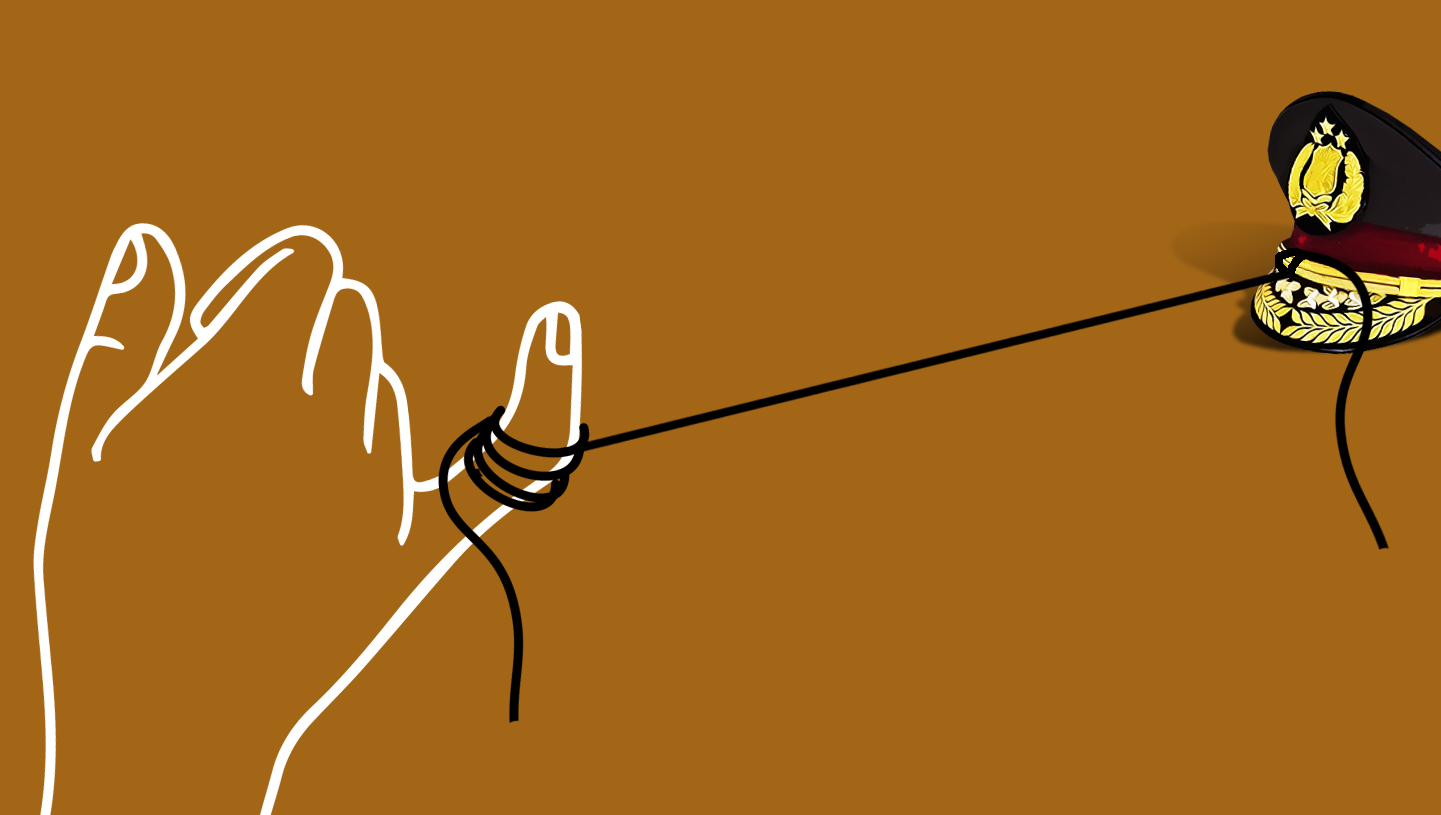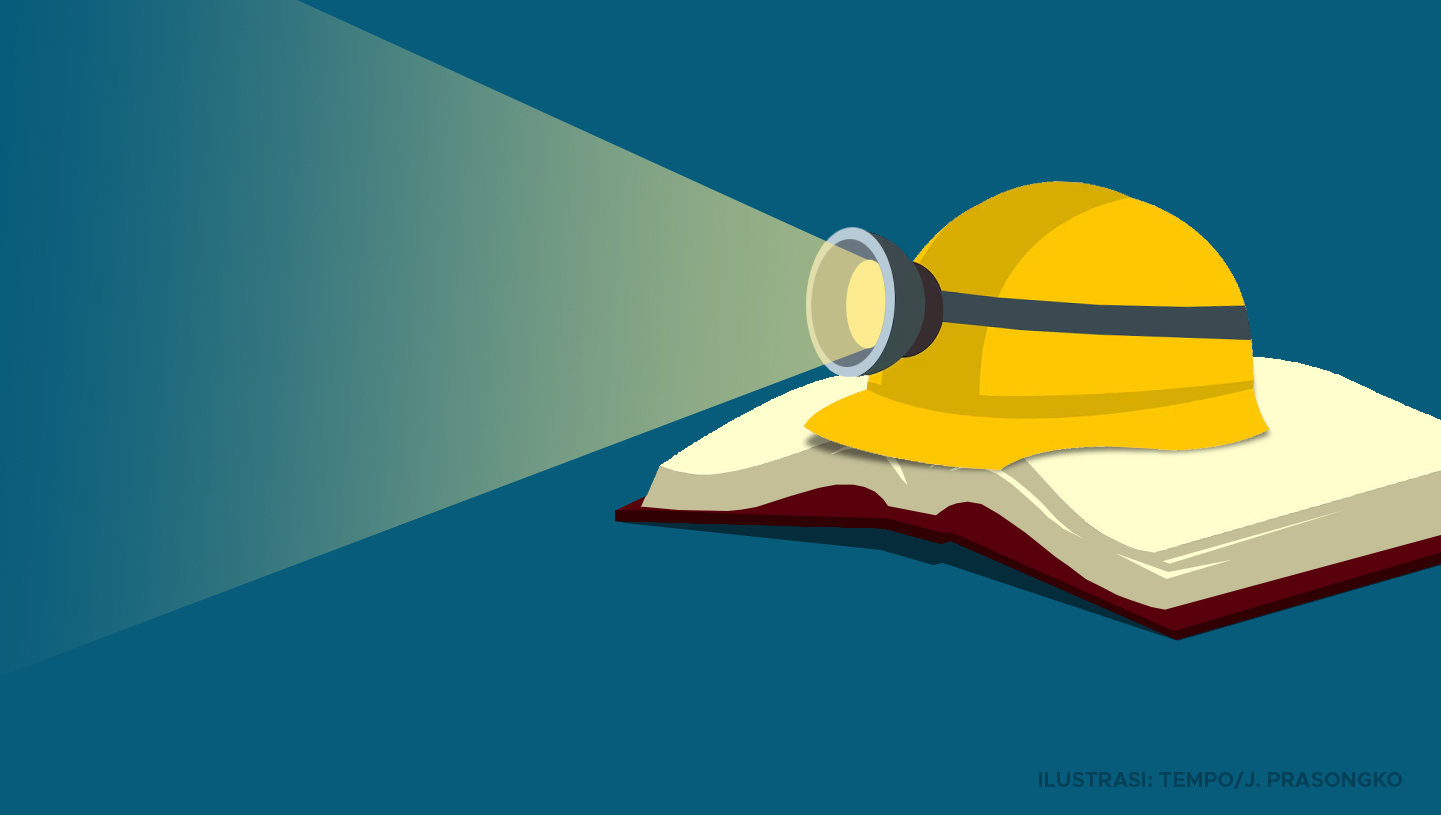Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEKS dan cinta berkecamuk dan berhenti di dunia privat—di palung rahasia yang tak terjangkau orang lain. Wilayah ini tak bisa ditilik ulama, padri, lurah, atau Bareskrim. Mustahil diadili dengan KUHP. Memang sesekali ada (misalnya penulis roman dan pornografi) yang mencoba mengintip proses seks dan cinta untuk diceritakan ke khalayak ramai. Tapi di sini kata dan kamera adalah ikhtiar yang gagal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yang berlangsung dalam diri seseorang saat bersetubuh, atau berhasrat, atau berahi, selalu luput dihadirkan kembali. Dunia privat tak pernah lengkap menyatakan diri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kata “privat” bermula pada kata Latin privatus, yang artinya “terletak terpisah” (dari pandangan publik), bagian diri (bukan milik Negara) yang sifatnya khas dan personal. Berlawanan dengan publicus, dunia orang ramai.
Kata “privat” tak punya padanan dalam bahasa Indonesia—dan mungkin itu menjelaskan latar sosial sikap kita kepadanya. Di sini orang hampir terus-menerus merasa dalam dunia publik.
Rumah, terutama rumah tradisional di Indonesia, umumnya ruang hidup bersama. Para penghuni saling melihat, mendengar, menghidu. Tak ada posisi menyendiri. Asas yang berlaku: “kita semua satu keluarga”.
Kata “keluarga”, menurut seorang pakar bahasa, berasal dari “kula-warga”, yang menunjukkan bahwa seorang “aku” (kula) selamanya anggota (warga) sebuah himpunan. Tapi ke-warga-an kemudian tak terbatas pada unit-unit biologis—ayah & ibu & anak—melainkan juga pada kesatuan nenek moyang.
Yang “privat”, yang menyendiri atau tersendiri, tampak menyimpang.
Di Eropa, privacy juga tak langsung diakui sejak mula. Di masa Yunani Kuno, belum ada pengertian keluarga yang seperti dikenal kini. Sejarawan Philippe Ariès, dalam L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime (saya baca versi Inggrisnya, Centuries of Childhood, 1962), menyebut bahwa pengertian “famili”, sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan, baru beredar sejak abad ke-16.
Dalam unit sosial ini, yang tak langsung dikendalikan Raja dan Gereja, sang bapak penguasa tunggal. Dia-lah pemegang kedaulatan bergerak dan berbicara. Sementara itu, sang ibu hanya bolak-balik antara bagian dalam rumah dan tangga pintu, mengurus “rumah tangga”: dapur dan anak-anak. Sang emak tak punya hidup sendiri. Kita ingat di Jawa abad ke-19 Ngasirah, yang melahirkan Kartini, hanya setengah tersembunyi di dapur, sebagai selir seorang bupati. Bahkan anaknya, yang kelak akan dikenal sebagai pelopor pembebasan wanita, nyaris tak menyebutnya dalam surat-suratnya yang terkenal.
Dari Ngasirah, kita bisa lihat, ada atau tak adanya dunia privat ditentukan oleh dan dalam “politik” atau hubungan kekuasaan. Salah satu jasa pemikir feminisme abad ke-20 adalah menguak kenyataan itu. Dari mereka lahir semboyan yang kemudian terkenal sebagai “the private is political”. Dengan itu, atas nama publik, orang berhak menghentikan perlakuan sewenang-wenang dalam keluarga.
Tapi ada yang bisa menyesatkan di celah kata-kata itu. Hubungan kekuasaan yang menerobos dan menginjak dunia privat—di mana manusia bisa bebas menyendiri—tak hanya berlangsung antargender di rumah bupati.
Doktrin Nazi Jerman meletakkan perempuan setara dengan mesin cuci dan perabot dapur, buat membereskan anak, masakan, ibadah, dan pakaian—Kinder, Küche, Kirche und Kleider. Dan itu bukan sebuah penghinaan tersendiri. Penindasan juga terjadi di media, sains, dan seni, di mana ruang yang privat leluasa memproduksi alternatif-alternatif baru. Hitler mematikan itu.
Juga Stalin di Rusia, Mao di Cina, dan dinasti Kim di Korea Utara. Totalitarisme punya ambisi yang berlebihan: bukan sekadar mau mengubah tatanan politik, tapi juga menciptakan jenis manusia baru, sampai ke batinnya, sampai ke dunia privatnya—yang mereka waspadai menyembunyikan bibit perlawanan.
Ironis, bahwa juga bagi totalitarisme, “the private is political”.
Begitu pula bagi rezim Wahabi di Arab Saudi dan para ayatullah di Iran. Di sana Negara menggantikan Agama, dan Agama menggantikan Negara, dalam mengutak-atik dunia batin manusia.
Kita ingat lembaga Inkuisi Gereja Katholik Spanyol di abad ke-15. Dengan teror, Gereja mengusut kemurnian iman seseorang. Saat itu Gereja, yang bukan Tuhan yang Maha Tahu, merasa perlu (dan mampu) menelisik batin dan mengambil alih posisi ke-maha-tahu-an.
Dalam novel termasyhur Dostoyevsky, Karamazov Bersaudara, ada cerita yang ajaib dari Spanyol. Di sana, lembaga padri yang berkuasa dengan siksaan dan ancaman hukum bakar memaksakan pengakuan dari orang yang imannya diragukan. Ketika Yesus turun ke bumi dan menunjukkan betapa salahnya tindakan sang Inkuisitor Agung, Almasih pun ditangkap dan dipenjarakan.
Tentu itu kisah fiktif. Tapi sejarah punya banyak cerita bagaimana agama dan ideologi totaliter tergoda jadi pengusut agung, karena selalu mencurigai isi dunia privat yang tak diketahuinya. Maka dikerahkanlah polisi dan pengintip. Dan dirumuskanlah KUHP.
Seperti di Indonesia kini.
Memang semua itu dilakukan atas nama Tuhan. Tapi jelas bukan Tuhan yang dirindukan Amir Hamzah. Bagi penyair sufi ini, seperti dalam sajak “Padamu Jua”, Tuhan ibarat:
…kandil kemerlap
Pelita jendela di malam gelap
Melambai pulang perlahan
Sabar, setia, selalu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo