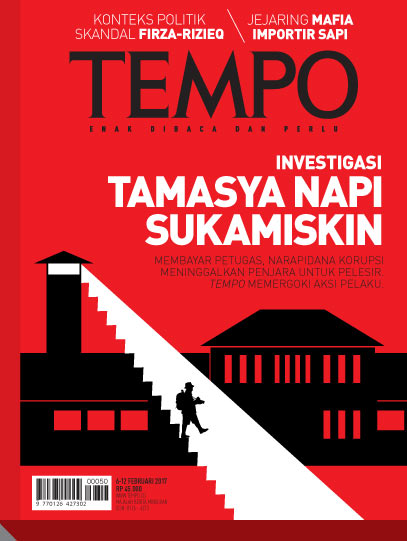Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kebenaran telah turun takhta. Ia jadi kebetulan. Ketika kita menyaksikan sampai mual kampanye politik yang dengan agresif minta diterima orang ramai-seraya mengerahkan kaum cerdik cendekia yang dianggap jujur dan disegani, tapi tetap berbicara dengan penuh nafsu dan membiarkan fitnah dan kabar palsu-"kebenaran" seperti terselip di suatu tempat. Jika mujur, kita bisa menemukannya.
Tapi tak semuanya harus disesali. Sebab dari sana juga kita menyaksikan kekerdilan dan batas manusia dalam berhubungan dengan kebenaran-justru ketika kebenaran tak lagi di singgasana tinggi.
Pernah ada masanya, kebenaran (Kebenaran, dengan "K") diletakkan di sana oleh para filosof dan ilmuwan-hingga dibayangkan tak akan tersentuh nafsu dan kepentingan sepihak. Di masa Yunani Kuno, Kebenaran yang suci dan abadi itulah yang hendak diteguhkan Plato. Di masa modern, itu juga yang hendak ditegakkan rasionalisme dan positivisme, dengan asumsi bahwa nalar bisa menjelaskan semuanya dan ilmu-ilmu bisa membuktikan apa yang benar.
Tapi pengalaman tak demikian. Seorang Plato akan galau andai ia kini, di abad ke-21, berada di sebuah ruang pengadilan. Di sana orang disumpah dan berjanji untuk berkata benar; dalam versi Amerika, "the whole truth, and nothing but the truth". Tapi segera tampak bahwa Kebenaran tak hadir di depan meja hijau itu. Yang ada tafsir akan satu kasus, diutarakan oleh pihak yang beperkara. Dan tafsir itu tak cuma satu; mereka bersaing. Keputusan final yang ada di hakim juga pada akhirnya hanya sebuah tafsir kebenaran. Vonis itu masih bisa digugat tafsir lain-dan proses ini akan berlanjut, sampai berhenti di suatu titik. Titik itu disepakati berada di pendapat Mahkamah Agung.
Pada akhirnya yang berlaku bukan kebenaran, melainkan otoritas: auctoritas, non veritas, facit legem.
Dan Plato kita akan galau. Ia tak pernah berpikir bahwa di dunia yang fana dan ribet ini, apa yang disebut "kebenaran"-yang selamanya diutarakan dengan bahasa yang fana dan ribet juga-adalah interpretasi, bukan kebenaran itu sendiri. Ia dibentuk oleh satu sudut pandang saja. Pasca-Plato, "Tak ada kebenaran yang utuh," kata pemikir dan matematikawan Alfred North Whitehead. "Semua kebenaran adalah setengah-kebenaran."
Dulu orang berpendapat bahwa sebuah pernyataan disebut "benar" bila pikiran kita mencerminkan secara obyektif sehimpun data yang ada. Dengan kata lain, kita "benar" bila apa yang ada dalam pikiran pas persis, memadai sepenuhnya, dengan apa yang ada di alam kenyataan. Tapi apa sebenarnya "pikiran"? Sekian ribu tahun pasca-Plato, "pikiran" makin tampak bukan cermin yang jernih. Ia tak bisa obyektif. Ia kini diakui sebagai fungsi yang tak terlepas dari tubuh dengan segala percikan hormon dan getaran sarafnya. Dan apa sebenarnya "kenyataan"? Sebuah proses yang tak stabil, sebuah kejadian yang selamanya berubah dan tak sepenuhnya bisa tertangkap pikiran.
Dahulu ilmu-ilmu tak mengakui keterbatasan itu. Tapi di masa pasca-positivisme kini datang kesadaran lain. "Ilmu-ilmu tak berpikir," kata Heidegger, filosof yang menggugat Plato. Ilmu-ilmu-yang cabangnya berkembang tiap kali-tak berniat menjelajahi kehidupan lebih dalam. Ilmu hanya memecahkan problem, namun menjauh dari misteri-tentang keindahan dan kebahagiaan, misalnya-yang tak pernah tuntas dijelaskan.
Zaman pun menyambut kebenaran yang berbeda-kebenaran yang tak berada lagi di singgasana. Filsafat tak menopangnya lagi; ia jadi bagian ilmu-ilmu. Tapi ilmu-ilmu juga tak bisa memonopolinya. Ada kebenaran dalam seni, ada kebenaran dalam pengalaman mistik, ada kebenaran yang tumbuh dari percakapan sehari-hari.
Maka kebenaran tak perlu dan tak bisa ditinggal pergi. Gianni Vattimo, yang menulis Addio alla verità (dalam versi Inggris, A Farewell to Truth), mengambil sepatah kata bahasa Yunani yang dipakai Santo Paulus: aletheuontes. Makna kata itu konon, diuraikan dalam bahasa Latin, berarti "membuat kebenaran dalam caritas, dalam mencintai sesama".
Itu berarti kebenaran yang bukan datang dari atas, melainkan sesuatu yang dibuat-dan dengan demikian kebenaran yang manusiawi. Ia tentu saja terbatas, tapi melibatkan diri si pembuat. Dan bila proses pembuatan itu berlangsung dalam caritas, kebenaran pun jadi penyambung ikatan sosial. Baik kebenaran maupun ikatan sosial itu bukan hasil sebuah desain yang logis dan pasti. Kebenaran dan ikatan sosial itu tumbuh melalui sambungan-sambungan sejarah, kenangan bersama, juga harapan kita yang sederhana.
Persoalannya: manusia tak selamanya manis. Tak ada jaminan caritas berhasil. Kebencian dapat berkobar dengan kebenaran yang dibuatnya sendiri.
Akhirnya memang manusia harus memilih. Ada sebaris sajak W.H. Auden yang berkumandang dari awal Perang Dunia Kedua: "We must love one another or die."
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo