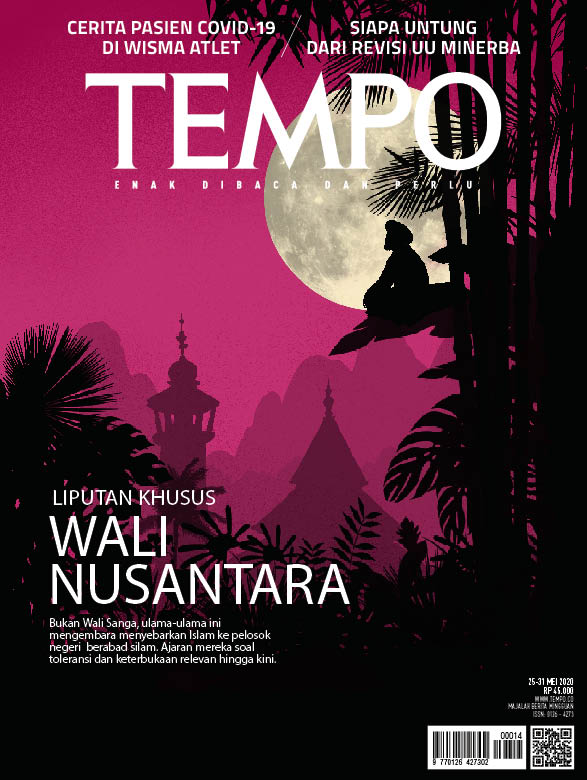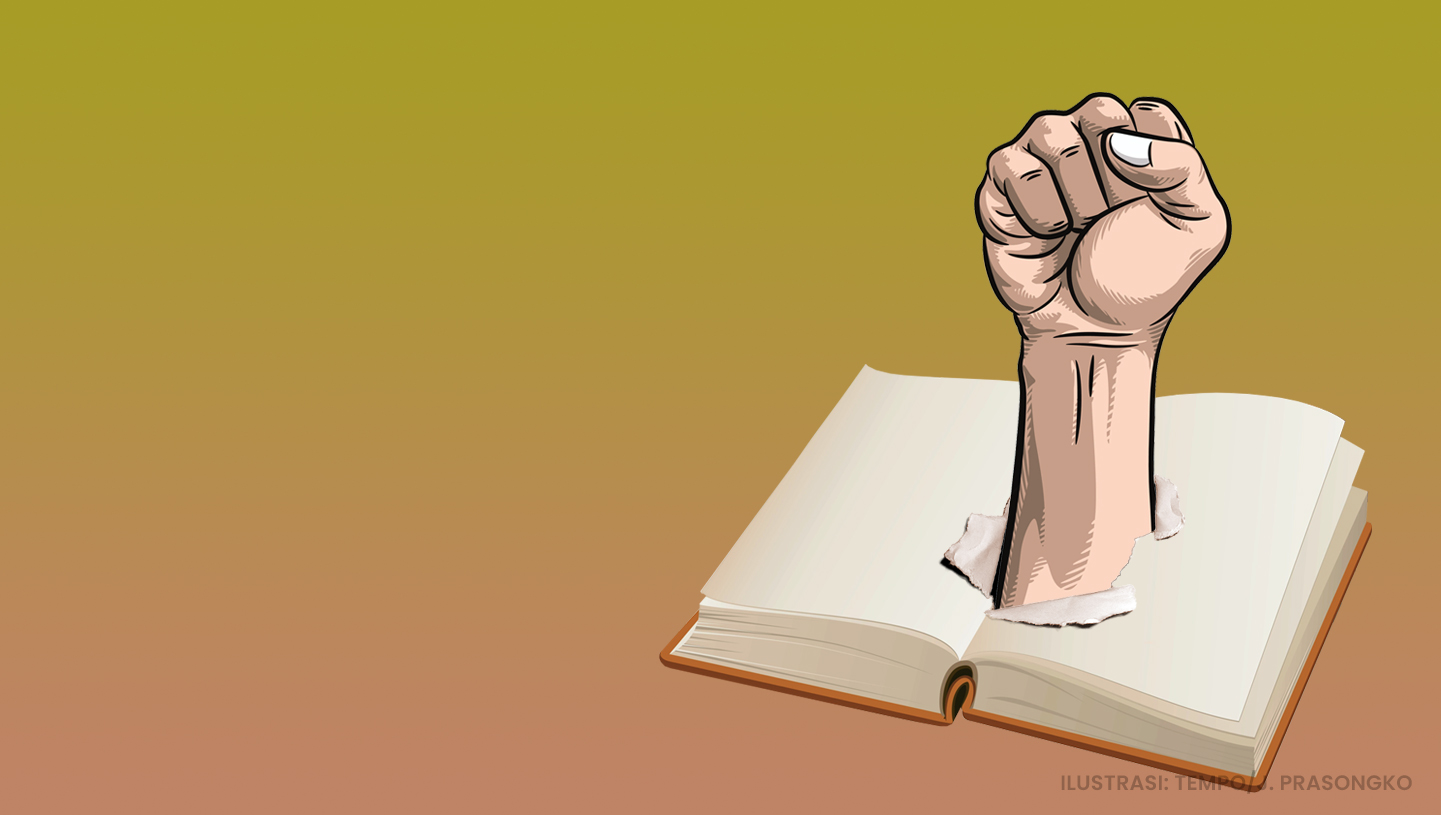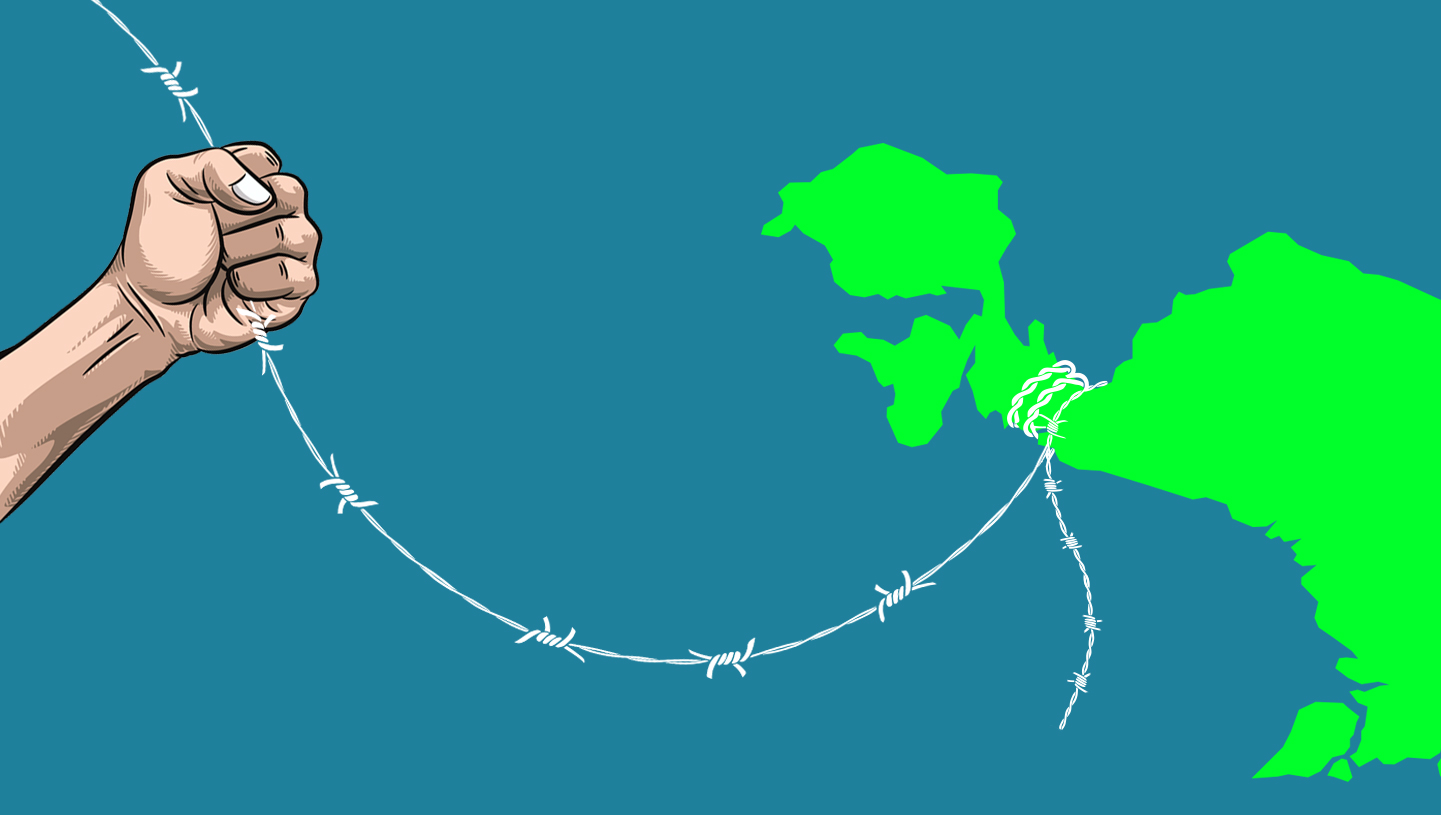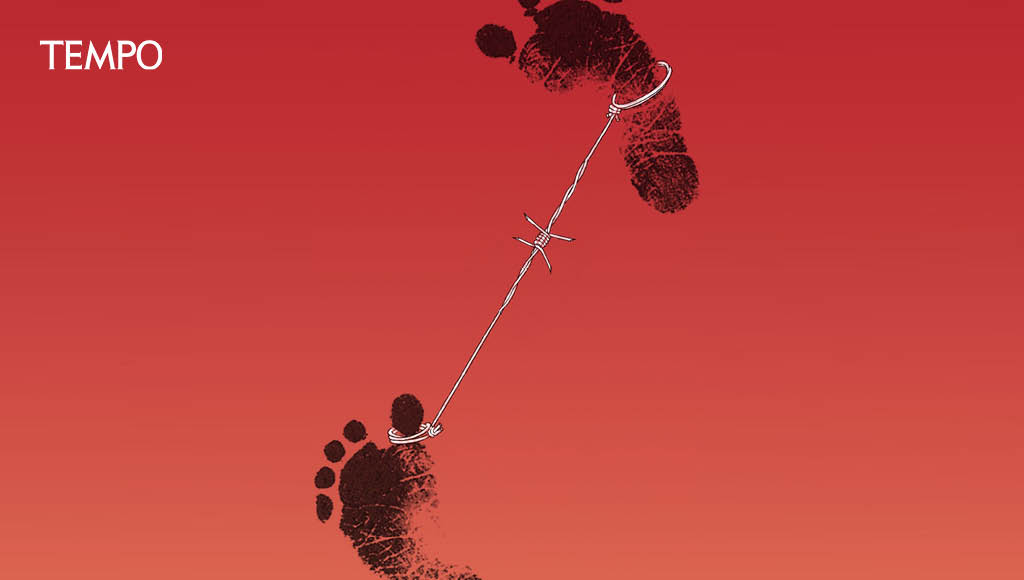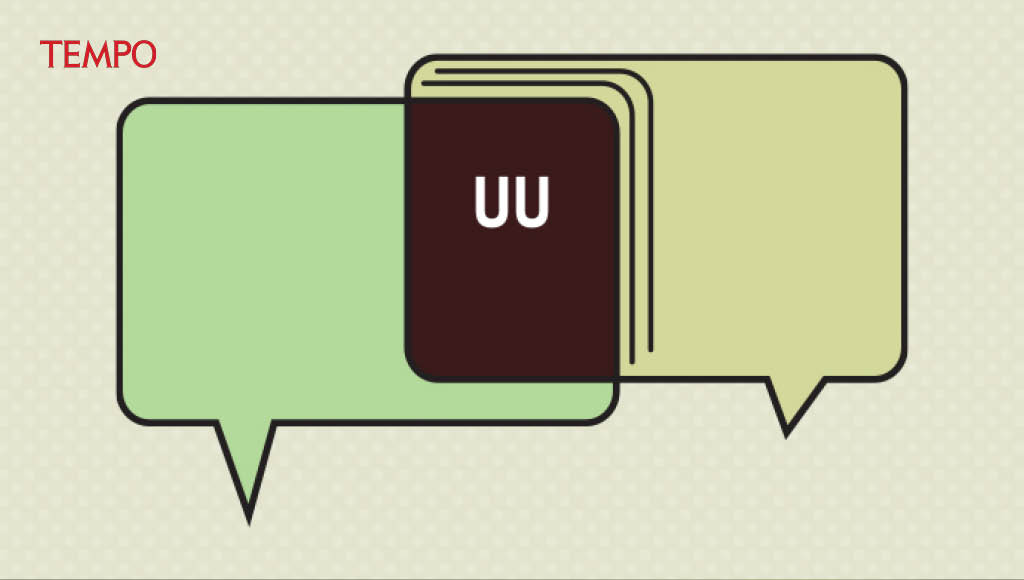Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hidup terdiri atas bermacam-macam kesendirian. Masing-masing kita sesekali punya (atau ingin punya, atau sebaliknya takut untuk punya) ruang isolasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam hikayat dan sejarah, ada orang-orang yang bersunyi diri untuk memperoleh sesuatu yang lebih bernilai dari yang selama ini ada pada dirinya, di sebuah hening yang total. Dikisahkan tentang Panembahan Senapati di abad ke-17 dalam Serat Wedhatama, “lelana lalading sepi/ Ngingsep sepuhing supana”: mengembara ke tempat-tempat yang sunyi, untuk merenung dan mendapatkan kearifan tentang hidup. Atau seperti Airlangga di Kerajaan Kediri di abad ke-12 yang turun takhta dan masuk hutan untuk “menyepi” sampai ia wafat. Isolasinya adalah sejenis penyucian diri dari najis yang selalu menempel pada kekuasaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Agama-agama memuliakan pilihan keheningan seperti itu—dan kita dibawa untuk percaya ada hubungan kesunyian dengan kesucian. Iman dibangun dengan sejumlah ikon meditasi: Gua Hira menjelang Muhammad menjadi Rasul; padang gurun tempat Yesus berpuasa dan menolak Kerajaan Dunia; pohon Bodhi di Bihar, tempat Siddhartha Gautama bersemadi setelah meninggalkan kehidupan seorang pangeran.
Dalam zaman yang bising kini agaknya Thomas Merton, seorang rahib Trappist, penyair, mistikus, dan filosof, yang masuk kembali ke hidup pertapaan sebagai sesuatu yang jauh tapi sekaligus dekat dengan sekitar. Tulisnya: “Menyendiri, solitude...” (saya temukan dalam A Year with Thomas Merton: Daily Meditations from His Journals) “...bukanlah semata-mata sebuah hubungan negatif.” Baginya, menyendiri adalah “berpartisipasi dalam kesendirian Tuhan, yang ada di segala hal”.
Umum diketahui, dalam pertapaan Ordo Trappist, para rahib hampir sepenuhnya hidup tanpa percakapan. Mereka hanya menggunakan kata-kata seperlunya, di celah-celah jam-jam panjang berdoa, kemudian jam-jam panjang bekerja, di ladang mereka yang selalu diolah. Dan dalam hal Merton: juga menulis. Salah satu catatan hariannya, 4 Januari 1950, mengungkapkan rasa berbahagia: “Kini aku tahu, aku memasuki hari di mana aku akan dapat hidup tanpa kata-kata.”
Thomas Merton tentu tak menafikan bahasa; ia orang yang telah menulis sekitar 50 buku. Tapi baginya bahasa mempunyai “daerah-tak-bertuan” yang tak secara sungguh-sungguh menggabungkan dirinya dengan orang lain.
Dari catatan harian 18 Januari, bisa kita bayangkan ia di luar pertapaan, mendengarkan dari tepi hutan lonceng berbunyi, dan merasakan keheningan dan kesendirian justru sebagai “bagian semesta—sepenuhnya pas ke dalam lingkungan pepohonan, kebisuan, dan kedamaian”. “Apa saja yang kaulakukan,” tulisnya, menjadi sebuah kesatuan dan sebuah doa. “Diamku adalah bagian dari diamnya seluruh dunia... membangun candi Tuhan tanpa suara palu bertalu-talu.”
Dari catatan itu kita segera tahu, pertapaan Thomas Merton bukan sebuah isolasi. Bahkan sebaliknya. “Kesendirian dan kesunyian mengajariku untuk mencintai saudara-saudaraku sebagaimana mereka adanya, bukan sebagaimana kata-kata mereka.” Isolasi Merton bukan kesendirian Chairil Anwar: “Ini sepi terus ada. Dan Menanti.”
Mungkin itu yang membedakan jarak fisik dengan jarak sosial: dalam ribuan kilometer ketika tubuh kita berpisah, keakraban bukan mustahil; demikian juga sebaliknya, kedekatan fisik tak membuat orang mau saling menyapa. Maka ada yang melihat isolasi—terutama di masa wabah—hanya sebagai cara penyelamatan diri atau, kalau tidak, cara mengunggulkan diri di atas yang lain yang rata-rata tak tahan.
Saya ingat Henry David Thoreau. Pada 4 Juli 1845, ia, seorang penulis berumur 28 tahun, mulai berdiam di sebuah pondok kayu kecil yang ia bangun sendiri di hutan sekitar Kolam Walden, tak jauh dari Concord, Massachusetts, di Amerika Serikat bagian timur. Thoreau, yang tak pernah menikah, hidup menyendiri di gubuk itu selama dua tahun. Catatannya tentang kehidupan sunyi itu ia terbitkan dalam sebuah buku yang kemudian termasyhur dalam sastra Amerika, Walden, or Life in the Woods—separuh memoar dan separuh rekaman renungan tentang manusia dan alam.
Buku itu, dalam kata-kata John Updike, novelis yang juga penulis kritik, “sebuah totem bagi semangat ‘kembali-ke-alam’”. Kini ia bisa dianggap pemberi ilham bagi kaum pencinta lingkungan—meskipun mungkin Walden, seperti kata Updike, punya risiko “akan dikagumi dan tidak dibaca—seperti Injil”.
Tak dapat dimungkiri Walden ditulis seseorang yang tekun merekam hampir tiap gerak alam di kesunyian itu. Tapi ketika saya membacanya (setelah mendengar pujian bertubi-tubi), saya temukan di dalamnya sebuah isolasi yang tanpa kompromi. Walden membuat jarak fisik menjadi jarak sosial sekaligus. “Berada bersama orang lain, bahkan dengan yang terbaik, segera akan meletihkan dan menguras tenaga. Aku suka bersendiri. Aku tak pernah menemukan teman bersama yang asyik selain kesendirian.” Bagi Thoreau dalam Walden, masyarakat umumnya “terlalu murahan”, commonly too cheap. Nilai manusia “bukan dalam kulitnya hingga kita harus menyentuhnya”.
Yang ditampik Walden adalah kenyataan bahwa manusia adalah kulit, jangat, darah, saraf. Pendek kata, tubuh, bukan hanya roh; gairah, bukan hanya pikiran.
Itu sebabnya manusia membentuk peradaban dengan karnaval, jemaat, nonton bola bersama, menari cak yang riuh dan rapat, bergoyang bareng dalam dangdut pantura, membuat flash mob berdansa di sudut jalan dengan Waltz No. 2 Shostakovich.
Apa boleh buat. Hari-hari ini saya cemas: dalam hidup bersama Covid-19, kita akan kehilangan yang bareng dan yang gayeng itu.
GOENAWAN MOHAMAD
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo