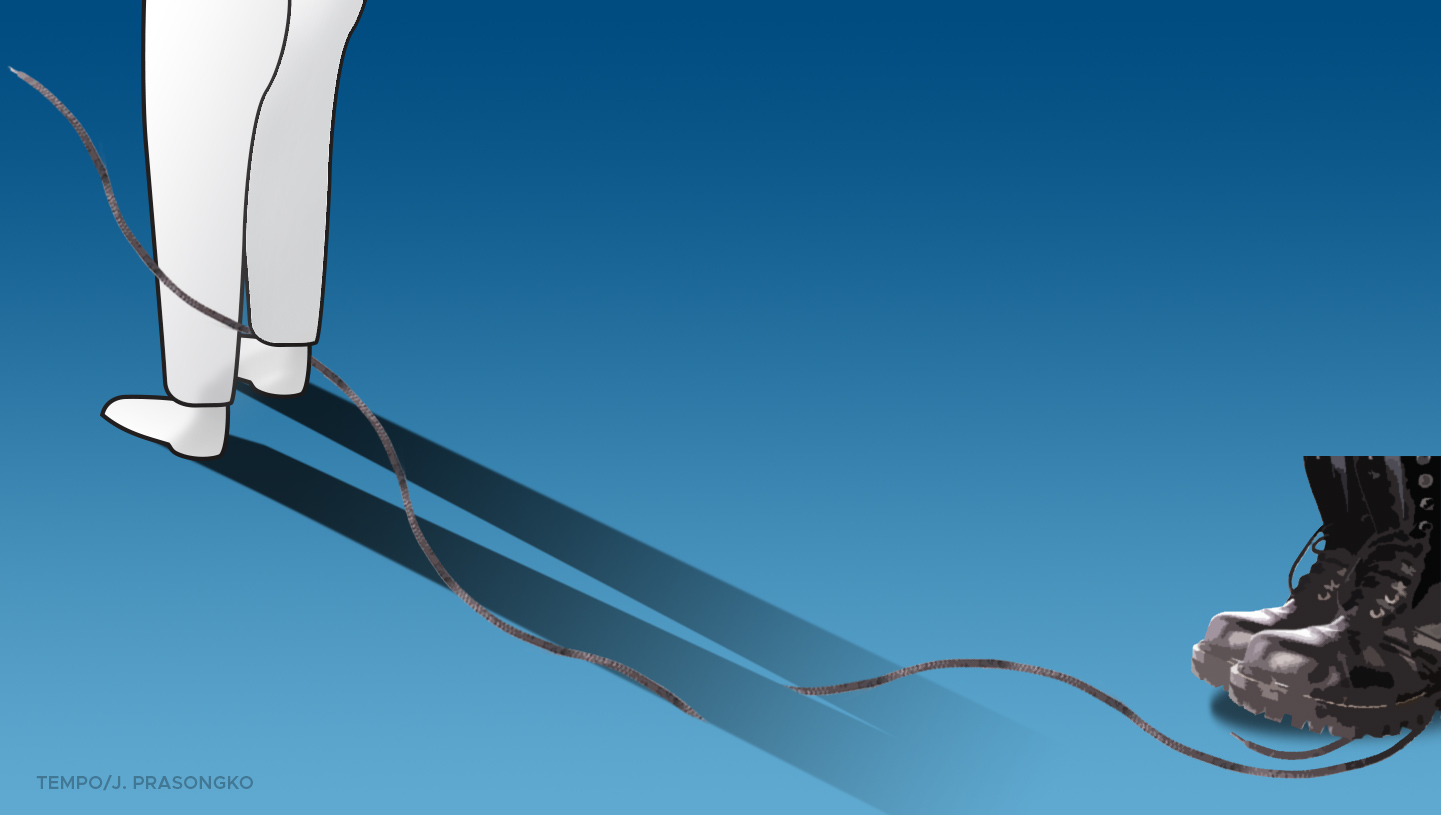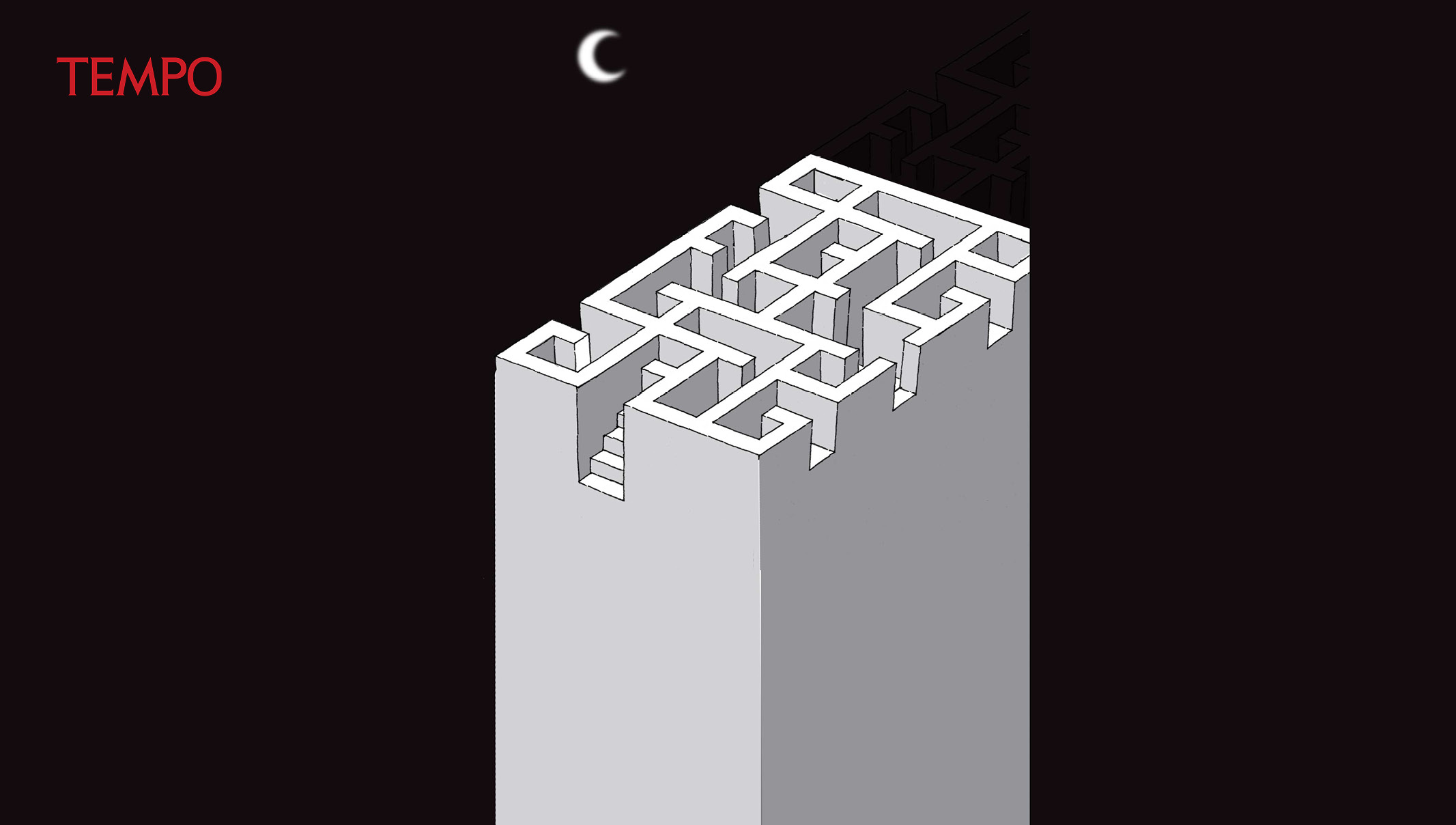Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kemala Atmojo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Alumni STF Driyarkara
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Virus corona Covid-19, yang kini menyerbu berbagai negara, mengingatkan saya pada penyakit sampar dalam novel La Peste (Sampar) yang ditulis Albert Camus pada 1947. Meski La Peste konon dimaksudkan Camus untuk menyimbolkan wabah gelap seragam tentara SS Nazi, ia juga ingin menggambarkan perjuangan manusia di depan absurditas hidup. Dalam banyak literatur, sampar memang sering dipakai untuk menyimbolkan banyak hal, misalnya dalam kitab suci Perjanjian Lama, penyakit ini disebut sebagai hukuman untuk musuh-musuh Tuhan; dalam tragedi Oedipus Raja, sampar adalah ganjaran untuk kejahatan yang belum terbalaskan; dan lain-lain.
Dalam La Peste, sampar digambarkan menghantam Kota Oran, Aljeria. Kekacauan terjadi. Dokter, pemerintah, media massa, dan masyarakat umum tidak satu kata. Muncul berbagai sikap dan karakter manusia dalam menghadapi wabah tersebut. Ada yang merasa terjerat, ada yang mengambil keuntungan, ada yang tidak peduli, dan lain-lain. Intinya, novel ini mengajak kita pada perenungan terhadap eksistensi manusia di depan bencana dan kematian.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita teramat sering menyaksikan aneka kejadian yang seakan-akan tak masuk akal. Ada anak membunuh ibunya, ada ayah memperkosa anaknya, ada peradilan memenangkan pihak yang bersalah, ada orang kaya yang terus korupsi, serta ada ibu-ibu dan para pekerja keras terkena virus corona. Sementara itu, pada saat yang sama, kita saksikan keluarga-keluarga miskin hidup turun-temurun di desa yang gelap dan becek. Anak-anak ingusan berkeliaran di perempatan jalan mengharap sisa rupiah.
Absurditas yang dimaksudkan Camus memang lebih mendalam. Baginya, absurditas adalah persepsi bahwa segala sesuatunya sia-sia; bahwa manusia merupakan orang mati yang tertunda. Rasa absurd itu makin menguat ketika manusia menghadapi kematian. Dalam La Peste, tokoh dokter Rieux melihat setiap hari puluhan pasiennya meninggal. Ia seperti tidak berdaya untuk melawan penyakit yang menggerogoti pasien dan bahkan istrinya sendiri. Rieux seperti hanya memperlambat kedatangan kematian para pasiennya.
Lalu, apa yang mesti kita lakukan? Haruskah kita terima begitu saja absurditas ini? “Lawan!” begitu kira-kira kata Camus. Seperti dokter Rieux, yang tanpa banyak berharap jalan keluar, berkeras untuk bergulat melawan sampar. Fondasi harapannya sama sekali bukan Tuhan, melainkan kemanusiaan. Sebab, dalam diri manusia lebih banyak hal untuk dikagumi daripada dicela. Maka kita harus melawan absurditas.
Sementara dalam novel L’etranger (1942) Camus menunjukkan kesendirian manusia di depan absurditas, dalam La Peste ia menunjukkan perlawanan manusia dalam kebersamaan. Maka kita juga harus bersama-sama melawan Covid-19. Tidak bisa tidak, corona merupakan urusan kita bersama.
Kita tidak bisa duduk diam menunggu Covid-19 hilang dengan sendirinya. Orang seperti Camus juga tidak bisa sabar menanti pengadilan pada akhir zaman dan suatu firdaus dalam kehidupan kekal kelak. Kita harus melawan penyakit, penderitaan, absurditas, dan ketidakadilan. Di sini dan sekarang.
Camus menolak setiap utopia. Sebab, dalam ide, gagasan, atau pikiran yang utopis, keadilan ditunda sampai masa depan yang jauh. Sedangkan penderitaan, kekerasan, dan ketidakadilan seakan-akan harus kita terima begitu saja. Camus tidak ingin kita menjadi seorang fatalis. Meski Tuhan tidak ada, kata dia, kita harus berjuang bersama korban melawan kebatilan. Absurditas adalah kebatilan tak bernama dan harus kita lawan. Kita harus aktif terlibat dan menolak kepasrahan nihilistik yang menghindari aksi, meski belum tentu mencapai kemenangan yang absolut. Bagi Camus, yang penting kita bertindak secara konkret membela manusia. Kita melakukan apa yang mungkin bisa dilakukan tanpa pretensi menghilangkan “akar kemalangan” dan tanpa percaya sebuah “keselamatan akhir”. Kita bertindak untuk setidaknya mencegah agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi.
Namun, di luar urusan corona atau sampar, bagaimana perlawanan atau pemberontakan terhadap absurditas itu diwujudkan? Misalnya, terhadap kekejaman rezim militer, kejahatan para penegak hukum, kebodohan dan kerakusan politikus yang menyengsarakan rakyat? Bisakah perlawanan itu dilakukan tanpa kekerasan sama sekali? Sebab, seperti kita tahu, dalam setiap kali pemberontakan terjadi, sulit bisa menghindari kekerasan. Camus hanya menawarkan agar si pemberontak tahu ukuran, tahu batas, dan jangan keterlaluan. Tapi di mana batasnya? Siapa yang menentukan itu?
Maka, sejauh perlawanan pemberontakan ini dinyatakan dengan cara-cara beradab dan konstruktif, hal itu merupakan tindakan yang masuk akal untuk diterima. Hidup memang absurd. Tapi, bukankah kita punya nurani, akal budi, yang bisa kita gunakan untuk berusaha memecahkan persoalan dengan cara-cara damai agar hidup di dunia ini, meski absurd, kita bisa tetap betah, kerasan.

![Pandangan sepi di sekitar patung Winston Churchill dan Big Ben di Westminster saat penyebaran penyakit virus Corona (COVID-19) berlanjut, di London, Inggris, 19 Maret 2020. [REUTERS / Hannah McKay]](https://statik.tempo.co/data/2020/03/20/id_924528/924528_720.jpg)