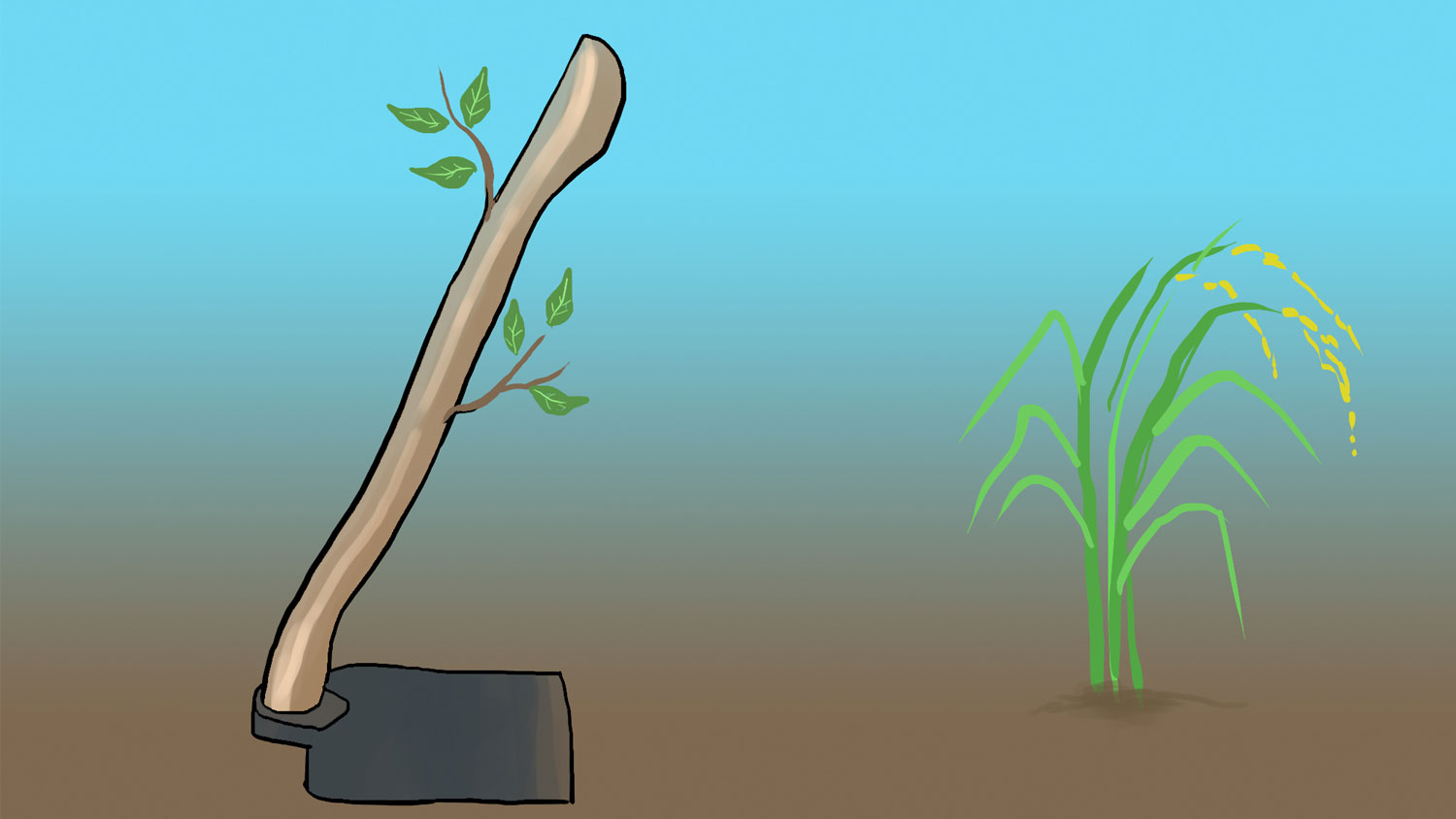Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Harga gabah di tingkat petani dan penggilingan jatuh di bawah harga pembelian pemerintah.
Jatuhnya harga gabah sudah terjadi sejak tahun lalu.
Penyebabnya adalah berubahnya kebijakan subsidi pangan, dari rastra menjadi Program Sembako.
Khudori
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan penulis buku Ironi Negeri Beras
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Petani sejak dulu adalah kelompok yang nrimo. Meskipun diperas tengkulak dan pengijon, mereka hanya pasrah. Ketika sulit mendapatkan bibit, pupuk, dan air untuk usaha tani, paling-paling mereka hanya menggerutu. Manakala harga jual gabah anjlok, bahkan biaya memanen lebih mahal daripada harga jual, petani biasanya membiarkan tanaman rusak. Kalaupun ada, bisa dihitung jari, yang secara demonstratif membuang hasil panen ke sungai atau jalan. Inilah, meminjam istilah James Scott, senjatanya kaum lemah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kini pun mereka harus nrimo. Mengawali 2021, harga gabah di tingkat petani dan penggilingan jatuh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Memang, persentase harga gabah yang jatuh pada Januari 2021 masih kecil, 5,29-5,43 persen. Tapi harga anjlok pada saat paceklik (Oktober-Januari) amatlah langka. Umumnya, harga gabah jatuh pada saat panen raya (Februari-Mei). Rupanya, harga gabah jatuh berlanjut hingga panen gadu yang dimulai pada Juni. Sepanjang Januari-Juli 2021, harga gabah di bawah HPP selalu terjadi. Jumlahnya antara 5,29 dan 46,66 persen di tingkat petani, sementara di level penggilingan berkisar 5,43-44,68 persen.
Rupanya, fenomena langka ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Sepanjang 2020, harga gabah di petani yang jatuh di bawah HPP berlangsung selama sembilan bulan (April-Desember) dan di penggilingan berlangsung sepanjang tahun. Pada tahun-tahun sebelumnya, kejadian semacam ini hanya terjadi pada 3-5 bulan dalam setahun. Bukan saja semakin masif, persentase harga anjlok juga semakin besar. Situasi paling parah terjadi pada Juli 2021. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah harga gabah di bawah HPP mencapai 46,66 persen di level petani dan 44,68 persen di penggilingan. Hal ini menandai bahwa situasi yang dihadapi petani padi kian buruk.
Mengapa ini terjadi? Kejadian langka ini adalah "bom waktu". Buah yang mesti dituai akibat perubahan drastis kebijakan subsidi pangan, dari beras sejahtera atau rastra (dulu bernama raskin) menjadi bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau saat ini dinamai Program Sembako. Perubahan ini membuat kebijakan perberasan yang semula terintegrasi hulu-tengah-hilir menjadi terfragmentasi. Sebab, dalam Program Sembako tak ada keharusan kehadiran Bulog di hilir. Akibatnya, kebijakan perberasan bukan saja menjadi tak utuh lagi, tapi juga membuat Bulog kehilangan pasar tertawan (captive market) yang amat besar, yakni 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) rastra.
Pada saat program rastra, setiap rumah tangga menerima 15 kilogram beras per bulan. Bulog bertugas melakukan pengadaan (dengan menyerap gabah/beras produksi petani domestik dengan mengacu pada HPP), pengelolaan dan distribusi stok, serta penyaluran beras. Namun, dalam Program Sembako, tak ada penyaluran beras langsung. Pemerintah mentransfer uang bantuan ke rekening rumah tangga sasaran. Uang hanya bisa dibelanjakan kebutuhan pokok, salah satunya beras, di outlet yang ditunjuk. Penyedia beras di outlet bisa siapa saja, termasuk Bulog.
Dibanding rastra, Program Sembako lebih tepat secara administrasi, sasaran, dan waktu. Ketepatan kualitas, harga, dan jumlah tak lagi relevan karena rumah tangga sasaran dapat memilih beras sesuai dengan preferensi. Skema baru ini juga tidak mendistorsi pasar gabah/beras, dan rumah tangga miskin/rentan juga tidak perlu menyediakan uang Rp 1.600 per kg beras seperti dalam rastra. Dana anggaran pendapatan dan belanja daerah pendamping dari kabupaten/kota, yang selama ini mengiringi rastra, dapat dihapus dan dialokasikan untuk yang lain.
Masalahnya, seiring dengan perubahan itu, penyaluran beras Bulog di hilir anjlok drastis. Dari rata-rata 2,825 juta ton pada periode 2014-2017, tinggal 351 ribu ton pada 2019, dan habis pada 2020. Sebagai pengganti outlet penyaluran yang hilang, pemerintah menyediakan opsi operasi pasar, yang disebut ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH). Agar volumenya besar, operasi pasar digelar sepanjang tahun. Selain menyalahi prinsip dasar operasi pasar, langkah ini membuat subsidi terarah menjadi tercemar oleh subsidi umum. Lebih dari itu, cara ini juga akan membuat salah urus perberasan nasional makin akut.
Ketika tidak ada lagi penyaluran beras bersubsidi di hilir, menjadi tak relevan bila menugaskan Bulog menyerap gabah/beras produksi petani domestik lewat target serapan tahunan. Akan dikemanakan beras hasil serapan domestik itu? Beras, selain bersifat bulky, mudah rusak. Tanpa outlet penyaluran yang pasti, menugaskan Bulog menyerap gabah/beras petani bisa dipastikan membuat BUMN ini bakal bangkrut. Karena itu, seiring dengan outlet penyaluran yang menciut ini, manajemen Bulog mengerem penyerapan domestik. Selama 2010-2016, rerata penyerapan beras Bulog 2,4 juta ton per tahun, tapi dua tahun terakhir (2019-2020) hanya 1,2 juta ton. Tahun ini bisa jadi akan lebih kecil lagi.
Penurunan penyerapan beras domestik bisa dimaknai sebagai cara direksi Bulog menjaga keseimbangan: tetap menunaikan fungsi publik (yang kian minimal) dan tak rugi. Apakah ini salah? Diakui atau tidak, manajemen Bulog terlalu lama hidup dalam zona nyaman. Mereka lupa bertransformasi. Namun mencabut bisnis inti Bulog tanpa proses transisi tentu tidaklah bijak. Bulog bukan hanya oleng, tapi juga berpotensi bangkrut. Lebih dari itu, penyerapan gabah/beras yang mengecil membuat petani tidak terlindungi. Apalagi penggilingan atau pedagang yang mengerem penyerapan karena merosotnya insentif giling gabah, menyetok beras, dan mendistribusikannya, maka pasar beras akan semakin lesu darah.
Bom waktu lain yang siap meledak setiap saat adalah peluang instabilitas harga gabah/beras. Rastra tidak hanya efektif menjamin warga miskin mengakses pangan murah, tapi juga sebagai instrumen stabilisasi harga gabah/beras. Volume penyaluran rastra sebesar 232 ribu ton per bulan atau 10 persen dari kebutuhan beras berpengaruh besar pada harga. Kala rastra diubah menjadi Program Sembako, bisa dibilang tak ada lagi instrumen stabilisasi yang penting. Memaksa Bulog menjaga stok beras sebesar 1-1,5 juta ton ada tiap saat tanpa outlet penyaluran pasti juga menciptakan "bom waktu" lain, yakni beras yang rusak kian banyak.
Ada dua solusi untuk keluar dari buah simalakama ini. Pertama, rumah tangga sasaran hanya membeli beras Bulog di outlet yang ditunjuk. Jumlah beras yang diserap sekitar 1,8 juta ton, setara dengan pengadaan Bulog untuk pengamanan HPP. Harga eceran tertinggi bisa dihapus. Jika ini dilakukan, Bulog wajib memasok beras lebih dari satu kualitas dengan harga sama di seluruh Indonesia agar rumah tangga sasaran mendapat keadilan dan tak turun kesejahteraannya. Cara tersebut tak membutuhkan anggaran baru dan membuat kebijakan beras kembali terintegrasi serta relatif tak mengubah mekanisme saat ini.
Kedua, menggairahkan pasar domestik dengan mengekspor beras besar-besaran, mencabut harga eceran tertinggi, pengadaan Bulog cukup 1 juta ton beras, dan beras lebih empat bulan atau turun mutu dilelang dengan kerugian ditanggung negara. Cara kedua ini perlu anggaran besar dan ada (potensi) rugi besar. Kini, bergantung pada pemerintah akan memilih solusi yang mana.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo