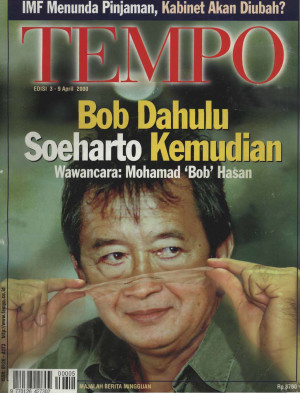Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEORANG padri pernah bercerita tentang sebuah naskah, dalam bahasa Jawa Kuno, tentang sebuah riwayat yang berdarah, kejadian di abad ke-11, mungkin ke-10, sebelum Kerajaan Singosari berdiri di Jawa Timur. Cerita itu menarik perhatian saya, karena padri itu juga menjelaskan bagaimana ia memberi tafsir. Ia menyebutnya riwayat Ken Arok dan sebilah keris.
Kemudian saya pun menemukan teks cerita itu di beberapa museum, dalam beberapa versi, dengan huruf tua yang separuh terang. Dan inilah kira-kira yang bisa saya ceritakan kepada pembaca, sebuah kombinasi empat versi yang tak saya ingat dengan persis tapi tetap meyakinkan, ditambah fantasi-fantasi yang timbul di kepala saya waktu cerita ini saya paparkan di sini.
Adegan pertama: di rumah sang pembuat keris. Namanya Empu Gandring. Ia seorang berumur 65 tahun yang tak mengenakan destar, dan rambutnya yang tergerai putih menutupi sebagian dadanya yang kisut. Orang tua itu tahu ketika seseorang datang memasuki halaman bengkelnya, sore itu. Ia dengar kuku kaki kuda mengetuk-ngetuk jalan batu, dan ia menghela napas. "Ken Arok…," bisiknya.
Ken Arok telah datang untuk mengambil sebilah keris yang dipesannya empat bulan yang lalu. Di salah satu dinding bengkel, bilah itu sudah terpacak. Rampung. Terhunus tanpa sarung. Lurus tanpa luk. Gagah seperti Pasopati. Relief pada batangnya tampak lamat di warna gelap batu meteor. Ia, Gandring, memang seorang empu. Dua generasi para bangsawan datang memesan keris dari tangannya, terutama orang-orang Tumapel yang menaiki kuda-kuda ranggi dengan pelana beludru. Tapi tak ada yang mendapatkan keris sebagus itu. Gandring sendiri tak menyangka bahwa hasil kerjanya akan demikian impresif. Dan kini si pemesan datang. "Ken Arok…."
Ada sesuatu dalam hati orang tua itu yang tak menghendaki keris itu diambil. Mungkin ia jatuh sayang kepada kreasinya sendiri. Mungkin ia tak merasa Ken Arok layak memiliki dan mengenakan karya sebagus itu di pinggangnya.
Memang, laki-laki itu tak membuatnya tenteram. Umurnya sekitar 26 tahun. Tubuhnya tinggi dan parasnya runcing, dengan tiga bekas luka di jidat dan pelipis. Rambutnya yang tebal tersanggul rapi. Tapi ada sesuatu yang liar di gerak matanya. Empu Gandring tahu ia bukan orang Tumapel.
Juga pernah didengarnya cerita-cerita menakutkan tentang Arok: kepala perampok yang pernah membunuh 30 orang dengan sekali tebas, penyamun yang menghimpun permata rampasan di tiga gua di luar Daha, dan kemudian datang ke wilayah itu sebagai pendekar yang dihormati.
"Aku datang untuk mengambil kerisku, Gandring."
"Belum siap…," jawab Gandring dengan gugup.
Dalam salah satu naskah yang saya baca,percakapan di bengkel itu berakhir dengan konflik. Ken Arok bukan hanya menganggap Gandring tak memenuhi janji, tapi juga ia menganggap pak tua itu mengganggu sebuah rencana. Ia sudah melihat keris yang anggun itu terpasang dekat dinding, rampung. Tapi Gandring tak mau menyerahkannya. "Sebilah keris yang bernilai, sesuatu yang indah dan magis, tak pernah siap dipakai," jawab sang empu.
Arok diam, tapi matanya menatap tajam. Gandring hanya bermain dengan kata dan arti, itulah kesimpulannya. Lalu dengan sebaris senyum di bibirnya yang tipis Arok bergerak mengambil keris itu dari tempatnya tersandar. Sebelum Gandring sempat memprotes, keris itu sudah menikam jantungnya. Darah muncrat sampai ke tanur. Tubuh orang tua itu terjungkal. "Aku telah buktikan sebaliknya," seru Arok. "Keris ini sudah selesai—dan ia bisa dipakai."
Gandring gugur. Menurut sebuah versi, ia sempat berkata sebelum mati: "Keris ini hanya kau beri fungsi tunggal, Arok, untuk mengalahkan. Kekerasan tak akan berhenti sejak hari ini."
Adegan kedua: di sebuah rumah besar. Ken Arok berbicara di depan dua pendekar yang menemaninya berlatih silat: "Aku membunuh orang tua itu tanpa kemarahan. Amarah hanya emosi. Aku tak ingin membuang waktu. Aku merancang. Keris itu milikku, sang pencipta sudah mati. Kini aku yang memberinya arti. Ia indah, mungkin magis, tapi aku bisa membuatnya jadi alat. Keindahan dan kemagisan tak bisa dibiarkan sendiri, bebas tanpa manfaat. Rancangan membutuhkan instrumen. Aku hidup dengan akal, dan aku menang."
Tentu para pembaca sudah tahu: ada cerita kelanjutannya. Saya tak perlu mengisahkannya kembali secara rinci, bagaimana Ken Arok kemudian, di suatu malam, membunuh Tunggul Ametung, akuwu Tumapel yang menguasai wilayah yang subur itu. Keris itulah yang dipergunakannya. Seperti kata Gandring, kekerasan tak berhenti sejak pembunuhan di bengkel itu. Ken Arok kemudian jadi akuwu, dan kisahnya baru berakhir ketika ia sendiri dibunuh oleh anak tirinya, Anusapati, dan Anusapati dibunuh oleh adiknya, Tohjaya.
Saya jadi ingat kepada tafsir sang padri. Kekuasaan dan penaklukan selalu mengandung kekerasan. Ketika hidup hanya bertopang pada alat (dan bila yang indah dan yang magis juga diperalat), kekerasan akan berlanjut. Alam, manusia, impian, tercekal.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo