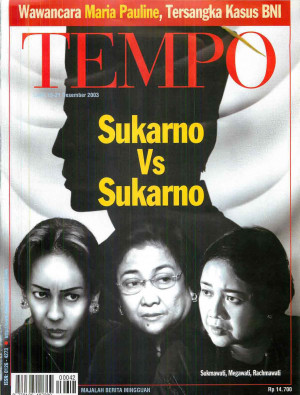Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prof. Dr. H. Paturangi Parawansa, politikus senior yang menjadi Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi (RUU KMI) DPR RI, tak kuasa menyembunyikan kerisauan hatinya. Hal ini terkait erat dengan keputusan Panitia Kerja RUU KMI, awal Desember lalu, untuk menyerahkan hasil kerjanya ke Panitia Khusus RUU KMI DPR RI dengan dua draf pilihan. Draf pertama berisi 10 bab dan 51 pasal, sedangkan draf kedua memuat 7 bab berikut 31 pasal.
Apa beda kedua draf itu? Draf kedua tidak menyebut-nyebut keberadaan Komisi.
Informasi dan Lembaga Informasi. Selain itu, masih ada materi yang belum bisa diterima untuk disepakati dan harus diserahkan ke Panitia Khusus, yaitu Pasal 15 Huruf g Angka 2, yang menyebutkan bahwa "asal-usul keterkaitan dengan ras, etnis, keyakinan agama, orientasi seksual, dan politik seseorang" adalah informasi publik yang tidak boleh dibuka, sebab dapat mengungkap rahasia pribadi.
RUU KMI, yang sudah tertahan di DPR sejak tahun lalu itu, memperkenalkan satu lembaga yang diberi nama Komisi Informasi. Komisi ini adalah lembaga mandiri. Fungsinya melakukan penyelesaian sengketa melalui bentuk mediasi dan/atau yudikasi yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi. Ia ada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Anggotanya tujuh orang. Putusannya mengikat dan dapat dikasasi ke Mahkamah Agung.
Bergigikah komisi ini? Tentu. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi atau melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan serendah-rendahnya satu tahun serta denda setinggi-tingginya Rp 500 juta dan serendah-rendahnya Rp 100 juta. Bahkan ada hukuman tambahan, yaitu uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar-besarnya Rp 1 juta.
Masalah timbul karena komisi tersebut nyaris tidak memperoleh hak untuk hidup di negeri ini. Ada-ada saja alasan untuk untuk itu. A. Kadir Souyb, Kepala Lembaga Informasi Nasional, dalam diskusi bertema "Selamatkan Komisi Informasi"—diselenggarakan oleh Indonesia Media Law & Policy Centre, 18 Desember 2003 di Jakarta—mengatakan bahwa komisi ini membutuhkan dana yang besar. Lagi pula, perannya dapat diambil oleh Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Bagaimana kalau terjadi sengketa? Gunakan jalur pengadilan, PTUN, pengadilan biasa, atau lembaga mediasi yang lain. Pendapat ini tak beda jauh dengan pandangan sebagian besar anggota Panitia Kerja RUU KMI DPR RI.
Menghadapi penolakan itu, Johnson Pandjaitan dari PBHI, Teten Masduki dari ICW, dan juga Leo Batubara dari Dewan Pers, dan sebagian besar peserta lain—termasuk Zulkifli Halim, salah satu anggota Panitia Kerja RUU KMI DPR RI—tak tinggal diam. Pada garis besarnya, mereka berpendapat bahwa kehadiran Komisi Informasi adalah suatu keharusan untuk menjamin hak asasi warga negara mendapatkan informasi yang sejak dulu dikuasai oleh negara. Sedangkan yang terjadi selama ini adalah praktek pasar gelap dan monopoli informasi. Dibutuhkan Komisi Informasi sebagai jembatan untuk mengakhiri pasar gelap informasi. "Konvensi internasional, konstitusi, dan perundangan lainnya te-lah menjamin hak asasi ini," Johnson menegaskan. Dari segi biaya, pembentukan Komisi Informasi memerlukan ongkos yang tidak besar dan diambilkan dari dana APBN.
Leo Batubara mengibaratkan pembentukan Komisi Informasi seperti mengeluarkan biaya untuk beli ikan teri, tetapi tujuannya untuk menangkap ikan paus. Sementara itu, Teten Masduki mengingatkan bahwa tugas mediasi yang diemban oleh komisi ini bisa diserahkan kepada Komisi Ombudsman Nasional, sedangkan Komisi Informasi cukup menangani sengketa yang muncul. Karena itu, anggota Komisi Informasi cukup tiga orang dan bersifat sukarela. Biaya yang dikeluarkan cukup hanya untuk biaya sekretariat dan persidangan. Yang penting, Komisi Informasi harus tetap ada. Ini adalah konsekuensi dari pilihan berdemokrasi dan amanat konstitusi.
Teten menambahkan, fungsi mediasi itu sudah diatur dalam RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang sudah masuk ke Badan Legislasi DPR RI. Dalam negara yang demokratis, urusan informasi adalah urusan warga negara, bukan urusan pemerintah. Pemerintah adalah subyek yang harus memberikan informasi secara aktif. Karena itu, sangat tidak masuk akal jika pemerintah pula yang menjadi wasitnya.
Pertanyaannya adalah, bagaimana political will anggota Dewan dan pemerintah dalam menuntaskan pekerjaan ini. Untuk itu, DPR perlu melakukan studi yang lebih dalam soal peran Komisi Informasi.
Dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, kehadiran Komisi Informasi akan meringankan tugas dan kerja Komisi Anti-Korupsi. Sebab, Komisi Informasi berada di garda terdepan, mencegah jangan sampai terjadi korupsi dengan cara memberikan jaminan atas semua informasi yang memang seharusnya dibuka kepada publik. Selain itu, DPR juga harus melakukan pembahasan yang paralel dengan RUU Ombudsman, yang juga berfungsi mengawasi penyelenggaraan tugas penyelenggara negara, untuk melayani publik dengan sifat mediasi. Dengan demikian, Ombudsman dan Komisi Informasi menjadi satu kesatuan dengan Komisi Anti-Korupsi.
Menolak Komisi Informasi bisa ditafsirkan sebagai menolak memberantas korupsi. Paralel dengan itu, menolak Komisi Informasi juga berarti menolak mencegah terjadinya korupsi. Rupanya, political will kita untuk memberantas korupsi masih pura-pura saja. Dan reformasi yang didengung-dengungkan selama ini ternyata pemanis bibir belaka—bukan sesuatu yang diyakini dan diperjuangkan tanpa kompromi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo