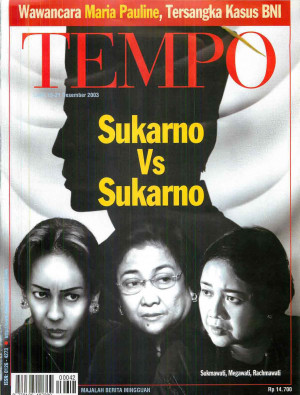Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Persoalan klasik mengenai lokal versus global kembali mengemuka dalam seminar dan workshop bertema "Fixing the Bridge", di Yogyakarta, 4-8 Desember 2003. Workshop itu kemudian dilanjutkan dengan pameran berupa presentasi hasil kerja kelompok-kelompok terlibat, yang berlangsung sampai 23 Desember mendatang di Lembaga Indonesia-Perancis, Yogyakarta.
Acara ini bisa dikatakan merupakan kelanjutan, dengan beberapa perkembangan, dari sebuah forum yang pernah diadakan pada awal tahun 2002 di Seoul, Korea Selatan, dan melibatkan berbagai ruang seni alternatif dan kelompok budaya independen, dari Tulungagung sampai Jakarta, dari Istanbul hingga Warsawa. Agenda pertemuannya meliputi usaha untuk mempropagandakan aksi-aksi lokal, komunitas, dan seni yang mengangkat berbagai ide kolektif dari seniman, kurator, serta teoretisi berdasarkan nilai lokal tiap-tiap alternative space kepada publik yang lebih luas.
Inilah usaha lintas batas kota dan negara Asia-Eropa untuk membentuk medium bagi pertukaran pengetahuan mengenai strategi lokal yang dilakukan oleh berbagai kelompok/komunitas, dalam menghadapi pelbagai persoalan yang disebabkan oleh globalisasi. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang perlu digarisbawahi dari pertemuan ini: ruang alternatif, serta persoalan hubungan seni dan komunitas.
Di Indonesia sendiri, komunitas selalu menempati posisi unik karena biasanya tidak mampu mengakses kuasa yang didominasi oleh negara. Di bawah kondisi seperti ini, suara-suara lokal/pinggiran tidak pernah sampai ke pusat. Maka, Klinik Seni Taxu (Denpasar, Bali), misalnya, hadir untuk mendobrak hegemoni atmosfer kehidupan seni rupa di Bali. Untuk konteks di luar Indonesia, kita bisa melihat pada Universitas Bangsar Utama (UBU), sebuah komunitas independen yang didirikan untuk memberikan pendidikan publik bagi anak-anak muda Malaysia.
Sedangkan Foksal Gallery Foundation (Warsawa, Polandia) awalnya adalah bagian dari Foksal Gallery, sebuah institusi di bawah struktur birokrasi manajemen kebudayaan pemerintahan Polandia yang komunis, tapi kemudian mengembangkan eksplorasi model baru fungsi institusi kebudayaan dalam masyarakat.
Di Asia, khususnya, menghadapi persoalan kebudayaan amat penting. Sejarah ideologi feodal, patriarki, heteroseksisme, rasisme, diskriminasi menjadi halangan bagi tumbuhnya demokrasi populer. Di sisi lain, globalisasi telah membuat Asia sebagai jalur dan tujuan perjalanan modal ekonomi, politik, dan kebudayaan. Ia telah memunculkan pengalaman-pengalaman baru—juga masalah-masalah baru—tentang keasiaan. Pada saat yang sama, globalisasi dan regionalisasi teknologi, produksi ekonomi dan budaya, runtuhnya struktur Perang Dingin telah membuka momen dialog yang unik antar-lingkup Asia dan internasional.
Di Indonesia, kolonialisme, revolusi kemerdekaan, pemerintahan otoriter Orde Baru, globalisasi, ingar-bingar reformasi, krisis ekonomi, kemiskinan, dan berbagai bentuk korupsi telah membentuk struktur perasaan yang ambigu tentang pengalaman keindonesiaan. Tetapi, ketika posisi ekonomi dan kultural Indonesia dalam sistem global terus berfluktuasi, identitas dan pengalaman keindonesiaan perlu dikritik dan dipertanyakan kembali.
Berkaitan dengan usaha untuk memberi suara kepada komunitas lokal, Etnoreflika (Yogyakarta), misalnya, mencoba mengembangkan pendekatan audio visual sebagai media pembelajaran dan pemberdayaan bagi beberapa komunitas. Kamera dijadikan sebagai medium bagi komunitas untuk mengekspresikan dirinya. Saat ini, Etnoreflika telah mencoba pendekatan tersebut pada komunitas anak jalanan dan kelompok petani yang tinggal di sekitar hutan.
Satu usaha menarik dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Mixrice (Seoul, Korea), suatu kelompok yang memfokuskan kegiatannya untuk mendukung aktivitas kebudayaan para pekerja asing yang hidup di Korea.
Mereka menggunakan video diary untuk mengungkap berbagai isu hak asasi manusia di kalangan para pekerja asing. Beberapa video yang ditampilkan dalam pameran dan presentasi adalah hasil karya para pekerja asal Indonesia yang berada di Korea mengenai persoalan hidup sehari-hari yang mereka hadapi di negeri itu, seperti pengalaman menikah di suatu masjid di Korea, rindu keluarga, dan lain-lain.
Pelbagai persoalan yang kemudian mengemuka sepanjang workshop ini adalah bagaimana pemahaman kelompok-kelompok alternatif ini mengenai lokalitas itu sendiri, apakah berbagai cara atau medium yang digunakan oleh berbagai kelompok alternatif itu kemudian relevan atau tepat bagi konteks komunitas lokal yang dihadapi. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengarah pada uji coba pemahaman tentang kelokalan.
Tampaknya, di sinilah pentingnya pertemuan itu: memperbanyak pertanyaan-pertanyaan, untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama bagi konteks lokal yang berbeda-beda.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo