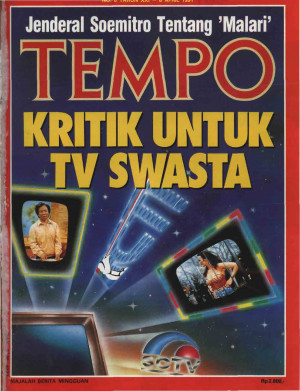ADA acara serius di Pusat Bahasa. Judulnya "Seminar Bahasa dan Ketahanan Nasional". Waktunya 11-14 Maret 1991. Sebagai anggota Himpunan Pembina Bahasa Indonesia, saya diminta menyampaikan makalah dengan judul "Pembinaan Bahasa Indonesia dan Ketahanan Nasional". Siapa tidak ngeri membaca judul itu? Entah dari mana ilhamnya, saya langsung menolak permintaan tersebut. Alasan saya sederhana saja. Hari Senin dan Selasa adalah "hari mati" saya. Tugas kantor tak bisa "dikalahkan". Itu alasan yang terucap. Alasan yang tidak terucap adalah kesulitan menghubungkan "Bahasa" dan "Ketahanan Nasional". Ternyata, perkiraan itu tak terlalu meleset. Beberapa pemakalah tampak sulit mencantolkan masalah bahasa pada ketahanan nasional. Ada sejumlah peserta seminar yang merasakan hal yang sama. Saya mulai mengantuk. Tanpa saya sadari ada telepon berdering. "Selamat siang, Mas," kata suara wanita di seberang, yang dalam memori saya antara ingat dan lupa. Penelepon adalah Michele Mulder, mahasiswa Jurusan Indonesia pada Department of Asian Languages & Studies Monash University, Australia. Ia menyatakan kebetulan bahwa saya sedang mengikuti "Seminar Bahasa dan Ketahanan Nasional". Ditanyakannya masalah nama-nama ruang di Gedung DPR/MPR yang pernah dikunjunginya. "Saya susah membacanya. Apa nama-nama itu nama Indonesia?" katanya. "Bukan, itu kata-kata Sanskerta," jawab saya, mengira-ngira. "Apakah yang dianggap asing oleh orang Indonesia adalah bahasa Belanda dan Inggris saja?" Sulit saya menjawabnya. "Mana yang benar, Mas, Bina Graha atau Graha Purna Yudha?" "Menurut saya, dua-duanya kurang tepat. Dilihat susunannya, Graha Purna Yudha lebih pas, tetapi kalau saya lebih senang memilih Graha Purnayuda. Berdasar rumus itu, Bina Graha lebih tepat kalau dibalik menjadi Graha Bina." "Saya membaca dari TEMPO, penertiban papan nama di Jakarta sulit dilakukan." "Ya, memang itu masalah lama. Dalam beberapa Kongres Bahasa Indonesia, hal tersebut sudah dibahas, tetapi orang akhirnya bosan." "Apakah peraturan daerah dengan sanksi akan menyelesaikan persoalan itu?" Pertanyaan tersebut juga tak mudah dijawab. Baru dalam soal ejaan pun sudah timbul soal. Selama ini banyak kantor dan organisasi memakai ejaan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ada Dharma Wanita, Kotamadya, Kepolisian Resort, Provoost, padahal menurut kaidah adalah Darma Wanita, Kota Madia, Resor, Provos. Sudah lumayan Bank Ekspor Impor Indonesia menggunakan ejaan seperti itu walaupun logonya tetap Exim. Saya ragu apakah Pemerintah DKI Jaya cukup berwibawa menindak pelanggar ketentuan papan nama bila Pemda DKI masih memakai Ibukota alih-alih Ibu Kota. Maksimal yang dapat dilakukan adalah tindakan persuasif, bukan penghukuman. Mereka yang sudah telanjur memakai nama dikecualikan karena hal itu menyangkut aspek hukum, biaya penggantian nama, dan soal-soal lain yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sampai sekarang masih banyak apotek yang mempertahankan ejaan apotik. Bahkan papan nama yang lebih murah pengubahannya, misalnya jam praktek dokter, tetap bertahan dengan ejaan yang sekarang. Hampir tidak pernah saya temukan kata praktik di papan nama dokter. Sementara itu, diupayakan pembuatan bahan panduan yang tidak memberi peluang untuk didebat. Mereka yang mengajukan nama badan usaha ke Departemen Kehakiman diminta memakai kata-kata Indonesia yang disusun menurut kaidah bahasa Indonesia. Bila ada niat, perubahan secara berangsur-angsur dapat dilakukan. Kita pernah akrab dengan Mobile Brigade (yang disingkat Mobrig), tetapi generasi sekarang lebih mengenal Brigade Mobil, yang bila dipendekkan menjadi Brimob. Pusat Bahasa perlu lebih aktif menyuluh lembaga tertinggi dan tinggi negara agar bila mereka membuat nama mau mengikuti kaidah dan kelaziman dalam bahasa Indonesia. Orang akan sulit menerima bineka karena Garuda Pancasila menggunakan bhinneka. Penyerapan dari bahasa asing (misalnya Arab) terpaksa menggunakan standar ganda karena salah satu kantor Pak Habibie memilih Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, mungkin dengan alasan pengajian hanya cocok untuk kepentingan keagamaan. "Mengapa diam saja, Mas?" "Tidak. Saya hanya teringat pertanyaan Anda dulu, mengapa di desa-desa terpencil pun banyak pemilik salon menggunakan bahasa Inggris, misalnya Lina Beauty Salon." "Itu saja. Maaf, koin saya sudah habis." Untung, ia segera mengakhiri hubungan telepon. Saya tersentak karena mendengar para peserta tertawa. Ternyata, yang membangunkan saya adalah S. Effendi. Pemandu salah seorang pemakalah ini mengisahkan bahwa pada hari pertama seminar itu tugasnya diambil alih orang. Effendi, yang dicari-cari panitia, sedang meninggalkan ruang seminar untuk cuci muka, menghilangkan kantuknya. Belakangan saya menyesal menolak menjadi pembicara karena sebenarnya soal remeh-temeh ini dapat dikait-kaitkan dengan "ketahanan nasional". Aspek lainnya adalah menjadi pemakalah jelas lebih bergengsi daripada pembawa makalah (membawa makalah orang lain ke rumah) dan, siapa tahu, ada honor. Karena ada tugas lain, saya hanya ikut sampai rehat minum kopi (coffee break). Di tengah perjalanan saya mampir, seperti biasa, makan mi ayam dorong di pinggir jalan. Di gerobak tukang mi itu selalu ada tulisan mie ayam. Saya tanyakan kepada abang penjual mi mengapa yang dipilih tulisan mie bukan mi saja. "Sudah dari sono-nya, dari juragan," katanya. Memang hampir semua penjual mi, baik mi gerobak dorong, mi yang pemiliknya mampu membeli kain rentang, maupun mi oleh pengusaha yang menempati lokasi elite (misalnya Mie Ayam Gondangdia) lebih senang dengan mie daripada mi. Bila ada bank yang mau memberi kredit, saya akan menjadi juragan kecil dengan membuka kios mi ayam. Walaupun mungkin kurang populer, mi yang saya pilih dan untuk warung itu akan dipasang papan yang berbunyi Mi Ayam Slamet.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini