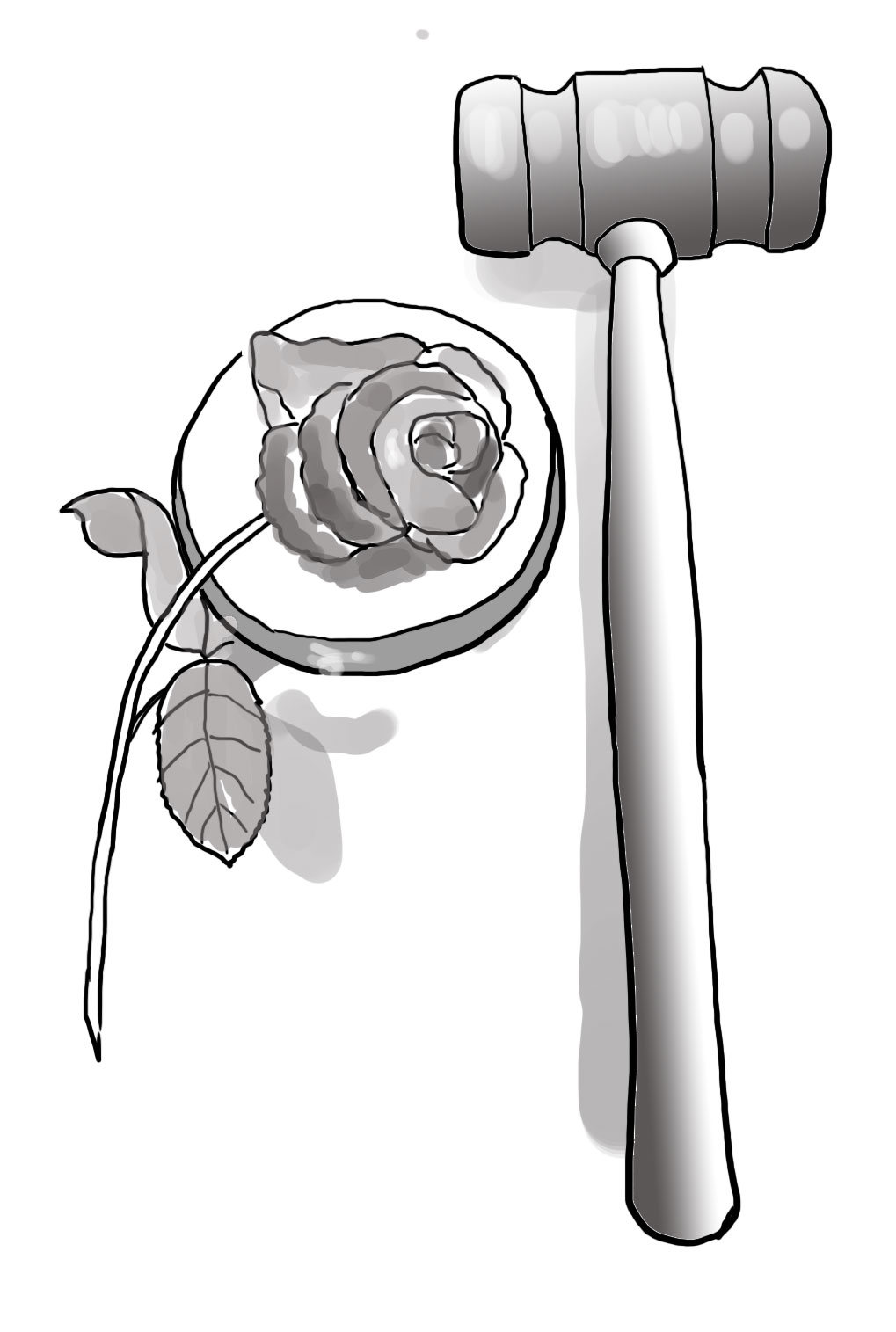Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Laras Susanti
Peneliti pada Law, Gender and Society Research Center, Fakultas Hukum UGM
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 menguatkan putusan kasasi MA dan menyatakan Baiq Nuril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ia dihukum pidana penjara 6 bulan dan pidana denda Rp 500 juta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Indonesia Criminal Justice Reform (ICJR) berpendapat, putusan kasasi tersebut adalah implementasi UU ITE yang tidak tepat dan tidak mempertimbangkan fakta bahwa Baiq Nuril adalah korban kekerasan seksual. Adapun Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan menilai kasus Baiq ini menjadi contoh buruk hilangnya rasa aman bagi perempuan, khususnya korban kekerasan seksual.
Juru bicara MA menyatakan Mahkamah hanya menjalankan tugasnya sebagai judex juris, yakni hakim yang memeriksa penerapan hukum oleh pengadilan yang lebih rendah. Majelis hakim yang memutus kasasi Baiq dipandang sudah menerapkan hukum dengan benar, sehingga permohonan peninjauan kembali oleh Baiq ditolak. Karena menggunakan konsepsi judex juris, MA tidak dapat memeriksa fakta-fakta dalam suatu perkara, atau yang dikenal dengan sebutan judex facti, yang selama ini dilakukan oleh hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
Pertanyaan mengenai kedudukan hakim agung sebagai judex juris atau judex facti jamak didiskusikan, baik di lingkungan kampus maupun MA. Contohnya, diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA pada 10 September 2013. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsepsi tersebut dikenal di lingkungan akademis tapi tidak terdapat asas, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dikotomi kewenangan hakim tersebut.
Jadi, hakim agung adalah hakim yang diharapkan memutus berdasarkan fakta-fakta serta sesuai dengan asas, nilai, dan norma hukum di masyarakat. Dalam memeriksa kasasi, misalnya, buku hasil penelitian badan tersebut menyebutkan bahwa hakim agung dapat mengadili sendiri, bukan sebagai upaya hukum tingkat ketiga, melainkan demi keadilan.
Dalam isu perlindungan hak-hak perempuan, buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang disusun oleh MA, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia UI, dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 menyebutkan beberapa contoh putusan landmark. Lewat putusan Nomor 179/SIP/1961, di tingkat kasasi, majelis hakim MA memutus diskriminasi hak mewarisi bagi keturunan anak perempuan pada sistem pewarisan adat patrilineal. Putusan tersebut didasari pertimbangan rasa kemanusiaan, keadilan umum, serta persamaan hak perempuan dan laki-laki. Putusan tersebut sampai sekarang terus dikaji civitas academica dan menjadi rujukan hakim lain.
Semangat yang sama salah satunya diteruskan oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi Jambi. Pada akhir Agustus 2018, WA, perempuan 15 tahun, dinyatakan bebas atas dakwaan perbuatan aborsi. WA adalah korban pemerkosaan oleh kakaknya. Putusan pengadilan tersebut mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menyatakan WA bersalah dan divonis 6 bulan penjara.
Sejumlah putusan pengadilan yang menjadi landmark itu menunjukkan pentingnya perlindungan atas hak-hak perempuan, bahkan dengan tegas memutus diskriminasi terhadap perempuan di hadapan hukum.
Mahkamah Konstitusi juga ikut mendorong narasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Pada Desember 2018, dengan putusan 22/PUU-XV-2017, Mahkamah menyatakan frasa "usia 16 tahun" pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakannya tidak mengikat.
Pasal tersebut mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Frasa "16 tahun" dalam pasal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum yang dijamin konstitusi dan tidak sejalan dengan undang-undang lain, khususnya yang mengatur perlindungan anak.
MA telah membuktikan komitmennya terhadap perlindungan perempuan dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hakim diharapkan mampu mengimplementasikannya, bukan hanya prosedur persidangan yang menghargai harkat martabat perempuan, melainkan juga nilai-nilai perlindungan hak-hak perempuan dalam memutus perkara, termasuk dalam kasus Baiq Nuril.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo