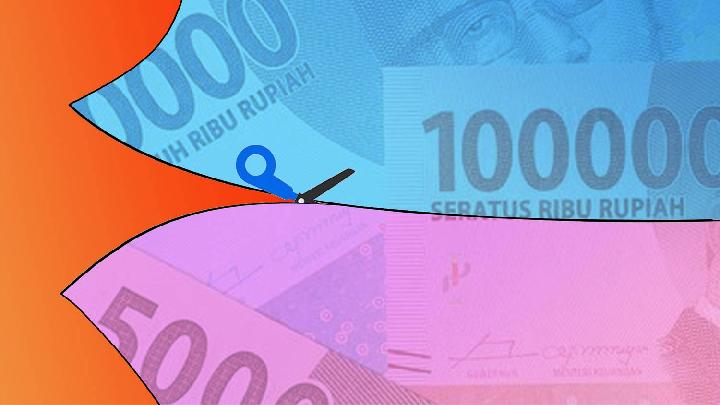Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 sedang disusun.
Kementerian Keuangan berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai.
Kenaikan tarif pajak justru bisa kontraproduktif.
Haryo Kuncoro
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sedang disusun. Penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional agaknya tetap menjadi figur sentral yang menyokong defisit fiskal sepanjang tahun depan. Namun, mulai 2023, defisit APBN harus kembali patuh pada Undang-Undang Keuangan Negara, yang secara tegas membatasi rasio defisit APBN maksimum 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Maka, APBN 2022 menjadi fase transisi memasuki era "normal" baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dari dua opsi yang tersedia, pemerintah agaknya memilih peningkatan penerimaan daripada pemotongan belanja. Pemerintah tampak optimistis dengan mematok penerimaan perpajakan antara Rp 1.499,3 triliun dan Rp 1.528,7 triliun pada APBN 2022. Angka tersebut naik 8,37-8,42 persen dari proyeksi penerimaan tahun berjalan.
Kementerian Keuangan juga berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), dari 10 persen menjadi 15 persen. Artinya, untuk mencapai target penerimaan perpajakan pada APBN 2022, manuver fiskal akan lebih banyak diletakkan pada kinerja PPN.
Pilihan pada rencana kenaikan tarif PPN sejatinya menunjukkan inkonsistensi. Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sudah mengenalkan pajak konsumsi sebagai pengganti PPN. Secara implisit, strategi otoritas fiskal condong pada perluasan basis pajak, alih-alih intensifikasi tarif.
Pergeseran ke arah kebijakan PPN agaknya didorong oleh faktor eksternal. Laporan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Corporate Tax Statistics, menyebutkan bahwa tarif PPN di berbagai negara mengalami tren kenaikan. Sejak 2008-2018, sebanyak 25 negara OECD pernah setidaknya satu kali menaikkan tarif PPN.
Sejak 1984, Indonesia belum pernah mengubah tarif PPN. Momentum inilah yang hendak dimanfaatkan pemerintah. Toh, Undang-Undang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mengizinkan tarif PPN berada di interval 5-15 persen.
Apa pun alasannya, kenaikan tarif PPN yang ditujukan untuk mendongkrak penerimaan pajak bisa menjadi bumerang. Sebagaimana diteorikan oleh Laffer (1974), penerimaan negara akan menurun tatkala tarif efektifnya terlampaui.
Tarif PPN 10 persen sudah mencapai titik optimum. Tarif itu sudah setara dengan margin keuntungan. Karena itu, kenaikan tarif PPN dikhawatirkan akan mengusik kondisi Pareto optimum, ketika sumber daya dalam sistem telah optimal, sehingga satu dimensi tidak dapat meningkat lagi tanpa membuat dimensi lain menjadi buruk. Dalam hal ini, pengusaha, misalnya, harus mengurangi margin keuntungan agar harga jual produk tidak naik terlalu tinggi. Strategi ini jamak dilakukan demi menjaga pangsa pasar.
Namun, jika pengusaha berkukuh mempertahankan margin, pengusaha akan menggeser beban kenaikan tarif PPN pada konsumen dalam bentuk kenaikan harga jual. Imbasnya, harga yang terkena kenaikan tarif akan naik dan efek domino bakal bekerja pada harga komoditas mata rantainya.
Hal ini berujung pada inflasi yang akan terkerek naik. Daya beli masyarakat yang lembek, karena terpapar pandemi Covid-19, kian tertekan. Konsumsi rumah tangga, sebagai kontributor terbesar dalam pembentukan PDB, dengan sendirinya menyusut, sehingga kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi.
Sistem multitarif belum bisa menyelesaikan persoalan. Akar masalahnya berkutat pada pendefinisian barang "pokok" dan barang "mewah". Kegagalan membuat batasan yang tegas akan menurunkan konsumsi keduanya, sehingga kenaikan penerimaan pajak tidak kesampaian.
Argumen bahwa kenaikan tarif PPN ditujukan untuk mengkompensasi pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) badan juga masih bisa diperdebatkan. Tarif PPh badan sudah lebih dulu dipangkas pada tahun lalu, dari 25 persen menjadi 22 persen, dan akan diturunkan lagi menjadi 20 persen pada tahun depan.
Pemotongan tarif PPh badan memang bisa menaikkan penerimaan. Tapi bukti empiris menunjukkan bahwa pemangkasan tarif pajak tidak berkorelasi dengan kepatuhan membayar pajak. Jika kenaikan tarif PPN tidak terkejar oleh pemotongan tarif PPh badan, penerimaan negara, lagi-lagi, bisa mengecil.
Sampai di sini, kenaikan tarif PPN menyisakan sejumlah risiko. Karena itu, kebijakan mengubah tarif pajak pada umumnya dihindari karena berdampak menyimpang pada perekonomian. Untuk itu, dengan ruang gerak yang terbatas, otoritas fiskal dituntut lebih kreatif dalam menyiasatinya. Metode intensifikasi dan ekstensifikasi lain sejatinya masih bisa dilakukan, seperti mengoptimalkan pajak orang super kaya dan menarik pajak warisan.
Optimisme penerimaan pajak APBN 2022 bisa tercapai jika sejak awal disiapkan strategi yang jitu. Ketika semua alternatif ikhtiar belum ditempuh, kenaikan tarif PPN terkesan hanya jalan pintas alias cari gampangnya, seperti berburu di kebun binatang.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo