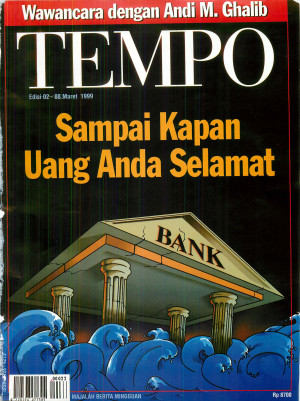Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Thung Ju Lan
Sosiolog, Staf Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Bagi banyak kalangan awam, "masalah Cina" diartikan sebagai masalah "pembauran" yang terkait dengan keberadaan atau masuknya "orang asing" yang bukan bagian dari "kita" ke dalam kelompok "kita". Untuk itu, ukuran hubungan antara "orang asing" itu dan "kita" sudah jelas, yaitu seberapa jauh "orang asing" itu dapat menyesuaikan diri dengan "kita". Tuntutan seperti ini kuat sekali pada kelompok yang "kekitaan"-nya sangat kental dan terpelihara. "Kekitaan" ini tidak hanya terkait dengan masalah etnis, agama, atau kebudayaan, tetapi juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi maupun politis.
Melalui Sumpah Pemuda dan kemudian didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pemimpin bangsa di masa lalu berusaha menciptakan identitas "kekitaan" nasional (Indonesia) yang mengatasi "kekitaan" kelompok-kelompok (etnis, agama, budaya, dan lain-lain). Masalahnya, "kekitaan" nasional ini tidak cukup hanya diciptakan, tetapi perlu dibangun di atas "kekitaan" kelompok agar akhirnya "kekitaan" nasional lebih besar dan kuat daripada "kekitaan" kelompok. Dan, proses ini membutuhkan waktu yang panjang serta perlu dilakukan secara konsisten dan terus-menerus.
Walaupun Pasal 26 UUD 1945 dan penjelasannya mengakui "peranakan" Tionghoa (dan peranakan Belanda serta peranakan Arab) sebagai warga negara yang sejajar dengan penduduk asli, jelas sekali bahwa untuk itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan pertama adalah "disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara" (hal. 12). Dan kedua, "bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia" (hal. 33). Dengan demikian, sejak awal sudah ada pembedaan antara kelompok etnis Cina dan penduduk asli. Sebagai yang bukan bagian dari "kita" (penduduk asli), kelompok etnis Cina hanya bisa menjadi "kita" melalui pemenuhan kedua syarat di atas.
Atas dasar inilah, posisi kelompok etnis Cina dalam proses pembentukan identitas "kekitaan" nasional perlu dibicarakan secara khusus setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Perdebatan tentang dwikewarganegaraan dan perdebatan politis dan ideologis antara kelompok pendukung konsep integrasi (Baperki) dan kelompok pendukung konsep asimilasi (LPKB) mencerminkan hal ini.
Sejak berdirinya pemerintahan Orde Baru, perdebatan tersebut dianggap sudah selesai dan posisi kelompok etnis Cina sebagai "orang asing" yang bukan bagian dari "kita" (penduduk asli) menjadi semakin jelas dengan diterapkannya kebijakan asimilasi. Sejak saat itu, secara legal-politis keberadaan kelompok etnis Cina dilihat atas dasar kedua persyaratan dalam UUD 1945 tersebut, khususnya tentang kewarganegaraan yang disahkan dengan undang-undang, dan kesetiaan kepada negara. Sementara itu, secara sosial-budaya hubungan antara kelompok etnis Cina dengan penduduk asli diukur dengan pertanyaan tunggal: apakah kelompok etnis Cina bisa menyesuaikan diri dengan penduduk asli. Jelas sekali, di sini ada pemisahan secara mental antara kelompok etnis Cina dan penduduk asli yang dikonstruksikan secara legal-politis dan diperkuat secara sosial-budaya. Pemisahan mental yang mendasari hubungan antara kelompok etnis Cina dan penduduk asli inilah yang selanjutnya menimbulkan permasalahan bagi proses penyatuan kelompok etnis Cina sebagai bagian yang integral dari bangsa dan negara Indonesia.
Dimulainya era reformasi dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru, yang terkait dengan tragedi Mei 1998, telah menggarisbawahi permasalahan yang panjang dan berkelanjutan antara kelompok etnis Cina dan penduduk asli. Pendapat yang muncul dari berbagai kalangan akhir-akhir ini tentang perlunya penyelesaian masalah Cina menunjukkan kesadaran bahwa masalah persatuan bangsa tidak bisa dilepaskan dari konflik antara kelompok etnis Cina dan penduduk asli, yang telah berlangsung lama dan tak pernah terselesaikan. Namun permasalahannya bukanlah sekadar menghapuskan peraturan-peraturan yang diskriminatif seperti yang diserukan oleh banyak orang. Ada yang lebih mendasar lagi, yaitu bagaimana mengubah konstruksi pemisahan mental yang sudah ada bahkan sebelum Negara Kesatuan Indonesia didirikan, yaitu sejak awal abad ke-20 ketika arus nasionalisme mulai melanda negeri ini dan membentuk kelompok-kelompok pergerakan nasional yang cenderung berbasis ras, dan mempunyai orientasi politik yang berbeda-beda. Pertanyaannya menjadi: mungkinkah kita mengubah konstruksi pemisahan mental yang dimulai hampir satu abad yang lalu dan sudah disosialisasikan selama hampir seratus tahun itu?
Kebijakan "pembauran" dituangkan dari konstruksi pemisahan mental "asing" versus "asli", yang melandasi hubungan antara kelompok etnis Cina dan penduduk asli sejak sebelum Negara Kesatuan Indonesia didirikan. Inti kebijakan ini adalah bahwa "asing" (kelompok etnis Cina) diharapkan terus menyesuaikan diri untuk pada akhirnya melebur kepada "asli" (penduduk asli atau pribumi). Berangkat dari pemikiran seperti ini, tidaklah mengherankan bila kelompok etnis Cina diharapkan untuk secara aktif membaurkan diri ke dalam masyarakat asli, dan permasalahan atau hambatan terhadap proses pembauran sepenuhnya merupakan tanggung jawab mereka. Seperti yang sering kali kita dengar, adalah kelompok etnis Cina yang tidak mau atau tidak bisa membaur. Mereka cenderung eksklusif dan memisahkan diri dari masyarakat asli. Mereka tidak tulus untuk menjadi bagian dari bangsa "Indonesia" karena mereka ingin mempertahankan tradisi dan segala ciri-ciri kecinaannya, dan seterusnya.
Pandangan seperti ini tidak sepenuhnya diterima di kalangan etnis Cina. Berpulang kepada pengertian sosiologis dari konsep asimilasi, mereka berargumen bahwa "pembauran" merupakan tanggung jawab bersama. Tanpa penerimaan dari pihak masyarakat asli, tidak mungkin bagi kelompok etnis Cina untuk sepenuhnya membaur ke dalam masyarakat asli. Selain itu, juga dikatakan bahwa "pembauran" harus terjadi secara alamiah, tanpa campur tangan atau paksaan dari pemerintah seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui peraturan-peraturannya yang melarang adanya sekolah berbahasa Cina, melarang penerbitan surat kabar berbahasa Cina, membatasi kegiatan keagamaan kelompok etnis Cina, dan sebagainya.
Perdebatan di atas menggambarkan perbedaan pandangan antara kelompok etnis Cina dan masyarakat asli. Ini tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan pandangan di dalam kelompok etnis Cina sendiri, atau di kalangan masyarakat asli, tentang kebijakan "pembauran". Baik kelompok etnis Cina maupun masyarakat asli bukanlah kelompok yang secara sosial, budaya, politis, maupun ekonomis homogen. Kemajemukan di dalam kelompok etnis Cina maupun masyarakat asli inilah yang melatarbelakangi perbedaan pandangan tentang "pembauran" di antara individu-individu atau kelompok-kelompok individu. Kemajemukan tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti tingkat sosial-ekonomi, latar belakang sosial-budaya, serta tingkat perkembangan lingkungan sosial masyarakat tempat yang bersangkutan tinggal.
Di Jakarta, perbedaan pandangan akibat kemajemukan ini lebih tampak jelas dibandingkan dengan di kota kecil seperti Solo. Misalnya, bagi seorang etnis Cina di Tangerang yang bekerja di Jakarta dan mempunyai tingkat sosial-ekonomi yang tidak terlalu tinggi, "pembauran" diartikan sebagai adanya kesamaan nasib dengan mayoritas masyarakat pribumi yang kurang mampu. Sementara itu, bagi seorang pengusaha menengah etnis Cina yang tinggal di pusat kota Jakarta, "pembauran" adalah menjadi tetangga dan warga yang baik di lingkungan tempat tinggalnya. Bagi pengusaha kelas atas etnis Cina yang tinggal di daerah pemukiman elite di pinggiran kota Jakarta, "pembauran" adalah menjadi warga negara yang baik, yaitu dengan mengikuti dan menjalankan program-program pembangunan yang telah digariskan oleh pemerintah.
Selanjutnya, perbedaan latar belakang sosial-budaya dan lingkungan sosial juga amat menentukan penafsiran seseorang tentang "pembauran". Seorang etnis Cina yang dibesarkan dan selalu berada dalam lingkungan komunitas etnis Cina yang "agak tertutup", seperti Glodok misalnya, cenderung menafsirkan "pembauran" sebagai hidup berdampingan secara damai tanpa saling mengganggu. Sementara itu, bagi etnis Cina yang hidup dan bekerja di lingkungan yang "terbuka" seperti di (dekat) Kampus UI di Depok, "pembauran" berarti bisa bergaul dan saling berbagi dengan teman-teman non-Cina. Di lingkungan yang "amat terbuka" seperti di perusahaan-perusahaan asing, etnis Cina yang bekerja di sana menafsirkan "pembauran" sebagai saling menghargai perbedaan dan hak untuk berbeda.
Penafsiran yang berlainan ini juga berlaku di kalangan masyarakat asli yang mempunyai tingkat sosial-ekonomi, latar belakang sosial-budaya, serta lingkungan sosial yang berbeda-beda. Misalnya, warga asli yang tinggal dalam lingkungan yang homogen asli cenderung menuntut warga etnis Cina yang datang untuk menyesuaikan diri dengan aturan dan adat-istiadat setempat. Dengan demikian, "pembauran" diartikan sebagai peleburan diri ke dalam kelompok mayoritas. Bahkan, untuk yang ekstrem, tuntutan ini mencakup usulan untuk kawin campur dan masuk Islam bagi kelompok etnis Cina. Sementara itu, warga asli yang hidup dan bekerja dalam lingkungan yang heterogen lebih bisa menerima perbedaan budaya mereka dengan warga etnis Cina sehingga bisa saling menghormati adat-istiadat masing-masing. Di sini "pembauran" diartikan sebagai adanya rasa toleransi yang besar di antara kelompok-kelompok yang berbeda.
Bertolak dari kenyataan adanya konstruksi pemisahan mental "asing" versus "asli" tadi, tampaknya harapan untuk menyelesaikan permasalahan kelompok etnis Cina saat ini menjadi sangat tipis. Namun, jika kita melihat pula kenyataan bahwa konstruksi tersebut selama ini tetap tidak mampu "menyeragamkan" pandangan berbagai individu atau kelompok individu, kita patut bersikap optimistis. Berangkat dari kenyataan tentang kemajemukan cara pandang, baik di kalangan etnis Cina maupun masyarakat asli, tampaknya ada satu hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menyelesaikan "masalah Cina", yaitu menempatkan permasalahan ini dalam konteks sosial yang berbeda-beda sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Hanya dalam konteks yang berbeda-beda itulah kita baru bisa berusaha mencari jalan keluar yang sesuai dengan konteks masing-masing. Selama kita bertahan untuk melihat permasalahan kelompok etnis Cina sebagai suatu permasalahan antara dua komunitas (Cina dan non-Cina) yang "homogen", kita tidak akan bisa menemukan permasalahan konkret yang ada di setiap unit sosial, sehingga sulit untuk mulai membicarakan solusi yang konkret pula. Jika kita sudah bisa menempatkan permasalahan ini dalam konteksnya, langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan barulah dapat kita diskusikan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo