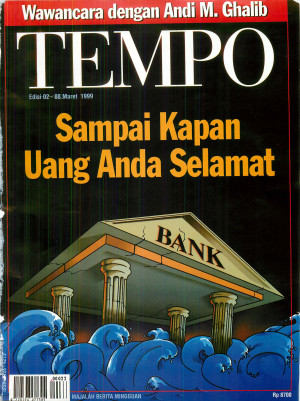Ignas Kleden
Sosiolog, tinggal di Jakarta
BEN Anderson, saat berbicara tentang ''Nasionalisme: Kini dan Esok", atas undangan Majalah TEMPO, pada 4 Maret lalu, dengan bahasa Indonesia yang fasih dan terkadang urakan, mencoba melukiskan ''riwayat hidup" nasionalisme Indonesia, yang disebutnya sebagai sebuah proyek bersama. Proyek ini dengan sendirinya mengandaikan adanya kepercayaan tentang nasib bersama, masa depan bersama, dan suatu kesetiakawanan yang melebar ke luar dan ke samping dalam bentuk solidaritas horizontal.
Tekanan yang diberikan semenjak awal pembicaraan ialah nasionalisme mengandalkan dan mendapatkan kekuatannya, pertama-tama dari hubungan antarorang dan bukannya antardaerah. Ternyata, menurut pengamatannya, adalah ironis bahwa selama Orde Baru, yang disebutnya secara konsisten sebagai Orde Keropos, proyek bersama itu lambat-laun berubah menjadi usaha bersama untuk bagi hasil. Akibatnya, daerah-daerah, dalam arti wilayah teritorial, menjadi jauh lebih penting daripada penduduk yang berada di wilayah tersebut. Yang diperhatikan bukanlah orang Timor Timur, orang Aceh, atau orang Irian, tetapi wilayah mereka. Selama usaha bersama di wilayah tersebut aman dan lancar, pemerintah—pusat dan daerah—akan tenang-tenang saja. Sebaliknya, kalau penduduk setempat mulai sadar tentang haknya dan menuntut otonomi lebih banyak, reaksi kejiwaan yang timbul adalah (mengutip Ben Anderson) ''Ah sayang, mengapa mesti ada orang Timor Timur di Timor Timur, mengapa harus ada orang Aceh di Aceh, dan mengapa masih saja ada orang Irian di Irian Jaya?"
Itu artinya, sementara wilayah-wilayah di daerah dianggap sebagai aset nasional, penduduknya dianggap sebagai liabilities—jika kita boleh meminjam istilah-istilah ekonomi perusahaan. Itu bukanlah istilah-istilah Ben Anderson, tapi tamsil dan ibarat penulis kolom ini. Dalam perbandingan yang lebih tajam, kalau pemerintah kolonial biasa menjalankan strategi ''bagi dan kuasai", pemerintah Orde Baru rupanya sedikit mengubah strategi itu menjadi ''bagi dan miliki".
Seorang yang terlibat dalam proyek bersama, yaitu seorang nasionalis sejati, tidak hanya mengambil keuntungan dari proyek bersama, tetapi seharusnya turut menanggung biaya yang dituntut oleh proyek tersebut. Dia tidak mempunyai alasan apa pun untuk mencuci tangan agar bebas dari berbagai kesalahan dan kebodohan yang mungkin saja tidak dilakukannya sendiri tapi tidak bisa dihindarinya sebagai anggota dari proyek bersama tersebut. Secara konkret, mengambil contoh yang dikemukakan oleh Ben Anderson, seorang nasionalis yang tidak menyesal dan tidak menyatakan penyesalannya terhadap pembunuhan ratusan ribu orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI atau terlibat dengan partai itu, bukanlah seorang nasionalis sejati.
Demikian pula, jika para politisi—atau setiap orang Indonesia yang sadar—bungkam saja terhadap pembunuhan yang terjadi di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya, atau Ambon, pada saat itulah proyek bersama telah dikhianati. Mengharapkan munculnya orang besar pada masa sekarang yang dapat dibandingkan dengan anggota generasi Soekarno-Hatta mungkin berlebihan. Namun, seorang nasionalis sekurang-kurangnya harus berusaha (dan berhasil) untuk tidak menjadi kerdil atau terlalu kerdil. Untuk itu, Ben Anderson melontarkan sebuah slogan yang dikutip dari sebuah bukunya, Long live shame! Hidup Rasa Malu!
Mendengar Ben Anderson adalah mendengar air mengalir: kadang mulus, kadang gemercik, kadang menderu seperti menerjuni jeram, tapi kita tak segera merasa pasti, apakah alirannya akan berpindah ke anak sungai atau masuk ke mulut samudra. Sebagai contoh soal, apakah semboyan long live shame itu adalah sebuah sindiran bahwa rasa malu sudah mati di Indonesia, seperti ucapan the king is dead, long live the king (raja telah mangkat, hiduplah saja raja).
Debat tentang shame culture dan guilt culture, yang dimulai oleh antropolog Ruth Benedict dalam The Chrysanthemum and The Sword, kemudian dianggap sebagai sebuah debat yang semu. Sebab, orang bisa merasa bersalah tanpa rasa malu, tapi hampir tak mungkin membayangkan seseorang merasa malu kalau tidak merasa bersalah (sekalipun rasa malu tidak hanya disebabkan oleh rasa bersalah). Sesal, misalnya, adalah rasa malu terhadap kesalahan yang sudah terjadi. Jadi, apakah kalau kita dapat berkata bahwa rasa malu sudah mati, sekurang-kurangnya rasa malu harus diperpanjang harapan hidupnya. Mungkin lebih beralasan mengatakan bahwa rasa malu dan rasa salah lebih mirip dua saudara kembar. Seseorang yang tidak merasa bersalah karena mencuri juga tidak akan malu kalau ketahuan mencuri dan yang timbul mungkin hanya rasa takut.
Dengan demikian, pertanyaan tentang apakah masih ada rasa bersalah dan malu di Indonesia adalah sebuah pertanyaan mengenai apa dan terhadap siapa orang-orang Indonesia sekarang merasa bersalah dan malu. Apakah orang hanya merasa bersalah, malu terhadap pembesar, dan merasa bersalah terhadap pejabat, tetapi tidak lagi merasa malu dan bersalah terhadap petani atau nelayan, mahasiswa atau buruh pabrik, pembantu rumah tangga, dan para pekerja bangunan?
Sewaktu korupsi mencapai puncaknya di Indonesia pada rezim Orde Baru, seorang birokrat yang jujur sangat mungkin merasa bersalah dan malu kalau tidak ikut makan uang haram. Teman-teman sekantornya akan menuduh dia tidak setia kawan, sulit bekerja sama, sok alim, atau bahkan hipokrit. Atas cara yang sama, anak-anak SMU di Jakarta, misalnya, mungkin akan malu kalau ketahuan temannya bahwa dia sedang giat belajar menghadapi ujian. Kalau temannya bertanya di telepon, ''Lagi ngapain lu, belajar ya?"sekali pun dengan buku pelajaran yang terbuka di meja, dia cenderung menjawab, ''Ah enggaklah, gue cuman lagi nonton tv." Dengan demikian, dalam birokrasi, seorang pejabat atau pegawai harus menanggung malu (dan mungkin rasa bersalah) kalau dia mencoba berlaku dan bertindak bersih, sementara di sekolah para siswa merasa malu (dan mungkin juga bersalah) kalau oleh temannya ketahuan sedang belajar.
Soal untuk Indonesia saat ini barangkali bukan ada-tidaknya rasa malu atau rasa salah atau panjang pendeknya usia rasa malu dan rasa salah (dalam arti pudor longus, vita brevis), tetapi apakah nilai-nilai dasar dalam kehidupan dan pergaulan bersama masih tegak dengan kepala ke atas atau sudah terbalik dengan kaki ke atas. Jangan-jangan yang terjadi adalah pemutarbalikan nilai-nilai dan bersamaan dengan itu juga terjadi penjungkirbalikan rasa malu dan rasa bersalah dengan kepala terhunjam ke tanah.
Dalam arti itulah sebuah konfrontasi dengan masa lampau perlu dilakukan walaupun bukan tanpa rasa getir. Di situ Ben Anderson banyak benarnya. Kalau konfrontasi ini tidak dilakukan, anggota sesama bangsa akan dengan enteng membunuh sesama bangsanya yang lain, pertama karena alasan kontra-revolusi, kemudian dengan alasan PKI, lain kali dengan alasan GPK, dan di masa depan dengan alasan kontra-reformasi atau yang semacamnya. Secara tata bahasa, pengertian tentang anggota bangsa tidak didasarkan pada subyek, tetapi hanya didasarkan pada predikat yang diberikan secara sewenang-wenang.
Persoalan Ben Anderson—yang seyogianya juga menjadi persoalan kita di Indonesia—ialah apakah anggota-anggota bangsa, peserta dalam proyek bersama itu, harus selalu menjadi anak-anak manis yang kemampuan satu-satunya ialah menuruti perintah dan manut terhadap petunjuk? Suatu bangsa yang seperti itu mudah memungut dan kemudian membuang anggotanya. Itu bukanlah bangsa yang kuat sekalipun dana besar dan beribu-ribu jam pelajaran dihabiskan untuk menatar ketahanan nasional wawasan kebangsaan. Bangsa yang tidak sanggup membela anggotanya—baik atau jahat, pahlawan atau pengkhianat—akan kehilangan dua kaki yang menunjangnya berdiri tegak. Ketahanannya akan timpang dan nasionalismenya akan keropos.
Barangkali Ben Anderson perlu menulis satu jilid lagi tentang bangsa dan nasionalisme, setelah terbitnya Imagined Communities, yang mendapat sambutan akademis yang luas, sebagai studi tentang asal-usul dan penyebaran nasionalisme. Yang amat dibutuhkan untuk memahami perubahan dan krisis di Indonesia saat ini adalah penyelidikan yang lebih teliti tentang tingkah laku dan kecenderungan ''makhluk" yang bernama bangsa dan nasionalisme.
Kalau bangsa—menurut buku tersebut di atas—mempunyai wujud yang hanya ada dalam imajinasi dan citra yang dihasilkannya, dengan gaya bahasa Cartesian kita bisa berkata, ''We imagine and therefore it is" (kita membayangkan bahwa bangsa itu ada, maka bangsa itu ada). Namun, alangkah umumnya istilah imajinasi. Lagi pula istilah itu dapat memberi kesan bahwa imajinasi hanyalah tindakan yang semata-mata deskriptif sifatnya. Padahal ada demikian banyak kandungan nilai di dalamnya, baik sentimen komunal, kecenderungan ideologis, maupun pilihan-pilihan normatif.
Dengan kata lain, imajinasi sering menjadi sarana untuk idealisasi dan bahkan sakralisasi bangsa yang melahirkan dua akibat yang berkerabat erat: berhala di satu pihak dan kutukan di pihak lain, semacam konspirasi antara idolatria dan anathema. Akibat konkretnya ialah mereka yang sejalan dengan pilihan nilai kita dengan mudah menjadi pahlawan atau orang suci dan yang berlainan atau bertentangan diapkir sebagai penjahat, pengkhianat, atau pendosa.
Demikian pula dengan sebutan komunitas memberi harapan bahwa imajinasi itu cenderung mempersatukan, meskipun yang lebih sering muncul adalah sekte-sekte politik yang saling membacok, bukan untuk merebut harta atau tanah, tetapi untuk memaksakan apa yang dibayangkan sebagai kebenaran. Yang terjadi di sana adalah kebalikan dari teori Ben Anderson: kita membayangkan bahwa bangsa itu ada, maka bangsa itu hilang lenyap.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini