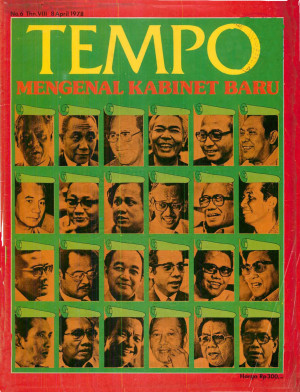CHAO Meng-fu hidup di Negeri Cina di abad ke-13. Para penulis
kemudian mengecamnya sebagai seorang cendekiawan yang salah. Di
abad ini mungkin ia akan didamprat sebagai pengkhianat, "pelacur
intelektuil".
Riwayatnya jelas. Ia mengabdi kepada kekuasaan Mongol yang
memerintah Cina di abad itu. Orang pribumi Cina tak menyukai
kekuasaan ini: bukan saja karena asing, tapi juga karena bangsa
pengembara yang datang sebagai penakluk itu hanya maju di bidang
militer, tapi mentah dalam kebudayaan. Betapapun besarnya kuasa
Kubilai Khan dan para penggantinya, mereka sukar menimbulkan
rasa hormat kalangan cerdik pandai Cina.
Chao Meng-fu sendiri--sarjana, seniman, penyair dan ahli
kaligrafi--agaknya sadar akan kemungkinan bahwa ia telah, atau
akan, dipandang membudak kepada kekuasaan. Menarik, bahwa dalam
sebuah sajaknya ia memuji T'ao Yuan-ming. Tokoh ini termashur
karena mengundurkan diri dari jabatan tinggi dan menolak bekerja
buat dinasti baru:
Ia ikuti jalannya yang luhur, agung bak pohon pina yang rimbun.
Ia ba-gaikan kembang krisan, yang disen-tuh salju tapi tetap
berkilau. Ia siap serahkan jabatan, lalu ia menanggung miskin,
tapi terangguk puas dekat jendela.
Tapi itu tak berarti bahwa Chao hendak memujikan sikap T'ao
Yuanming sebagai satu-satunya pilihan. Dalam sajaknya itu
sekaligus ia menyatakan bahwa tiap orang harus mengambil jalan
menurut situasinya masing-masing: "Apakah seseorang akan tampil
dan mengabdi, atau undur menyisihkan diri, itu bukanlah
keputusan yang kebetulan."
Untunglah, meskipun waktu orang Mongol datang menaklukkan Cina,
Chao sendiri sudah berusia 20-an tahun, baru 10 tahun kemudian
ia mau terima jabatan dalam kerajaan. Kubilai Khan yang sudah
tua memang tertarik akan kecakapannya. Dan Chao terbukti
kemudian menghasilkan hal-hal yang sangat berharga di masa
itu--satu prestasi yang agaknya menolongnya dari kutukan sebagai
si "lapar posisi" di kelak kemudian hari. Tentu saja harus
dicatat bahwa meskipun ia tak dianggap sebagai si culas yang
berambisi, ia juga bukan tauladan utama bagi para penulis Cina.
Untuk tauladan, mereka mungkin lebih tertarik akan figur lain:
Cheng Ssu-hsiao.
Cheng adalah tokoh yang setia kepada dinasti Sung. Dengan benci
ia memandang kekuasaan Mongol yang muncul kemudian. Pada dirinya
tertanam ajaran untuk berpegang pada kesetiaan yang tak berubah
menurut waktu. "Aku dengar ayahku berkata," demikian tulis
Cheng, "hidup atau mati adalah soal sepele, tapi sikap abadi
dalam moral adalah soal besar." Moral yang pokok baginya ialah
bahwa "pengabdian seorang penguasa lebih baik mati daripada
harus mengabdi penguasa lain. Tak heran bila ia mengejek orang
sebangsanya yang bekerja untuk penguasa yang sedang ,naik itu.
Aneh juga bahwa cendekiawan macam Cheng dibiarkan saja oleh
penguasa. Seorang ahli Sinologi, Frederick W. Mote, dalam
sumbangannya untuk buku The Confucian Persuasion (editor: Arthur
F. Wright, Standford University Press, 1960) menduga bahwa itu
antara lain karena Cheng tak dianggap sebagai ancaman. Ia bukan
pemimpin pasukan bersenjata, ucapannya pun kurang-lebih hanya di
lingkungan terbatas. Dan si raja yakin akan kekuatannya sendiri.
Sementara itu penguasa Mongol bukannya tanpa sikap bijaksana.
Kaisar Kubilai Khan, misalnya, menunjukkan itu dalam kasus Liu
Yin. Cendekiawan ini ditawari pelbagai posisi terhormat, antara
lain dalam Akademi Konfusian. Tapi Liu Yin menolak. Waktu
mendengar ini Kaisar mengatakan: "Di zaman dulu orang mengenal
'para pengabdi yang tak dapat dipanggil menghadap'. Mereka
tentulah seperti orang ini!."
Agaknya Kubilai Khan dengan arif teringat akan ucapan Mencius: "
.... seorang raja yang akan merampungkan tindakan besar pasti
akan memiliki menteri-menteri yang tak dapat dipanggilnya
menghadap. Bila ia ingin mendapat nasihat, dialah yang datang
pada mereka " Mencius dengan itu membentuk satu ideal tentang
cendekiawan yang independen, yang punya harga diri, kepandaian
dan kebajikan, dan menilai pengabdiannya tak lebih rendah
bahkan dari raja sendiri.
Hebat juga bahwa Kubilai Khan tidak menolak itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini