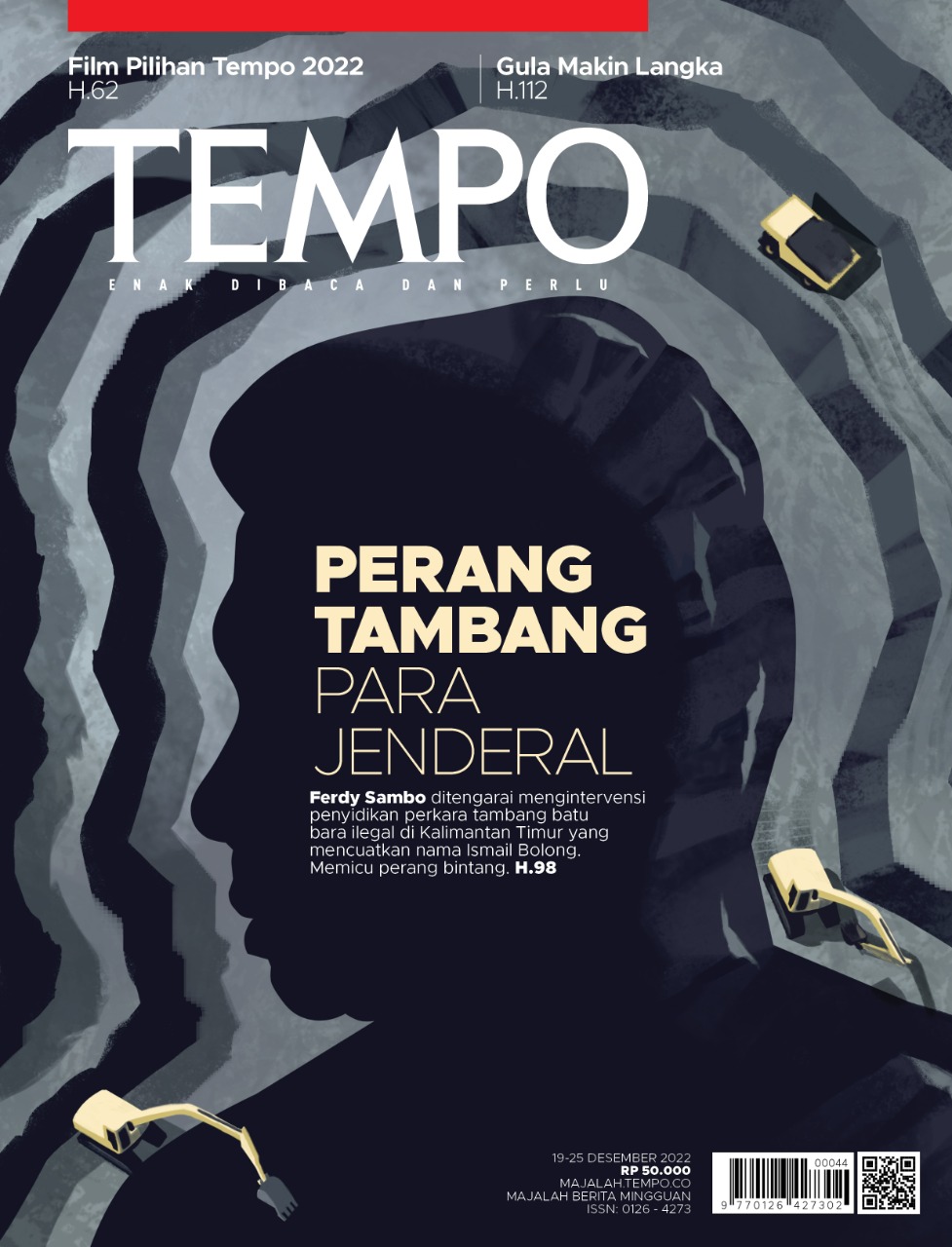Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan untuk membatasi kritik. Alasan pemerintah membuat pasal ini, menurut Menteri Yasonna, adalah setiap orang memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya. Dalam pikiran Yasonna, pasal ini menjadi penegas batas bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beradab.
Dengan melihat alasan-alasan Menteri Yasonna Laoly, yang menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan Rancangan KUHP dengan Dewan Perwakilan Rakyat, “keadaban” memiliki tiga dimensi: menyangkut kehormatan seseorang atau pejabat, bisa dicapai dengan aturan atau hukum, serta ciri masyarakat sebagai suatu totalitas dengan ukuran dan standar yang terumuskan dalam hukum tersebut.
Dimensi pertama mengandung konsekuensi bahwa makin tinggi keadaban makin perlu hukum melindungi posisi itu. Di titik ini kita melihat kekeliruan sekaligus konservatisme yang lazim di kalangan para autokrat. Benarkah keadaban identik dengan hukum? Dalam negara yang menjunjung kedaulatan rakyat, perlukah penguasa dilindungi “keadabannya”?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Keadaban publik” adalah terjemahan bahasa Indonesia untuk public civility. Terjemahan ini kadang memberi pengertian yang melenceng karena dua faktor. Pertama, istilah civility tumbuh dan berkembang serta dihayati dalam tradisi spasial budaya politik kewargaan (citizenship) Eropa. Begitu juga dengan istilah public yang berakar dalam tradisi humanisme klasik. Keduanya acap sulit dicari padanan persisnya dalam konsepsi politik di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Civility memiliki akar kata yang sama dengan “city”, “citizen”, dan “civics”, yakni istilah Latin “civilis” atau “civilitas” yang berarti “citizens”. Bahasa Indonesia hanya menyediakan kata “warga” untuk padanan ini. Dalam penggunaan awalnya, “civilis” adalah konsep untuk menunjukkan “a state of being citizen” atau public life. Sementara itu, citizenship atau kewargaan dalam konteks Eropa selalu mengandaikan dimensi spasial, yakni kota. Civility, dengan begitu, selalu terkait dengan “a state of being citizen” dalam konteks sebagai penduduk sebuah komunitas politik, yakni kota.
Kedua, istilah public bisa kita lihat dari asal-usul Latin, yakni “populus” yang berarti “rakyat” atau orang banyak. Ia memiliki akar kata yang sama dengan pubes (orang dewasa). Dalam tradisi kekaisaran Romawi istilah ini berkembang menjadi “res publica” yang berakar dari kata “republic”. Dalam arti umum, res publica merujuk pada “public affairs” atau sistem umum pemerintahan. Menurut filsuf Jerman Hannah Arendt (1906-1975), “res publica” dalam bahasa Yunani adalah “politea” atau “polis”. Dengan rujukan ini, Arendt meletakkan konsepsi publik dalam konteks politik kewargaan.
Pengertian civility klasik sebagai “a state of being citizen” dalam konteks spasial memiliki kedekatan dengan istilah “adab” yang diambil dari bahasa Arab. Kedekatan ini bisa kita lihat setidaknya dari tafsir para tokoh dan intelektual muslim Indonesia seperti Profesor Azyumardi Azra dan Profesor Haedar Nashir.
Profesor Haedar mengartikan “keadaban publik” dengan menunjuk ciri-ciri sosiologisnya: masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang menjunjung nilai-nilai sopan santun, gotong-royong, dan kebiasaan berbuat baik kepada tetangga. Ciri-ciri sosiologis ini sesungguhnya tampilan etika keadaban publik yang baik, moderat, dan toleran.
Untuk mengembangkan keadaban publik seperti itu, Profesor Haedar mengajukan empat cara: membangun masyarakat ilmu, memperkuat dunia pendidikan, memperkokoh institusi keluarga, dan menciptakan ruang sosial yang lebih luas untuk kaum moderat. Sementara itu, Profesor Azyumardi menuliskan, “Krisis keadaban publik (public civility) masih melanda berbagai aspek kehidupan bangsa-negara dalam bidang politik, hukum, sosial-budaya, ekonomi serta keuangan, bahkan agama”.
Pernyataan ini menunjukkan Azyumardi memisahkan keadaban publik dari agama. Atau setidaknya keadaban publik tidak pertama-tama atau mesti berkaitan dengan agama. Dengan begitu, keadaban publik menjadi “nilai” lain di luar nilai agama yang bisa bermanfaat memperkuat nilai-nilai baik.
Karena itu, Profesor Azyumardi menyarankan pentingnya integrasi keadaban publik dalam praktik keagamaan. Dengan sedikit membandingkan makna generik public civility, kita mendapatkan pemahaman bahwa keadaban publik merentang dari level individual (sebagai kesopanan) hingga level sosial. Azyumardi dan Haedar, selain menempatkan keadaban publik sebagai bagian dari etika personal dan publik sekaligus, mereka berhati-hati dengan tidak menempatkannya sebagai hukum. Keduanya memaknai keadaban publik sebagai rentang tindakan “sopan santun” yang mengarah pada kepedulian terhadap kepentingan umum (public mindedness).
Richard Sennett, sosiolog London School of Economics, Inggris, berupaya menafsirkan keadaban publik sebagai “yang pantas di ruang publik”. Uniknya, publik dalam kacamata Sennett berbeda dengan pengertian konvensionalnya di Indonesia. Menurutnya, keadaban adalah “it is the activity which protects people from each other and yet allows them to enjoy each other’s company. Wearing a mask is the essence of civility. Masks permit pure sociability, detached from the circumstances of power, malaise, and private feeling of those who wear them”. Di sini keadaban terasosiasi dengan aktivitas yang melindungi masyarakat tapi memungkinkan mereka menikmati kebersamaan dan bertindak bersama sebagai “warga” dalam urusan politik dan sosial kota.
Dalam masyarakat dengan kehidupan demokrasi yang dinamis, keadaban publik penting sebagai basis perjumpaan kewargaan. Dasar keadaban adalah hak berbicara dengan orang asing tanpa dibebani tetek-bengek kengerian kehidupan batin dan personal Anda sendiri. Di saat yang sama, keadaban publik mensyaratkan konvensi “topeng kesopanan”. Dengan kata lain, syarat keadaban adalah pluralisme kehidupan yang membiarkan tiap orang menampilkan aneka gagasan, kostum, termasuk diri yang asing sekalipun. Karena itu, keadaban tidak bisa dibatasi oleh mistar hukum. Sebab, hukum bisa membunuh keadaban.
Ketidakadaban terjadi manakala seseorang tidak mampu membedakan fungsinya di ruang publik privat. Di negara demokratis, penguasa adalah pejabat publik. Dengan begitu, mereka semestinya memahami bahwa kritik, ejekan, bahkan cemooh adalah konsekuensi. Ia tidak boleh menerima dan mencampuradukannya sebagai serangan personal. Dalam pandangan Sennett, personalisasi politik adalah pelanggaran terhadap keadaban publik.
Sennett mendeteksi sejarah kemerosotan keadaban publik adalah menguatnya nilai-nilai familialisme, hubungan kekeluargaan dan invasi keintiman yang menerpa ruang publik. Di abad ke-19 di Eropa keluarga diposisikan sebagai kantong ideal dengan nilai moral yang dibikin seakan-akan lebih tinggi daripada ranah publik. Keluarga borjuis dianggap sebagai kehidupan yang tertib dan otoritas tidak tertandingi. Keamanan serta kekayaan material dianggap sebagai pendamping cinta perkawinan yang nyata.
Nilai-nilai dan relasi keluarga akhirnya menjadi penggaris moral dalam mengukur ranah publik. Dengan begitu, domain publik tak lagi menjadi rangkaian hubungan sosial yang utama, sebaliknya, inferior secara moral. Keintiman privat pun merajalela dan merusak ruang publik. Dengan kata lain, menurut Sennett, ketidakadaban terjadi justru ketika hal-hal privat merembes bahkan menabrak dan menginvasi ranah publik. Ideal-ideal dalam keluarga menjadi ideal-ideal kepublikan, kepentingan keluarga dititipkan ke dalam hal-hal publik.
Menurut Sennet, begitu orang beralih fokus pada kehidupan pribadi dan diri sendiri, saat itu pula mereka mengambil pendekatan politik yang pasif bahkan koruptif. Alih-alih peduli akan urusan negara, tiap orang berfokus pada kepentingan pribadi. Alih-alih meneliti kinerja perwakilan politik, kebijakan, dan peran publik, mereka berorientasi pada apa yang “nyata”, yakni kepentingan pribadi dan keluarganya.
Republik atau yang publik sebagai prinsip politik di Indonesia pun kini makin dirongrong oleh invasi keintiman dan familialitas. Media kita dipenuhi curahan hati selebritas yang mengeluhkan urusan rumah tangga hingga seksualitas. Para pendukung poligami bahkan memamerkan istri-istri mereka di media sosial. Di saat yang sama, dinasti politik dan keluarga-keluarga penguasa mengambil alih demokrasi kita di tingkat lokal hingga nasional.
Indonesia butuh keadaban publik, bukan pidana politik obsesi penguasa.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo