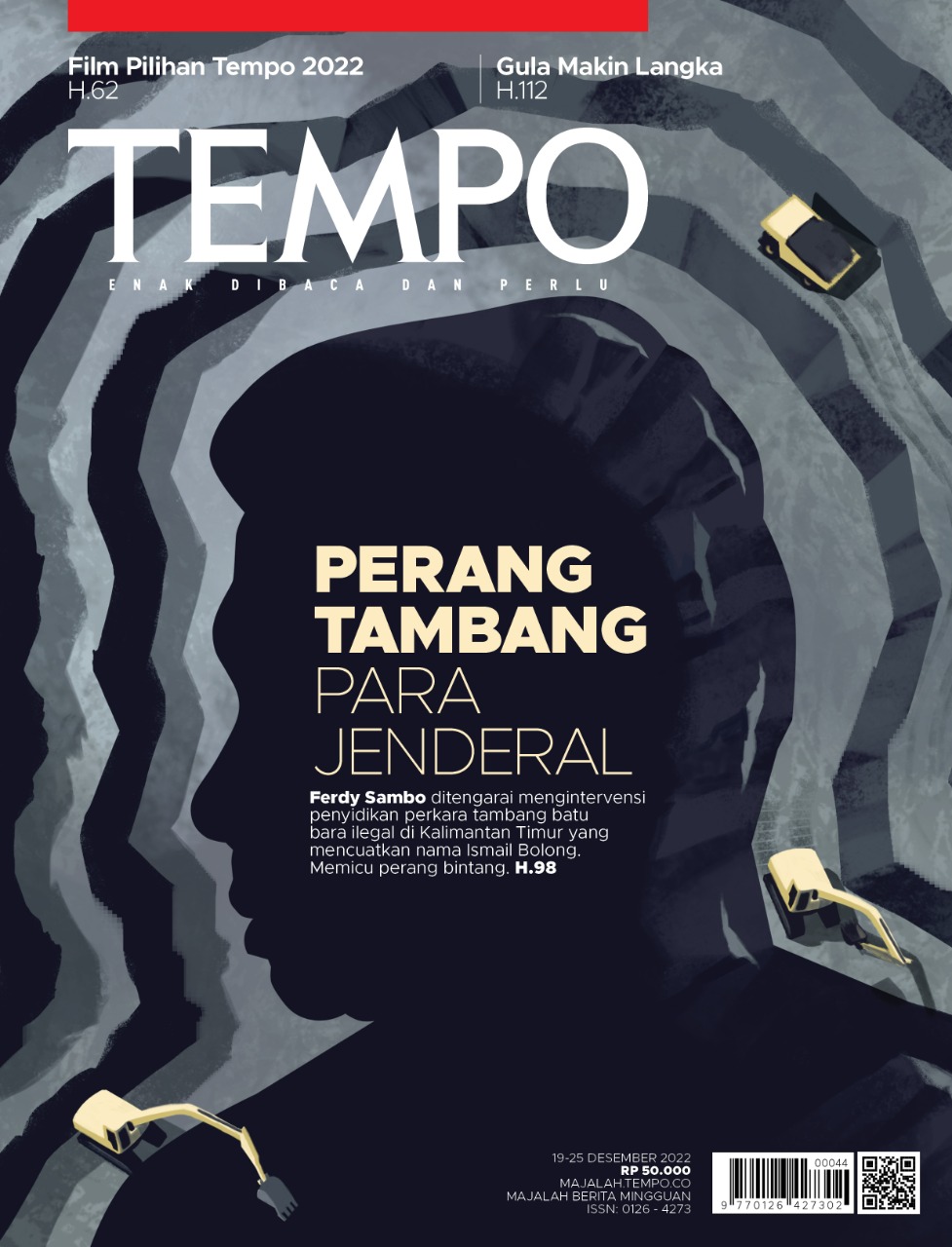Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
ADA sebuah tim sepak bola yang tak terkenal, dengan penjaga gawang yang 30 tahun kemudian termasyhur ke seluruh dunia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ini cerita dari kota Algiers di tahun 1920-an, ketika Aljazair masih di bawah kekuasaan kolonial Prancis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tim itu lazim disebut RUA, singkatan dari “Universitaire Racing Algérois”. Pada 1928, penjaga gawangnya seorang mahasiswa bertubuh kecil, yatim yang datang dari keluarga miskin. Ia dipanggil ‘Bébert’. Nama sebenarnya Albert Camus. Lebih seperempat abad kemudian, ia menerima Hadiah Nobel untuk kesusastraan. Karyanya diterjemahkan ke pelbagai bahasa di dunia.
Dalam biografinya yang ditulis Herbert Lottman, Camus, sebagai kiper, dikatakan bermain dengan bagus dan berani. “Ia sering luka karena melontarkan diri ke kaki lawan di lapangan yang keras”. Seorang temannya ingat, suatu hari, di stadium Algiers, bola lawan yang ditembakkan membentur dada Albert. Ia jatuh pingsan.
Peristiwa itu agaknya terjadi setelah 1930, ketika mulai diketahui TBC menyerang paru-parunya. Ketika suatu ketika ia ikut bertanding di lapangan bola dekat pekuburan kota, ada yang bilang, ada jalan langsung antara kedua tempat itu.
Tapi bukan keberanian yang diperoleh Camus dari sepak bola, seraya berdiri sepi di tengah dua tiang. Ia anggota kesebelasan, dengan warna kostum berbeda, yang hanya diperhatikan orang di saat gawat. Ia hampir tak pernah dapat bola dari teman. Tapi di tubuhnya yang sendirian, kalah dan menang ditentukan. Ia bisa gugup dan gentar, tapi itu bagian dari beban yang tak bisa dialihkannya ke teman seregu. Ia harus berdamai dengan kecemasannya, harus siap menerima kemungkinan yang terburuk: tendangan lawan yang sukses. Seperti dikatakannya kemudian, dalam posisi itu ia “langsung belajar bahwa bola tak pernah datang dari arah yang kita harapkan”.
Pelajaran itu berguna, ketika di umur 37 ia pindah ke Paris, bergaul, bersaing, dan bermusuhan dengan para intelektual di kota itu. Di sana, katanya, “tak seorang pun bermain lurus”.
Seorang penjaga gawang tampak soliter, tapi sepakbola juga membuat Albert terbiasa dengan solidaritas. Para anggota kesebelasan biasa berbagi kegembiraan dalam kemenangan, juga dalam rasa capek, dan mereka juga bisa merasakan “rangsangan yang tolol untuk menangis di malam setelah kami kalah”.
Camus, yang diajarkan olah raga adalah moralitas dan “tugas manusia”. “Saya berutang kepada sport, dan saya belajar itu dalam RUA”.
Terlalu romantis, tentu saja. Camus, si penjaga gawang kesebelasan kampus, tak pernah mengalami jalan gemerlap—tapi dengan lobang-lobang gelap—yang ditempuh para pemain profesional hari ini. Dunia sepak bola berubah sejak awal 1990-an.
Camus, pengagum kebudayaan Yunani Kuno, mungkin hanya meneruskan cerita tentang para atlit 2.700 tahun yang lalu—yang bertanding di arena Olympiade dengan telanjang bulat. Bugil, berotot, berkeringat, adalah bagian acara akbar kompetisi itu. Konon kata gymanstics dan gymnasium berasal dari gymnos, ajektif yang berarti “tipis busana”. Semua bersahaja. Hadiah seorang juara juga hanya seuntai ranting Laurus nobilis yang diletakkan di kepala.
Ada tanda keikhlasan—dan sikap tanpa pamrih material—dalam hadiah itu.
Tapi kita tahu, itu zaman ketika uang belum menang. Kini para penggemar bola, yang melihat dari pesawat TV yang jauh, tak lagi tergetar akan moralitas yang diekspresikan sport. Kini kita kagum melihat Ronaldo membuat hattrick—dan kemudian membaca angka €15 juta buat harga transfernya. Tak ada ranting Laurus nobilis.
Harga dan jual beli muncul di tiap fase. Dan menanjak, dan makin penting. Jika pada 1993 upah rata-rata pemain profesional Premier League di Inggris sekitar £2.000, pada 2010 seorang pemain bisa beroleh kira-kira £34.000 per minggu. Bakat cemerlang pun datang dari mana-mana—juga dari Aljazair, tapi dalam sosok yang belum pernah dilihat Camus.
Sepak bola adalah globalisasi modal dan internasionalisasi teamwork. Batas kebangsaan, kewarganegaraan, dan agama tak lagi relevan. Uang adalah pembaharu yang makin sering menggeser nilai-nilai yang semula diluhurkan.
Kabur juga apa arti “harkat” dan “perdagangan manusia”—sebagaimana kaburnya batasan “proletar”. Dulu, pada 1930, kelas pekerja digambarkan dengan memelas dan kocak oleh Charlie Chaplin dalam film Modern Times. Kini ke kelas manakah akan tergolong Messi, Ronaldo, dan Kylian Mbappé?
Majalah Forbes menghitung, superstar kesebelasan Prancis ini, dalam usia 23 tahun, akan berpenghasilan US$ 128 juta setahun sebelum dipotong pajak dan pembayaran agen. Bukan pemilik modal, ia praktis menjual hasil keringat semata. Mbappé dan Messi bisa mengklaim mereka bagian dari “kelas pekerja”—meskipun harta dan gaya hidup mereka setara para superkapitalis. Melihat mereka, kaum Marxis (dengan ide dari abad ke-19) akan bingung untuk merumuskan pembagian kelas masyarakat.
Walhasil gawang Marxisme jebol, kapitalisme masuk. Tapi juga guyah sisi manusia yang lain. Dalam Le Mythe de Sisyphe, sang kiper RUA menulis, orang kini habis-habisan meraih uang agar berbahagia. Uang sarana, bahagia tujuan. Tapi akhirnya “kebahagian pun dilupakan; sarana telah mengambil alih tujuan.”
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo