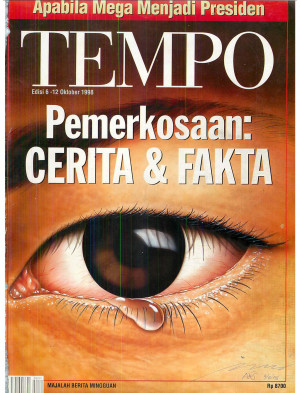Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tidak diketahui, apakah orang banyak senang waktu itu. Novel itu sebenarnya tidak hendak menghibur. Ia lebih berupa sebuah propaganda Partai Komunis Indonesia ketimbang sebuah cerita yang mengasyikkan. Pidato, statemen, dialog-dialog yang sudah bisa diduga sebelumnya, merupakan bagian penting tubuhnya. Ditulis dengan bahasa Melayu yang kikuk, novel ini barangkali memang tak mempunyai ambisi yang lain. Kesusastraan tidak lebih dan tidak kurang, dalam tahap itu, sebuah proyek politik. Tetapi yang menarik ialah bahwa Hikajat Kadiroen, sebuah buku tentang seorang anak muda yang kemudian terpikat oleh komunisme, menunjukkan sesuatu yang agak aneh tentang nasib sebuah kisah.
Semaoen lebih merupakan seorang aktivis Sarekat Islam kiri ketimbang seorang sastrawan. Menjelang menulis novel itu, ia dipenjarakan selama empat bulan karena koran tempat dia bekerja, Sinar Hindia, memuat sebuah tulisan tokoh sosialis H.J.F.M. Sneevliet, Kelaparan dan Pertunjukan Kuasa. Novel yang menyebut diri dengan kata benda kuno ("hikayat") itu adalah kisah tentang seorang anak muda yang hendak menjadi asisten residen tetapi kemudian terpikat oleh ide-ide komunis, sebagai seorang "satria"--suatu kombinasi antara yang "baru" (ide-ide komunis) dan yang "lama". Ceritanya sarat dengan cita-cita untuk membebaskan diri dari adat priayi dan kolonialisme--tetapi pada akhirnya kita tidak menemukan perjuangan kelas. Tidak ada pula kritik kepada Belanda sebagai sosok kolonialisme. Seorang asisten residen bahkan digambarkan sebagai "seorang manusia (yang) tjinta kepada rajat Boemipoetera". Yang lebih menakjubkan bagi kita--yang tidak hidup di zaman itu--ialah pernyataan novel ini bahwa Partai Komunis Indonesia lahir sebagai "kodrat Allah". Mungkin sebab itu Hikajat Kadiroen tidak menjadi buku yang dilarang di masa yang menakutkan revolusi itu. Ia menjadi salah satu buku di antara sederet buku lain, yang rutin, seakan-akan sosok tanpa panggung.
Barangkali sebuah kisah akhirnya memang cenderung mengembangkan dirinya sendiri. Ia lari keluar dari rencana awal sang pengarang. Ide atau ideologi, niat atau program, mungkin ibarat sebuah titah, sebuah Sabda. Tetapi titah itu pada akhirnya menemukan sebuah hidup di perjalanan, yang tikungan dan tebingnya tidak terduga-duga. Seakan-akan novel itu bisa merupakan kiasan sendiri bagi sejarah manusia dalam politik. Juga di Indonesia.
Tetapi apa sebenarnya politik? Ada yang mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan "perjuangan" seorang "satria". Kisah Kadiroen menunjukkan sebuah dongeng moral seperti itu ketika kolonialisme mencekik. Tapi ada juga yang bisa menunjukkan bahwa politik pada hakikatnya menyangkut soal sepele, misalnya botol bekas.
Pada suatu hari di tahun 1970, seorang penyair Amerika datang ke Indonesia dan ia memberi ceramah yang mengecewakan. Ia berbicara tentang hubungan seorang penulis dan politik, tapi yang dibacakannya adalah sebuah esai pendek tentang pengalamannya dengan botol bekas. Jangan salah paham. Sang penyair datang dari sebuah kota kecil di California. Di kota itu hanya ada 15 ribu penduduk, dan pada suatu waktu ia menjadi anggota parlemen lokal. Ia mencalonkan diri, berkampanye, dan menang karena ia punya program yang menarik tentang bagaimana mengumpulkan kembali botol bekas yang dibuang setelah orang minum-minum di taman tiap akhir pekan.
Ceramahnya sebetulnya lucu dan cerdas, segar dan setengah mencemooh diri sendiri, tetapi para pendengarnya di Indonesia bersungut-sungut dan bertanya: kok ini politik? Bukankah "politik", di Indonesia, hampir sama dengan pekerjaan membuat Sejarah (dengan "S") dan mengubah Dunia (dengan "D")? Dengan kata lain, sesuatu yang serius, ramai, panas--sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan dengan konsekuensi berat?
Mungkin sebab itu pengertian Mao--yang datang dari sebuah negeri yang sama-sama gawat--agak cocok dengan konteks kita ketika ia mengatakan bahwa politik adalah perang tanpa pertumpahan darah. Meskipun tak seluruhnya benar, tentu. Darah bisa juga tumpah. Indonesia punya sejarah yang panjang tentang "politik" sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan orang dibuang atau dipenjarakan, diculik dan dibunuh. Dengan kata lain, "politik" adalah drama. Dalam drama seperti itu mau tak mau ada yang terbaca sebagai pahlawan, ada yang terlihat sebagai korban, ada yang tampak pengecut dan terdengar berkhianat. Dari segi pandang ini, "politik" menjadi sesuatu yang bertaut dengan narasi besar, skenario agung, bukan botol bekas.
Tetapi barangkali tak akan seterusnya. Suatu hari nanti, Indonesia akan masuk ke dalam sebuah zaman ketika politik kehilangan drama, dan skenario besar apa pun akan menjadi sebuah Sabda--dari para perumus ideologi--yang tak akan mampu menciptakan perjalanan yang mutlak dan lempang. Dalam keadaan Sabda mati, proses politik mau tak mau akan menjadi rutin. Yang penting akan bukan lagi sejumlah pemberani, melainkan orang-orang yang sabar. Yang akan mengambil peran di sana bukan lagi pekik pertempuran, melainkan perundingan. Tawar-menawar akan menjadi galib dan orang akan mulai melihat kebajikan dari kompromi. Tidak ada lagi suasana yang dibentuk oleh krisis, tidak ada lagi suasana darurat sehingga tentara menjadi merasa wajib untuk masuk ke dalam arena, dengan bedil mereka.
Memang proses itu akan jadi hambar, seperti sekadar mengurus botol bekas. Tetapi adakah ia akan kehilangan maknanya? Mungkin tidak. Bagaimanapun, inilah sebuah kesibukan yang terpaut dengan kehendak untuk memelihara kehidupan dalam suatu lingkup kebersamaan, dalam suatu "polis". Di situ akan selalu bisa lahir "satria", yang dalam Hikajat Kadiroen disebut--dengan kalimat yang agak membingungkan--sebagai orang yang "melepaskan semoea keperloeannja (untuk) orang banjak". Meskipun tanpa panggung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo