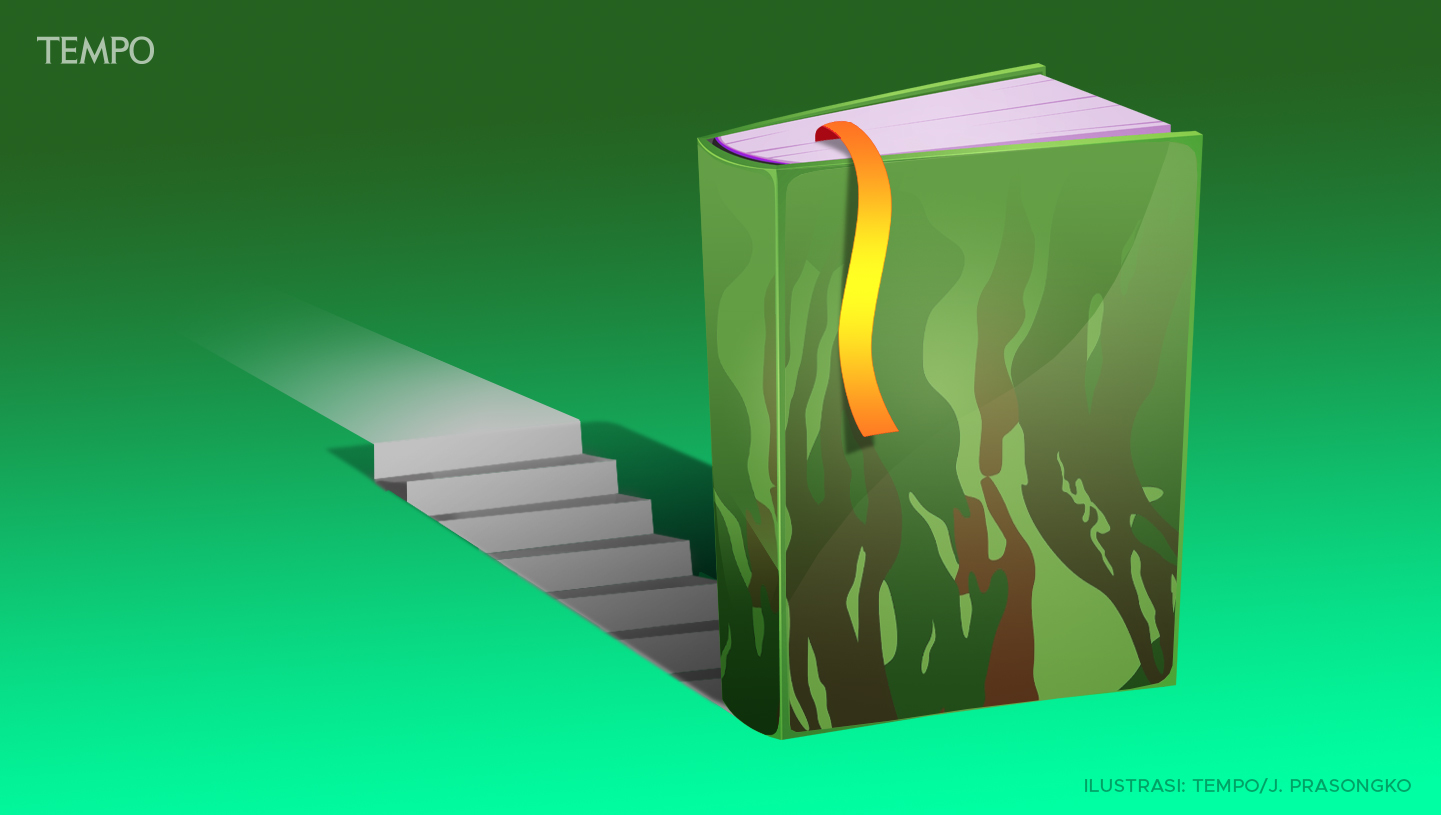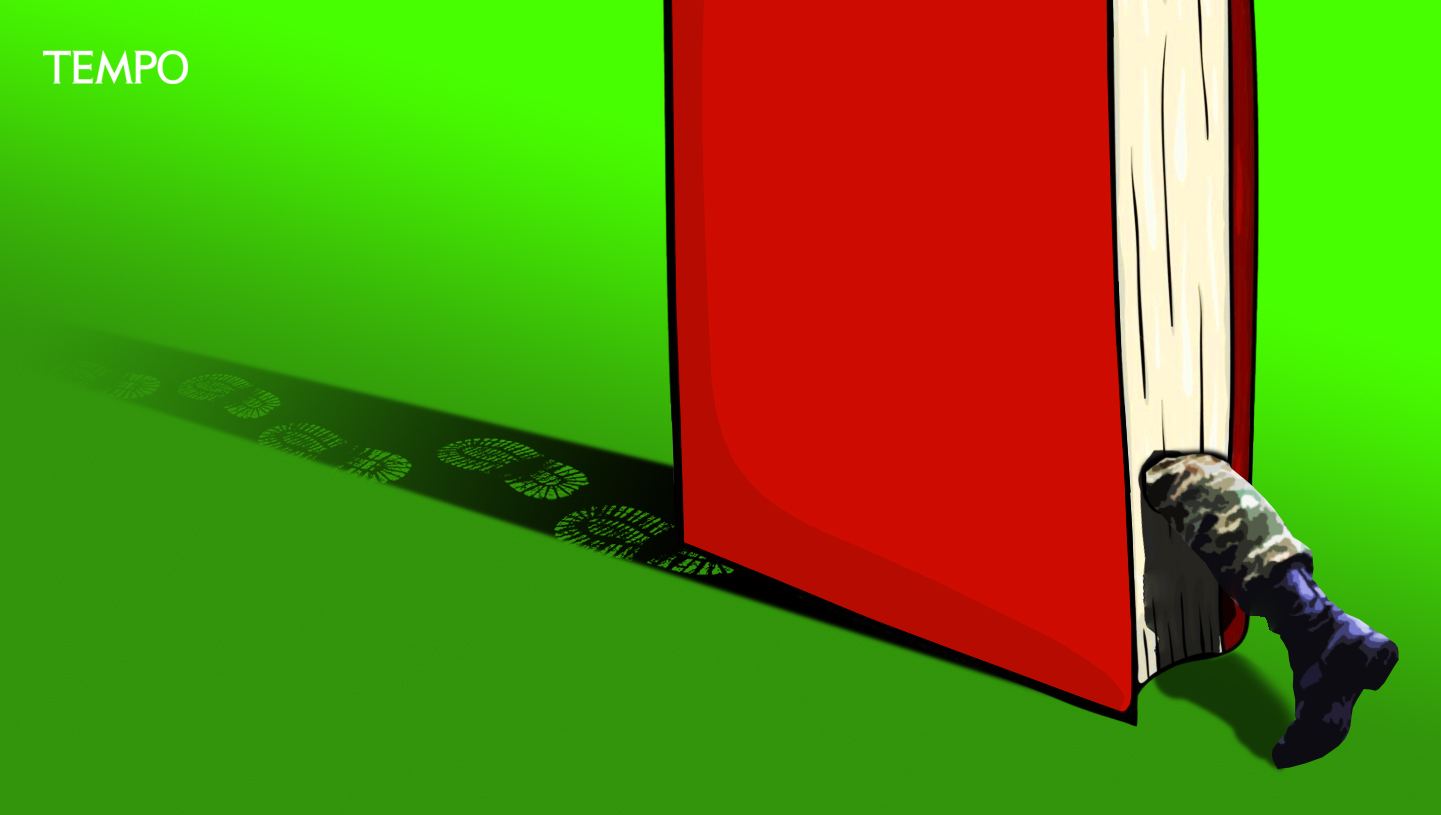Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Miko Ginting
Pengajar hukum pidana STH Indonesia Jentera
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara bukan sekadar bentuk kepatuhan administratif. Pelaporan harta kekayaan sering dikenal sebagai assets disclosure atau wealth reporting adalah instrumen pemberian integritas dan kepercayaan terhadap jabatan publik sekaligus instrumen deteksi potensi kejahatan korupsi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam tataran regulasi, pelaporan itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di situ dinyatakan bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Ketentuan itu sejalan dengan kewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Aturan itu kemudian diturunkan dalam beberapa instrumen hukum lain. Selain itu, kewenangan menerima pelaporan diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut hukum, kewajiban pelaporan harta itu melekat pada jabatan-jabatan penyelenggara negara tertentu. Jadi, pelaporan itu merupakan konsekuensi ketika seseorang menduduki jabatan tersebut.
Konsekuensinya, tidak semua pejabat wajib melaporkan harta kekayaan. Tapi, dalam beberapa peraturan internal kementerian/lembaga/instansi, subyek yang wajib melaporkan harta diperluas sampai jabatan yang tidak disebut dalam undang-undang.
Idealnya, tujuan pelaporan harta ini tidak sebatas mekanisme birokratis administratif. Pengungkapan harta itu setidaknya memiliki empat tujuan. Pertama, pelaporan itu merupakan bentuk pemberian kepercayaan terhadap integritas suatu jabatan penyelenggara negara. Kedua, pelaporan itu merupakan instrumen untuk mendeteksi dan menghindari situasi benturan kepentingan yang potensial atau dimiliki penyelenggara negara. Ketiga, pelaporan itu menjadi alat untuk mendeteksi penambahan kekayaan yang ilegal. Keempat, pelaporan itu menjadi basis untuk memulai penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana.
Namun fakta yang muncul ternyata tidak sejalan dengan gambaran ideal terkait dengan kepatuhan dalam pelaporan harta kekayaan. Sampai dengan Desember 2018, KPK mencatat hanya 63,34 persen penyelenggara negara yang menyerahkan laporan harta kekayaannya. Total penyelenggara negara yang seharusnya menyerahkan laporan adalah 304.646 orang.
Dari sektor eksekutif, KPK telah menerima 65,58 persen dari 238.482 pejabat. Dari sektor legislatif, pelaporan harta kekayaan baru mencapai 24,62 persen dari 18.224 orang, diikuti dari sektor yudikatif sejumlah 47,75 persen dari 22.522 orang. Persentase tertinggi ditempati oleh pejabat BUMN/BUMD sebesar 84,02 persen dari 25.418 orang.
Kepatuhan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya terbilang cukup rendah. Bahkan, baru-baru ini, tak satu pun dari 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada KPK. Kasus di DKI Jakarta ini mengulang kasus-kasus serupa sebelumnya. Kepatuhan yang rendah itu bahkan secara terang-terangan dilakukan dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti pengisian laporan yang sulit, lupa, dan tidak mengerti bahwa hal ini merupakan kewajiban jabatan.
Salah satu faktor utama rendahnya kepatuhan itu adalah lemahnya konsekuensi bila kewajiban pelaporan tidak dilakukan. Salah satu bentuk sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Penyelenggaraan Negara. Persoalannya, sanksi administratif ini melekat pada jabatan atau posisi yang mengikuti alur kerja birokrasi dengan sanksi administratif paling tinggi adalah pemecatan.
Karakter sanksi ini tidak bisa diterapkan pada posisi atau jabatan yang tidak mengikuti alur kerja birokrasi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Mekanisme pemecatan dalam alur legislatif sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum dilakukan melalui mekanisme recall. Selain itu, sanksi administrasi ini berhenti ketika si wajib lapor memilih untuk mengundurkan diri.
Padahal, di sisi lain, pelaporan harta kekayaan saja belum tentu efektif menekan benturan kepentingan dan potensi korupsi. Beberapa modus yang dilakukan, misalnya, adalah dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar. Di sisi lain, KPK tidak memiliki perangkat dan mekanisme yang efektif untuk melakukan verifikasi yang berdaya guna.
Untuk itu, solusi yang perlu dilakukan adalah memperkuat dorongan pelaporan ini dengan menyertakan konsekuensi apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan. Bagi posisi atau jabatan yang mengikuti alur kerja birokrasi, pelaporan harta dan pembaruannya perlu dijadikan syarat untuk rekrutmen dan promosi serta mutasi. Tanpa kepatuhan terhadap syarat ini, rekrutmen, mutasi, dan promosi tidak dapat dilakukan.
Bagi posisi dan jabatan politis, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketentuan pelaporan ini perlu didorong untuk diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai syarat pencalonan. Untuk pembaruan dan pasca-jabatan, pelaporan ini harus didorong oleh partai politik pengusung sebagai syarat minimum bagi para kader. Tujuan besarnya adalah untuk menjaga integritas jabatan publik sebagai bukan jabatan untuk kepentingan pribadi.