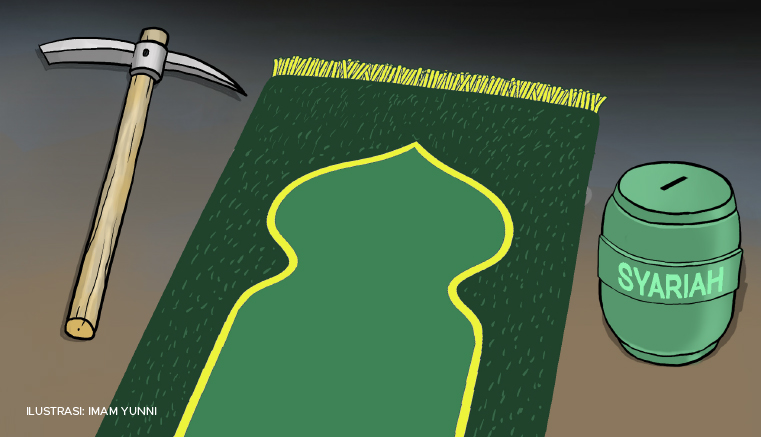Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SORE yang hening di Desa Bili, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, pecah oleh suara ekskavator. Aiyub Sakti, warga setempat, menyaksikan alat berat itu tiba-tiba masuk ke kompleks Rumoh Geudong. Di tempat itu, pada 1989-1998, terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer terhadap masyarakat Aceh.
Menurut Aiyub, 32 tahun, keranjang bercakar dari ekskavator langsung menggaruk tanah dan bebatuan besar di sekitar Rumoh Geudong. Tak lama kemudian, mobil-mobil berpelat merah datang. Sejumlah aparatur sipil negara berseragam cokelat pun menjejak di kawasan rumah panggung yang tinggal menyisakan anak tangga, sebagian tembok, serta sumur tua berlumut itu.
Aiyub, korban penyiksaan di Rumoh Geudong, langsung cemas melihat rombongan pegawai negeri berkerumun di sisa bangunan berusia lebih dari dua abad itu. “Saya khawatir petugas datang untuk meruntuhkan sisa bangunan Rumoh Geudong,” kata Aiyub kepada Tempo melalui panggilan telepon, Kamis, 6 Juli lalu.
Beberapa hari sebelumnya, Aiyub mendengar kabar bahwa pemerintah akan merobohkan sisa bangunan Rumoh Geudong. Sebagai gantinya, akan dibangun masjid dan tugu peringatan untuk mengenang kekejian di rumah itu. Pembangunan itu rencananya dimulai setelah Presiden Joko Widodo membuka peluncuran program penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat.
Tim Pemulihan Korban dan Pencegahan Pelanggaran HAM (PKPHAM) mengusulkan tiga lokasi acara peluncuran program. Selain Rumoh Geudong, ada Simpang PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh Utara dan Jambo Keupok di Aceh Selatan. Semuanya menjadi lokasi pelanggaran HAM berat di tanah Aceh.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Rosseno Aji dan Imam Hamdi berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Luka Baru Korban Lama"