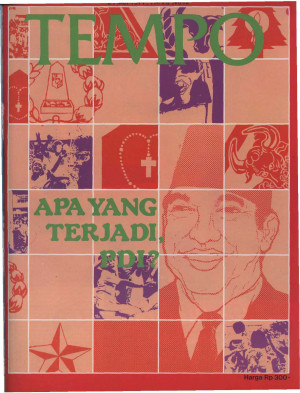KURIKULUM SD terlalu berat. Setidaknya begitulah pendapat
Saadoe'ddin Djambek, bekas Rektor IKIP Muhammadiyah dalam acara
diskusi IKIP Jakarta, 10 Mei pekan lalu.
Rektor IKIP itu kemudian menunjuk angka putus-sekolah di SD yang
sangat besar. Katanya, sejak 1963 anak putus-sekolah SD berkisar
63%. Berarti setiap tahunnya usaha pendidikan bagi 63% murid
kelas satu SD akan sia-sia saja. Jadi kalau pada tahun 1972
murid yang diterima di SD berjumlah 13 juta lebih, delapan juta
lebih di antaranya diperkirakan tidak akan menerima ijazah.
Jumlah ini setiap tahun akan meningkat. Sehingga, menurut
Saadoe'ddin Djambek, usaha penanganan yang dilakukan oleh
Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dengan paket bukunya hanya
semacam "ein Lied Ohne Ende" Semacam nyanyian tanpa akhir -
suatu usaha yang tak akan pernah selesai.
Nah, dari keadaan yang serupa itupun, ledakan lulusan SD akan
masih banyak. Bahkan Presiden April kemarin telah memberikan
instruksi agar P&K menyiapkan program untuk mengatasi ledakan
lulusan SD yang pada akhir 1980 diperkirakan berjumlah 1« juta
pelajar.
Kurikulum Bakal Tetap
Maka Prof. Santoso Hamidjojo, Dirjen Pendidikan Dasar dan
Menengah, selesai menghadap Presiden menegaskan bahwa sistim
baru pendidikan tingkat SD untuk mengltadapi ledakan tersebut
tidak akan merubah kurikulum yang berlaku sekarang. "Tujuan
institusionil SD untuk mendapatkan ijazah guna meneruskan
pelajaran tidak akan ditinggalkan", ujar Santoso. Dan alternatif
untuk mengatasi ledakan tadi antara lain berupa penambahan
kursus ketrampilan bagi murid SD, baik dalam kurikulum maupun
secara ekstra kurikuler.
Apakah setelah itu kurikulum SD tidak semangkin berat? Agaknya
yang penting di sini adalah mengatasi ledakan lulusan SD. Tentu
tidak misalnya dengan mendirikan SMP Inpres."Mendirikan SLTP
sebanyak-banyaknya relevan tidak?" tanya Santoso. Maksudnya,
menambah bangku di atas SD belum merupakan cara pemecahan yang
benar.
Memang, menurut Dirjen, semua tentu ingin melanjutkan
pendidikan. Tapi suatu kenyataan pula bahwa tidak semuanya
mampu, baik karena tak tertampung, putus-sekolah dan sebab lain.
Sebaliknya, penambahan ketrampilan di tingkat SD bukan pula
merupakan vonis, seolah-olah sudah ditentukan bahwa sebagian
lulusan SD tidak diperkenankan masuk SLTP. Jadi yang penting
kini, menurut Santoso lagi, P&K berusaha untuk menajamkan
persoalan dulu. "Sebab ibarat kamera, fokusnya belum tajam",
katanya.
Karena itu beberapa model dari alternatif yang akan diambil kini
tengah dipersiapkan. Misalnya masih diperdebatkan apakah ke
trampilan itu diberikan penuh di SD atau setelah lulus. Kalau
ketrampilan itu diberikan secara penuh di tingkat SD, maka
lulusannya yang akan terjun ke dunia kerja, umurnya masih di
bawah 16 tahun, batas usia kelayakan kerja yang ditetapkan oleh
Departemen Tenaga Kerja. "Tidak akan baik akibatnya bagi
anak-anak usia muda itu. Sebab paling banter mereka hanya akan
jadi tukang. Dan kalau tukang ini sudah terlalu banyak, siapa
yang akan jadi pemimpin?", ucap sebuah sumber di P & K.
Sang Pemimpin
Memberi ketrampilan penuh kepada murid SD, akan menutup
tampilnya seorang pemimpin. Tidak semua anak bakatnya jadi
tukang. Karena itu alternatif yang baik adalah tetap berpegang
pada Kurikulum 1975. "Di sana sudah cukup ketrampilan yang
membuka kemungkinan siswa yang tak berbakat jadi tukang bisa
melanjutkan sekolahnya", tambah sumber tadi.
Santoso Hamidjojo juga setuju kalau ketrampilan penuh diberikan
setelah SD. "Yang paling baik ketrampilan penuh diberikan di
tingkat SLTP", ucap Santoso.
Di SD, ketrampilan juga penting. Namun tak usah murid-murid itu
terlalu awal diberikan ketrampilan penuh. Karena niat membangun
SD Inpres adalah untuk perataan pendidikan. "Kita harus punya
persediaan banyak lulusan SD untuk menjadi karyawan ataupun
pegawai swasta", tambah Santoso. Maksudnya agar tenaga-tenaga
itu minimal tamat SD. Namun bila sudah banyak lulusan SD, apa
mereka akan mudah jadi karyawan atau pegawai?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini