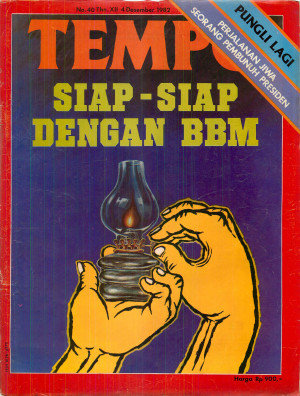SEKOLAH pembauran tiba-tiba dipertanyakan, dan disinggung pula
dalam satu seminar. Selama ini ada anggapan bahwa sekolah
pembauran telah berhasil karena rata-rata komposisi murid "pri"
lebih separuh dibanding dengan yang "nonpri". Namun di kota-kota
tertentu, seperti Pontianak dan Banda Aceh, siswa "nonpri" tetap
saja mengelompok dan ngomong bahasa Cina.
Hal itu terungkap dalam diskusi bebas di lobby Hotel Kapuas
Permai, Pontianak, tempat suatu seminar pers berlangsung (18-20
November). Menurut Ny. Zainidal Tasnin, Kepala SMAN I Pontianak,
memang siswa "nonpri" yang hanya sekitar 30% dari keseluruhan
928 di sekolahnya secara berangsur telah membaur. Walaupun
bahasa Cina masih terdengar di Pontianak, dengan penduduk "pri"
dan "nonpri" kira-kira satu banding satu, hal yang diutarakan
Ny. Tasnin itu boleh disebut menggembirakan. Sebab dulu, kata
Drs. Soenarpo, Kepala SMAN V Pontianak, "sebelum tahun 1979
siswa 'nonpri' suka menyelenggarakan pesta perpisahan sendiri."
Tapi kini antara siswa "pri" dan "nonpri" konon sudah pula
terjadi pacaran.
Dalam soal bahasa itu Pontianak tidak sendiri. Di Banda Aceh, di
sekolah milik Yayasan Perguruan Setia, percakapan bahasa Cina
sewaktu jam istirahat sudah biasa terdengar. Apa boleh buat,
masih 80% lebih siswa SD-nya adalah "nonpri". Dan pelajaran
bahasa Indonesia di situ memang berjalan seret. Keluarga mereka
di rumah pun tetap berbahasa Cina.
Tapi sekolah bisa mengarahkan agar siswa di luar kelas pun
berbahasa Indonesia--seperti yang terjadi di Perguruan Husni
Thamrin, Medan -- bila jumlah siswa "pri" dan "nonpri" memang
berimbang. Di Perguruan Husni Thamrin siswa "nonpri" di SMA-nya
hanya 40%, sedang di SMP-nya lebih banyak, 60%. Dengan
perbandingan seperti itu Iryanto, koordinator perguruan
tersebut, bisa menerapkan kebijaksanaan satu bangku diduduki
bersama oleh siswa "pri" dan "nonpri". Selain itu semangat
pembauran digalakkan dengan kegiatan belajar bersama dan hobi
bersama.
Perguruan inilah yang mempopulerkan hobi sepatu roda di Medan.
Dan ternyata lewat sepatu roda itu "jarak" mereka agak bisa
dijembatani.
Di luar Pontianak (dan Kalimantan Barat umumnya) dan Banda Aceh,
sekolah pembauran boleh dibilang berjalan. Di Jakarta, beberapa
SMA yang kini berstatus negeri adalah bekas sekolah Cina, yang
dianggap berhasil menjalankan misi pembauran. Misalnya SMAN
XVII, dan SMAN XIX, kata Ending Karnadi, Humas Kan-Wil Dep. P&K
DKI.
Di Bandung, SMA Kristen Dago di tahun 50-an mempunyai siswa
"pri' kurang dari 10%, tapi kini 60%. Suasana di sekolah ini pun
biasa saja. "Di waktu istirahat kami bisa berbicara tentang
pelajaran dan apa saja dengan semua teman tanpa merasakan
perbedaan 'pri' dan 'nonpri'," kata Embang Simanjuntak, Ketua
OSIS SMA Kristen tersebut.
Dan di SMA Bhineka Tunggal Ika, Yogyakarta -- yang di tahun
50-an masih bernama SMA Penyaluran dan hingga awal 70-an
siswanya masih 90% lebih "nonpri" -- berbagai cara dilakukan
untuk menjembatani pembauran. Ada keharusan, yang dikontrol
ketat, untuk pak.aian seragam. Ada pula larangan bagi siswa
menggunakan alat tulis-menulis dan kendaraan yang mewah di
sekolah. Dan para guru di situ, menurut Drs. M. Agung Kresna, 43
tahun, pemimpin sekolah ini, dianjurkan mendekati orang tua
murid, terutama yang "nonpri" untuk tidak memperuncing masalah
keturunan.
Di Solo, kota yang mengalami huruhara rasialisme dua tahun lalu,
hal pembauran di sekolah agaknya bukan masalah lagi. SMA Warga,
yang sebelum 1961 adalah sekolah Cina, kini punya siswa "pri"
30%. Dan di sekolah ini tak terdengar lagi percakapan bahasa
Cina. Toh, kasus kecil masih muncul. Misalnya, tutur Teguh
Yuwono, 41 tahun, Kepala Sekolah di sini, perkelahian bisa
timbul hanya karena ejek-mengejek warna kulit, atau hanya karena
soal pinjam buku. "Kalau sudah begitu, kami para pengasuh
langsung menanganinya dan memberikan penyuluhan tentang
pembauran," katanya.
Hanya seorang siswa 'pri" diketahui tidak kerasan di SMA Warga.
Ia harus pindah ke SMA negeri dan kembali duduk di kelas I,
meski dia di SMA Warga bisa melanjutkan di kelas II.
Komposisi jumlah siswa "pri" dan "nonpri" belum menjamin sekolah
pembauran akan berhasil. Bila itu ukurannya, maka di Jakarta
bisa menjadi soal besar. Jakarta Kota -- sebagian besar
penduduknya keturunan Cina--punya sejumlah sekolah swasta dengan
mayoritas siswanya "nonpri". Juga begitu di sebagian wilayah
Jakarta Barat. Yayasan Pendidikan Ricci di Jalan Kemenangan,
misalnya, siswa TK, SD dan SMP-nya hanya 5-8% yang "pri". Bahkan
di SMA-nya hanya seorang siswa yang bukan keturunan Cina, tapi
keturunan Arab. Juga di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur,
Yayasan Cahaya Sakti memiliki TK sampai SMA dan SMEA, dengan
hanya 7% siswa "pri". Mungkin ini terjadi karena ada ketentuan
rayonisasi di DKI Hingga anak-anak perlu memilih sekolah yang
terdekat jaraknya dari tempat tinggal.
Jadi? "Jangan menilai sekolah pembauran dari segi fisiknya,"
kata Ending Karnadi dari Humas Kan-Wil Dep. P&K DKI Jakarta.
"Yang penting segi mentalitasnya. Misalnya, apakah di sekolah
itu terasa suasana Indonesia atau suasana Hongkong? "
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini