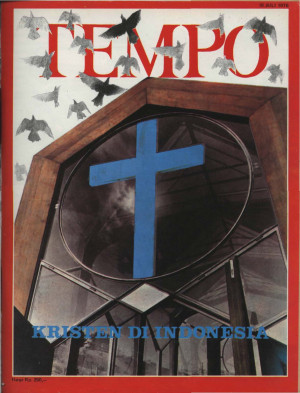KERUKUNAN agama, itulah topik sambutan Presiden Soeharto dalam
Sidang Raya DGI ke-8 di Salatiga. Tapi lain lagi topik
terpenting yang akan dibicarakan oleh gerejawan-gerejawan
Protestan itu sendiri. Kerukunan antar gereja Kristen, itulah
topik yang bakal makan paling banyak waktu selama sidang raya
itu. Di samping topik pergantian BPH (Badan Pengurus Harian)
DGI, tentunya. Dalam yargon DGI temanya. adalah: "Bersatu Untuk
Bersaksi dan Melayani."
Sebetulnya, soal kerukunn antar gereja alias "keesaan" itu
bukan barang baru lagi. Dari sidang raya ke sidang raya,
masalahnya itu-itu juga. Suatu problematik laten, yang
diwariskan oleh sidang raya pertama yang membentuk Dewan
Gereja-Gereja di Indonesia di Jakarta, 25 Mei 1950. Entah
terdorong oleh perjuangan penyatuan bangsa dan penyatuan
gereja-gereja Protestan (yang beberapa tahun sebelumnya masih
terpisah antara gereja-gereja di daerah pendudukan Belanda dan
gereja-gereja di daerah kekuasaan de facto RI), 30 pimpinan
sinode gereja Kristen yang berkumpul di Jakarta sepakat uruk
mencantumkan satu kalimat keramat dalam Anggaran Dasarnya.
Itulah pasal 3 yang sudah diperdebatkan selama 26 tahun ini,
yang mencantumkan tujuan DGI untuk menuju "satu Gereja Kristen
yang Esa di Indonesia".
Dari sidang raya ke sidang raya, para gerejawan yang sementara
ini sudah bertambah menjadi 44 sinode anggota DGI sering maju
mundur dalam menafsirkan pasal itu. Boleh dikata, sampai hari
ini perdebatan itu belum mencapai garis konsensus, melainkan
berputar-putar sekitar tiga soal "keesaan" alias "kesatuan"
gereja-gereja Kristen itu:
* Pertama, soal "isi" dari pada gereja-gereja anggota yang konon
mau bersatu itu. Maksudnya soal penyeragaman liturgi, bahasa,
tata-cara keagamaan dan adat-istiadat, serta untung-ruginya
penyeragaman itu bagi jemaat maupun masyarakat di luar gereja.
* Kedua, soal "wadah pemersatu" atau organisasi Gereja yang Esa
itu, di mana DGI diharapkan menjadi embrionya. Ini menyangkut
hubungan antara DGI dengan gereja-gereja anggotanya, serta
hubungan antara gereja-gereja setempat itu dengan
bentukan-bentukan baru seperti DGW (Dewan Gereja-gereja Wilayah)
dan DGS (Dewan Gereja-gereja Setempat).
* Ketiga, yang mulai muncul ke permukaan, adalah soal yang
menyangkut solidaritas antar dan intra-gereja. Atau menurut
kata-kata seorang tokoh DGI, drs. Pooroe, menyangkut "keesaan
fungsionil, yang tidak perlu menunggu terwujudnya keesaan
formil-organisatoris".
Gereja-gereja Protestan memang di negeri asalnya (Eropa) lahir
dari pembaharuan oleh mereka yang tidak senang terhadap kebekuan
Gereja Katolik Roma yang monolitik itu. Semangat itu mewariskan
tradisi berbeda pendapat di antara penganutnya di Indonesia.
Kendati demikian, sepintas lalu dapat dikatakan bahwa perbedaan
penafsiran soal pasal 3 AD DGI itu juga dilatar-belakangi oleh
perbedaan sumber reformasi gereja-gereja anggota DGI. Khususnya
perbedaan antara gereja-gereja yang lebih berorientasi pada
kesukuan, dengan yang lebih "nasional". Juga perbedaan kedudukan
antara tokoh DGI alias "orang Pusat" dan tokoh gereja lokal
alias "orang jemaat".
"Pada umumnya", kata J.L.Ch. Abineno, ketua umum DGI pada TEMPO,
"kami tidak menghendaki gereja yang monolitik seperti Gereja
Katolik". Lantas apa? "Keesaan dalam keanekaragaman, hampir
serupa dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini masalah prinsipiil,
sebab karunia-karunia yang Tuhan berikan pada tiap-tiap gereja
tidak sama. Jadi kalau kita paksakan struktur yang seragam, itu
tidak akan bisa jalan. Selain itu ada pula keberatan praktis
untuk tidak membentuk satu gereja Kristen Indonesia yang
tunggal. Letak gereja-gereja tersebar di seluruh tanah air.
Makanya sudah pasti kita tidak akan mampu mewujudkan satu gereja
nasional dengan pimpinan yang sentral. Sekalipun komunikasi
sekarang lebih mudah, toh biayanya lebih mahal dari pada kalau
masing-masing gereja mengurus dirinya sendiri seperti sekarang.
Di samping itu gereja-gereja kecil belum yakin bahwa kalau kita
semua bersatu mereka tidak akan didominir oleh gereja-gereja
besar", tutur pendeta kelahiran Timor itu di kamar tidurnya di
Institut Roncalli, Salatiga.
PEMIMPIN Protestan itu juga mencatat, bahwa di lingkungan gereja
Katolik juga sudah terdengar suara yang tidak menyukai bentuk
gereja yang monolitik. Sedang gereja-gereja Protestan sejak
semula berniat mempertahankan kebebasan mereka masing-masing.
Tapi sebaliknya, Abineno juga kurang puas terhadap pengaruh suku
yang sangat besar di beberapa gereja. "Sekarang, ruang pekabaran
Injil lebih besar dari pada ruang lingkup suku. Itu berarti,
gereja-gereja harus berani keluar dari batas-batas suku mereka
dan bekerjasama dengan suku-suku lain". Kalau menurut kata-kata
T.B. Simatupang: "Ada bahaya gereja-gereja jadi museum suku.
Padahal gereja sebenarnya harus mengantisipasi pembaharuan,
bukan hanya di masa depan, tapi juga sekarang, di sini. Itulah
yang disebut membaca tanda-tanda zaman".
Lain pula komentar Dr Soritua Nababan, Sekretaris Umum
BPH-DGI. Yang penting, menurut cendekiawan muda lulusan STT
Jakarta itu, adalah "supaya dunia sekitar melihat kesatuan
antara kata dan perbuatan gereja-gereja". "Gedung-gedung gereja
yang menonjol, mengkhianati kesaksian Kristen", ujarnya
berapi-api. Sambil menambahkan bahwa "mungkin gereja-gereja
kecil di pelosok-pelosok yang miskin lebih menampakkan
orijinalitas Kristen dari pada gereja-gereja kaya di kota-kota
besar". Dan ketimpangan itulah yang ingin digempurnya terus,
walaupun sesudah masa jabatannya sebagai Sekum -- yang sudah
dipegangnya 2 x berturut-turut -- akan berakhir di Salatiga.
Kendati demikian dia toh mengakui bahwa keesaan gereja-gereja
Kristen di Indonesia itu perlu, "supaya tidak membingungkan".
Namun apa pun komentar para tokoh DGI di Jakarta, banyak
cendekiawan dan pemimpin jemaat berfikiran lain. Pokoknya,
seperti ditegaskan oleh pendeta Christopus Kitting dari Gereja
Kristen Evangelis (Kalimantan) dan Dr W.P. Sijabat dari HKBP:
"Keesaan tidak bisa didrop dari atas, tapi harus dimulai dari
bawah. Tumbuh dari jemaat-jemaat". Mengapa demikian? Menurut Dr
Soetarno, Rektor Universitas Kristen Satya Wacana yang juga
seorang tokoh GKJ (Gereja Kristen Jawa) dan anggota BPL (Badan
Pengurus Lengkap) DGI: "Kita harus menjaga jangan sampai DGI ini
menjadi panggung yang terlalu spektakuler, sementara jemaat
gereja-gereja lokal sendiri masih tetap terkebelakang". Katanya
lebih lanjut pada TEMPO di kampus Satya Wacana, "panggung yang
terlalu spektakuler, tentunya harus diisi dengan aktor-aktor
terbaik yang bermutu nasional. Kalau bisa malah internasional.
Akibatnya dana dan personil kita yang terbaik tersedot ke atas,
dan ketergantungan gereja-gereja lokal pada wadah nasional itu
makin membesar".
"Sekarang saja", kata sang rektor, "sudah terasa adanya jurang
komunikasi antara DGI dengan gereja-gereja anggotanya. Karena
itu saya rasa, bahwa gerakan keesaan ini lebih baik diturunkan
ke tingkat yang lebih rendah, DGW dan DGS. Juga putera-putera
terbaik dari masing-masing gereja sebaiknya tidak semua mau
pindah ke Jakarta, tapi baiklah tetap tinggal di daerah
memperkuat basis-basis gereja-gereja kita. Hanya dengan
demikian kita bisa mencegah DGI makin menjadi terlalu berat di
atas. Ini bukan sekedar menyangkut soal dana, tapi juga
fleksibilitas gereja-gereja kita menghadapi perubahan situasi di
sekitarnya. Jadi tidak perlu setiap saat menunggu BPH atau BPL
berapat dulu, yang makan banyak waktu dan dana".
Sorotan soal organisasi ini juga dilakukan oleh Julius R.
Siyaranamual, redaktur Beita Oikumene. "Kendati ada
kecenderungan untuk meyakinkan diri pada suatu keyakinan iman
yang sentral", tulisnya dalam BO Juni 1976, "faktor
pengorganisasian dengan kekuasaan senantiasa merupakan
penggodaan yang perlu dikuatirkan". Kecenderungan ini tampak
dengan kuat dalam proses pergantian BPH, di mana jabatan
Sekretaris Umum lebih dianggap penting dari pada kursi Ketua
Umum. Maklumlah, kepemimpinan sehari-hari ada di tangan Sekum,
lengkap dengan seluruh aparat dan dananya. Sedang para ketua
kerjanya hanya berapat sekali-sekali. Pada TEMPO Julius juga
mengemukakan bahwa DGI lebih berfungsi sebagai "tempat
penampungan orang-orang pensiunan. Termasuk pensiunan DGI
sendiri, yang ditempatkan di badan-badan bentukan DGI".
Daftar ini masih bisa diperpanjang lagi. Misalnya kritikan
pendeta HF Tan dari Gereja Kristus di Jakarta bahwa "fungsi DGI
itu seperti Sinterklas saja: membagi-bagi fasilitas dan bantuan
luar negeri. Sedang dari sinode-sinode anggotanya tiap tahun
paling banter bisa dipungut iuran 1 juta rupiah saja" (TEMPO, 24
April 1971). Atau sorotan John Titaley, ketua DM-Satya Wacana,
yang mengemukakan bahwa "potret" DGI di mata seorang mahasiswa
Kristen di Kalimantan Utara adalah "penyalur bea siswa
semata-mata".
Namun pada umumnya boleh dikatakan bahwa ada terasa kurang
pendelegasian wewenang kepemimpinan gereja dari DGI pada
anggota-anggotanya sendiri. Malah di sana sini terasa ada
tumpang-tindih (overlapping) kegiatan oleh DGI dengan aktifitas
yang sudah dapat dikerjakan oleh umatnya sendiri. Sehingga tidak
selalu kegiatan badan-badan DGI itu "melayani" kegiatan
anggotanya sendiri, atau badan-badan Kristen non-DGI, -- malah
kadang-kadang sudah maju ke tingkat "persaingan".
Tapi memang tidak dapat dikatakan bahwa segala keributan soal
keesaan macam mana, dan bagaimana pun bentuknya -- bukan
semata-mata kesibukan BPH atau BPL-DGI saja. Keresahan umat
Kristen sendiri -- paling tidak sebagian -- yang mau keluar
dari kungkungan liturgi, adat atau pergaulan setempat yang sudah
berkatat ikut mendorong gerakan oikumenisme itu. Antara lain
seperti dilukiskan oleh kritikus sastra M.S. Hutagalung dari
kampus UI Rawamangun, seorang warga gereja biasa. "Soal keesaan
itu penting direnungkan", tulisnya dalam BO, Juni lalu, "karena
masih tebalnya perasaan banyak orang bahwa hanya gerejanya
sendirilah yang sah. Orang yang mau masuk anggota sebuah gereja.
walaupun ada membawa surat anggota dari gereja lain,
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini