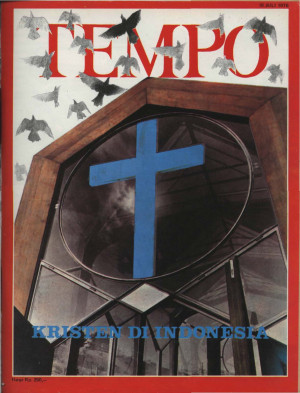Suara lapisan muda, juga yang tidak langsung duduk dalam
kepengumsan DGI atau badan-badan kerjasama DGI, menarik juga
dikemukakan. Paling tidak sebagai umpan-balik yang datang dari
anggota jemaat yarg justru menjadi obyek pembicaraan dalam 'MPR'
DGI ini. Berikt ini pendapat John Titaley, ketua Dewan
Mahasiswa Universitas/IKIP Kristen Satya Wacana.
Mahasiswa Teologia ini menulisnya khusus sehubungan dengan
sidang raya.
OIKUMENISME, ternyata suatu konsep yang tidak terlalu mudah
dipahami. Pengetahuan orang tentang DGI -- dan ini, selain pada
sebagian jemaat, juga pada banyak mahasiswa Kristen -- terbatas
pada DGI sebagai "wadah" umat Kristen di Indonesia, yang selalu
menawarkan bea-siswa bagi yang sempat memenuhi "prosedur"
tertentu. Lebih jauh pengetahuan itu hanya terbatas pada
pengertian kasar, bahwa oikumenisme ala DGI tak lain berarti
usaha mempersatukan gereja-gereja yang ada di Indonesia menjadi
satu Gereja saja. Itulah Gereja yang Esa. Nampaklah betapa
kurangnya informasi bagi warga gereja, apalagi bagi jemaat yang
tinggal jauh dari Jakarta.
Perlu Dihapus?
Oikumenisme adalah gerakan keesaan. Hanya ada satu, tidak ada
lain lagi. 'Keesaan" dibedakan dari 'kesatuan' dalam arti
"menjadi satu". Istilah 'Gereja' pun dibedakan sedikit dari
'Kristen', karena gereja terlalu banyak mengesankan kepelbagaian
dari segi lokal, rasial maupun denominasional. Gereja terlalu
berat konotasi sosialnya walaupun kata Gereja itu sendiri adalah
kata teologia (= kumpulan jemaat). Sedang istilah Kristen di
sini, dipakai dalam pengertian pengikut Kristus, memberi kesan
sikap kepercayaan.
Menjadi pengikut Kristus di berbagai tempat membawa konsekwensi
macam-macam. Adanya perbedaan cara dan pola dari tiap-tiap
kelompok, harus diterima dengan hati terbuka. Namun sejauh itu
harus pula dijaga prinsip-prinsip serta nilai-nilai Kristen
sendiri. Tanpa itu akan timbul pengertian yang berbeda-beda.
Prinsip-prinsip serta nilai-nilai Kristen yang universi ini
memang dapal diterapkan pada setiap bangsa --- dengan akibat
adanya perbedaan ekspresi sesuai dengan latar-belakang
kebudayaan setempat, dan itu harus diterima juga. Kepelbagaian
inilah yang mengakibatkan orang-orang Kristen yang menyatu dalam
gereja- gereja itu, kelihatan berbeda. Kalau
"perbedaan-perbedaan" ini harus dihapus dan disatukan, sulit
juga. Lagi pula apakah perlu? Untuk apa? Tidak ada hal yang
lebih perlu dari pengakuan gereja-gereja terhadap Yesus.
Keesaan Sudah Ada
Dr Francis Schaefer, dalam The Mark of the Christian, mengutip
perkataan Yesus bahwa :hanya kalau murid-murid itu saling
mengasihi barulah dunia tahu mereka itu murid Tuhan Yesus.
Tindak saling-kasih ini dikatakannya merupakan tanda orang
Kristen. Inilah yang selama ini kurang mendapat perhatian baik
antar gereja maupun di dalam gereja sendiri. Gereja-gereja
terlalu sering memperhatikan dirinya sendiri sehingga kurang
memberi perhatian terhadap gereja atau orang Kristen lain.
Apalagi di Indonesia ini, yang terlalu dimanjakan oleh bantuan
rekan-rekan Kristennya di luar negeri -- seolah-olah
gereja-gereja di Indonesia sendiri tidak sanggup saling beri.
Mengapa mereka tidak menempatkan solidaritas ini sebagai satu
sasaran kerja?
Kalau semua gereja sadar bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan
prinsipiil di antara gereja-gereja -- yang berarti keesaan
Kristen sudah ada -- mengapa gereja-gereja masih perlu
di-esakan? Menyatukan gereja-gereja hanya membuang banyak energi
untuk hal yang tidak prinsipiil. Selain tidak perlu, juga tidak
akan tercapai karena pengaruh latar belakang budaya gereja
setempat. Keterbukaan terhadap kebudayaan daerah malah baik
dipakai sebagai bahan yang dapat membantu dalam memikirkan
keesaan gereja.
Motivasi Baru
Lalu kalau keesaan Gereja tidak perlu lagi diusahakan, apakah
gerakan oikumenisme juga tidak perlu? Keesaan Kristen memang
telah ada. Hanya satu yang belum tercapai, yaitu tindak saling
kasih itu. Tentu untuk mengatur pelaksanaan ini secara oikumenis
dibutuhkan suatu lembaga. Dan lembaga semacam itu telah ada
dalam diri DGI, dengan segala usaha kerjasamanya. Kalau
demikian, apa bedanya DGI sekarang dengan lembaga baru yang
dicita-citakan itu?
Hal pertama yang perlu dikembangkan adalah motivasi. DGI, dalam
bentuknya seperti sekarang, terlalu luas cakupannya karena
berusaha menciptakan satu gereja yang esa di Indonesia dengan
satu pengakuan dan satu tata-gereja -- sambil menjadi
satu-satunya badan penyalur bantuan asing bagi gereja-gereja di
Indonesia. Sedang badan baru yang dicita-citakan itu semata-mata
hanya mengurus bagaimana kerjasama yang merupakan perwujudan
tindak saling kasih itu diatur. Dengan demikian motivasi DGI
harus diubah. Tidak lagi berusaha menciptakan kesatuan gereja,
sehingga segala dana dan daya dikerahkan untuk itu sebab "DGI
baru" itu semata-mata hanya berangkat dari titik-tolak bahwa
keesaan sudah tercapai. Tinggal bagaimana menampakkannya harus
terlebih dahulu 'bertobat' dan mengaku salah di depan jemaat.
Banyak gereja hanya dapat mengawinkan anggota-anggota resmi dari
gereja itu sendiri. Bahkan sudah dalam tahun-tahun 'oikumene'
sekarang ini, masih ada gereja yang tidak mau ikut dan
melaksanakan doa bersama kalau anggota sebuah gereja 'musuh'
ikut serta".
Dan memang, masalahnya memang tidak tinggal bahan renungan saja.
Sudah bertahun-tahun yang silam orang-orang Kristen dari
Indonesia Timur (Ambon, Trmor, Minahasa) membentuk jemaat GPIB
(Gereja Proestan Indonesia bagian Barat) di luar kampung
halamannya. Di sana mreka bergaul dan membuka pintu dengan
saudara-saudara seiman dari suku-suku lain, antara lain karena
perkawinan dan pekerjaan. Juga orang-orang Kristen Tionghoa,
yang dulu tergabung dalam gereja Kie Thok Kauw Hwee, sesudah
kemerdekaan mengganti nama gerejanya menjadi GKI (Gereja Kristen
Indonesia) dan membuka pintu bagi orang-orang Kristen pribumi.
Dan sementara ini, gereja-gereja Kristen di Sulawesi Utara
berusaha meningkatkan kegiatan-kegiatan bersama mereka ke
tingkat pembentukan Sinode Am (Sinode Bersama). Juga di Lampung,
perantau-perantau Kristen yang jauh dari kampung halaman dan
sinode asalnya, sedang menjajaki pembentukan Gereja Lampung yang
Esa. Sementara di Kalimantan kerjasama antar DGW keempat
propinsi itu makin menjadi kenyataan. Gereja Kristen Evangelis
pimpinan pendeta Kitting malah sudah melangkah begitu jauh
dengan melarang orang-orang Dayak yang merantau membentuk cabang
GKE di luar Kalimantan. Padahal gereja Balak HKBP dan GPIB masih
tetap mempetahankan ke-sendiri-an mereka dengan membentuk
cabang-cabangnya di Kalimantan.
Ini terang bukan pekerjaan mudah. Sebab tradisi dakwah Kristen
yang dibawa orang-orang Barat puluhan tahun yang lalu, secara
tidak sadar sudah mendirikan tembok-tembok yang sukar dijebol
sesudah proklamasi kemerdekaan. Juga politik "kerukunan agama"
zaman Belanda, yang tidak menginginkan benturan-benturan antara
pelbagai mazhab Kristen itu, telah mempertebal tembok itu dengan
membatasi "konsesi dakwah" dalam daerah-daerah yang saling
terpisah. Dan berabenya lagi, sampai hari ini bibit-bibit
perpecahan secara teratur masih melahirkan gereja-gereja baru.
Bibit-bibit perpecahan, yang hanya sebagian kecil berbau
'teologis' dan lebih banyak merupakan soal-soal teknis
organisatoris dan pamrih pribadi (TEMPO, 24 April 1971).
Tapi mungkin kecenderungan berpecah-belah itukah yang makin
mempertebal semangat bersatu, yang tidak selalu dalam akarnya
itu?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini