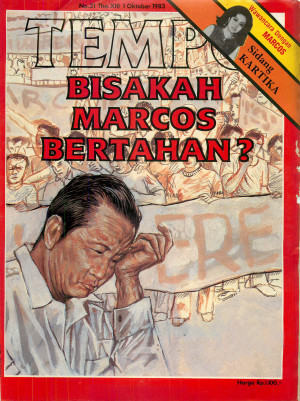RUMAH itu berbentuk joglo, menempati tanah 1.700 meter persegi,
di kawasan Wirobrajan, Yogyakarta. Di halaman depan, yang tak
begitu luas, bunga-bunga ditanam, mencerminkan kesegaran dalam
kesederhanaan. Di situlah, sejak dua tahun lau citra SPG
Muhammadiyah I, Yogyakarta, pelan-pelan dicoba diubah. Dan 15
September lalu, bersamaan dengan peringatan ulang tahun
Muhammadiyah ke-37, secara resmi dinyatakan, sekolah guru itu
mengubah sistem pendidikannya menjadi sistem pesantren.
"Kelemahan oendidikan formal." kata Hajam Murusdi, 43 tahun,
kepala SPG Muhammadiyah itu, "ialah singkatnya waktu bertemu
antara siswa dan pendidik." Rumusan inilah yang mendorong Hajam
dan rekan-rekannya menerapkan pendidikan sepanjang waktu.
Pagi hingga siang siswa SPG tersebut, yang kini disebut santri,
tetap belajar seperti dulu ketika belum ada perubahan. Tapi
lepas dari sekolah, mereka masuk asrama dan harus mengikuti yang
disebut kurikulum pengembangan. Tekanan kurikulum ini memang
pada pendalaman agama Islam. Ada pelajaran tafsir Alauran dan
tafsir hadis. Juga ada pelajaran bahasa Arab dan metode dakwah.
Dan di asrama, sistem belajar lebih menitikberatkan pada sistem
sorogan atau privat. Guru, atau kini disebut ustad, tidak
memandang kelas, tapi siswa orang per orang.
Dan sebetulnya kurikulum pengembangan tak hanya berisi
pendalaman agama. Dari pukul 15.00 hingga 22.00, resminya para
santri dipersilakan menanyakan dan mendiskusikan apa pun dengan
para ustad yang secara bergilir datang di asrama putri ini.
Santri putra masih dititipkan di asrama Mu'alimin, milik PP
Muhammadiyah. Maka, mereka tiap sore diharuskan bergabung ke
asrama putri.
Di asrama putri itu sendiri ada Ahmad Dunuwi Hamim, 52 tahun,
yang menjadi pimpinan asrama. Ahmad, lulusan SMP yang sejak 1949
hidup dari pesantren ke pesantren, inilah tokoh teladan di situ.
Ia bukan sekadar guru mengaji yang disegani, tapi ia juga
menjadi wakil orangtua murid. "Bukan cuma ilmu, tapi juga soal
jodoh dan kesulitan ekonomi ditanyakan kepada saya," tutur
Ahmad, yang mendapat honorarium Rp 20 ribu per bulan dari SPG
Muhammadiyah ini.
Dengan cara itu, boleh dibilang lulusan SPG Muhammadiyah I itu
benar-benar siap terjun ke masyarakat. Tentu saja ini bisa
dicapai berkat pengertian 37 guru yang mengaiar di sekolah itu.
Mereka, menurut para santri yang ditemui TEMPO, bukanlah
"guru-guru yang pelit". Maksudnya, mereka selalu terbuka untuk
ditanya apa pun, untuk diajak diskusi soal apa pun. "Semua waktu
saya, saya curahkan untuk murid saya," kata Sualun, salah
seorang guru. Dan hebatnya, untuk datang dan "mengajar" di
asrama di luar jam sekolah "para guru hampir-hampir tak menerima
tambahan gaji," kata Hajam, lulusan IKIP Negeri Yogyakarta.
Tak mengherankan, misalnya, bila Ahmadi, 20 tahun, yang baru
tahun lalu lulus dari sekolah ini dan mengajar di sebuah SD di
Kampung Brosot, Kulonprogo, Yogyakarta, tak canggung bergaul di
masyarakat. Tak hanya di sekolah ia bersedia membimbing siswa,
tapi juga di masyarakat ia tak menolak ditunjuk menjadi ketua
pengajian. Ahmadi memang merasa dibentuk oleh sistem SPG
Muhammadiyah I itu. Misalnya, "saya terbiasa hidup teratur dan
memegang disiplin," katanya. "Pengalaman itulah yang kini saya
tularkan kepada murid-murid saya." Dan karena ia merasa
mempraktekkan ajarannya sendiri, ia merasa lebih mudah
membimbing anak didiknya.
Disiplin di asrama SPG Muhammadiyah memang ketat. Santri putri
tak diperkenankan ke luar asrama sendirian, tapi harus bertiga.
Izin pulang - sekitar 50% siswi datang dari Yogyakarta dan harus
tinggal di asrama - tak diberikan sembarangan. Surat izin itu
pun, bila mereka kembali ke asrama, harus dikembalikan dan harus
ada tanda tangan orangtua siswa yang menyatakan bahwa anaknya
benar-benar pulang ke rumah.
Apa yang kini diperoleh sekolah ini? Hajam mengakui hal itu
belum tampak benar. Apalagi keharusan masuk asrama baru
ditujukan pada siswa kelas III. Baru tahun depan direncanakan
semua siswa yang kini berjumlah hampir 450 itu bisa ditampung di
asrama. Tapi dia yakin, dengan adanya tokoh sentral macam Ahmad
Dunuwi, adanya kesempatan berdiskusi secara akrab dengan semua
guru di luar jam sekolah "pasti aspek kepribadian yang kurang
di sekolah biasa, di sini bisa dikembangkan."
Bagi para santri sendiri, perubahan sistem sekolahnya disambut
dengan bangga. Ajaib juga, di masa sekarang mereka justru lebih
senang dengan sebutan santri. "Itu 'kan artinya intelektual
muslim," kata Soleh, 19 tahun, siswa kelas III. Dan seperti
bertentangan dengan suasana rumah joglo dan kerudung santri
putri, di asrama ada anjuran agar para siswa, eh, santri, lebih
banyak berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Tentu kebiasaan ini
sangat berguna bagi 18 lulusan sekolah ini yang melanjutkan ke
IKIP dan bagi 25 lulusan yang melanjutkan ke IAIN tahun ini.
Bagi yang kemudian langsung mengajar pun, tentulah kepandaian
itu bisa menjadi bekal untuk belajar sendiri.
SPG ini memang termasuk sekolah "makmur". Dana dari para donatur
lumayan lancar. Selain itu. ada uang sekolah Rp 4.000, uang
asrama Rp 2.500, dan uang makan Rp 10.000 per bulan dari tiap
siswa. "Kami memang bukan mencari untung, tapi pahala," kata
Dunuwi tentang biaya tinggal di asrama yang rendah itu.
Kabar adanya perubahan ini rupanya disambut baik oleh kepala
Kanwil P & K Yogyakarta, G.B.P H. Poeger. Apa pun nama sistem
Ini, "tapi dengan adanya pelajaran tambahan, itu bagus,"
katanya.
Di tengah kecenderungan yang sebaliknya - pesantren membuka
sekolah umum yang dilakukan SPG Muhammadiyah ini memang unik.
Bak sebuah benteng yang berupaya membangun aspek spiritual lewat
pendidikan, di tengah dunia pendidikan yang konon cenderung
menjadi cuma pabrik iazah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini