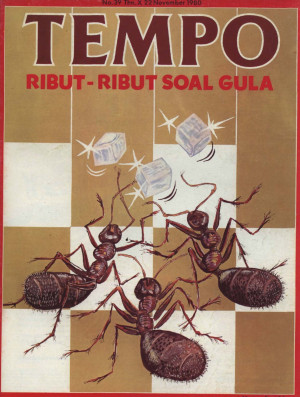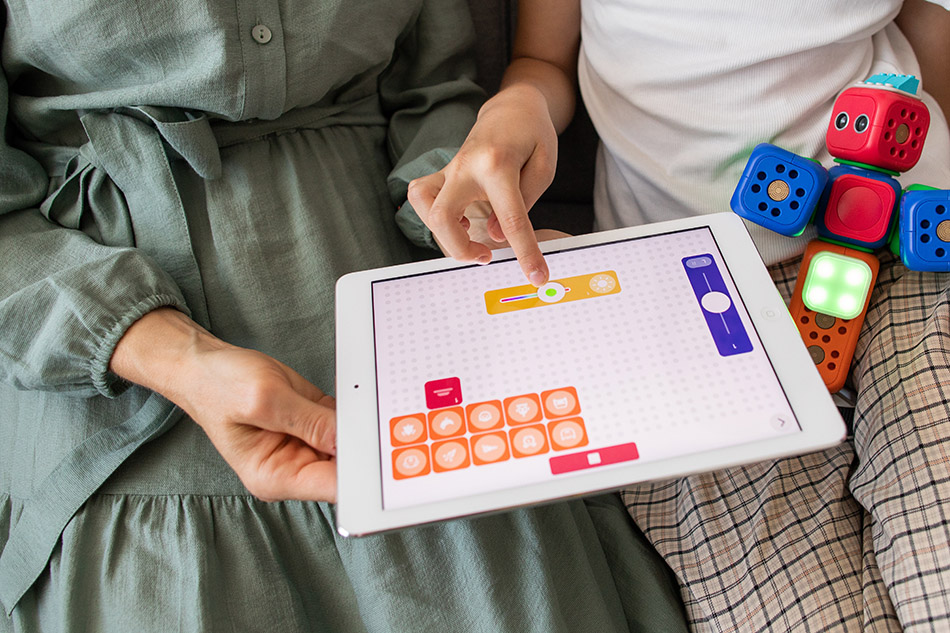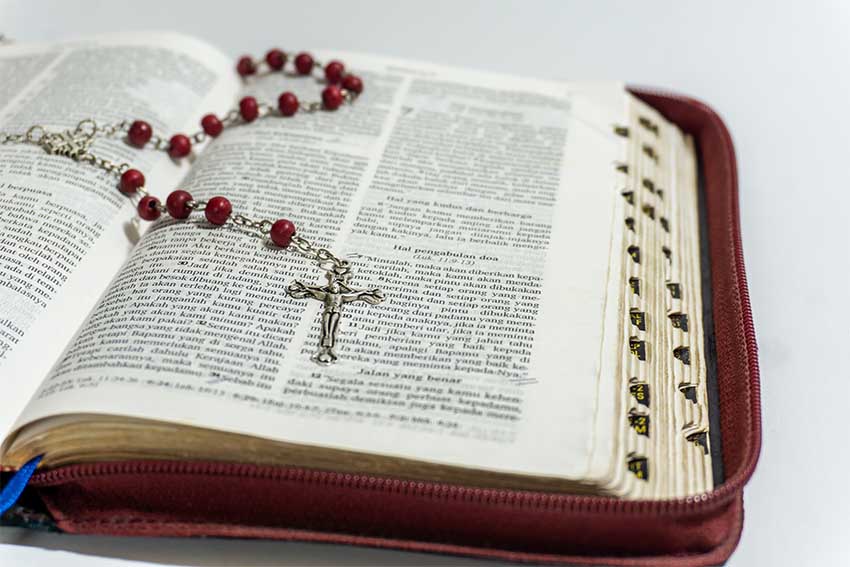GULA bukan hanya tak disenangi para penderita penyakit
kencing manis. Tapi juga sesuatu yang terkadang terasa sakit di
telinga para petani tebu. Terutama bagi petani Tebu Rakyat
Intensifikasi (TRI) --baik ia berpenyakit gula atau tidak.
Karena itu, harga gula di pasaran boleh terayun-ayun atau
diatur setiap hari--seperti terjadi dalam beberapa minggu
terakhir ini--tapi agaknya tak akan banyak berarti bagi para
penanam bahan bakunya. Alasan: nilai keringat mereka masih dirasa
tak memadai, bila dibanding dengan jumlah tetes tebu yang
kemudian mereka dapat.
Tebu, sebagai bahan pokok pabrikpabrik gula, didapat melalui
penanaman oleh pabrik di atas tanah yang disewa dari pemilik
tanah. Ini disebut tebu sewa. Ada juga hasil penanaman oleh
petani di atas tanahnya sendiri. Dan terakhir ada yang melalui
TRI: penanaman oleh petani di atas tanahnya sendiri, dengan
bimbingan Badan Pelaksana TRI.
Mulai musim tanam 1980/1981 sekarang, tebu sewa diganti
dengan TRI. Sistem ini mengharuskan para pemilik tanah di
daerah-daerah tertentu untuk hanya menanam tebu. Mereka kemudian
harus menjual hasilnya dengan harga yang sudah ditentukan kepada
pabrik.
Karena itu ketak-puasan justru banyak datang dari para
petani TRI. Di beberapa tempat, terutama di daerah pertanian
yang sudah memiliki irigasi, petani beranggapan, bahwa menanam
padi atau palawija jauh lebih menguntungkan dibanding tebu.
Dengan bahan baku gula itu, petani baru dapat menikmati hasilnya
setelah 16 hingga 18 bulan kemudian. Padahal, dalam jangka waktu
selama itu, petani akan memungut hasil 2 hingga 3 kali panen
bila tanah ditanami padi atau palawija.
Adiwarto, petani TRI di daerah Klaten (Ja-Teng) yang berada
di lingkungan Pabrik Gula (PG) Gondang Baru, misalnya membuat
perhitungan. "Satu patok tebu untuk satu musim (18 bulan) hanya
menghasilkan uang Rp 150.000," tuturnya, "sedang kalau ditanami
padi dalam waktu 18 bulan dapat 3 kali panen dengan hasil 3 kali
lipat dibanding hasil tebu."
Lebih tak sedap lagi pengalaman Yusak Pranoto, petani TRI di
Desa Padomasan, Kecamatan Kencong, Jemoer yang biasa menjual
tebunya ke PG Semboro. Dalam musim tanam tahun lalu, katanya, ia
hanya mendapat uang Rp 200.000 dari tiap hektar tebunya.
"Padahal kalau sawah itu saya sewakan kepada orang kaya di sini,
tiap hektar dapat laku Rp 350.000 setahun--apalagi kalau saya
garap sendiri," tambahnya.
Toh Adiwarto dan Yusak tetap menimami sawah mereka dengan
tebu, karena "sudah begitu ditentukan atasan."
KETIKA mula-mula TRI harus dilaksanakan, tak sedikit petan yang
kecewa. Malahan di Desa Pabuaran, Cirebon, puluhan petani
mencoba memboikot Mereka tak mau menanam apa-apa--lebih-lebih
karena pada musim panen I dan II hampir tak ada tebu yang dapat
mereka pungut karena dilalap tikus. Tapi kemudian mereka
melaksanakan TRI itu juga, "karena tak ada pilihan lain."
Ketentuan tentang pelaksanaan TRI dikeluarkan melalui Inpres
no. 9/1975. Maksudnya tak lain untuk memperluas areal penanaman
tebu. Karena sebelum itu PG-PG mengeluh kekurangan areal tanaman
tebu, sehingga target produksi jauh dari memadai, dan PG pun
megap megap.
Tiap petani TRI dirangsang dengan kredit dari Bank Rakyat
Indonesia (BRI) sebagai modal penggarapan, pembeli pupuk,
obat-obatan anti hama, bibit, ongkos tebang dan pengangkutan
serta biaya hidup selama tebu belum menghasilkan gula atau uang.
Jumlah kredit tergantung pada letak, luas tanaman dan keadaan
tanah berdasarkan penelitian Ketua Kelompok (mewakili beberapa
petani), BRI dan pihak PG.
Somawinata, petani TRI di Pabuaran (Cirebon) dengan areal
tebu 5 hektar, misalnya untuk musim tanam 1980/ 1981 menerima
kredit Rp 479.500. Uang ini diperincinya: biaya penggarapan Rp
200.000, membeli 7 kuintal pupuk Rp 45.500, obat antihama Rp
30.000, bibit Rp 9.000, ongkos tebang dan angkut Rp 125.000.
Sisanya Rp 70.000. Ini untuk biaya hidupnya selama 18 bulan
mengerjakan areal itu, sampai tebunya berubah jadi gula setelah
digiling pabrik. Pinjaman tadi berbunga 1% setahun.
Liku-liku dalam pelaksanaan TRI itu sendiri tak kurang
mencemaskan petani. Pertama-tama, jabatan Ketua Kelompok,
dipandang sebagai salah satu sumber kebocoran pendapatan petani.
Sebab sang ketua inilah yang mengelola pengeluaran
kredit--sekaligus menerima hasil penjualan gula dari pabrik.
"Digunakan untuk apa saja uang kredit tadi, petani tidak
pernah tahu persis -- begitu pula pendapatannya," kata H. Muanif
Basuni, seorang petani di Jatiroto (Ja-Tim), di kawasan PG
Jatiroto yang terkenal itu. Sebab, tambah Munif, bisa saja biaya
pembabatan sawah tetap dikeluarkan meskipun kenyataannya tanah
di sana sudah bersih.
Ketua Kelompok sebenarnya harus dipilih oleh dan di antara
para petani. Tapi dalam kenyataannya banyak ditentukan oleh
lurah. Bahkan di beberapa desa bagian timur Kabupaten Cirebon,
jabatan itu dikomersialkan--hampir sama dengan kebanyakan
jabatan kepala desa.
Juga proses produksi, maupun menentukan rendemen (kadar gula
dari tebu), sering tak memuaskan banyak petani. Hasil penelitian
Balai penyelidikan Perusahaan Perkebunan Gula (BP3G)
menyebutkan, rendemen tebu milik pabrik gula rata-rata 9,60.
Sementara itu tebu rakyat hanya 8,62. Akibatnya hasil
gula dari areal tebu rakyat hanya 62,1 kuintal/hektar, sedang
dari kebun pabrik 81,4 kuintal/hektar.
Kecurigaan para petani timbul, karena sampai hari ini mereka
tidak pernah mendapat penjelasan mengapa terjadi perbedaan
begitu besar antara hasil mereka dengan hasil kebun milik
pabrik.
Berbagai macam pungutan juga memberatkan petani tebu. Di
daerah Cirebon, pungutan itu ditetapkan 10% dari hasil gula,
setelah dikurangi biaya eksploitasi. Ditambah berbagai pungutan
lain, misalnya atas nama Adat Desa, sehingga semuanya berjumlah
12%: 6% untuk pengurus kelompok, Tripida desa 2%, Tripida
kecamatan 2%, dan lain-lain 2%. Ini belum terhitung kewajiban
membayar bunga kredit tiap bulan, cukai gula, karung, pajak
penjualan, ongkos timbangan dan MPO.
Di berbagai PG di kawasan Surakarta dan Banyumas, pungutan
terhadap petani tebu berjumlah 9 macam. "Entah untuk apa-apa,
saya sampai tak ingat lagi," keluh seorang petani TRI di daerah
Karanganyar.
Dari tanaman tebunya, tiap petani akan- menerima imbalan
berupa gula sebanyak 65% dari seluruh hasilnya. Yang 35% diambil
pabrik sebagai upah giling. Untuk bagiannya si petani menerima
D0 yang menyebutkan jumlah kuintal gulanya yang ada di dalam
gudang pabrik. Gula itu kemudian dilelang dengan patokan harga
antara Rp 310 hingga Rp 320 per kg. Para pedagang boleh menawar
lebih dari harga itu, tapi jika tidak, Bulog (Dolog) yang akan
membelinya. Menurut Menterl Perdagangan Radius Prawiro, harga
baru dan sistem pembelian oleh Dolog dimaksudkan untuk menolong
para petani. Yaitu memotong jalur tengkulak yang selama ini
mengijon para petani tebu.
Dari harga dasar Rp 310 hingga Rp 320 per kg tadi, yang
benar-benar akan jatuh di kantung petani sekitar Rp 260 sampai
Rp 270/kg. Yaitu setelah dipotong berbagai pungutan tadi.
Petani tebu yang tak sabar, biasanya menyerahkan batang
tebunya kepada pedagang (tengkulak) begitu tiba saat tebang. Si
petani tak mau tahu berapa kuintal jumlah tebu maupun gulanya
kelak yang penting ia segera menerima pembayaran dari si
tengkulak untuk tiap hektar tanamannya. Kebiasaan ini tentu saja
kerap membuat petani gigit jari, jika begitu selesai masa
giling, harga gula ternyata naik.
Dan itu misalnya terjadi di Sragen belum lama ini. Seorang
pedagang, melalui lelang resmi, berhasil membeli hampir 15.000
kuintal gula milik petani dengan harga Rp 28.550/kuintal. Maka,
ketika pemerintah menetapkan harga gula af-pabrik menjadi Rp
350/kg sejak 21 Oktober lalu, para petani pun berputih mata
menghitung keuntungan si pedagang.
Adapun ketetapan pemerintah tentang harga baru bagi gula itu
tampaknya belum seluruhnya memuaskan hati petani. Sebab dari Rp
350/kg itu, harga yang sebenarnya diterima petani hanya Rp 307,
setelah dipotong cukai, uang karung, MPO dan seterusnya. Padahal
banyak pedagang yang bersedia membeli Rp 330/kg langsung dari
petani," ung kap seorang pegawai musiman PG Madukismo (Yogya),
Hadi Prabowo.
Dalam ketetapan pemerintah 21 Oktober itu disebutkan bahwa
yang berhak- membeli gula dari pabrik hanya Dolog--sedangkan
sebelumnya pembelian dapat dilakukan oleh Dolog maupun pedagang
melalui lelang. Dengan harga itu Dolog (Bulog) akan menjual
kepada para agen dengan harga Rp 360/kg dan sampai ke tangan
konsumen tak lebih dari Rp 380 hingga Rp 400/kg.
Karena itu Wakil Ketua KUD Tani Binangun di Bantul (Yogya),
Warnodihardjo, menyimpulkan, bahwa ketetapan harga baru
af-pabrik itu merugikan petani. Petani, dalam hal itu, tak dapat
menjual gulanya lagi kepada pedagang secara langsung. Mereka
hanya bisa menjual kepada Dolog dengan harga yang telah
ditentukan. "Padahal harga di pasaran sekarang cukup tinggi,"
kata Warnodihardjo.
Tapi tak semua orang sependapat. Petani Munif di Jatiroto
melihat ketentuan harga baru dan monopoli oleh Dolog itu akan
menguntungkan petani. "Agar petani tak jadi bulan-bulanan
pedagang," ucapnya. Tapi Munif menambahkan, dalam penyaluran
gula itu selanjutnya hendaknya Dolog menyerahkannya kepada KUD
milik para petani tebu. "Agar petani menikmati subsidi gula,
yang biasanya diberikan kepada para penyalur," katanya.
Dengan begitu Munif berharap KUD petani tebu akan mempunyai
modal. Dan kalau modal petani sudah dirasa cukup kuat, menurut
Munif apa salahnya pemerintah megharuskan PG-PG menjual sahamnya
kepada para petani tebu. "Dan semua itu akan membuat petani
bergairah menanam tebu," tambah Munif yang tamatan pesantren
Gontor itu. Sayang, tak seorang pun dari pihak perkebunan yang
bersedia menanggapi kcluhan maupun usul para petani tadi
Namun rupanya harga beh Dolog itu masih jauh dari memuaskan
Direktur PG Madukismo, Ir. Noerjono. Sebab, katanya, harga gula
seharusnya 2 kali harga beras (di tingkat eceran).
Ia mengambil contoh November 1980 ini. Harga rata-rata beras
Rp 230/ kg, sehingga seharusnya harga gula Rp 460/kg. Harga ini
masih jauh lebih rendah dibanding harga pembelian gula impor
oleh pemerintah yang kalau dirupiahkan Rp 700/kg.
Apapun tujuan pemerintah dengan peraturan baru mengenal
tata-niaga gula, yang pasti hingga pekan lalu harga gula belum
stabil. Begitu pula perbedaan harga di pasaran masih banyak
berbeda antara berbagai daerah, meskipun telah dilakukan injeksi
di pasar-pasar. Di Jakarta misalnya tercatat harga antara Rp 400
hingga Rp 425 per kg. Di Pati sekitar Rp 500/kg, Klaten antara
Rp 450 sampai Rp 600 dan di Kota Surabava Rp 550/kg.
Tapi mungkin saja harapan pemerintah akan tercapai: dengan
penetapan harga beli baru, para petani Insya Allah akan lebih
terangsang menyediakan petak sawahnya bagi tebu. Sehingga jumlah
gula impor yang saat ini hampir 1/4 dari kebutuhan (tahun ini
hampir 2 juta ton) makin kecil.
Harapan itu ada dasarnya. Terutama bila dikaitkan dengan
rencana pemerintah untuk merehabilitasi 27 buah pabrik. "Kalau
rehabilitasi itu semua sudah selesai, produksi gula kita dapat
mencapai 1,7 juta ton/tahun," kata seorang anggota direksi
PNP XX. Rehabilitasi itu diperkirakan akan menelan biaya
Rp 31 milyar.
Keadaan pabrik gula di lndonesia kini umumnya sama: tua,
dengan peralatan tambal sulam. Dari 62 PG yang ada di Jawa (12
buah di antaranya milik swasta), hanya 4 buah yang dapat
dikatakan baru. Yaitu Madukismo di Yogyakarta, Jatitujuh di
Majalengka, Pesantren Baru di Kediri dan Krebet Baru di Malang.
Selebihnya adalah sisa-sisa peninggalan Belanda--rata-rata
berusia 80 tahun. Bahkan PG Kali Bagor di daerah Surakarta
didirikan di tahun 1835.
Meskipun hampir tak pernah terdengar macet, ketuaan usia
PG-PG itu tetap menciutkan kapasitas giling "Ratarata hanya
mampu bergiling 70%," tutur seorang anggota direksi PTP di
Ja-Tim. Untuk mempertahankan kapasitas itu pun perbaikan tambal
sulam harus sering dilakukan. Dan ini tidak gampang: onderdil
harus dipesan khusus, dari dalam maupun luar negeri.
Dalam usia tua renta serupa itu, tentu saja PG-PG serupa
itu, tentu sajaPG-PG tadi harus hidup terengah engah. Tak
didapatkan angka pasti, PGPG mana yanguntung atau rugi. Tapi
menurut Ir. Noerjono, salah seorang pimpinan PG Madukismo,
pabrik ini rugi sampai Rp 852 juta pada 1978 (termasuk
penyusutan Rp 430 juta). "Tapi, perusahaan telah memasukkan
cukai dan lainlain kepada negara sebanyak Rp 1,1 milyar," tambah
Noerjono,
Karena itu, Noerjono mengusulkan agar segala jenis pajah
yang memberatkan pabrik dipungut setelah diketahui bahwa pabrik
sudah untung. "Sehingga, kalau pemasukan pemerintah yang
Rp 1,1 milyar tadi dikurangi kerugian kami yang Rp 852 juta,
masih terdapat untung," kata Noerjono. Keuntungan itulah baru
yang dikenai pajak perseroan 50%, tambahnya.
Sekarang, PG Madukismo sendiri menyatakan diri sudah mulai
mengantungi keuntungan. "Meskipun sebenarnya masih sangat
mepet," ungkap Presdir PG Madu Baru (Madukismo), Haji KGPH
Mangkubumi. Ia melihat selisih harga di luar negeri maupun di
pasaran dalam negeri masih terlalu jauh dibanding harga
eks-pabrik. "Sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati
pedagang," tambah Mangkubumi.
Rupanya kebijaksanaan pemerintah terhadap gula harnpir tak
ubahnya dengan sistem Belanda dulu. Yaitu di dalam harga gula
yang resmi, dimasukkan komponen-komponen pungutan: cukai, pajak
penjualan dan MPO. "Semua pabriki harus menanggung beban itu,
meskipun rugi." Kata Noerjono lagi. Dan keadaan serupa tambahnya
benar-benar dapat mematikan PG swasta.
Keluhan serupa tak hanya datang dari PG-PG swasta.
Terlebih-lebih PG-PG milik PNP?PTP - sehingga setiap bulan
pabrik-pabrik milik pemerintah ini harus disuapi subsidi. "Hanya
pabrik yang mempunyai areal cukup luas yang masih bisa untung,"
ujar seorang anggota direksi PTP di Ja-Tim.
Dan justru mendapat areal yang memadai ital. Sampai sekarang
yang tetap jadi masalah hampir semua pabrik. PG Madukismo
misalnya 1979/1980 mentargetkan areal tanaman tebu 5.000
hektar. Yang tercapai tak sampai 75%. Tahun 1980/1981,
PG ini mentargetkan 5.000 hektar lagi. Yang terwujud hanya 65%.
Semua mencakup TRI maupun non-TRI .
Sementara itu PG di luar Jawa tampaknya berjalan seret.
Kecuali barangkali PG Gunung Madu di Lampung. PG Cot Girek di
Aceh misalnya, hanya mampu menghasilkan gula 839 ton sepanjang
tahun 1978, dari areal tebu seluas 2.100 hektar. Padahal di Jawa
dengan areal yang sama dapat dihasilkan 1.800 ton.
Keadaan serupa itu juga terjadi di beberapa PG Mini, seperti
di Silih Nara (Aceh) dan di Bone (Sul-Sel). Di Aceh, PG Mini
yang diresmikan Presiden Soeharto akhir tahun lalu sampai
sekarang belum berfungsi. Karena beberapa peralatannya belum
dipasang, ia hanya mampu menghasilkan gula merah. Padahal,
pabrik mini ini mampu menggilas 200 ton tebu dengan hasil gula
14 ton sehari.
UNTUNG bahwa para petani di sekitar Silih Nara yang sudah
telanjur menanam tebu, melanjutkan pengolahan tebu secara
tradisional alat penggilingnya diputar oleh kerbau. Hasil
perasnya dimasak di atas tungku. Produknya: gula merah,
yangrupanyalaku juga di pasaran Medan sebagal bahan baku kecap
maupun ramuan minuman Vigour.
Barangkali karena melihat beberap. PG di luar Jawa kurang
lancar, belum la ma ini terbetik berita: di Jawa akan se gera
dibangun lagi 5 PG baru. Dua buah di antaranya sudah menemukan
lokasi yaitu di Benculuk, Banyuwangi. Kepu tusan ini agak
berbeda dengan "arus' yang menghendaki agar pembangunan PG baru
dilakukan di luar Jawa supaya Jawa makin banyak menghasilkan
beras.
Mengapa perubahan rencana terjadi? "Setelah dipikir
masak-masak, ternyata lebih ekonomis mengimpor beras daripada
mengimpor gula," kata seorang ahli di BP3G Pasuruan, Jawa Timur.
Apalagi, tambahnya, kalau harga gula di pasaran internasional
sampai mencapai 1100 US dollar seperti sekarang--sama dengan Rp
687 per kg. Belum termasuk biaya angkut.
Kalau demikian halnya, rencana pemerintah untuk membuka
areal pertanian padi baru akan lebih banyak dilakukan di luar
Jawa. Banyak yang mencemaskan bahwa ini akan menelan biaya lebih
besar. Sebab harus dibangun irigasi irigasi baru yang selama ini
boleh dikatakan masih cukup langka di luar Jawa.
Biaya besar juga akan tersedot, bila pertanian padi di luar
Jawa itu dilakukan dengan cara pasang surut--satu sistem yang
sudah banyak dicoba selama ini di Sumatera dan Kalimantan,
dengan hasil yang kurang memuaskan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini