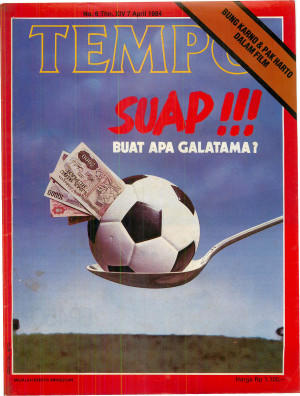WAJAH Jember semrawut. Jalan-jalan rusak, lampu-lampu penerangan umum tidak menyala, dan sampah berceceran di mana-mana. Keluhan masyarakat, dari segala lapisan, hampir tiap hari bisa didengar. Di pinggir jalan, di warung-warung kopi, di pasar-pasar, di kantor-kantor. "Mana wali kota mau memperbaiki listrik, sedangkan jalan saja dibiarkan rusak," kata seorang tukang ojek yang berpangkal di lorong Talangsari. "Pak Wali cuma mau uangnya." Padahal, kata Nur Hasan si tukang ojek, di Jember setiap pelanggan listrik diharuskan membayar biaya tambahan Rp 100 per bulan untuk memikul rekening lampu penerangan umum. Konon, rusaknya Jember dan keluhan masyarakat sudah sejak lama terdengar. Sudah sejak kursi wali kota diduduki Syafi'i Asy'ari. tanda-tanda kerusakan sudah ada. Setelah jabatan itu pindah ke tangan Hirdjan Soewarno, wali kota yang sekarang, kerusakan kota makin nyata. Tapi soal itu baru menjadi bahan pembicaraan terbuka menjelang habisnya jabatan Soepono sebagai bupati Jember, Senin pekan ini. Padahal, Jember dijadikan kota administratif, delapan tahun silam, pada zaman Wali Kota Syafi'i, dengan harapan pembangunan di kota inl makin laju. Dulu, bupati Jember waktu itu, Abdul Hadi, menilai Jember memenuhi syarat diusulkan menjadi kota administratif, sesuai dengan UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Sebab, sudah sejak Indonesia belum merdeka, kota ini menjadi kota transit ekonomi dari kota-kota sekitarnya: Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, Surabaya. Dan, Kota Jember menjadi pasar dari sekitar 70 perkebunan (antara lain kopi, karet, tembakau, dan cengkih) yang mengelilinginya. Di kota ini pula ada Universitas Negeri Jember. Perputaran ekonomi, perdagangan, dan moneter cukup besar, terbukti dengan adanya empat bank pemerintah dan tiga bank swasta yang berjalan lancar. Maka, Amirmachmud, mendagri waktu itu, langsung saja menyetujui usul bupati Jember. Dan lahirlah Kota Administratif Jember, lewat Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1976. Tapi yang terjadi kemudian justru sebaliknya: Jember tak semakin cantik, justru bertambah kusam dari hari ke hari. Wali kota administratif, yang lebih punya wewenang, punya anggaran belanja sendiri, seharusnya lebih leluasa menjalankan pembangunan di kotanya. Sebab, ia tak lagi harus tergantung kepada bupati. Tapi, hak-hak itu (antara lain pemungutan pajak pendapatan dari pajak reklame, radio, anjing, bangsa asing, minuman keras, dan kendaraan bermotor) selama ini cuma hak semu. Bahkan ketetapan anggaran 25% dari APBD Kabupaten Jember untuk Kota Administratif-nya, yang ditetapkan pada 1975, tak pernah terlaksana. Pun subsidi dari pemerintah pusat, Rp 100 juta sejak 1980, tak pernah mampir ke Kantor Wali Kota. Masih ada lagi, subsidi pembangunan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, Rp 50 juta sejak 1981, tak pula sampai di tangan Pak Wali. Wali Kota Hirdjan Soewarno tak mengelak tudingan masyarakat bahwa dia tak bisa membangun kotanya. "Saya memang wali kota, tapi tak ubahnya seperti patung," tuturnya kepada wartawan TEMPO di Jawa Timur. "Semuanya ditangani bupati," tambah wali kota berusia 55 tahun itu. Maka, bayangkan saja bila wilayah kota Jember yang hampir 84 km persegi dan mempunyai lebih dari 72 km jalan harus dikelola hanya dengan sebuah truk sampah dan tiga gerobak. Sementara itu, Bupati Soepono tak bersedia diwawancarai. "Saya 'kan punya atasan, kalau saya tidak benar atau menyimpang 'kan dipanggil," kata Soepono 58, ayah enam anak, bekas komandan Kodim Jember itu. Tapi menurut Soedjalmo, Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur. "Soal Jember, soal rumah tangga mereka. Saya tidak bisa bicara." Dan, menurut sumber di Gubernuran Jawa Timur, Jember hanya satu contoh. Konon, di 20 kota administratif di Indonesia, pengaturan keuangannya memang sering kacau dengan keuangan kabupaten.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini