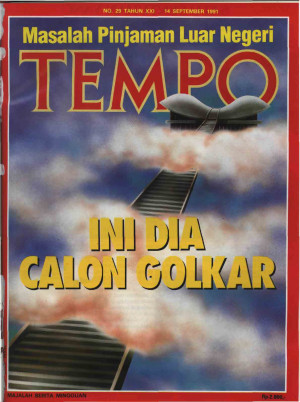Buruh Indonesia kalah produktif dibanding negara lain. Orang Jawa, menurut Raffles, termasuk pemalas. Orang Melayu Riau mau jadi pegawai negeri. PARA pendekar silat butuh arena sabung untuk mengukur keterampilan. Para ilmuwan pun perlu gelanggang serupa, dalam bentuk simposium atau seminar. Pekan lalu, hampir 500 ilmuwan, dari pelbagai cabang ilmu dan kota, berkumpul di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, mengikuti Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (Kipnas) V, selama lima hari. Kipnas V ini memilih tema "Membangun Masyarakat Industri Modern". "Kita akan segera memasuki era industri modern, maka tema Kipnas kali ini menyesuaikan diri ke sana," kata Samaun Samadikun, Ketua LIPI, yang menjadi tuan rumah bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Perhelatan ini menelan ongkos Rp 340 juta, dan mengetengahkan hampir 60 makalah. Adalah Presiden Soeharto yang membuka Kipnas V ini di Istana Negara. Kepala Negara tampaknya masih merasa perlu untuk mengingatkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam bidang ilmu dan teknologi. "Kita perlu bekerja keras untuk mengejarnya," kata Presiden. Namun, penguasaan ilmu dan teknologi semata belum cukup untuk mewujudkan masyarakat industri modern. Presiden menyebut satu hal lain: etos kerja. Masalah etos kerja hingga kini memang masih menjadi soal. Tenaga kerja Indonesia, misalnya, sering diolok-olok kurang produktif dan lembek. Dirjen Bina Ketenagakerjaan Dr. Payaman Simanjuntak mengakui soal itu. "Tenaga kerja kita memang masih kalah dengan orang-orang Filipina atau Malaysia," ujar Payaman, yang menjadi salah satu pembicara. Apalagi kalau dibandingkan dengan buruh Korea Selatan. Bisa jadi, produktivitas mereka dua kali lipat, terutama untuk garmen dan sepatu. Prof. Sediono Tjondronegoro, sosiolog IPB, menyoroti etos kerja itu secara khusus dalam makalahnya. Tapi Sediono tak suka menyelidiki soal etos kerja itu semata-mata dari pendekatan empiris, misalnya dari hitungan produktivitas. Alasannya, etos kerja terkait dengan soal lain seperti idealisme, kepercayaan, nilai-nilai masyarakat, dan kepribadian. Mengingat ciri-ciri itu, menurut Sediono, etos kerja itu bukan soal orang per orang. "Etos kerja itu menyangkut pelaku-pelaku sosial secara kolektif," katanya. Soal ini kini jadi penting dikaji, lantaran sedang terjadi arus transformasi dari pertanian menuju industri dalam masyarakat. Wajah etos zaman pertanian, bagi Sediono, masih tampak dominan di Indonesia. Kondisi ini memang tak menutupi muncu lnya sosok pekerja yang tekun dan giat. Alhasil, motivasi kolektif untuk bekerja mati-matian belum pula menjadi norma baru. Penilaian Sediono ini memang hanya seperti rabaan-rabaan sepintas. Studi khusus tentang etos kerja orang Indonesia, sebagai satu kesatuan bangsa, menurut guru besar sosiologi pedesaan IPB itu, tak pernah ada. Tinjauan yang pernah dilakukan, terutama oleh pengamat asing, sejauh ini baru melihat Indonesia dari suku per suku. Orang Jawa adalah suku yang paling banyak dibahas. Gubernur Jenderal Raffles, misalnya, pernah menuliskan kesannya atas orang Jawa, pada awal 1800-an. Orang Jawa dinilainya pemalas. "Cuma ketakutan terhadap atasan dan paksaan yang bisa membuat orang Jawa mau bekerja," tulis Raffles. Namun P.J. Veth, seorang sarjana Belanda, datang membela orang Jawa pada awal 1900. Dari pengamatannya, Veth menuliskan: orang Jawa adalah pekerja yang ulet, tekun, apalagi kalau kerja untuk miliknya sendiri. Namun, menurut Veth, mereka jadi tak mempedulikan hasil kerjanya, bila hasilnya akan dipetik orang lain. Setengah abad kemudian, ihwal etos kerja orang Jawa itu diselidiki kembali oleh Clifford Geertz, antropolog Amerika. Dalam pengamatannya terhadap tiga kelompok orang Jawa -- santri, priayi, dan abangan -- Geertz sampai pada kesimpulan bahwa di antara mereka kaum santrilah yang punya etos kerja paling tinggi. Tapi, dalam pandangan Sediono, etos kerja santri Jawa yang ada sekarang belum cukup untuk menopang masyarakat industri modern. Penyelidikan etos kerja ini telah pula dilakukan oleh Ary Wahyono dan Sutamat Arybowo, staf peneliti Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, terhadap masyarakat Riau. Dari pengamatannya itu, kedua peneliti ini menyimpulkan, etos kerja orang Melayu Riau masih tertinggal dibanding perantau-perantau yang datang ke kampung halamannya. Arybowo, dalam penelitiannya setahun lalu, mengaku menemui industri karet yang baru buka kekurangan pekerja. Dari 50 buruh yang diperlukan, hanya tersedia enam orang. "Orang-orang setempat enggan bekerja dalam sektor industri," katanya. Apa boleh buat, para pendatang pun kemudian mengisinya. Kedua Ary itu juga menyebar kuisioner kepada 120 responden, untuk diukur mobilitas dan persepsinya atas pekerjaan. Dari jumlah 120 orang itu, cuma 12,5% yang pernah merantau. Mereka masih merasa erat terikat dengan kampung halamannya. Seperti kata pepatah: "Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri." Orang Melayu Riau itu bukan pula kelompok yang suka mengadu nasib, pindah pekerjaan. Dari sejumlah petani nelayan yang diwawancarai, 40% merasa pekerjaan itulah yang cocok buat mereka, 30% yang lainya ingin menjadi pegawai negeri, dan hanya 5% yang ingin ke swasta. Dari kelompok pegawai negeri, 64% mengaku pekerjaannya sudah cocok. Hanya 4% yang ingin pindah jadi swasta. Uniknya, dari kelompok pedagang, 50% dari mereka ingin menjadi petani. Secara umum, para mayoritas responden menyatakan pegawai negeri sebagai pilihan yang dianggap paling aman. Arybowo dan Ary Wahyono pun menyimpulkan, pilihan itu mencerminkan etos kerja yang rendah. "Sebab, mereka lebih suka menempati lapangan pekerjaan yang kurang produktif," katanya. Putut Trihusodo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini