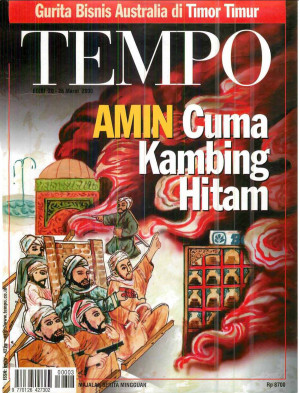Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelum menuliskannya, ia membahas kesimpulan itu bersama saya di Jakarta. Van Fenema berpendapat, GFJA berada di depan dalam mengembangkan wacana fotografi dalam seni rupa kontemporer. Saya tidak segera setuju dan mencoba membandingkan GFJA dengan beberapa galeri sejenis di Thailand dan Jepang. Namun, pada kenyataannya memang tidak ada galeri lain di Asia yang menoleh ke kemungkinan mengisi wacana seni rupa kontemporer melalui foto jurnalistik.
Dasar pembicaraan kami ialah kembalinya kecenderungan representasional dalam perkembangan seni rupa kontemporer, tempat representasi tidak lagi hanya akibat mengalami realitas, tapi juga akibat mengetahui realitas. Kami sepakat, pada masa kini, representasi (penggambaran realitas) pada karya seni rupa tidak lagi berpangkal pada kontak perupa dengan kenyataan secara aktual. Sejak terjadinya revolusi komunikasi, representasi tidak bisa menghindar dari hadiahnya kenyataan yang dicerap melalui media komunikasi. Dalam hal ini, foto jurnalistik punya peran besar dalam membangun gambaran kenyataan.
GFJA, karena itu, merupakan salah satu tanda penting dalam perkembangan fotografi dan seni rupa kontemporer di Asia. Galeri ini, yang berada di bangunan tua Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Pasarbaru, memang bukan sekadar sebuah ruang pameran. Galeri ini telah terbentuk menjadi galeri yang berperan dalam mengembangkan wacana fotografi dalam lingkup Asia.
Kenyataan itulah yang membuat saya khawatir ketika tahun lalu mendengar isu bahwa GFJA akan dibubarkan. Memang, hingga kini tidak bisa dipastikan apakah GFJA secara resmi dibubarkan atau tidak. Namun, akhir bulan lalu, saya mendapati kurator GFJA, Yudhi Soerjoatmodjo, dan staf GFJA yang lain tidak lagi bekerja di galeri ini. Bagi saya, ini tanda keruntuhan GFJA dan kekhawatiran saya ternyata beralasan. Dua pekan lalu, sejumlah foto tua yang digantungkan di galeri ini yang sekadar direproduksi dengan teknik yang buruk dari buku menjadi tanda yang jelas tentang hilangnya kendali mutu GFJA. Ini sebuah kehilangan besar dalam pembentukan "dunia seni rupa" Indonesia yang lagi berproses.
Istilah "dunia seni rupa" sekarang ini bukan lagi sekadar seluk-beluk karya seni rupa dan dunia penciptaannya. Dalam wacana seni rupa yang kini berkembang, "dunia seni rupa" meliputi pula infrastruktur seni rupa. Pengertian ini menimbang kenyataan pemaknaan karya seni rupa. Perkembangan seni rupa dan pembentukan wacananya ternyata sangat dipengaruhi kehadiran museum, kurator, galeri, penulisan kritik, penulisan sejarah, lembaga patron, tradisi mengoleksi, bahkan pasar dan publik.
Di negara maju, kesadaran tentang pengaruh infrastruktur itu mengemuka setelah jaringan museum, jaringan galeri, dan pemikiran tentang seni rupa berkembang luar biasa—di Jepang, pertumbuhan museum pernah mencapai 200 buah per tahun. Kaum esensialis, yang melihat dunia seni sebagai dunia otonom, menyesali kenyataan ini dan menganggap seni rupa sudah "mati". Namun, pandangan baru yang melihat karya seni rupa justru sebagai "teks terbuka" (pemaknaannya, penggalian nilainya yang mengikuti konteks dan wacana) membuat kenyataan itu malah membangun kesadaran baru tentang proses pemaknaan karya seni rupa.
Ketika kesadaran baru itu meluas di negara-negara berkembang di Asia, muncul kesadaran yang lain, yaitu tidak adanya infrastruktur di sebagian besar negara. Lembaga seperti museum, galeri nasional, dan fasilitas pameran yang ada jauh dari cukup dan tidak memadai. Lembaga-lembaga ini rata-rata mengalami kesulitan dana, dikelola birokrat (karena umumnya milik pemerintah), dan tak mempunyai visi. Sementara itu, infrastruktur seni rupa bukan cuma soal ada atau tidak adanya lembaga infrastruktur, yang menyangkut ada atau tidak adanya pranata (institusi) seni rupa. Dengan kata lain, infrastruktur bukan cuma soal kehadiran museum, galeri, atau galeri nasional, tapi yang lebih penting adalah kehadiran organisasi dan pengelolaannya yang berhubungan dengan visi, manajemen, dan policy.
Kesadaran itu menunjuk kenyataan yang terabaikan selama ini, yaitu seni rupa modern di Asia hanya menjadi tradisi praktek tanpa tradisi pemaknaan. Menelusuri sebab mengapa keadaan ini terjadi selama hampir satu abad (bila seni rupa modern di Asia dianggap muncul pada awal abad ke-20), boleh jadi keadaan itu didasari keyakinan "nabi-isme" sederhana. Pada keyakinan ini, karya seni rupa bisa "bicara" sendiri. Kini terungkap, nabi-isme sederhana ini menyesatkan, dan karya seni rupa memang tak mampu menampilkan nilai-nilanya. Tidak terjadinya proses pemaknaan karya dalam kurun waktu sangat panjang pada akhirnya mengakibatkan ketidakjelasan fungsi seni rupa modern dalam masyarakatnya.
Menyadari kenyataan itu, muncul spirit yang hampir sama di Asia dalam menumbuhkan infrastruktur seni rupa. Selama 10 tahun terakhir, sejumlah lembaga seni rupa di Asia mengembangkan organisasinya. Bersamaan dengan pertumbuhan ini, muncul mediasi yang memperlihatkan pembentukan wacana seni rupa Asia. Identifikasi ini segera berdampak munculnya perupa-perupa Asia di forum seni rupa dunia.
Di Indonesia, pertumbuhan infrastruktur itu diawali kemunculan galeri swasta pada pertengahan 1980-an, yang secara bermakna meningkatkan jumlah publik seni rupa. Setelah itu, museum-museum swasta yang sebagian besar diprakarsai para perupanya sendiri segera lahir. Dari pertumbuhan ini, muncul kesadaran mengenai proses pemaknaan karya seni rupa dunia.
Sejak awal 1990, pertumbuhan infrastruktur itu mulai memperlihatkan perannya dalam pembentukan wacana. Dalam "peta" terakhir, tiga lembaga patut dicatat karena memiliki visi dan secara sadar mengembangkan wacana (peran mereka diakui dunia seni rupa internasional), yakni Rumah Seni Cemeti, yang mempunyai sayap Yayasan Cemeti (di Yogyakarta), Galeri Lontar, bagian dari Pusat Kesenian Komunitas Utan Kayu (di Jakarta), dan GFJA, yang ternyata merupakan satu-satunya lembaga yang bernaung di bawah badan pemerintah.
Melihat pertumbuhan infrastruktur yang masih berbentuk kecambah, sementara perannya sangat menentukan, kematian salah satu sektor pada infrastruktur seni rupa Indonesia bagi saya merupakan hal dramatis. Apalagi, kelahiran lembaga-lembaga yang membentuk infrastruktur ini tidak sepenuhnya direncanakan. Banyak di antaranya yang muncul karena berbagai faktor kebetulan yang tidak mungkin diulang. Inilah yang saya lihat terjadi pada GFJA.
GFJA muncul pada 1992, ketika LKBN Antara memutuskan membuat museum di bangunan bersejarah Antara, yang merupakan bangunan cagar budaya. Pada tahun yang sama, fotografer Antara, Oscar Motuloh, yang memimpin proyek museum ini, melengkapi Museum Antara ini dengan ruang pamer GFJA. Ia resmi berdiri dan sejumlah pameran foto jurnalistik diselenggarakan di sini.
Dalam jangka waktu setahun, GFJA memperlihatkan kemajuan. Organisasinya berkembang setelah Oscar Motuloh merekrut Yudhi Surjoatmodjo, fotografer yang belajar di Inggris, untuk menjadi kurator GFJA. Setelah ini, GFJA bukan lagi sekadar ruang pameran foto, tapi galeri yang memperlihatkan visi dan tempat bagi berbagai kegiatan yang bermuara pada wacana fotografi. Pada 1994, ketika Joyce Van Fenema mengunjungi GFJA, galeri ini sudah memperlihatkan ujudnya yang ideal.
Pada 1995, LKBN Antara mengukuhkan kedudukan GFJA melalui surat keputusan. GFJA dinyatakan sebagai bagian LKBN Antara yang berfungsi meningkatkan citra lembaga itu. Kegiatannya yang tidak mencari keuntungan—sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cagar Budaya 1992 tentang Penggunaan Bangunan Tua—diharapkan bisa mengembangkan wacana fotografi. LKBN Antara tidak membiayai program GFJA, tapi menyediakan dana taktis operasional dan gaji kurator dan stafnya.
Berdasarkan perjanjian itu, tim GFJA melaksanakan programnya dengan dana sponsor. Reputasi GFJA membuat galeri ini tidak sulit mendapat bantuan dari berbagai yayasan seni rupa internasional. Dengan dana ini, GFJA menyelenggarakan pameran, workshop, pertukaran perupa, rangkaian ceramah, pengoleksian karya foto, dan pembentukan masyarakat fotografi.
Dalam jangka waktu enam tahun, GFJA telah menyelenggarakan lebih dari 60 pameran foto dalam dan luar negeri—sebagian besar bermakna dalam pembentukan wacana fotografi. Intensitas diskusi di galeri ini meningkat karena didukung masyarakat fotografi yang terbentuk. Dari 1.000 nama anggota masyarakat fotografi dalam database GFJA, 700 di antaranya tercatat sebagai anggota aktif.
Akhirnya, pada 1999, terjadi perubahan manajemen di LKBN Antara, yang ternyata mengguncang kedudukan GFJA. Dalam sebuah iklan kecil di harian Kompas, tahun lalu, Museum Antara dan GFJA disebutkan termasuk ke unit usaha strategis LKBN Antara. Kendati masih harus ditunggu apa yang dimaksud dengan unit usaha strategis itu, sudah bukan persoalan apakah GFJA akan dipertahankan atau diubah ke bentuk lain. Perubahan yang mendasar, yang bagi saya menunjukkan apakah GFJA masih ada atau tidak, sudah terjadi.
Organisasi yang membuat GFJA mempunyai visi dan berperan dalam pembentukan wacana fotografi dan seni rupa secara resmi sudah tidak ada. Karena itu, nyaris tidak mungkin mempertahankan reputasi yang pernah dicapai GFJA. Ini bukan cuma karena tim Yudhi Soerjoatmodjo sepengetahuan saya adalah satu-satunya tim yang akrab dengan perkembangan wacana fotografi di Indonesia. Hal lain, rasanya mustahil mengulangi berbagai kebetulan pada proses pembentukan GFJA selama delapan tahun—semangat mencari dalam membangun galeri foto jurnalistik, spirit yang memungkinkan terbentuknya masyarakat fotografi dengan 700 anggota aktif, dan berbagai mediasi yang memungkinkan GFJA mendapat pengakuan internasional.
Kalaupun GFJA dipertahankan—barangkali sebagai ruang pameran yang disewakan—galeri ini akan menjadi galeri foto jurnalistik "tanpa nyawa", dan penggunaannya kelak akan dipertanyakan karena ada Undang-Undang Cagar Budaya, yang sudah menetapkan peruntukannya dengan jelas.
Jim Supangkat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo