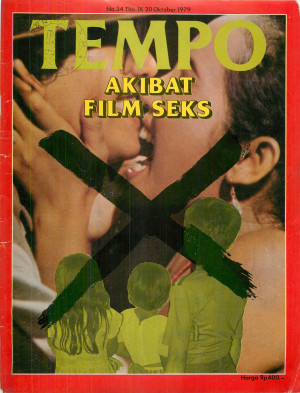SEBUAH ide yang unggul dari Sardono. Ia mendatangkan 16 buah
truk berisi tanah ke dalam kompleks Taman Ismail Marzuki. Dengan
itu diubahnya lapangan dalam, yang selama ini dikenal sebagai
Teater Halaman, menjadi sawah berlumpur. Tiga minggu lamanya ia
bersama grupnya berlatih di lumpur dan sekitarnya itu -- untuk
kemudian mentas 12-15 Oktober. Pengunjung, baik duduk di
panggung di lapangan itu maupun di sekeliling "sawah", cukup
padat.
Sardono berkisah. Selama tiga bulan, waktu pengambilan film
November 1828 di dusun di Yogya, ia sebagai salah seorang pemain
memilih tinggal di gubuk jauh memencil di tengah sawah. Ia
mendapat kesadaran bahwa selama ini, tuturnya kepada TEMPO,
sawah dan lumpur ternyata lewat begitu saja dari perhatiannya --
sebagai seorang anak desa. Padahal, "lihatlah: seorang yang
sedang berjalan di lumpur sawah misalnya, baik sedang menabur
atau menanam atau apa, ia menunjukkan gerak keseimbangan tubuh
yang lain dari kalau ia berjalan misalnya di pematang."
Sebuah Upacara
Tertarik pada penemuan semacam itu, dan membaca berbagai berita
tentang soal-soal sawah, pedesaan, kelestarian alam, ya,
ekologi, ia dan kawan-kawan lantas menyewa sebidang sawah di
Pondok Gede, Bekasi. Di situ mereka bermain dengan lumpur,
menyelam-nyelam, merasakan kecintaan kepada tanah dusun sampai
benar-benar ke tingkat fisik, dan bersiap untuk pementasan.
Tampaknya sebuah potret tentang dusun di sekitar sawah. Di TIM
itu, bidang berlumpur dibatasi pematang dari bidang bertanah
lunak. Di luar, saluran air dari bambu melintang setinggi kepala
dan menjatuhkan tetesan dan bunyi gemericik di ujungnya. Di sini
pula dipasang "kincir" kecil yang selalu berbunyi "tik . . . tak
. . . " akibat kucuran air. Pohon asam besar di sudut lapangan
dibalut kain putih, dan dilatarbelakangi layar biru--agaknya
sekedar membikin sosok pohon menonjol -- dan digantungi beberapa
tali dari cabangnya buat dipakai bergelantungan satu-dua pemain
(bagai kera, atau memang dimaksud begitu). Sebatang pohon nyiur
gundul (seperti bekas disambar petir) ditegakkan pula di
seberang sana.
Sementara itu di bidang tanah lunak di luar daerah lumpur, orang
menyalakan api dan membelah-belah kayu. Orang berjalan
berkeliling di pematang, atau duduk-duduk di pinggir sawah,
sementara di udara terdengar suara burung dan kadang kucing. Dan
semuanya, bersama tembok belakang panggung TIM itu plus
lampu-lampu listrik, anehnya menghadirkan sebuah sawah yang
tidak lagi "asli", yang telah didesak oleh benda-benda asing
"pembangunan". Hanya, barangkali saja, kesan itu tak disengaja.
Tapi adakah latar belakang keprihatinan dari tindak
berlumpur-lumpur ini? "Ya, ada juga," kata Sardono. Dalam
selebaran 3 «2 kwarto yang ditulis Franki laden, anggota grup,
didesakkan kesadaran pada sesuatu yang hilang. Dan judul
'meta-ekologi' memang datang dari lranki, kalau tidak Danarto.
Meski tulisan Franki (dengan gaya gagah benar) tidak dimaksud
sebagai juru bicara melainkan sebagai bagian dari kegiatan, tapi
memang terasa satu sikap yang berbeda dalam pementasan--seperti
dikatakan Franki: "manifestasi artistik sudah tidak menjadi
obsesi" dalam kebutuhan ekspresi. Orang boleh diberi tahu dengan
itu, bahwa apa yang mereka lakukan (menyurukkan kepala dalam
lumpur, telentang di situ bermenit-menit), tak lain sebuah
upacara. Sardono sendiri bilang: apa-apa yang dihargai sebagai
pencapaian artistik, dari orang Bali, Nias, Kalimantan,
misalnya, sebenarnya toh tidak dimaksud ber"seni". Itu sebuah
upacara.
Meskipun sudah tentu "enak dilihat". Dan kegiatan kawanan
Sardono itu pun enak dilihat--untuk sebagiannya. Tubuh-tubuh
yang bangkit utuh dari lumpur misalnya, menyentakkan kenyataan
adanya potensi teater yang betapapun mencekam.
Hanya potensi itu tak dikembangkan. Konsep untuk tidak (melulu)
ber"seni", menyebabkan tak terasa ikatan apapun antara berbagai
kegiatan di situ -- kecuali sawah itu sendiri. Padahal ketika
seorang gadis menancapkan kembang kamboja pada bilah-bilah di
sawah atau ketika Tetet menari di lumpur pada "upacara" sore
hari, sedikit 'atraksi" memikat orang. Tapi jangan diharap tempo
akan berjalan dengan pertimbangan ritme.
Sedihnya, tujuan berupacara itu sendiri jarang bisa ditangkap.
Atau, setelah orang diberi tahu, kesimpulan yang muncul
paling-paling sebuah upacara ternyata sama sekali tidak penting
bagi orang luar. Kalau saja orang tak diberi tahu apa yang ada
di benak para seniman, orang paling hanya akan melihat sebuah
kegiatan agak ganjil di lumpur dan sekitarnya. Di mana
"meta-ekologi"? "Meta-estetik"? Tak ada strum.
Barangkali saja, sekiranya Sardono (seniman teater yang
berangkat dari tari) lebih siap dalam pengendapan subyeknya,
dari lumpur akan muncul sebuah kesenian yang betul-betul
menarik--yang toh sekaligus bisa menggaet kesadaran orang akan
ekologi dan semisalnya kalau toh memang dimaksud.
Sayang. Sebuah ide yang unggul sebetulnya.
Syu'bah Asa
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini