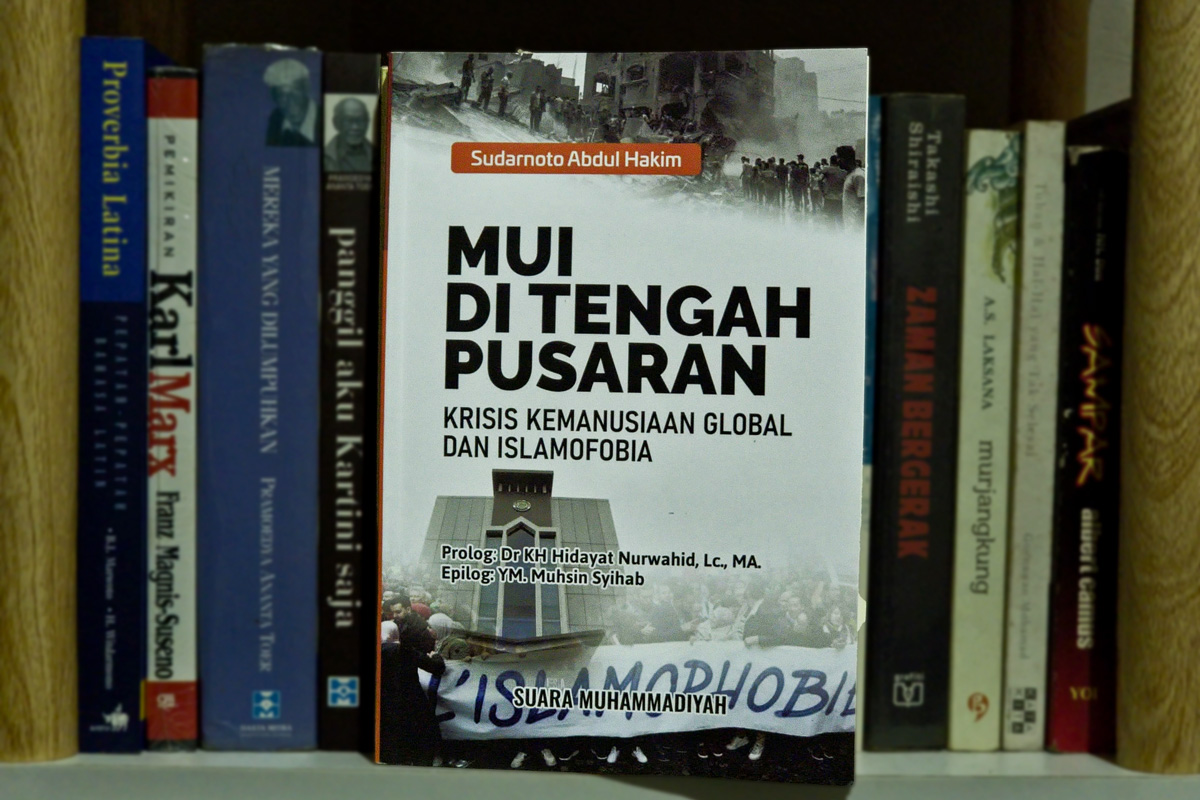Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tunggulah, Hingga Putih Bulu Hidung
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adam Gottar Parra
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bagi yang pernah berkunjung ke Teluk Sepi, dan berjalan-jalan menyisir semenanjung di waktu pagi atau sore, saat berdiri—menghadap ke timur laut—di ujung semenanjung, dengan wajah agak mendongak ke lereng Bukit Botek, jika udara sedang cerah, tidak tertutup kabut, akan tampak sebuah kemah usang berwarna tanah (dulunya kemah itu berwarna biru, tapi perjalanan waktu puluhan tahun telah mengubah warnanya menjadi warna tanah). Di belakang kemah akan terlihat kepulan asap kecil yang membubung dari tungku. Sesekali, di antara debur ombak dan kesiur angin di pohon bakau, akan terdengar salak anjing mengusir monyet yang bergelayut di pohon mente.
Pada sebongkah batu di bawah pohon mati—yang tinggal batang dan dahan lapuk—di sisi kemah, akan duduk mencangkung seorang wanita menjelang separuh baya yang rambutnya mulai bersepuh uban tipis. Matanya memandang kosong ke tengah laut, sembari memegang ponsel butut yang layarnya telah berkabut. Ia berharap pada salah satu kapal yang datang dari Bali dan Jawa itu, di antara para penumpang terdapat Dion, kekasihnya. Sehingga, setiap melihat ada benda hitam bergerak-gerak di tengah laut, hatinya akan membuncah sembari berharap-harap cemas, membayangkan Dion berada di dalam kapal yang tengah merapat ke Pelabuhan Lembar itu. Dengan raut muka berbinar, jarinya pun akan menekan-nekan tombol HP, lalu menempelkan ke kupingnya.
“Hallo, hallo, Mas Dion? Mas ada di kapal itu, kan? Saya lihat kapalnya dari sini, Mas...” katanya sambil mengangkat leher, melihat-lihat ke tengah laut. “Hallo, hallo…”
Tentu saja tak ada sahutan. Bukan saja nomor yang dihubunginya telah lama hangus (terakhir terdengar nada sambungnya sembilan tahun lalu), tapi ponsel jadul di tangannya juga sudah lama rusak, selain di lereng bukit itu tidak tersedia aliran listrik untuk ngecas baterai. Tetapi ia terus berusaha menghubungi nomor mati itu dengan ponsel rusak di tangannya, lalu bicara sendiri.
“Mas, kapan balik? Kok tidak berkabar, sih? Huhh…!” keluhnya, kesal, karena tak ada jawaban, lalu membanting ponsel butut itu ke tanah. Itu terjadi berulang-ulang, setiap melihat ada kapal mendekat ke Pelabuhan Lembar.
Ketika tambang emas Bukit Botek mulai dibuka pada 2008, beribu-ribu warga menyerbu ke lokasi tambang, yang terletak di kawasan pegunungan Mareje itu. Para petani, peternak, nelayan, dan kuli bangunan, yang tidak punya pengalaman bekerja di tambang, mendadak menjadi penambang emas. Mereka membawa peralatan seadanya, seperti linggis, martil, betel, dan dulang. Karena buta sama sekali soal tambang, malah ada yang membawa ayakan pasir. Lalu mulai memukul-mukul batu di lereng bukit yang masih tertutup pohon-pohon itu. Di sepanjang hari akan terdengar orang-orang memecah batu. Serpihan-serpihan batu itu akan dimasukkan ke karung, lalu dibawa ke rental-rental gelondong di kaki bukit.
Sejak itu Bukit Botek tak pernah sepi dari kesibukan para penambang, yang dari hari ke hari jumlahnya semakin bertambah. Karena para penambang dari luar daerah, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa, juga mulai berdatangan. Mereka datang berkapal-kapal di Pelabuhan Lembar, hingga sempat berurusan dengan aparatur setempat, karena area tambang Bukit Botek berstatus ilegal. Benarlah kata pepatah, ketika ada gula, maka semut-semut akan berdatangan. Mereka pun menyerbu Bukit Botek, lalu mulai menggali lubang-lubang terowongan yang kelak tembus ke mana-mana, mengikuti urat emas.
Selain bunyi tog-tag batu-batu yang dihantam martil, terdengar juga ratusan mesin genset dan raungan senso, serta derak pohon tumbang. Bisa dibayangkan, beribu-ribu orang memukul-mukul batu, seolah-olah di tengah hutan sedang berlangsung konser batu manusia purba. Kawasan hutan yang semula tenang, dan sesekali ditingkahi kicau burung kakaktua di pohon kayu putih, berubah menjadi tempat yang ingar bingar, membuat lutung dan bakeq-beraq kabur tunggang-langgang entah ke mana.
Dalam hitungan pekan, pohon-pohon di Bukit Botek pun rata dengan tanah. Hutan yang tadinya hijau kini digantikan deretan kemah-kemah dan lubang-lubang galian yang kelak ambruk dan menimbun ratusan penambang.
Karena orang-orang ingin kaya mendadak dari emas, akibatnya, banyak sawah-ladang dan ternak yang terbengkalai. Beratus-ratus sampan telantar di pesisir, hingga sejumlah pasar di Lombok sempat mengalami kekurangan pasokan ikan.
Hampir bersamaan dengan kehadiran para penambang liar itu, warung-warung tenda juga mulai bermunculan di lereng bukit. Di tengah carut-marutnya perekonomian dan langkanya lapangan kerja, kehadiran tambang emas Bukit Botek ibarat mukjizat di tengah kemiskinan.
Di malam hari, kawasan perbukitan yang sebelumnya gelap-gulita kini bertabur kelap-kelip cahaya lampu dari warung-warung tenda, mirip kota ajaib dalam dongeng. Bukit kecil itu seolah-olah menjelma menjadi surga bagi para gurandil. Di antara gelak tawa dan irama dangdut koplo di radio, dari warung-warung meruap aroma minuman keras. Orang-orang yang ketika di kampungnya selalu bersikap santun kini menunjukkan sifat aslinya. Bahkan tak sedikit yang berubah jadi liar, seperti hewan lepas dari kandang.
Mungkin karena jauh dari rumah dan keluarga, mereka merasa bebas melakukan apa saja di lereng bukit yang seolah-olah baru muncul dari dalam tanah itu. Kata-kata tertentu yang semula jarang terdengar, karena dianggap tidak sopan, kini dengan bebas diucapkan, oleh siapa saja, dan tak ada yang keberatan. Malah jadi bahan tertawaan. Mungkin benar komentar seorang pemerhati sosial, bahwa daerah tambang di mana pun sama saja, cenderung bebas nilai.
Di lokasi tambang inilah Monah bertemu dengan Dion, penambang yang posturnya mirip Tarzan itu. Pagi itu hujan lebat. Air menetes-netes dari atap warung yang bocor. Dion datang berbasah-basah, tanpa baju, untuk memesan indomi. Saat itu hanya Monah sendiri di warung yang terletak di bawah pohon bungur itu. Agar tidak dikira sombong, karena membiarkan pembeli duduk bengong, Monah pun mengajak Dion bercakap-cakap. Awalnya mereka saling menanyakan asal-usul masing-masing. Dion mengaku berasal dari Medan, meskipun logat Bataknya terkesan dibuat-buat. Tetapi gadis kampung seperti Monah tidak cukup pandai membedakan logat masing-masing daerah. Apalagi di hatinya mulai tumbuh benih-benih kekaguman, seandainya ada keraguan pun bakal menguap dengan sendirinya. Mereka pun berbincang-bincang lebih jauh tentang pribadi masing-masing. Dan, saat Dion hendak kembali ke lubang, mereka pun bertukar nomor kontak. Itulah awal mulanya, hingga berlanjut menjadi hubungan asmara.
Cinta lokasi semacam itu sudah umum terjadi di lingkungan tambang. Mungkin karena jauh dari rumah penduduk, mereka yang berpacaran akan terlihat lebih intim dari biasanya, laiknya pasangan suami-istri. Orang-orang di sekitar juga akan berpura-pura tidak tahu. Mungkin karena ini lokasi tambang, bukan lingkungan RT/RW, orang-orang merasa tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Di lokasi tambang, orang cenderung bersikap nafsi-nafsi.
Dari ratusan penambang yang datang dari luar daerah, Dion termasuk yang berhasil. Hampir setiap pekan ia akan turun ke Kota Sekotong untuk menjual emas dan menabung uangnya di bank. Tiap kembali dari kota, Dion akan selalu membawa oleh-oleh untuk Monah, selain membayar kebutuhan makan dan minumnya selama sepekan. Itu yang membuat Monah sangat percaya bahwa Dion bersungguh-sungguh padanya, bukan sekadar cinta lokasi, seperti yang dialami kebanyakan temannya, sesama pedagang warung. Namun Monah lupa menelusuri asal-usul Dion. Ia percaya begitu saja pada setiap kata-kata lelaki itu.
Waktu terus bergulir seperti komidi putar mempermainkan nasib manusia. Tak terasa sudah dua tahun Monah menjalin hubungan dengan Dion. Keduanya sudah hafal letak tahi lalat di tubuh masing-masing. Monah pun berkali-kali mewanti-wanti Dion, jangan sampai meninggalkan dirinya jika tidak ingin melihat dirinya hancur.
Tetapi, siang itu, sekembalinya dari toko emas, Dion mengatakan kepada Monah bahwa dirinya harus pulang ke Medan. Neneknya sakit keras. Dion juga berjanji akan segera kembali bersama orang tuanya untuk melamar Monah. Mendengar kata-kata itu, bukan main girangnya hati Monah. Ia langsung menubruk tubuh Dion dan menghadiahinya dengan ciuman bertubi-tubi. Monah ikut mengantar Dion sampai ke kaki bukit untuk naik ojek ke pelabuhan.
Tetapi, seminggu kemudian, nomor ponsel Dion tidak bisa dihubungi. Jawaban operator selalu: “Nomor yang Anda tuju berada di luar jangkauan.” Awalnya Monah tidak menaruh curiga karena bisa jadi posisi Dion memang berada di luar jangkauan. Hal itu biasa terjadi ketika seseorang sedang berada di pelosok terpencil yang sulit terjangkau sinyal. Tapi ketika beberapa waktu kemudian jawaban operator berubah menjadi, “Nomor yang Anda putar salah.” Monah pun syok! Sebodoh-bodohnya perempuan yang tidak tamat SMP itu, tahu bahwa dirinya telah dibohongi. Tubuh Monah pun lunglai, hingga ponsel butut di tangannya jatuh menggelosor ke tanah.
Sejak itulah, Monah menunggu kekasihnya di atas bukit. Tak peduli ribuan penambang dan rekan-rekannya sesama pedagang warung telah lama meninggalkan lokasi tambang. Monah tetap bertahan di bekas warungnya, ditemani seekor anjing. Saban pagi dan sore, ia akan duduk di atas batu. Setiap melihat benda hitam bergerak-gerak di tengah laut, hati Monah akan membuncah karena mengira di dalam kapal yang sedang menuju Pelabuhan Lembar itu terdapat Dion, kekasihnya. Lalu menekan-nekan tombol ponsel butut dan menempelkan ke telinga, “Hallo, Mas Dion…”
Orang tua dan saudara-saudaranya telah berkali-kali datang menjemput untuk membawanya pulang ke Batugong, sekitar 40 kilometer dari Bukit Botek. Tapi Monah selalu menolak. “Kalau tetap memaksa saya pulang, saya akan bunuh diri!” katanya sambil mengacungkan pisau dari dalam kemah.
Orang-orang kampung yang sesekali naik ke bukit untuk mencari kayu bakar juga tak lupa menasihati Monah agar mau pulang. Karena tidak pantas seorang perempuan tinggal sendiri di lereng bukit. “Nanti kalau tunanganmu datang, saya yang mengantar ke sana...” kata Rosidi, kepala dusun terdekat, karena prihatin melihat kondisi Monah yang mirip tengkorak hidup. Namun semua nasihat itu ditampik.
Kini rambut Monah pun sudah bersepuh uban. Ia masih setia menunggu kekasihnya di lereng Bukit Botek, ditemani si Buntung yang sesekali menyalak mengusir monyet di pohon mente.
“Tunggulah, sampai putih bulu hidung!” kata orang-orang yang sesekali naik ke bukit untuk mencari kayu bakar.
Mataram, 4 Oktober 2021
Keterangan:
Betel: Sejenis pahat untuk mengorek/memotong urat batu yang mengandung emas.
Bakeq-beraq: Hantu berambut panjang, bermata merah (bahasa Sasak, Lombok).
Gelondong: Mesin heler penghancur batu.
Adam Gottar Parra, lahir di Praya, 12 September 1967. Cerita pendeknya terbit di sejumlah media cetak dan online, juga dalam beberapa antologi bersama. Penulis tinggal di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo