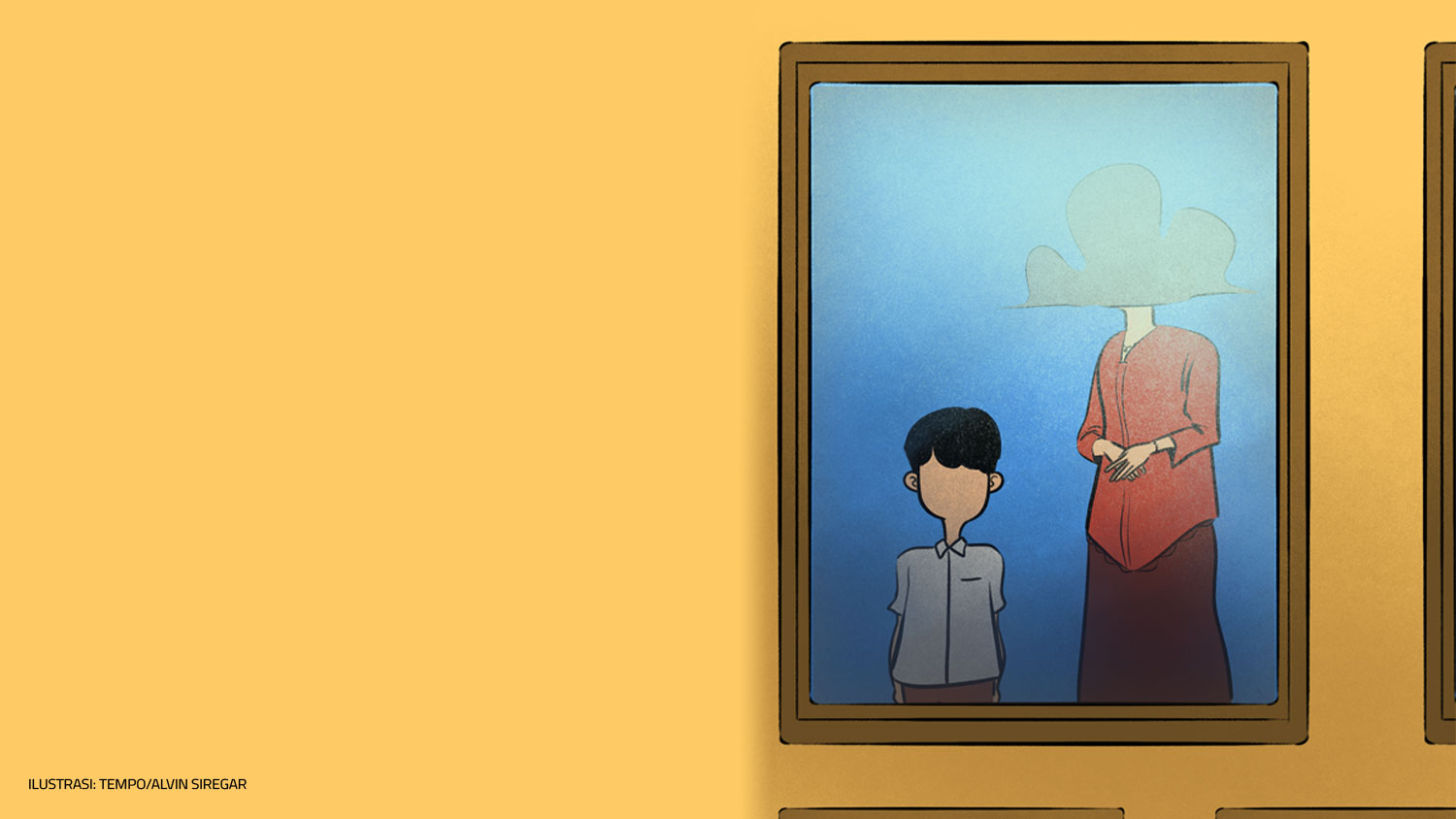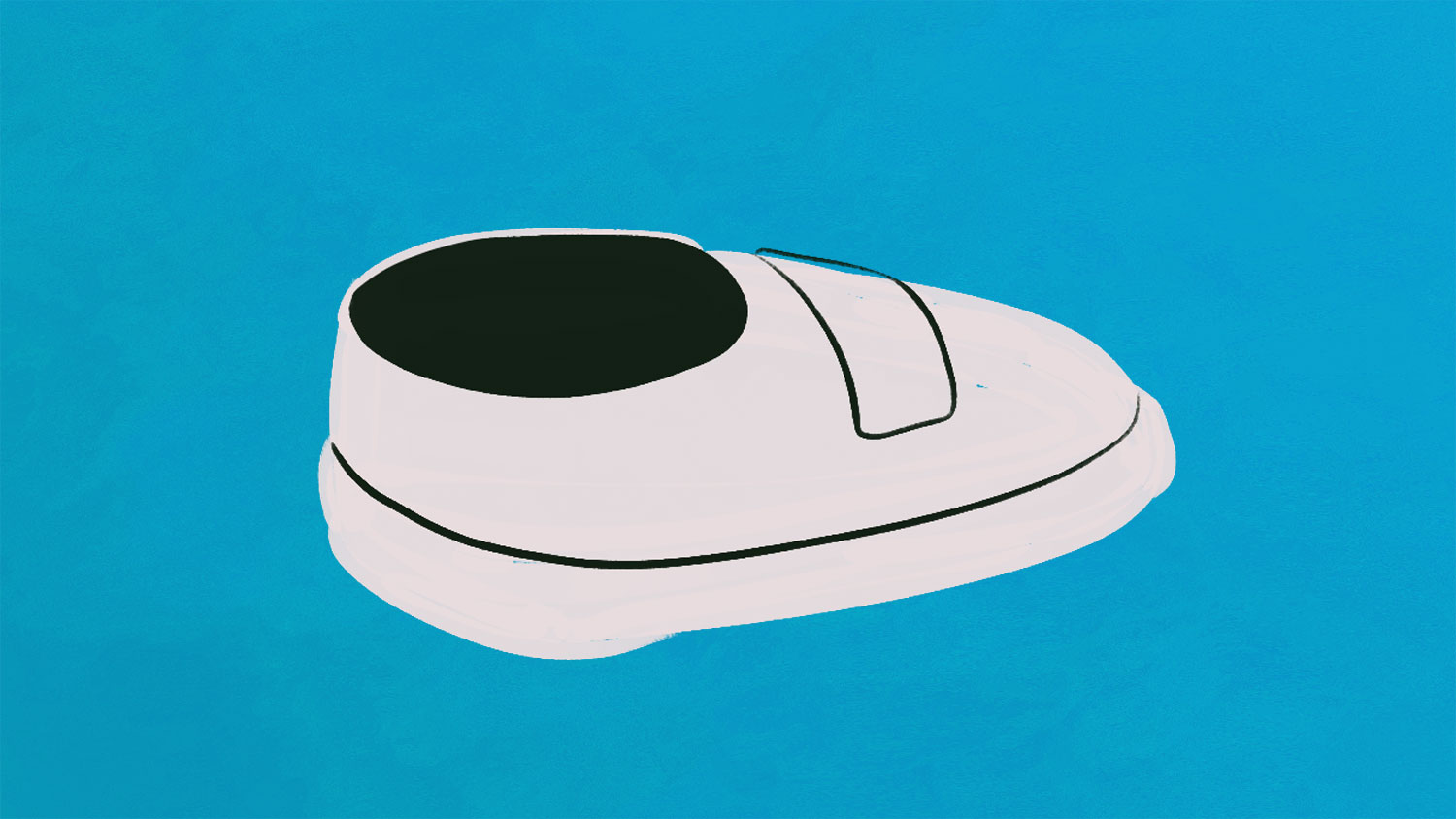Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Aku terbangun dan tubuhku sudah 25 tahun.
Waktu begitu jauh melompat dan aku seperti sebuah benda di atas trampolin.
Aku merasa baru kemarin melihat Ibu menyeka air mata sembari memandang wajah seseorang dalam pigura.
AKU terbangun dan tubuhku sudah 25 tahun. Waktu begitu jauh melompat dan aku seperti sebuah benda di atas trampolin. Aku merasa baru kemarin melihat Ibu menyeka air mata sembari memandang wajah seseorang dalam pigura.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hari ini saat aku terbangun, aku mendapati tubuhku telanjang dan baju kecilku tergeletak tepat di samping ranjang. Dengan tergesa kugunakan apa pun untuk menutupi ketelanjanganku sampai aku menemukan sarung. Aku masih menemukan Ibu di ruang tengah memandang pigura-pigura di tembok. Ibu mengenakan daster berbunga, duduk di kursi ruang tengah rumah ini. Digulirkannya pandangannya pada pigura-pigura yang menempel di dinding semen yang tak dicat itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Ibu menangis?”
Buru-buru Ibu menyeka air matanya dengan ujung dasternya saat mendengar suaraku. Tubuhnya kurus, lengannya begitu ringkih. Tapi aku tak ingat, apakah memang Ibu dari dulu kurus atau bagaimana.
“Ada makanan di bawah tudung, sarapan dulu,” kata Ibu.
Sebenarnya aku tak lapar. Tapi aku ingin menyantap masakan Ibu. Barangkali aku pernah mencicipinya, tapi lupa rasanya. Selama apa 25 tahun itu? Apakah rentang waktu itu cukup untuk membuat manusia lupa dengan yang terjadi di tahun-tahun lampau?
Seperti kata Ibu, memang ada makanan di bawah tudung. Sepotong ayam goreng tepung, sup dingin, dan nasi. Aku menyantapnya dengan lahap sambil mengingat-ingat apakah Ibu memang bisa memasak. Sepertinya ini makanan dari warung cepat saji. Setelah 25 tahun, segala apa pun memang mesti instan. Setelah makan, tubuhku terasa remuk. Barangkali efek terlalu lama tidur. Aku menyalakan TV, menyaksikan berita apa hari ini.
Aksi demonstrasi makin luas.
“Sial. Hari ini masih ada orang yang berdemonstrasi!”
Tak sadar aku mengumpat keras setelah menyaksikan cuplikan berita itu. Kupikir, aksi demonstrasi hanya terjadi pada tahun-tahun sebelum aku lahir. Dan setelahnya kehidupan baik-baik saja. Memang tak baik jika terlalu lama tidur. Tapi, ngomong-ngomong yang berdemonstrasi ini siapa? Kumatikan TV. Tak ada bedanya saat aku lahir dan hari ini. Oh iya, aku punya ponsel pintar. Kunyalakan dan aku tenggelam di lini masa media sosial. Hal-hal yang nyaris sama di TV, dengan propaganda yang lebih vulgar lagi gesit. Ampun. Tubuhku makin remuk, seperti dilindas mobil balap, secepat berita-berita tersiar.
Kuhampiri Ibu yang masih duduk di ruang tengah. Sekali lagi, saat aku mendekat, dengan buru-buru Ibu menyeka air matanya. Aku duduk di sebelahnya. Ibu meletakkan telunjuknya di depan bibir memberi isyarat agar tak bersuara. Seseorang entah siapa dan di mana sepertinya sedang mengawasi Ibu. Aku menurut dan ikut memandang pigura-pigura di tembok itu. Ada lima pigura, dua di antaranya lebih besar dan terpasang lebih di atas, dan tiga pigura lainnya lebih kecil dan ukurannya sama yang satu di antaranya berisi lembar penghargaan yang dipasang tepat di bawah dua pigura yang besar.
Di salah satu pigura, ada potret tiga orang. Seorang lelaki dewasa mengenakan jas, seorang perempuan mengenakan kebaya, seorang anak lelaki yang berdiri tepat di depan lelaki dewasa. Setiap wajah tampak tidak jelas dan buram, seperti pemandangan puncak gunung yang ditutupi awan. Apakah itu potret keluargaku?
Aku tak mengenali wajahku, tapi aku mengenali beberapa wajah dalam pigura itu. Aku yakin Ibu menangisi lelaki berkemeja kedodoran itu yang sedang bersalaman dengan orang yang berkopiah dan berbalut jas dengan sungging senyum aneh, orang paling mengerikan di republik ini.
Apa kabar, Bapak?
•••
AKU terbangun dan tubuhku menua 50 tahun. Orang-orang kehilangan ingatannya dan hanya mengenakan keinginannya, tapi semua keinginan bukan dari diri mereka. Kalimat kedua terlalu puitis! Kondisi saat ini sangat kacau dan sangat tidak puitis.
Begini, saat aku terbangun dan melihat kalender yang menunjukkan tahun 2048, usiaku tepat 50 tahun. Aku telah pensiun. Kupikir, aku tidur terlalu lama karena aku terlalu lelah. Faktanya, tempat tidurku terlalu nyaman.
Semestinya kehidupan makin baik. Nyatanya aku sadar Ibu sudah tidak ada, dan Bapak belum juga pulang. Saat aku keluar hendak menikmati udara, yang kuhirup rasa-rasanya bukan lagi udara. Secara refleks aku terbatuk. Entah ini malam atau subuh atau apalah, sebab tak ada matahari, sebab gedung-gedung makin tinggi tak terlihat ujungnya. Rumah-rumah di sekitar permukimanku makin padat, sesak, dan lembap. Orang-orang yang kujumpai adalah orang-orang sakit. Mereka mengenakan masker. Tidak, sepertinya mereka tidak sakit. Aku yang butuh masker! Hei, tak ada pepohonan! Apakah pohon adalah spesies yang langka dan hanya ada di hutan? Memangnya hutan masih ada?
Kulangkahkan kakiku beberapa saat. Aku mendapati orang-orang sedang berkerumun di depan sebuah kantor pemerintahan. Ketika aku mendekat dan bertanya kepada salah satu dari mereka, dia menjawab sedang menunggu bantuan sosial.
“Hei, bos! Harusnya kamu tak langsung masuk ke kerumunan. Antre, bos!” teriak salah seorang di kerumunan.
Aku buru-buru meninggalkan kerumunan tersebut. Aku berjalan dengan lunglai di pelataran perkantoran yang bagiku tak asing. Ada banyak pamflet digital yang menawarkan lowongan pekerjaan: “Segera! Dibutuhkan psikolog!”
Apakah orang-orang di sini kebanyakan telah gila dan sinting? Bukankah tingginya permintaan berbanding lurus dengan kebutuhan? Memikirkannya lama-lama, sepertinya aku butuh psikolog juga.
Di jalan protokol, kudapati jalanan penuh dengan kendaraan. Jika ingatanku tak salah, ini adalah kemacetan. Bukankah kemacetan seharusnya sudah tak ada dengan program-program pemerintah bahwa sekian tahun lagi negara ini bebas macet, atau kampanye serupa negara ini bebas sampah plastik, atau semacamnya. Dulunya kupikir kampanye itu akan membuat punah pekerjaan pemulung. Tapi pekerjaan itu tetap eksis dan abadi sepanjang usia plastik itu sendiri. Aku terlalu banyak di luar. Kepalaku pening dan kuputuskan untuk pulang dan tidur. Barangkali aku bisa memimpikan Bapak pulang dan Ibu menunggu di depan pintu rumah.
Pakaianku tanggal dan tinggal di ranjang rapuh masa lalu.
•••
AKU terbangun dan aku tidak ke mana-mana. Aku seperti orang linglung, terbata merangkai ingatan dan peristiwa. Beberapa kata bakal, sedang, dan telah hilang. Orang-orang bercakap dengan bahasa baru yang senantiasa asing, begitu asing, dan sangat asing.
Seseorang telah merampas sesuatu dariku, entah apa. Kudengar suara sesenggukan Ibu, entah dari mana. ●
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo