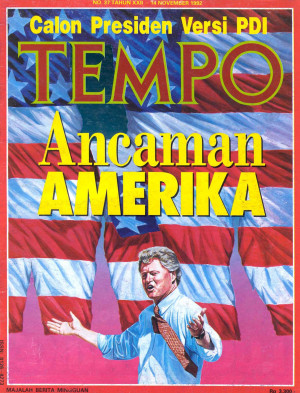PERSIS empat tahun silam, George Bush menjanjikan sebuah Amerika yang lebih "manusiawi dan lembut". Bush menjadi presiden. Tahun ini, karya terbaik World Press Photo 1992 adalah potret seorang serdadu Amerika pada hari terakhir Perang Teluk. Wajahnya yang berlinang air mata -- prajurit itu meratapi rekannya yang tinggal jasad dalam karung mayat di sisinya -- memang bukan lagi wajah Amerika yang beringas dan raksasa. Toh kemanusiaan itu bukan seperti yang dimaksud Bush. Di Amerikanya yang putih bersih, kelembutan itu tak lebih dari sebuah nostalgia tentang kue applepie, bocah-bocah berambut blonda: kelembutan yang harus dibela dengan rudal-rudal nuklir. Sebaliknya, kepedihan sang prajurit yang direkam fotografer David Turnley adalah kemanusiaan yang sebenarnya, yakni yang bisa dirasakan setiap orang -- hitam atau putih, Amerika atau bukan. Maka, kita bisa menengok jauh ke belakang, ke adegan eksekusi dalam lukisan Goya, ke wajah-wajah suku Indian terakhir yang dibantai pasukan jubah biru di Wounded Knee untuk memahami air mata sang prajurit. Tidaklah mengherankan bila karya tersebut mengingatkan juri World Press pada Perang Vietnam: entah berapa juta serdadu Amerika yang pernah mempunyai wajah dan menangis seperti prajurit yang dipotret Turnley. Selain itu, di Vietnamlah pertama kali kepalsuan kata-kata terbongkar oleh rekaman gambar para foto-jurnalis. Dan pertentangan itu belum juga selesai. Saat Perang Teluk, lembaga sensor angkatan bersenjata Amerika bukan cuma berhak membatasi gerak wartawan, tapi juga menyunting hasil liputan mereka sebelum diterbitkan. Untuk menghindari pengawasan, serta bosan memotret tank dan jet Amerika yang pasang aksi di depan musuh yang tak kelihatan, Turnley diam-diam bergabung dengan unit rumah sakit tempur. Di atas helikopter yang mengangkut prajurit luka dan mati itulah, pada hari terakhir pertempuran, ia bertemu dengan serdadu yang menangis. Akibatnya, fotografer kantor foto Black Star itu terpaksa berseteru dengan badan sensor yang "mengamankan" rekaman gambarnya. Turnley menjadi contoh betapa setiap tahun perjuangan para foto-jurnalis menjadi semakin berat. Tapi sensor dan kontrol politik bukan satu-satunya tantangan utama. Beberapa fotografer kini tak lagi puas sekadar menjadi saksi sebuah tragedi. Merasa sebagai tanggung jawabnya memperbaiki dunia, mereka pun memberi contoh nyata. Ini kemajuan dari karya karya World Press Photo terdahulu. Tengok And Baby Makes Five", kisah sehari-hari seorang ibu yang mengandung, menjaga anak, sekaligus mengurusi suami dan rumahnya yang amburadul. Esei-foto ini memenangkan penghargaan khusus Budapest Award karena berhasil mengajak kita tersenyum menyaksikan ketabahan sang ibu. Dalam karya fotografer April Saul itu perasaan iba telah diganti oleh humor dan optimisme. Mungkin itu pertanda kita mulai kembali percaya pada manusia. Dalam Deadwood Creek, Oregon, misalnya, eseis-foto Eugene Richards berkisah tentang anggota-anggota sebuah komune pertanian. Mereka membangun rumah, beternak, dan saling menyayangi sebagaimana layaknya sebuah keluarga besar. Yang tua dirawat bersama yang muda didengar pendapatnya. Ini menjadi bukti bahwa masih ada kapasitas untuk berbuat baik dalam diri manusia. Sebastiao Salgado, rekan Richards di kantor berita foto ternama Magnum, melihat bukti itu di tengah-tengah neraka. Di ladang minyak Kuwait yang ditelan api, foto-foto hitam-putih Salgado menggambarkan para pemadam kebakaran bagai jihad yang menggempur setan. Sayangnya, konteks seperti ini luput dari pameran karya foto-jurnalis Indonesia yang diselenggarakan PWI sebagai pengiring World Press Photo 1992. Masalahnya, orang paling awam bisa paham karya-karya World Press yang dicetak besar, disusun secara konseptual, dan dilengkapi naskah jelas. Tapi, orang yang sama akan mengingat foto-foto hasil perlombaan PWI hanya sebagai sederet judul yang kelewat puitis. Gambar-gambarnya pun dicetak terlalu kecil. Padahal, banyak yang bagus. Misalnya: Hak Azasi karya wartawan Berita Nasional Eddy Hasby, atau Tantangan Seusai Sahur yang dipotret Enday Sudiat dari Pikiran Rakyat. Toh karya-karya itu menjadi serba tanggung karena tampil hanya sebagai gambar lepas yang tanpa ujung-pangkal. Kita pun bertanya, apakah hanya dengan satu gambar, sang foto-jurnalis menganggap tugasnya sebagai saksi dunia selesai. Demikian pula foto kemarau Rully Kesuma akan lebih kuat bila dirangkai dengan karya-karyanya yang lain tentang tragedi Kedungombo. Satu gambar memang berbicara seribu kata, tapi kita jangan lupa bahwa satu momen bukan substitusi dari seribu penderitaan atau seribu tahun. Sebagai perbandingan, perlombaan yang diselenggarakan yayasan World Press Photo sudah berlangsung hampir empat dasawarsa -- artinya sejak perang dingin, Vietnam, AIDS, dan kelaparan Etiopia, sampai menghilangnya Uni Soviet. Selama itu, ia menjadi semacam barometer dunia. Karya yang menang tahun ini bagai musim Semi dibanding visi pesimistis World Press 1991. Dan bagaimana kita menyelamatkan dunia sangat bergantung pada bagaimana kita memandang dunia itu: paling tidak, itu yang kita pelajari dari kesaksian April Saul, Eugene Richards, dan Salgado tahun ini. Siapa tahu, suatu hari dunia yang lembut dan manusiawi itu berhenti menjadi kata-kata. Dan mulai menjadi kenyataan. Yudhi Soerjoatmodjo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini