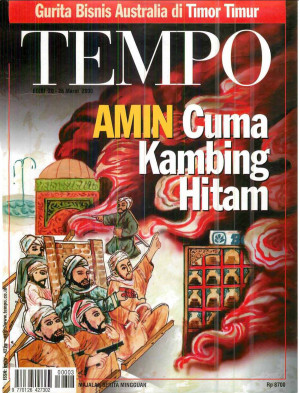Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penghancuran musik semacam itu tentu bukanlah yang pertama kali dilakukan. Pada 1979, kelompok musik punk asal Inggris, Sex Pistols, mengobrak-abrik karya agung sang flamboyan Frank Sinatra, My Way. Keindahan tembang legendaris itu seolah punah, digantikan oleh suara yang sember dan musik yang ribut. Anehnya, remaja Inggris waktu itu berjingkrak-jingkrak senang.
Kecenderungan mendekonstruksi harmonisasi lagu ini boleh jadi merupakan sikap pemberontakan kelompok ini terhadap kemapanan. Namun, yang tidak bisa disangkal, cara semacam itu mampu mendongkrak popularitas kelompok generasi baru musisi Indonesia dalam waktu yang singkat. Kelompok Sex Pistols, yang sebelumnya memang sudah banyak dikenal, makin meroket saja namanya setelah melantunkan tembang My Way dengan gaya itu.
Hal itu pula yang dialami kelompok Netral. Kelompok musik dengan penjaga gawang Bagus, Mitend, dan Bimo (drummer saat itu)—sebelumnya mereka melemparkan lagu Wa..lah!—tiba-tiba menjadi perbincangan khalayak musik Indonesia pada 1994, salah satunya karena mereka ”merusak” harmoni lagu itu. ”Musik mereka, untuk ukuran Indonesia, memang baru. Pada masa lalu, (musik seperti ini) barangkali tak mungkin ada,” ujar Ian Antono, gitaris God Bless. Album pertama kelompok Netral, yang bertajuk Netral, pada 1994 itu memang terbilang baru, terutama karena gaya punk dalam album itu.
Akibatnya, kesuksesan album itu membuat kelompok Netral masuk ke dalam daftar ”ikon” baru industri musik Indonesia. Bersama kelompok musik lainnya seperti Slank, Pas, Dewa 19 dan Gigi, kehadiran kelompok Netral bagai buldoser yang menggusur generasi sebelumnya, yang menjadi raja dan menguasai pasar musik waktu itu. Nama besar seperti God Bless atau Iwan Fals, yang semula menjadi idola, tiba-tiba terlihat renta dan kikuk untuk bersaing dengan generasi ini.
Kehadirannya terasa mendadak dan nyaris berbarengan. Namun, bila dirunut ke belakang, kelompok Slank boleh disebut sebagai perintis jalan buat serombongan kelompok musik generasi baru yang kemudian menyusul di belakangnya. Awalnya, grup musik yang dimotori Bimbim ini berdiri pada 1983 dengan nama Cikini Stones Complex. Mereka membawakan lagu-lagu The Rolling Stones. Setelah malang melintang dari panggung ke panggung, pada 1990, mereka memutuskan untuk rekaman.
Namun, demo kaset Slank selalu ditolak oleh perusahaan rekaman besar. Alasannya, musik mereka tak laku dijual. Bisa dimaklumi, akhir dekade 1980, pasar musik didominasi God Bless atau Nicky Astria. Akibatnya, siapa pun yang mencoba masuk ke dalam industri ini setidaknya harus berbau seperti dua nama kondang itu. ”Sudah, deh, kami sembarangan saja. Terserah mau bikin album apa,” kata Bimbim, penabuh drum sekaligus penggagas band ini.
Mereka memutuskan untuk melawan dengan musik rock and roll dengan sentuhan balada yang ”bluesy”, sedangkan lirik-liriknya berkesan seenaknya. Perlahan tapi pasti, kelompok Slank mulai menempati posisi teratas dalam industri musik kala itu. Album mereka, Suit, Suit, He-he-he (1989), laku keras. Keberhasilan kelompok Slank memicu anak-anak muda lainnya untuk mengikuti jejak serupa. Salah satunya adalah kelompok Dewa 19, yang meluncur dalam kemasan pop yang manis.
Pada saat yang bersamaan, di belahan dunia lain tengah berkecamuk sebuah epidemi yang cakarnya begitu mengoyak. Tiga pemuda asal Kota Seattle, Amerika Serikat, Kurt Cobain, Chris Novoselic, dan Dave Grohl, mengibarkan sebuah warna musik yang terdengar tak lazim, grunge. Album kedua Nirvana, Never Mind (1991), meledak dan laku hingga 4 juta kopi. Album yang fenomenal ini mampu menyeret mereka menduduki posisi puncak tangga lagu di pelbagai negara. Kesuksesan ini membuat popularitas kelompok Nirvana melonjak melebihi Michael Jackson. Dunia pun langsung dibekap Seattle Sound. Pada remaja menggila-gilai musik ”baru” ini. Mereka membawakan musik yang mirip Pearl Jam dan Nirvana.
Sebetulnya tidak ada yang tahu persis asal kata grunge. Kata terdekat adalah grungy, yang bermakna sampah. Pemberian nama ini agaknya didasari penilaian kritikus musik terhadap perkembangan kelompok musik yang berkembang di Seattle, yang berasal dari glam rock yang enteng, menjadi lebih keras dan kasar. Dan kelompok Nirvana berhasil mengubah sound musik. Bunyi gitar yang meraung digantikan dentuman bas dan ketukan drum yang kentara, sehingga iramanya cenderung mudah dicerna dan terasa lebih ngepop.
Kurt Cobain lantas menjadi dewa. Lirik yang berbau kemarahan dan keputusasaan membuat dia ditahbiskan sebagai juru bicara ”Generasi X”. Pers mulai mengusik kehidupan pribadinya. Perlakuan itu menjebloskannya dalam ke keadaan yang menyiksanya. Cobain menembak kepalanya pada 8 April, 1994. Kematian itu pula yang mengakhiri era grunge. Pihak industri musik mencoba berpaling pada Pearl Jam dan Sound Garden untuk menggantikan sosok Nirvana. Tapi, Eddie Vedder bukanlah Cobain. Ia cenderung menjauhi pers. Grunge tak bisa dipisahkan dari Nirvana dan Cobain.
Meski cuma berumur jagung, kehadiran mereka mampu melibas jenis musik lainnya. Bintang besar redup cahayanya tersapu lagu Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Bon Jovi terpaksa harus memasukkan unsur-unsur grunge dalam musiknya. Lebih gawat lagi, kelompok speed metal seperti Metallica secara tegas mulai mengubah pola bermusiknya.
Fenomena ini juga hinggap di Indonesia. Bukan hal yang aneh, memang. Perkembangan industri musik di Indonesia selalu mengikuti trend yang terjadi di Amerika Serikat, yang menjadi kiblat musik dunia. Apa saja yang terjadi di sana biasanya dengan cepat mengimbas ke Indonesia. ”Referensi anak-anak muda sebagian besar dari luar negeri. Dengan referensi tersebut, pemusik-pemusik di sini bisa menciptakan hal baru yang segar,” kata Jan N. Djuhana, Artist and Repertoire Director PT Sony Music Indonesia.
Keadaan ini sangat dipengaruhi kiprah kapitalis musik dunia seperti Warner, Sony Music, EMI, yang memiliki jangkauan distribusi yang luas. Perusahaan-perusahaan rekaman besar—lazim disebut major label—dengan gencar menawarkan musik yang bentuknya sudah direkayasa untuk kemudian dijual ke seluruh jagat raya. Para ”penguasa industri musik” ini memilih grunge, saat heavy metal—yang sebelumnya jadi tambang uang— telah kehabisan tenaga. Sebagai produk dagangan, grunge kemudian dikemas dengan sempurna.
Hal ini juga diperkuat dengan kehadiran saluran televisi musik MTV, yang mengudara selama 24 jam nonstop. Stasiun televisi yang mengkhususkan diri untuk menayangkan acara musik itu memutar klip video musik dengan sebuah gaya baru yang pada gilirannya disebut sebagai gaya MTV. Akibat pengaruh global itu, citra rasa menjadi mulai ”seragam”. Saluran musik ini juga memperkenalkan gaya menikmati musik yang baru. MTV kemudian melakukan sebuah terobosan secara audio dan visual, sehingga ia bukan cuma memberi pengaruh yang dahsyat pada kecenderungan bermusik, tetapi juga pada busana dan gaya hidup musisi dunia.
Pengaruh MTV yang begitu mencerap pemirsanya, yang notabene anak-anak muda, telah membuat dunia berubah menjadi sebentuk kotak kaca yang hadir di kamar ataupun ruang keluarga, menyajikan klip band-band Seattle secara konstan dan habis-habisan. Sementara itu, media asing, majalah lokal, serta radio-radio sedunia seakan berlomba-lomba mengupas fenomena musik ”baru” ini.
Akibatnya, anak-anak muda di Indonesia pun terimbas epidemi gaya dan musik khas Nirvana, yang kemudian sempat mendapat julukan sebagai ”musik alternatif”. Selanjutnya, musik gaya ”baru” ini tiba-tiba meruyak hingga ke kota kecil sekalipun. Pergelaran musik alternatif tiba-tiba bagai jamur di musim hujan. Mereka melakukan ”moshing”, tarian khas musik alternatif. Gaya rambut poni, janggut kecil seujung rumput, celana jins sobek, dan kaus oblong menjadi pemandangan yang umum saat itu.
Satu peristiwa penting yang tak boleh dilupakan adalah digelarnya Jakarta Alternative Festival, awal 1996. Saat itu, ”pembesar” musik alternatif macam Foo Fighter manggung di Jakarta bersama band-band lokal, di antaranya Pas Band. Pergelaran ini bagai bensin yang menyiram api. Mendadak sontak, band baru bermunculan. Mereka membawakan musik dengan irama yang kencang dengan lirik bahasa Inggris.
Umumnya lirik musik kelompok generasi baru seperti Pas ini berisi ketimpangan sosial. Bahkan, ada beberapa lagu yang isi liriknya, dalam lagu Impresi yang ditulis Yukie dan Pas, dianggap ”keras”:
”…aku sudah bosan dengarkan kata-kata
aku sudah muak dengarkan ceritaku
aku sudah lelah dengan harapan
aku mulai muak dengarkan ceritamu….”
Lirik ini sebetulnya sungguh biasa saja dibandingkan dengan, katakanlah, protes sosial dalam lirik lagu-lagu Iwan Fals. Tetapi, toh, klip video kelompok ini ditolak untuk ditayangkan stasiun televisi negeri ini. Alasannya, klip video itu menayangkan adegan live lengkap dengan adegan moshing (tarian khas alternatif ketika salah satu penonton dengan sikap telentang akan diusung oleh puluhan penonton lain ke panggung), sementara Yuki, sang vokalis, membuka baju dan bertelanjang dada. ”Pihak stasiun televisi menganggap kami seperti tengah mabuk,” kata Richard Mutter, eks-drummer Pas. Yang menarik, klip video lagu ini malah mendapat sambutan di layar MTV Asia.
Secara umum, lirik musik kelompok-kelompok musik ini menunjukkan sebuah keprihatinan tentang keadaan sosial di Indonesia. Bisa dimaklumi, kebanyakan band jenis ini seperti Koil, Kubik, Cherry Bombshell, Waiting Room, LFM, dan Plastik lahir dan besar dari pergaulan mereka di kampus. Maka, pers kemudian menggolongkan mereka sebagai pengusung musik alternatif.
Lalu, apa sesungguhnya musik alternatif? Kelompok mana saja yang bisa dikategorikan sebagai pembawa musik itu? Dan apakah ini sebuah ”aliran” baru? Erwin Gutawa, arranger kondang, menyatakan musik alternatif merupakan perkembangan dari musik-musik yang lebih banyak memiliki unsur rock ketimbang unsur aliran lain. Unsur-unsur lain yang terdapat dalam musik lain begitu beragam, dari jazz, pop, klasik, hingga musik etnik. Selain itu, menurut Erwin, ia juga melihat gejala ini hanya sebagai istilah yang terdapat dalam industri musik.
”Dalam konteks industri, alternatif menjadi suatu istilah yang bermakna musik yang berkembang lima tahun terakhir,” tutur Erwin. Ia menganggap musik alternatif di Indonesia lahir karena mengikuti gejala saja, sedangkan para pemain band itu tampaknya tak tahu, tak paham (bahkan mungkin tak peduli) dengan spirit musik itu.
Berbeda dengan para pemusik pendahulunya, meski cengkeraman budaya global begitu kuat, para pemusik generasi baru ini tak lantas mengekor saja sosok musisi idolanya. Tampaknya, soal identitas dan ”harga diri” menjadi hal penting, meski memang inspirasi awal musik generasi ini tentu lahir dari berbagai kelompok musik negara Barat. Kelompok Dewa 19 pada masa awalnya bahkan mengakui banyak mendapat pengaruh dari kelompok musik Toto, misalnya. Kelompok musik alternatif di Indonesia memang sempat membawakan lagu-lagu kelompok besar Amerika, tapi belakangan timbul semacam ”pencerahan”. Mereka membuat lagu sendiri dengan gaya dan cara bermusik sendiri, meskipun pengaruh musisi luar itu begitu kuat. ”Mereka membuat lagu apa adanya saja. Mereka menerapkan warna musik, bukan konsep” ungkap gitaris God Bless, Ian Antono.
Hal itu tentu tak terjadi pada generasi sebelumnya. Band macam Cockpit, God Bless, Rollies, atau Acid Speed Band, yang malang melintang pada dekade 1970-1980, lebih banyak membawakan lagu-lagu milik kelompok lain. Malah kemudian, mereka rela menjadi imitator band-band itu. Sampai sekarang, Cockpit lebih dikenal sebagai ”Genesis” dari Indonesia, sedangkan Acid Speed Band mengkloning dirinya seperti The Rolling Stones.
PARA MUSISI generasi musik alternatif ini—dengan segala keunikannya itu—tampaknya harus berjuang sangat keras. Maklum, habitat musik mereka masih terasa kecil. Tak aneh bahwa perusahaan rekaman pada mulanya agak ogah memberikan kesempatan kepada pendatang baru itu. Keadaan semacam ini tak ubahnya seperti leher botol, besar di tengah tapi menyempit di pintu keluar. Kesempatan untuk keluar menjadi sebuah bintang teramat sulit. Terlebih lagi, musik yang dimainkan saat itu bak bunyi yang berasal dari planet lain. Aneh, bising, tak merdu, dan ini yang penting: kagak komersial.
Dengan pertimbangan bisnis, pihak perusahaan rekaman cuma melirik mereka yang telah ketahuan bakal laku dijual. Jangan heran jika pada masa itu, nama-nama yang sudah punya banyak penggemar macam KLA Project-lah yang lebih disambangi produser. Buat pendatang baru? Sori, pintu masih digembok.
Namun, itu tak bikin mereka patah arang. Mereka merekam lagu-lagu sendiri dan menjualnya sendiri, tak peduli bakal laku atau tidak. Dalam benaknya, yang penting karya mereka bisa sampai pada komunitasnya. Dengan cara bergerilya, mereka membuat jalur distribusi sendiri. Cara demikian ini dikenal dengan nama independent label. Gaya distribusi yang berawal dari Amerika pada dekade 1970 itu akhirnya menjadi jawaban terhadap pongahnya perusahaan besar yang cuma mau melirik artis-artis yang sudah terkenal.
Lewat cara itu, mereka yang tak punya akses ke perusahaan besar bisa dengan segera menjual karyanya, meski dalam jangkauan yang terbatas. Seperti dikatakan Bruce Iglauer, Presiden Alligator Records di AS—perusahan rekaman independen yang berdiri pada 1971—kelahiran sebuah generasi baru berasal dari komunitas independen dalam kancah industri. Nah, sedikit demi sedikit, upaya mereka berbuah hasil positif.
Pas Band, kelompok musik dari Bandung, adalah salah satu yang segera mencomot gaya gerilya ini. Pada 1994, diawali dengan ide dari Samuel Marudut (almarhum), seorang penyiar Radio GMR Bandung membuat terobosan baru. Saat itu, popularitasnya di Bandung tengah menanjak. Mereka mencoba peruntungan dengan membuat kaset demo yang kemudian dijajakan kepada berbagai perusahaan rekaman, tapi selalu ditolak. Alasannya, biasa…, alasan klise: tak layak jual.
Mereka potong kompas. Dimodali orang tua salah satu kawan, mereka langsung tancap gas bikin kaset. Uang itu dipakai untuk biaya rekaman, membuat master, dan menduplikasikan menjadi 6.000 kepingan kaset. ”Saat itu kami sudah menggunakan studio beneran, pakai 24 track,” tutur Richard Mutter, penabuh drum Pas Band. Hasilnya, bak salesman, mereka menjual secara door-to-door. ”Soalnya, memang sudah tidak ada harapan lagi untuk bekerja sama dengan major label. Kaset itu ditawarkan kepada teman atau dititipkan di penjual kaset di pinggir-pinggir jalan,” ujar Denny M.R., manajer Pas.
Hasilnya? Cukup mengejutkan. Empat lagu yang bertajuk Four through the SAP itu hampir ludes dalam waktu singkat. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan kaset—yang dijual per keping Rp 5.000—itu bisa dipakai untuk mengembalikan utang kepada pemilik modal awal, sedangkan sisanya dipakai untuk melancong ke Singapura selama beberapa hari.
”Mereka seperti merombak pakem,” tutur pengamat industri musik, Theodore K.S. ”Kelompok ini tidak mengikuti alur industri, tapi toh pada akhirnya mereka masuk juga dalam industri. Sebab, kalau hanya bertumpu pada ”indie” label, gerak mereka menjadi sangat terbatas. Ketika mereka sudah eksis, kalangan industri segera melirik,” kata Theodore. Theo boleh jadi benar. Sukses yang diraup Pas itu membuat mereka dilirik Aquarius, perusahaan yang sebelumnya pernah menolak demo kelompok Pas. Nama lainnya, Noin Bullet, yang meluncur di jalur ska, mengawali langkahnya di dunia ”indie”. Jalur independen di dunia industri musik Indonesia akhirnya menjadi jalan lain untuk masuk ke label mayor.
Setidaknya, hal ini bisa dilihat dari jumlah demo lagu yang masuk ke perusahaan rekaman. Sony Music Indonesia, misalnya, setiap bulan menerima 60 hingga 70 buah demo. Selanjutnya, demo-demo itu diseleksi berdasarkan aroma komersial yang dikandungnya. Bila nalurinya tepat, keuntungan besar bisa segera diraup. Jan N. Djuhana dari Sony Music menyebutkan, lebih dari 50 persen keuntungan perusahaannya berasal dari kelompok musik pendatang baru. Ia memberi contoh kelompok Sheila on 7, yang kasetnya terjual di atas 700 ribu kopi. Itu artinya sama dengan tingkat penjualan lima album yang mendapat platinum.
Namun, kerja pihak perusahaan rekaman tidak lantas berhenti di situ. Mereka harus memelihara kelompok musik itu sebagai aset. ”Caranya, kami memintanya membuat lagu yang cocok dengan kriteria mereka,” kata Chairul Saleh, Manajer Promosi Aquarius. Namun, hal itu bukan berarti kebebasan sepenuhnya milik sang artis. Bagaimanapun, menurut Chairul, pihak perusahaan rekaman mempunyai kesepakatan dengan para pemusik.
Hal itu pula yang membuat beberapa kelompok musik lebih suka berada di jalur indie. Kelompok Puppen, misalnya—yang dikenal sebagai kelompok hardcore—memilih memasarkan dua album melalui perusahaan rekamannya sendiri, Pup Record. ”Masalahnya, pihak major label suka banyak maunya dan meminta kami untuk mengikuti kemauan mereka,” kata Richard Mutter, yang pernah membuat proyek kompilasi indie label bertajuk Masa Indah Banget Sekali Pisan, yang pada 1997 menampilkan sekitar 15 band baru.
Apa kata pihak produser? ”Sikap musik mereka memang tergolong keras. Mereka relatif sulit untuk diatur,” kata Seno M. Hardjo, produser yang beberapa kali meluncurkan album musik tak lazim ini dengan label ”Target Pro”. Hal itu menurut Seno tidak saja terjadi pada kelompok musik besar seperti Dewa 19, yang bisa menaklukkan produsernya, tapi juga pada kelompok musik yang baru muncul.
Upaya ini patut diacungi jempol. Hal ini juga bisa memperbaiki posisi tawar-menawar dengan produser yang pada masa silam begitu perkasa mendikte para artisnya. Dan keteguhan sikap itu berbuah hasil: perusahan major label seperti Aquarius ternyata menangani Suckerhead, Edane, Flowers, Dewa 19, Tipe-X, Pas, Romeo, dan Protonema.
Dewa 19 adalah kelompok yang kasetnya terjual dalam jumlah besar. ”Album Pandawa Lima laku 900 ribu kopi. Album terbaru Pas Band, Psyco Id, terjual mencapai 75 ribu kopi,” ujar Seno. Sedangkan penjualan album kelompok Slank rata-rata bisa mencapai angka 200 ribu keping setiap album. Sebuah prestasi—karena industri rekaman tentu saja mempunyai ukuran sukses yang dihitung berdasarkan jumlah kaset yang terjual—yang sulit dicapai kelompok musik pada masa lalu.
KEBERHASILAN ini tentu saja ikut mempengaruhi gaya hidup kelompok generasi muda musisi Indonesia. Banyak di antara mereka yang meng-investasikan hasil keringatnya untuk memenuhi kebutuhan bermusik, misalnya dengan membangun studio musik. Tampaknya timbul kesadaran untuk mempertebal sikap profesionalisme bermusik. Tapi, di sisi lain, ada juga di antara mereka yang terperosok dalam kubangan narkotik (lihat tulisan tentang hubungan pemusik dan narkotik—Red).
Waktu pun terus bergerak. Perkembangan musik kiwari terbilang sangat cepat. Dunia sudah begitu sempit. Apa yang tengah menggejala di Amerika Serikat serta-merta segera mengimbas ke negeri ini. Musik alternatif, yang rasanya baru saja menderu, seperti sudah ketinggalan dengan bermunculannya musik-musik baru.
Apa yang sempat dinamakan ”musik alternatif” mampus sudah, meski penggantinya pun dianggap sebagai alternatif dari yang ada. Ia digantikan musik ”electronica”, yang sempat diminati anak-anak muda, dengan penyajinya macam Prodigy atau Chemical Brothers. Pelakon lokalnya: Agus Sasongko, yang sempat mengeluarkan dua album. Namun, belum sempat jenis musik itu menggoyang, ia seperti tenggelam digempur musik baru, yaitu jenis musik ska. Nah, sekarang, hip metal siap menerkam. Seperti biasa, aliran musik ini telah memiliki pengusungnya, salah satunya adalah kelompok Brain Machine.
Namun, harus diakui, durasi dan ketahanan musik ska dan heap metal masih dipertanyakan, juga keabadian dan pengaruhnya terhadap gaya hidup anak-anak muda masa kini.
Kehadiran generasi baru musik Indonesia, dengan segala pernik musik yang dibawanya, agaknya belum bisa menjawab pertanyaan esensi: seperti apakah musik Indonesia yang sesungguhnya? Yang terjadi, musik para musisi generasi kini hanya memasukkan bahasa Indonesia dalam lirik, sementara ”bau” musik Barat tetap tidak hilang. Tampaknya, selama Amerika menjadi kiblat musik, munculnya musik yang memiliki ciri khas Indonesia tetap cuma angan-angan.
Irfan Budiman, Agus Slamet Riyanto, Andari Karina Anom, Dwi Arjanto, Dwi Wiyana
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo