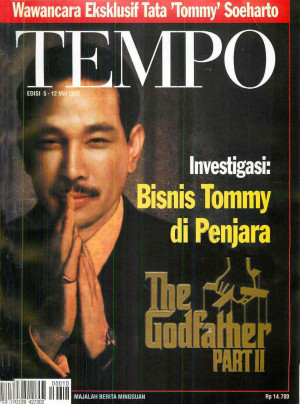Voices of the Puppet Master: the Wayang Golek Theater of Indonesia
Penulis : Mimi Herbert
Fotografer : Tara Sastrowardoyo
Penerbit : Yayasan Lontar
BABAKAN Losari adalah sebuah desa yang berisi para penari topeng dan wayang golek. Seolah bakat itu turun dari langit ke tubuh, dalang wayang golek di sana sudah memasuki generasi ke-22. Adalah Mimi Herbert, sarjana sejarah seni Asia Tenggara dari Universitas Pennsylvania, yang memutuskan untuk datang ke desa yang letaknya 30 kilometer dari Cirebon Timur itu.
Ia ”sowan” ke tempat Kamarudin, seorang dalang wayang cepak, sanak dekat almarhum penari topeng legendaris Sawitri. Kamarudin, 60 tahun, memperlihatkan sebuah wayang golek ber-karakter tokoh Walang Sungsang yang berumur 300 tahun.
Herbert kemudian mengembara dari satu desa di Cirebon sampai desa-desa di kabupaten-kabupaten Bandung, menemui para dalang tua dan perajin wayang golek. Ia menemui sesepuh seperti Otong Rasta, Aki Mama Taryat, dan Endang Subrata. Hasilnya adalah buku berjudul Voices of the Puppet Master: the Wayang Golek Theater of Indonesia yang memikat. Buku setebal 250 halaman yang dijual seharga Rp 450 ribu itu begitu dipersiapkan secara serius dan dilengkapi dengan serangkaian foto fotografer Tara Sastrowardoyo bersama serombongan fotografer asing.
Melalui buku ini, rasanya dengan mudah kita bisa segera menangkap bahwa dalam jagat wayang golek sesungguhnya ada dua genre besar, yaitu wayang golek parwa dan wayang golek menak. Para dalang di Bandung, Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Banten, dan beberapa kota lain di Jawa Barat umumnya memainkan wayang golek parwa, yang kisah-kisahnya bersumber dari khazanah Mahabarata dan Ramayana. Sedangkan rata-rata dalang dari Cirebon dan Tegal memainkan wayang golek menak, yang bersumber dari Serat Menak, kisah Panji dan Amir Hamzah, yakni sebuah genre yang kerap menceritakan asal-usul Nabi Muhammad.
Dalam menyajikan semua itu, Mimi Herbert tidak pretensius. Buku ini bukan tulisan ilmiah dan tidak menampilkan referensi yang membuat kening berkerut. Bak yang dilakukan wartawan, Herbert melakukan wawancara mendalam. Gaya penulisannya menyajikan kutipan-kutipan langsung yang rileks dan intim dari para dalang. Bahkan ia melakukan—yang kini mulai jarang dilakukan wartawan karena kemalasan dan kedunguan—reportase yang basah tentang kehidupan sehari-hari. Melalui reportase itu, pembaca dapat merengkuh suasana. Alhasil, ini adalah sebuah feature yang menawan tentang profil para dalang. Dari tuturan langsung sang dalang, Herbert menggali banyak hal, dari pakem-pakem, musik, gaya pe-dalangan, hingga cara pembelajaran.
Mimi Herbert, yang juga dikenal sebagai pematung, agaknya peka ter-hadap anatomi. Pertanyaannya mampu menggali ”ilmu” para dalang hingga mereka mau bercerita dengan rinci tentang perbedaan ornamen dan motif kostum. Kita disadarkan bahwa wayang kulit gaya Solo atau Yogya memiliki perbedaan karakter tatahan. Tatahan dahi kepala wayang golek Cirebonan, misalnya, umumya datar sehingga disebut wayang cepak.
Herbert juga menyajikan peristiwa yang menggetarkan. Saat ia nyasar ke tempat perajin wayang golek di Desa Ciberu, sebuah desa miskin, 25 kilometer dari Bandung Utara, ia bertemu dengan Aki Supatma, bekas maestro wayang golek. Umur Aki Supatma diperkirakan 119 tahun. Tubuhnya sudah ringkih, nyaris hanya terdiri atas tulang. Giginya ompong. Saat wawancara, karena bergairah, ia tiba-tiba mengenakan topeng Cepot, menggerakkan kepalanya, dan astaga… ia menari!
Herbert juga mengarungi ”suasana mistis” pertunjukan. Ia mengikuti ruwatan yang dilakukan Aki Mama Taryat dari dini hari sampai selepas subuh. Kepadanya, Kamarudin bercerita pernah menggelarkan kisah Hasan Husen gugur—cerita putra Sayyidina Ali dan cucu Nabi yang tewas dibantai Muawiyah itu—dalam pesta perkawinan. Percaya atau tidak, perkawinan itu langsung retak.
Tak ketinggalan, Herbert menampilkan Kathey Foley, pengajar wayang golek dan tari topeng Sunda di Universitas California Santa Cruz. Foley adalah dosen yang memukau hadirin Kongres Internasional I Kebudayaan lantaran bahasa Sundanya yang meluncur deras bak mojang Priangan. Foley pulalah yang kerap menggarap mitologi Barat ke dalam gaya golek Sunda. Bekerja sama dengan komposer Lou Harrison, ia misalnya mengangkat kisah Faust dan Helen Troy dengan struktur dan boneka-boneka ala wayang golek.
Karena foto-foto buku ini menampilkan koleksi wayang cepak yang dimiliki para dalang, buku ini juga bisa disebut sebuah dokumentasi. Maklum, dulu para dalang membuat wayang golek sendiri, terutama tokoh favoritnya. Banyak keluarga dalang yang masih menyimpan koleksi turun-temurun itu—karena biasanya dianggap magis. Aki Supatma, misalnya, tiba-tiba mengeluarkan kepala Gatotkaca yang disimpannya di kotak puluhan tahun dan jarang diperlihatkan ke orang lain. ”Kakek saya yang bikin ini,” katanya.
Selain foto-foto wayang golek, ditampilkan juga foto-foto suasana keseharian kecintaan masyarakat Sunda terhadap wayang golek. Pembaca dapat melihat bagaimana anak-anak Asep Sunarya bermain wayang di belakang panggung. Sayang, foto seperti ini tak banyak tampil, padahal itu akan membuat pembaca mendapatkan gambaran betapa wayang golek meresap ke bawah sadar masyarakat. Yang juga membuat secara visual desain buku ini menarik adalah ditampilkannya sketsa karya Herbert yang membuat ilustrasi Cepot, Batari Durga, Arjuna, dan Arimba. Goresan pensilnya tak kalah dengan sketsa perupa Indonesia.
Buku ini mungkin tidak menyajikan sebuah gambaran komplet. Masih banyak persoalan dalang Sunda yang belum disentuh, misalnya hubungan antara wayang golek dan wayang potehi.
Melalui buku ini, Mimi Herbert mendeskripsikan bagaimana generasi muda dalang wayang golek berusaha sekuat tenaga mengalahkan VCD yang merasuk ke desa-desa. ”Hidup wayang golek lebih lama dari hidup kita semua,” kata Aki Supatma, yang usianya di batas senja itu. Ini adalah kalimat yang mengharukan, yang bernada harapan, nasihat, dan juga penuh harga diri. Harapan itu adalah keinginan agar wayang golek tetap selamanya langgeng, tanpa mengkhianati spirit sakralnya. Inilah buku tentang hati nurani para dalang wayang golek.
Seno Joko Suyono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini