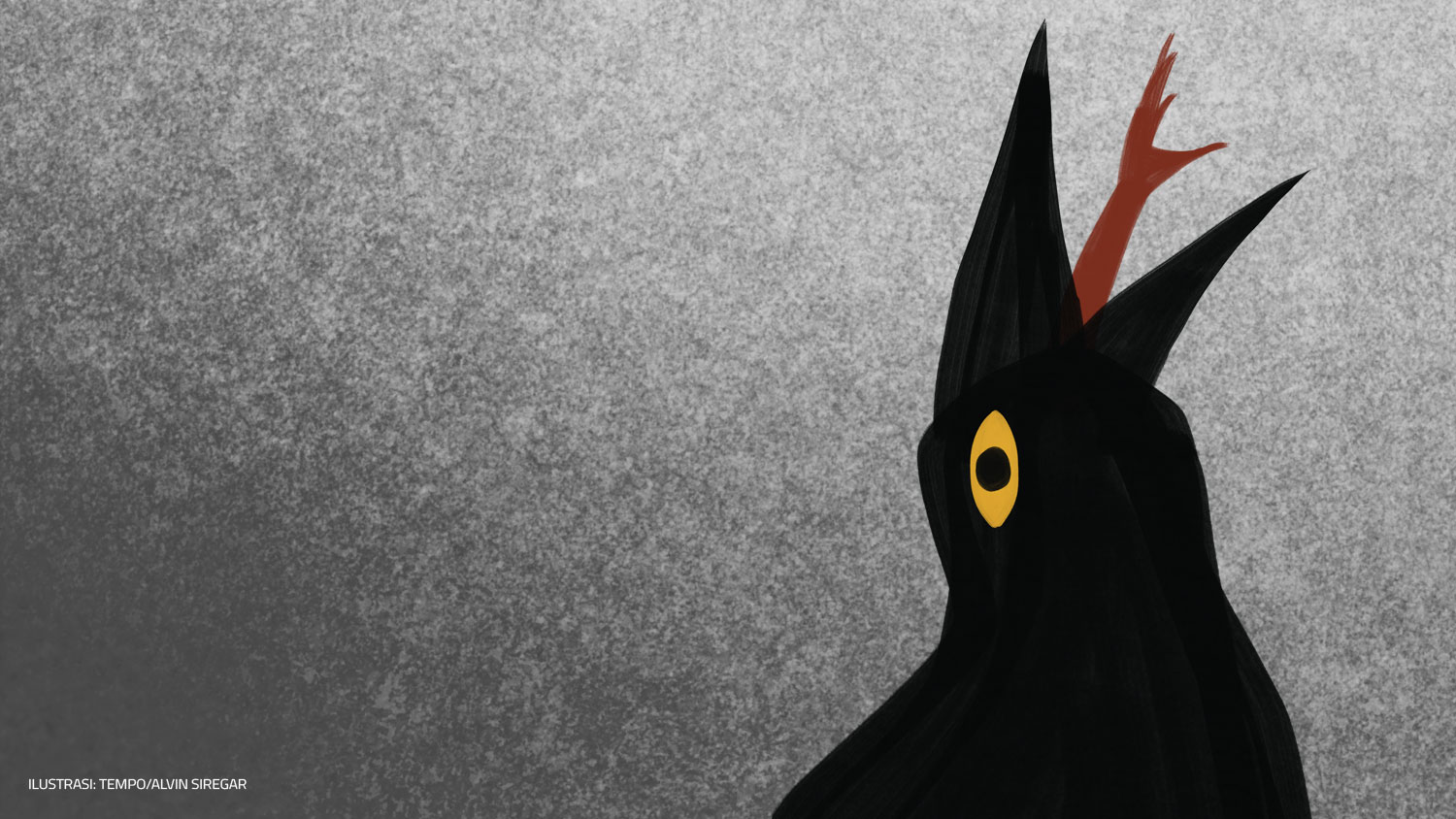Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kawat-kawat besi antikarat itu melengkung-lengkung membentuk dua kerangka kapal tradisional Cina setinggi orang dewasa yang tegak di atas sepasang sepatu kayu. Bayangan kerangka kapal itu jatuh ke layar di belakangnya, yang menayangkan Laut Jawa dan beberapa kapal nun di ufuk yang tampak bergoyang-goyang diayun gelombang.
Suara pecahan ombak dan desiran angin laut menjadi latar musik yang membuai penonton yang menikmati instalasi The Coasters karya perupa Nindityo Adipurnomo dan istrinya, Mella Jaarsma. Berdirilah di atas sepasang sepatu kayu itu, maka Anda akan merasakan sensasi seolah-olah terbawa kapal kuno tersebut berlayar menuju cakrawala.
Karya itu dipajang dalam pameran seni rupa "Toekar Tambah" di Semarang Contemporary Art Gallery, Jalan Taman Srigunting Nomor 4-5, Semarang, sejak Ahad pekan lalu hingga 10 Maret nanti. The Coasters diciptakan Nindityo khusus untuk anak-anak dan pertama kali dipamerkan di Belanda tahun lalu. Karya itu mengajak pengunjung membayangkan orang yang hidup berabad lampau yang meninggalkan keluarga mereka untuk berlayar mengarungi lautan penuh marabahaya buat mencapai tanah asing yang penuh hal baru dan ketidakpastian. Hal itulah yang dilakukan orang Cina yang akhirnya tiba di pulau-pulau Nusantara, termasuk Jawa.
Pameran ini merupakan terjemahan dari riset dan studi budaya asimilasi Cina peranakan di Kota Semarang dan Lasem, Rembang, Jawa Tengah, selama setahun lebih. Nindityo dan Mella termasuk seniman terkemuka di dunia seni rupa kontemporer Indonesia. Keduanya alumnus Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan sama-sama tertarik pada kajian sejarah dan budaya, yang kemudian diterjemahkan dalam karya seni rupa.
Nindityo sebelumnya memusatkan perhatiannya pada budaya Jawa, khususnya sanggul atau konde. "Kini saya bergeser pada budaya Cina peranakan, yang juga tak kalah kompleksnya," kata pendiri Rumah Seni Cemeti Yogyakarta itu.
Nindityo menuturkan, dalam penelusurannya, kaum Cina peranakan muncul di Indonesia sejak abad ketujuh dan memiliki dampak budaya yang kuat, karena bercampur dengan berbagai ras yang ada di Indonesia. Hal ini yang membedakan keberadaan Cina peranakan di Indonesia dengan Cina peranakan di kawasan lain di Asia Tenggara, seperti Singapura dan Malaysia.
Kelebihan Cina peranakan adalah kelenturannya dengan budaya setempat, sehingga akulturasi bisa berjalan secara alamiah. Sayangnya, kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda mencederai akulturasi tersebut dengan memisahkan komunitas Cina peranakan dengan komunitas ras lain. Nindityo, yang lahir pada 1961 dan besar di kawasan Kota Lama Semarang, menjelaskan, sebelumnya kawasan pecinan Semarang berada di sepanjang pantai. Tapi Belanda mengubah sebagian kawasan itu menjadi perumahan dan pusat bisnis Belanda, yang kini menjadi kawasan Kota Lama Semarang.
Diskriminasi politik ini diteruskan oleh pemerintah Indonesia, terutama oleh Presiden Soeharto. Komunitas Cina peranakan selalu dijadikan kambing hitam jika konflik sosial terjadi, seperti menuduh rumah mereka sebagai tempat pertemuan pelaku kerusuhan. Saat di Lasem, misalnya, Nindityo dan Mella menemukan belasan rumah tua dengan arsitektur Cina dengan atap pelana kuda sebagai ciri utamanya. Rumah-rumah tersebut dalam kondisi tak terawat. Temboknya dipenuhi lumut dan rumput. Beberapa daun pintunya berlubang, yang tampaknya sengaja dibikin oleh aparat pemerintah untuk mengawasi kegiatan penghuninya. Berdasarkan pengalaman itu, sang pemilik rumah merasa ragu akan ketulusan pemerintah dalam menawarkan rumah-rumah tersebut sebagai bangunan cagar budaya.
Atas perlakuan itu, banyak kaum Cina peranakan yang melakukan eksodus ke Singapura. Pada awal kemerdekaan Indonesia, misalnya, keturunan raja gula Semarang, Oey Thiong Ham, memilih tinggal di Singapura. "Cerita keturunan Cina lebih nyaman berinvestasi di Singapura sudah berlangsung sejak dulu," kata Nindityo.
Sikap berbeda ditunjukkan oleh Singapura atau Malaysia, yang mampu memanfaatkan keberadaan kaum Cina peranakan secara maksimal, baik secara politik maupun ekonomi.
Karya-karya video, instalasi, dan lukisan di pameran ini menjadi semacam kritik terhadap sikap pemerintah Indonesia yang tidak bisa mengelola perkawinan budaya lokal dengan budaya Cina peranakan menjadi potensi positif. Alih-alih memanfaatkan potensi, pemerintah justru memberi perlakuan diskriminatif kepada kaum Cina peranakan. Padahal, secara alamiah, proses akulturasi sebenarnya bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gesekan.
"Toekar Tambah", kata Nindityo, adalah kalimat yang sering dia dan Mella temui di toko-toko loak di pinggir jalan. Oleh Mella, kalimat itu diusulkan sebagai tema pameran, yang secara filosofis juga menunjukkan proses tukar-tambah dalam akulturasi budaya satu dengan lainnya.
Proses akulturasi budaya itu muncul, misalnya, pada karya kuas di atas kertas, Napoleon Kompleks Saudagar Komprang. Nindityo melukis sosok laki-laki berpakaian celana komprang dan bertopi tinggi yang menggendong gembolan kain besar di punggung sebelah kanan layaknya sosok saudagar Cina yang sering kita jumpai pada komik atau film. Di sampingnya, wajah sang saudagar berubah. Dia kini mengenakan peci dengan tangan kanan mengepal ke atas.
Pada karya instalasi video Der Verehrungstisch, Nindityo menampilkan perempuan Cina yang mengenakan kain batik dan bersandal bakiak duduk di atas meja menyerupai altar pemujaan. Di sisi kanannya berderet aneka kosmetik modern dan di sisi kirinya berderet beberapa pasang sandal model terbaru. Nindityo mengaku dia diilhami buku sejarawan Ong Hok Ham tentang sejarah Cina peranakan di Jawa dan Madura, yang menyebutkan bagaimana perempuan Cina di sini tak lagi terbiasa mengikat kaki dan memakai sepatu kecil, yang sebenarnya dimaksudkan untuk membatasi pergaulan para perempuan, seperti tradisi leluhur mereka di daratan Cina.
Selama penelitian, Nindityo juga menemukan kangpo (meja persembahan kepada leluhur), yang dilengkapi foto dan dupa persembahan, serta sinci (tulisan leluhur), yang tak hanya berisi leluhur laki-laki sebagaimana tradisi di Tiongkok, tapi juga leluhur perempuan. "Mungkin ini hanya terjadi pada Cina peranakan di Indonesia," kata dia.
Harmoni akulturasi juga ditunjukkan dalam karya Post Tolerance, baik dalam karya instalasi maupun video. Dalam versi instalasi, terlihat moncong pengeras suara warna merah yang disangga dengan kaki tiga. Di bawahnya terdapat replika pura, gereja, wihara, dan candi yang terbuat dari kayu. Sang perupa sengaja mengganti simbol masjid dengan corong pengeras suara yang mengumandangkan azan lima kali sehari-semalam. Pada versi video, pesan tersebut lebih kentara melalui suara azan.
Sohirin (Semarang), Kurniawan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo