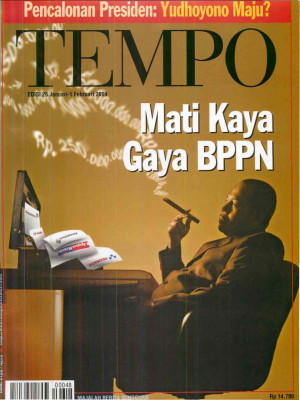Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Library: An Unquiet History
Penulis: Matthew Battles
Penerbit: New York & London; WW Norton & Company, 2003
Novelis Spanyol, Jorge Luis Borges, pernah membayangkan perpustakaan sebagai surga yang menyimpan jutaan buku. Matthew Battles dalam bukunya, Library: An Unquiet History, tentu tak sedang membela Borges. Tapi Battles, pustakawan dari Universitas Harvard, membuktikan bahwa perpustakaan—sumber bagi ide-ide kreatif yang membangun peradaban—kerap kali justru diperlakukan sebaliknya: dibakar, dibeslah, bahkan dijadikan neraka. Pembakaran perpustakaan telah menjadi modus bagi kekuasaan untuk menghabisi lawan politik dan ideologi mereka.
Kisah terbaru bisa kita petik dari Irak. Juli tahun lalu, ketika pasukan Inggris menyerbu Kota Basra di Irak, entah dari mana api membakar habis perpustakaan nasional di sana. Buku-buku yang tersisa diungsikan ke rumah kepala perpustakaan, Alia Muhammad Baker. Di rumah Alia, dari kamar sampai dapur sekitar 30 ribu judul buku bertumpuk-tumpuk mengenaskan. Baker menerawang: apa salah buku-buku itu?
Di zaman Nazi, menurut Battles, bukan hanya enam juta jiwa terbunuh, tapi juga lebih dari seratus juta buku dibakar. Tahun 1914, menjelang pecahnya Perang Dunia I, perpustakaan nasional Bosnia juga hangus. Juga ketika masa revolusi kebudayaan di Cina, Tentara Merah Cina menyerbu Tibet. Ratusan ribu buku kuno amblas.
Perpustakaan Alexandria—berdiri pada 290 sebelum Masehi di Mesir—pada tahun 48 SM dibakar oleh Julius Caesar. Di perpustakaan itu, kita tahu, Ptolemy I pernah mengundang pelbagai cerdik-pandai lintas negara untuk berdiskusi dan menulis di lontar-lontar hingga mencapai 700 ribu gulung papirus. Salah satunya adalah Kitab Perjanjian Lama pertama yang diterjemahkan dari bahasa Yahudi ke bahasa Yunani (Nurcholish Madjid pernah menyatakan, seandainya perpustakaan Alexandria tak terbakar, orang seperti Einstein bisa muncul lebih awal).
Battles mencatat, perpustakaan juga pernah menjadi bagian dari rasisme. Di zaman perbudakan masih kental di Amerika, banyak perpustakaan di bagian selatan Amerika menolak keanggotaan masyarakat kulit hitam. Pada tahun 1936 di Georgia, misalnya, dari 53 perpustakaan yang ada, hanya lima di antaranya yang memperbolehkan masyarakat Afro-Amerika jadi pengguna perpustakaan. Mereka yang ingin meminjam buku harus berpura-pura menjadi suruhan seorang kulit putih.
Seorang bernama Richard Wright Wright, seperti dituturkan kembali oleh Battles, mengenang bagaimana ia, misalnya, untuk bisa membaca buku-buku karya H.L. Mencken, harus berpura-pura disuruh majikannya. Suatu saat petugas curiga dan menginterogasinya. Ia lalu pura-pura tak bisa membaca.
Selain soal bakar-membakar, Battles juga berkisah tentang awal mula penemuan berbagai metode pengarsipan dan penyimpanan buku. Battles mengulas para tokoh penting dalam dunia perpustakaan, seperti Antonio Panizzi dan Melville Louis Kossuth Dewey. Panizzi adalah seorang Italia yang kabur ke London sebagai buron. Walau memiliki sertifikat advokat, ia akhirnya malah dikenal sebagai penemu sistem katalog. Sistem ini memudahkan pengguna perpustakaan untuk pencarian buku. Juga dikisahkan tentang Dewey, tokoh penemu rumus klasifikasi subyek dalam dunia perpustakaan.
Buku ini memang ditulis dalam konteks Amerika, dalam konteks masyarakat yang sudah sangat sadar akan pentingnya menyimpan naskah, buku, dan berbagai bentuk arsip lainnya. Membaca buku ini, pembaca Indonesia akan mengelus dada, kapan punya perpustakaan sedemikian baik di sini? Kapan ada usaha serius membenahi perpustakaan umum? Sebab, kalaupun ada perpustakaan yang bagus di sini, sudah pasti itu bukan milik pemerintah—termasuk universitas-universitasnya—melainkan milik swasta atau orang per orang.
Toh, perpustakaan perorangan pun pernah ”diperkosa” oleh penguasa. Ingat, bagaimana koleksi bahan sejarah milik sastrawan Pramoedya Ananta Toer habis dilalap api penguasa Orde Baru. Sementara itu, yang masih utuh—misalnya koleksi Soedjatmoko, Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan lain-lain—tak terurus dan dalam keadaan mengenaskan. Kalau begini, kapan kita bisa seperti Borges, membayangkan surga seperti sebuah perpustakaan?
Ignatius Haryanto (peminat buku)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo