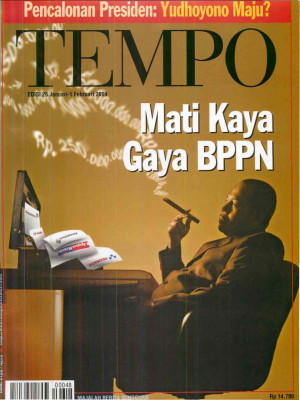Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TUAN Hakim, seorang perempuan marah di depan majelis, dan melontarkan sepatunya ke arah kolega Tuan yang duduk bertoga di ruang itu….
Ingat? Sepatu: benda yang tiap kali bersentuhan dengan debu, lumpur, serba-serbi tahi, sisa makanan yang dimuntahkan, air comberan yang disiramkan ke trotoar. Sepatu: bagian dari proteksi tubuh yang menempuh perjalanan.
Tuan tentu tahu, di tungkai kaki orang kebanyakan, sepatu adalah tanda ikhtiar untuk pantas, bersih, dan aman di permukaan bumi. Tapi jika Tuan lupa apa yang terjadi, inilah ceritanya: pada tahun 1987. Mimi, perempuan itu, kecewa dan marah kepada bapak bertoga yang duduk angker dan terhormat di belakang meja tinggi itu. Ini berlangsung di sebuah ruang pengadilan di Jakarta. Sepatu itu dilontarkannya untuk menyatakan sebuah perasaan, juga sebuah pendapat.
Mimi kemudian dihukum penjara enam bulan. Ia dianggap menghina mahkamah. Tapi perempuan itu sempat bercerita: berminggu-minggu ia beperkara, mengadukan Nina, yang menurut Mimi pernah menipunya sampai Rp 76 juta. Ia ingin agar Nina dihukum berat. Ia menyuap hakim dengan uang Rp 2,5 juta. Tapi hakim itu, kata Mimi, tak berbuat sebagaimana dipesan. Ia menduga, sang hakim curang: Nina memberi sogok yang lebih besar….
Seperti Tuan Hakim pasti akan sepaham dengan saya, Mimi telah menghina mahkamah dua kali. Pertama, ia melontarkan sebuah benda yang biasanya bersentuhan dengan najis ke arah hakim. Kedua, ia memandang para hakim mirip pelacur yang mengecewakan—tenaga yang bisa dipesan, dibeli, dan diharapkan memuaskan nafsu.
Sebuah perilaku yang mengagetkan? Tidak rupanya. "Insiden Mimi" tak mendorong Menteri Kehakiman atau Ketua Parlemen atau Majelis Ulama untuk berbuat sesuatu. Tuan juga diam saja. Saya tahu kenapa demikian: di belakang insiden itu telah hadir sebuah penghinaan yang lebih lama dan lebih besar—penghinaan kepada harapan. Juga penghinaan kepada Republik. Dan kedua-duanya bukan Mimi yang melakukannya.
Sebab inilah tema yang umum diketahui: kian hilangnya kepercayaan kami, orang Indonesia, kepada mahkamah Tuan. Bagi kami sulit berharap dari proses yang harus kami tempuh untuk mendapatkan keputusan yang adil. Pada tahun 2002, Mardjono Reksodiputro, seorang guru besar ilmu hukum di Universitas Indonesia, menerbitkan hasil penelitiannya tentang keharusan menyogok yang mencegat kami, warga masyarakat, di sepanjang perjalanan pro justicia, sejak dari di kantor polisi sampai di kantor hakim. Ia mengutip apa yang kami gerundelkan bila kami melapor kepada yang berwajib ketika barang kami dicuri: "Melaporkan ayam kita hilang, akhirnya kambing kita ikut hilang."
Sebuah catatan Bank Dunia dan Bappenas yang kemudian diterbitkan pada 1999 memang menunjuk: di Indonesia, seorang yang mencari keadilan harus membayar—dalam arti menyuap—jumlah uang yang memberatkan, sejak awal sekali, bahkan ketika ia baru mendaftarkan perkaranya ke mahkamah. Dan jika nanti vonis jatuh, dan keputusan hakim dibuat, pihak yang bersengketa masih harus membayar lagi untuk mendapatkan salinan surat keputusan itu.
Ketika tak ada jalan lain ke arah keadilan, cerita seperti itu menjadi sebuah cerita putus asa. Tepatnya, sebuah putus asa yang dianggap sah. Di antara kami, harapan telah jadi makhluk yang ganjil. Kami, orang Indonesia, akan tampak ajaib bila mempunyainya.
Saya tak tahu siapa yang mula-mula membuat Indonesia sebuah negeri tempat rasa putus asa telah sampai ke tungkai kaki. Bahkan telah membuat Indonesia tak layak sebagai sebuah negeri. Sebuah negeri membutuhkan "negara". Dalam pengertian yang sekarang lazim, "negara" berarti kekuasaan sebagai milik publik, bukan milik pribadi.
Tapi di mana gerangan "negara"? Kami bingung. Seorang sejarawan pernah mengatakan kepada saya, memang hanya baru setelah administrasi VOC digantikan oleh birokrasi kolonial Hindia Belanda, kehadiran "negara" di kepalauan ini mulai berdampak. Tapi agaknya sampai kini pun ia samar.
Kalaupun tak samar, "negara" adalah sesuatu yang amat tipis. Untuk 220 juta penduduk, hanya ada sekitar 3.500 hakim dan sekitar seperempat juta tentara militer dan hanya 270 ribu polisi. Bersamaan dengan itu, bagi banyak orang, "negara" yang tipis itu belum merupakan sosok yang utuh. Ia belum hadir sebagai sebuah struktur dengan seperangkat aparat yang efektif menyentuh kehidupan sosial. Ketika jalan macet, KTP hilang, utang tak dibayar, kami sering tak tahu siapa yang akan membereskan itu sampai tuntas. Negarakah? Jika Tuan seorang Mimi, "Negara" adalah person-person yang bisa ia ketuk pintunya di rumah.
Dan semuanya kian rancu, ketika otoritas di balik pintu itu ternyata bisa diperjual-belikan. Tuan tahu apa yang terjadi karena itu? Negara, yakni kekuasaan milik publik, berubah. Privatisasi yang serong telah berlangsung. Pada saat itu, Republik pun runtuh, tanpa diumumkan, tanpa jerit dan gelegar. Bahkan kejadian itu disembunyikan. Dan runtuh pula sebuah kehidupan bersama, di mana orang bisa saling percaya, di mana konflik dikelola dengan damai dan tak berat sebelah. Yang ada: sebuah labirin gelap kekuasaan-kekuasaan pribadi.
Itu sebabnya Mimi melontarkan sepatu. Benda itu tak akan membuat kepala pak hakim benjol. Perkara itu tak akan diperiksa lebih jauh. Mimi akan kehilangan 50 persen pelindung kakinya. Uang Rp 76 juta itu tak akan kembali. Ia sendiri dihukum.
Tapi bukankah sepatu itu satu-satunya alat ekspresi yang ada padanya—benda yang harus dilontarkan, seakan-akan sebagai laku simbolik: ia semula mengenakannya agar bersih, pantas, dan aman, tapi ia ternyata berada di gedung mahkamah yang tak bersih, tak pantas, dan tak aman. Bukankah sepatu Mimi yang terlontar pada hari itu bisa ditafsirkan sebagai penunjuk kontras yang merisaukan itu, Tuan Hakim?
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo