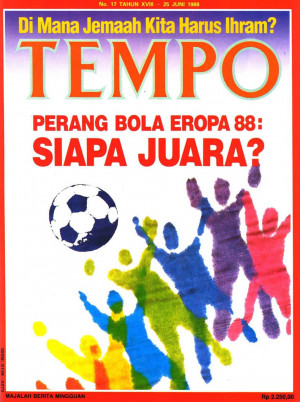PEREKONOMIAN INDONESIA: PERTUMBUHAN DAN KRISIS Oleh: M. Dawam Rahardjo Penerbit: LP3ES, Jakarta, 1987, 299 halaman PEMBANGUNAN ekonomi yang tengah berlangsung di Indonesia dewasa ini tidak selamanya melalui "jalan bebas hambatan". Banyak "kerikil" yang menghadang, sehingga perjalanannya senng terasa kurang mulus. Tentu saja guncangan-guncangan sepanjang perjalanan itu lebih terasa bagi penumpangnya dibanding, misalnya, bagi pengemudi. Sesuai dengan judul bukunya, Perekonomian Indonesia: Pertumbuhan dan Krisis, Dawam Rahardjo lebih banyak mengulas "kerikil-kerikil" yang menghadang di sepanjang jalan pembangunan untuk mencapai tujuan akhir, yakni peningkatan kualitas kehidupan. Bahkan dengan gamblang ia melemparkan kritik ke alamat pemerintah, yan terkesan tidak bersunguh-sungguh melaksanakan amanat GBHN untuk memeratakan buah pembangunan. Mungkin pangkal masalahnya bukan GBHN itu sendiri, tapi pada penjabaran dan pelaksanaan "garis-garis besar"-nya. Apakah GBHN hanya akan menjadi sekadar bagian pendahuluan dalam setiap bab yang membahas sektor-sektor dalam Repelita, atau lebih dari itu? Kenyataannya, Repelita telah mulai disusun sebelum GBHN disahkan. Ini mirip dengan menambahkan cream pada sajian es krim pisang yang telah tersedia. Dan sejauh mana wakil-wakil rakyat ingat pada amanat GBHN -- sewaktu pemerintah memberikan pertanggungjawaban- patut dipertanyakan dan direnungkan sebelum langsung menuduh GBHN kurang membawa amanat seluruh anak bangsa. Meskipun terasa kurang menyeluruh, buku ini boleh dianggap sebagai evaluasi terhadap kebijaksanaan pemerintah selama ini sampai dengan mid-term review Pelita IV. Dari hasil analisa dalam buku ini, tampak peranan pemerintah yang semakin menonjol. Peranan pemerintah yang sangat menonjol itu oleh Dawam disebut sebagai big government. Tulisnya: "Ini akan membawa pemerintah pada sikap merkantilis, yaitu ingin memperoleh dana yang sebesar-besarnya guna bisa membiayai pemerintahannya. Jalan yang terbuka adalah menjadikan negara sebagai suatu korporasi..." . Artinya, negara sangat berperan sebagai regulator dan rakyat semakin bergantung padanya. Mungkin hal itu tidak terlalu mengkhawatirkan selama "raksasa" tersebut masih perkasa. Namun, ketika mulai terasa peranan itu jadi limbung, maka semua pihak menjadi bingung. Tabrak sana tabrak sini, dan muncullah gejala monopoli dan oligopoli yang mendesak kepentingan rakyat. Apalagi ditambah semakin berperannya ciri dualistis dalam struktur perekonomian kita yang memang merupakan warisan sejak zaman kolonial. Maka, lengkaplah sudah gambaran pincang ini: sebagian kelompok masyarakat yang basMki (sejahtera), sementara bagian terbesar kelompok lain masih harus memikul bea dalam proses pembangunan nasional. Menyadari kenyataan ini, pemerintah melakukan serangkaian kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi yang banyak mendapat acungan jempol. Tapi prakarsa perintah - yang lebih banyak disebabkan berkurangnya penerimaan negara dan sektor minyak ini - sering menjadi bumerang. Misalnya, aparat pemerintah yang belum slap menjadi abdi masyarakat bisa menyebabkan pelaksanaan debirokratisasi dan deregulasi agak tersendat-sendat. Agaknya, perkembangan sumber daya manusia di kalangan abdi negara belum berlangsung sempurna. Mungkin Menpan juga merasakannya. Di pihak lain, seiring dengan tekad untuk mengikuti gerak dunia usaha, usaha swasta digalakkan. Sementara itu, dipromosikan privatisasi, sebagai upaya melepaskan diri dari inefisiensi yang membebani harta negara. Tapi, kata Dawam, keinginan menggerakkan privatisasi atau swastanisasi harus selalu memperhatikan konflik yang mungkin timbul karena adanya aspirasi, sementara di pihak lain ada kepentingan tertentu yang ingin dipertahankan. Bagian pertama buku ini lebih banyak mengulas masalah-masalah perekonomian internasional, sedangkan bagian kedua yang memuat sekitar lima karangan - lebih menukik, menganalisa perekonomian Indonesia itu sendiri. Dengan kaca mata politik ekonomi, yang memang sering dipakainya, nawam Rahardjo mengupas seluk-beluk ekonomi nasional. Bagian yang diakhiri dengan ulasan mengenai daerah Condet juga terasa menggigit. Misalnya, " . . . Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kedudukan Condet dan kantongkantong pedesaan Jakarta di masa mendatang. Pertama, adalah terjadinya krisis akumulasi kapital, di mana kapital tidak atau sulit menemukan sektor-sektor produksi baru, karena kelesuan pasar pada umumnya atau karena lemahnya tenaga beli akibat kurang meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Dalam situasi ini bisa terjadi spekuiasi di bidang property, termasuk tanah...". Mudah-mudahan tidak ada kcinginan untuk mengungkapkan Condet sebagai prototip desa-desa pinggiran yang patut menenma beban pembangunan. Seperti kasus kemiskinan Sriharjo yang diungkapkan sedemikian rupa oleh Masri Singarimbun dan Penny sehingga menyebabkan banyak negara industri iba. Begitu miskinnya penduduk desa di Indonesia. Dan mereka tidak berdaya. Pilihan karangan dalam buku ini secara keseluruhan memang penting untuk direnungkan. Apalagi dia lahir dari tangan ilmuwan yang tumbuh dari suatu lembaga swadaya masyarakat -- bukan cendekiawan kampus ataupun dari kalangan peerintah. Prijono Tjiptoherijanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini