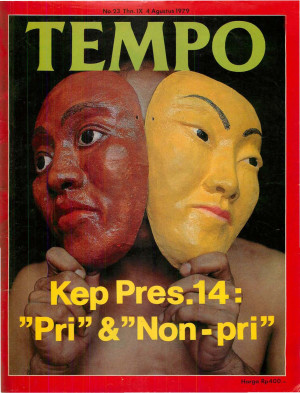SEKAR PEMBAYUN
Penata Tari: Retno Maruti, Sulistyo S. Tirtokusumo.
Prodoksi: Padneswara.
SEORANG lelaki konon dilahirkan untuk menaklukkan dunia, tetapi
wanita dilahirkan untuk menguasai hati laki-laki.
Ki Ageng Mangir, seorang lelaki pilihan pemberontak terhadap
kekuasaan Mataram di bawah Panembahan Senopati Sang Raja tahu
bahwa musuh yang satu ini, yang juga bergelar Ki Ageng
Wanabaya memang sangat berbahaya. Maka dengan cerdik
dipasangnya peranghap, walau untuk itu jiwa puterinya, Sekar
Pembayun, harus dipertaruhkan.
Mangir masuk bubu mengawini Sekar Pembayun yang menyamar sebagai
penari barangan. Dia akhirnya terpaksa harus mengorbankan
martabat dan jiwanya sebagai seorang menantu harus ngabekti (=
berbakti) kepada mertua yang ternyata musuh bebuyutannya.
Dalam upacara ngabekten inilah dengan disaksikan oleh sekalian
yang hadir, Mangir mati sia-sia ketika hendak mencium duli kaki
sang raja kepalanya dibenturkan dengan keras ke batu singgasana
oleh sang mertua.
Kisah tragis ini diangkat ke pentas oleh Grup Padneswara di
Teater Arena, TIM, 28, 29 dan 30 Juli 1979. Ditangani bersama
oleh Retno Maruti dan Sulistyo S. Tirtokusumo.
Walaupun kisah ini tentang pemberontakan dan peperangan,
penonton yang mengharapkan adegan-adegan seru akan kecewa. Arah
garap pementasan memang tidak ke sana. Sekar Pembayun tampil
dalam bentuk langendriyan yang lembut dan halus.
Paduan gaya garap kedua murid almarhum R.T. Kusumokesowo
(seorang tokoh tari Keraton Surakarta) itu ternyata cukup
memikat, baik -- dari segi tari, karawitan maupun garapan
tembang.
Beberapa catatan kecil memang ada: latar belakang gerakan penari
pria yang sulit serempak, cara berkain Mangir yang walaupun
bagus tak menguntungkan proporsi tubuh penari. Namun secara
keseluruhan langendriyan ini cukup mengendap.
Yang menarik justru pendekatan garapan tari yang tidak
semata-mata naratif. Gerak tari, iringan gending dan tembang
secara keseluruhan mampu membawa suasana batin penonton ke
pengalaman lengang, tragis dan sekaligus kesumat. Dan sejak awal
suasana rudatin yang dingin memang telah menyelimuti pentas dan
menguasai penonton.
Kelewat Mriyayi
Lawung Sala yang dikembangkan untuk memulai pementasan ini,
memang menyuguhkan suasana yang berbeda dengan Lawung Yogya yang
bersemangan Yang dari Sala lebih terasa anggun. Dan keanggunan
itulah yang mewarnai pementasan dari awal sampai akhir. Adegan
demi adegan merambat dengan tenang dan perlahan sesuai dengan
kaidah tari keraton umumnya. Dan semua hal diungkapkan sinamun
ing samudana --secara samar bagaikan diselubungi kabut yang
indah -- memenuhi selera Jawa.
Tapi ketegangan bukannya tak berhasil ditampilkan. Justru dari
pergantian adegan yang merayap perlahan dan vokal-vokal yang
melankolis ketragisan jadi lebih menyayat.
Tak ada yang digambarkan secara wadag, tak ada perang otot,
sampai-sampai adegan barangan-pun digarap kelewat mriyayi.
Adegan percintaan Mangir dan Pembayun misalnya, digarap lewat
cakepan, sindenan, tari dan iringan bedaya duradasih yang
wingit. Sementara kedua insan yang ber-langen-asmara duduk
bersila berhadapan di latar belakang arena, sekelompok bedaya
memperagakan adegan -- atau lebih tepatnya suasana-suasana yang
menyarankan kisah cinta yang tragis.
Bahkan ketika Mangir sadar telah masuk perangkap, emosi penari
(Sentot) cukup terkendali. Demikian pula adegan terakhir saat
dibunuhnya Mangir oleh Senopati, sang mertua, ditampilkan secara
halus dan simbolis. Ditopang cahaya merah terang yang
berangsur-angsur memudar secara perlahan, suara empat tombak
yang digedrugkan ke papan arena berhasil secara puitis
mengakhiri kisah ini Ki Ageng Mangir telah perlaya.
Bagi penonton yang tak paham kultur Jawa, tontonan ini
barangkali terlalu menuntut kesabaran, kelewat halus atau
kelewat tersembunyi. Apa lagi bagi mereka yang datang menonton
untuk mencari hiburan. Tetapi yang biasa matmatan menikmati
klenengan nyamleng, suasana khas priyayi Jawa itu hadir di
sana.
Bening Dan Dingin
Tak dinyana garapan klasik semacam ini justru muncul, tumbuh dan
berkembang di Jakarta. Dan ternyata mulai memiliki penggemar
tetap yang berlimpah tanpa tersedot oleh penonton Sri Mulat,
yang main di Teater Terbuka. Di masa silam, orang sering dengan
sinis mencemoohkan tontonan Jawa di Jakarta sebagai bergaya
pesisiran, yang artinya selalu kelewat kasar dan bernilai lebih
rendah dari pada yang berkembang di pusat kerajaan. Keadaan itu
mungkin masih benar sampai dengan lima tahun yang lewat. Tetapi
kini, Jakarta agaknya mulai berbicara lebih mantap juga dalam
percaturan tari tradisi, terutama Jawa.
Sementara di tempat asalnya tontonan yang sae tur kathah
luconipun (=bagus karena banyak humornya) lebih disukai,
tontonan di Jakarta kini lebih banyak menampilkan gaya garap
yang lebih halus dan lembut. Agaknya banyaknya orang Jawa
Jakarta yang rindu suasana Jawa masa lalu, membantu menyuburkan
berkembangnya tontonan yang lebih menampilkan unsur Jawa yang
khas.
Sekar Pembayun kali ini, jauh lebih berhasil daripada Roro
Mendut (digarap oleh Maruti juga) misalnya. Sekar Pembayun
membawa khayal kita kepada ungkapan ceritera tragis Noh -- drama
klasik Jepang yang terkenal itu: bening dan dingin.
Sal Murgiyanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini