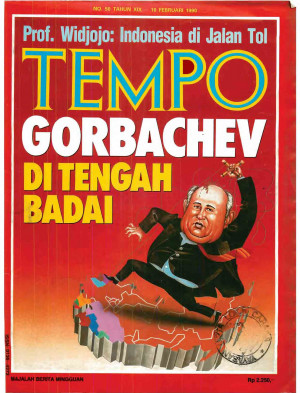BEBERAPA pengarang Indonesia memulai kariernya sebagai anak ajaib. Mereka menulis dalam usia amat muda, dengan kualitas bagus. Tapi beberapa di antaranya kemudian memudar sesudah mulai dewasa. Yang tetap gigih dan kemudian berhasil mempertahankan reputasinya di antaranya adalah W.S. Rendra, Ajip Rosidi, dan Yudhistira A. Nugraha. Leila S . Chudori, 27 tahun, yang menulis sejak kelas V SD, adalah anak ajaib yang lain. Ia sudah terkenal di media massa remaja sebagai penulis yang produktif pada saat rekan-rekan seusianya masih belajar menyusun kalimat. Alumni Universitas Trent, Ontario, Kanada, ini kemudian mulai menembus selaput "remaja" pada tahun 1980-an. Cerpennya mula-mula muncul di majalah Zaman, kemudian harian Kompas, majalah Matra, dan akhirnya menghuni majalah sastra Horison. Malam Terakhir adalah buku ke-4 Leila (Hadiah, 1976 Seputih Hati Andra, 1981 Sebuah Kejutan, 1983). Tetapi, berbeda dengan bukunya yang terdahulu, paket yang berisi 19 cerpen ini adalah sebuah loncatan. Khususnya buat Leila sebagai bagian dari pendukung sastra Indonesia kontemporer. Kia tahu, sastra Indonesia pada dekade 1970 mulai mencatat nama banyak penulis wanita. Tapi sampai sejauh itu, buat saya, Nh. Dini dan Marianne Katoppo (novelis) dan Isma Savitri (penyair) yang tetap unggul. Leila muncul sebagai kuda hitam. Malam Terakhir adalah sebuah kumpulan yang mearik. Ditulis dengan amat lancar oleh seorang penulis yang menguasai medianya, dengan sikap yang "berani". Secara umum, kumpulan cerita ini adalah suara seorang wanita Indonesia masa kini. Yang dengan tanpa rasa malu mempergunakan kata-kata "ereksi", "persetubuhan", "taek". Yang berbicara lantang, penuh kepercayaan diri dengan latar belakang berbagai bacaan sastra "Barat" (baca Inggris). Cerpen-cerpennya cenderung sebagai esei-esei kehidupan dari seorang wanita muda "Menteng" (dalam pengertian yang baik), yang juga tak asing dengan dunia "wayang". Dalam cerpen Air Suci Sita, ditulis di Jakarta 1987, Leila memulai ceritanya dengan kalimat: "Tiba-tiba saja malam menabraknya". Sebuah kalimat padat yang sugestif dan kental. Meskipun kalimat yang hebat itu tak bisa dilanjutkannya dengan baik pada kalimat-kalimat berikutnya, cerpen ini adalah cerpen yang bagus. Dengan teknik bercerita yang menarik, Leila berhasil mengangkat gugatan mengapa hanya kesetiaan wanita yang dipersoalkan, bagaimana dengan kesucian para pria? "Wanita itu masih menatap bibir tunangannya yang begitu sibuk dengan dirinya sendiri. Namun, di matanya terlukis wajah Sang Raja Agung titisan Wisnu dengan permaisurinya yang sudah siap terjun ke lautan api penyucian diri. Ia baru ingat sekarang. Permaisuri itu tak pernah diberi kesempatan bertanya pada suaminya, misalnya. "Kakanda, apakah selama kita berpisah, tak pernahkah engkau tergoda untuk bercengkerama dengan wanita lain?," tulis Leila dalam akhir cerita itu. Beberapa tahun yang lalu, penari dan pencipta tari Farida Feisol juga pernah menggarap soal kesucian Dewi Sita itu dalam karya tarinya. Tema yang sudah amat dikenal oleh kaum "feminis" itu dengan berhasil bisa diramu Leila menjadi sebuah cerita pendek yang bagus. Yang terbaik buat saya dalam kumpulan ini. Cerpen lain yang mengesankan saya adalah Adila. Meminjam tokoh seorang anak yang selalu didominasi oleh ibunya, Leila dengan cerdik mengajak pembaca "membaca" bagian-bagian yang paling disukainya dalam buku The Rainbouw (D.H. Lawrence), Summerhill (A.S. Neill), A Portrait of the Artist as a Young Man (James Joyce). Juga menyeret pembaca teringat pada Erich Fromm, Kahlil Gibran. Leila (baca: pembaca) bercakap-cakap dengan tokoh Ursula Brangwen dalam The Rainbow, Tuan Neil (Summerhill), dan Stephen Dedalus-nya James Joyce. Tipikal obsesi intelektual yang hidup dalam dunia buku. Tokoh-tokoh itu berpesta dengan Adila menegak "Baygon". Dan ketika Adila kemudian tinggal jenazah, ibunya masih bersuara, "Kutang itu.... Kutang itu harganya 30 dolar... kutang kesayanganku. Dan alat-alat rias itu. Dila..., Dila." Buat saya, cerpen ini sebuah protes yang berhasil. Ada unsur teror di dalamnya, yang bermaksud menggugah pembaca teringat kepada sesuatu yang kukuh yang perlu dijebol. Untuk itu, diperlukan sebuah tindakan yang radikal. Sebagaimana juga yang disuarakan oleh pengarang dalam cerita pertama Sebuah Buku Merah dan Karbol. Ketika Suwarto mengakhiri cerita dengan sebuah tindakan yang penuh risiko, "ia mengambil bolpoin hitam Marwan. Dibukanya buku itu dengan gemetar. Digoretkannya sebuah garis panjang pada halaman putih bersih itu. Garis yang amat panjang." Sebagai awal dari perjalanan panjang Leila sebagai salah seorang penulis di masa depan, kumpulan ini penuh janji. Saya tidak tahu apakah kelak penulis akan terus berkutat dalam dunia buku, sehingga renungannya pada kehidupan hanya renungan manusia dalam kamar. Ia jatuh cinta pada tokoh-tokoh dan pemikiran para penulis yang mendahuluinya (baca: yang dibacanya). Itu untuk sementara memang menambah gengsi, tapi pada waktunya bisa merupakan halangan besar untuk menyentuh kehidupan yang kompleks ini secara langsung dan total. Juga kebiasaan tokoh-tokohnya mengekspresikan diri dalam bahasa Inggris membuat "merinding". Mengingatkan pada para intelektual di masa lalu, yang merasa kurang "lengkap" kalau tidak melontarkan beberapa kalimat/kata bahasa Belanda. Pastilah penulis tidak berniat berlagak snob, karena bahasa tersebut agaknya sudah amat dikuasainya. Dengan demikian, peluang untuk memisahkan antara tokoh-tokohnya dan dirinya sebagai penulis tak dipergunakan. Putu Wijaya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini