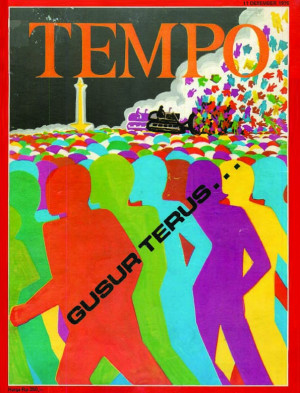Naskah: Arthur Miller
Terjemahan: Tatiek Maliyati WS
Sutradara: W. Sihombing
Produksi: Teater Lembaga.
***
WILLY Loman (Bambang S. Santoso), seorang pedagang keliling,
menemukan kebrengsekan hidupnya tatkala ia mulai tua dan
terhimpit oleh impian-impian besar pada masa lalu. Cita-citanya
untuk menjadi seorang pedagang yang kaya, hanya sampai pada
kenyataan yang pahit. Usia tua menyebabkan ia tidak sukses lagi
di antara langganan-langganan barunya--setelan
langganan-langganannya yang lama pensiun atau mati.
Hasil yang terbesar dalam kariernya barangkali adalah karena dia
berhasil menjadi seorang tukang mimpi di samping mencicil rumah
yang ditempatinya. Kemajuan tata kota tiba-tiba membuat
lingkungan n1mah itu tidak menyenangkan lagi untuk ditempati.
Pada setiap kesempatan Willy selalu menyesali dirinya kenapa
tidak memenuhi ajakan abangnya Ben (Ruslan Umbaran) untuk
membuka daerah baru di Alaska dan menjadi kaya. Ben yang sukses
itu selau muncul pada saat ia menyesali kenyataan.
Terlebih-lebih karena orang yang dipujanya itu mati terlalu
cepat.
Pelacur
Kesalahan Willy yang lain adalah karena dia memuja anak
sulungnya Biff (Gandung Bondowoso) sehingga anak itu sendiri
tidak pernah siap untuk memasuki kehidupan. Sementara rekan
bermainnya Bernard (Suwanto Erlangga) kemudian berhasil menjadi
seorang pengacara, Biff masih mencari-cari dirinya dan hanya
berhasil sampai pada kesimpulan bahwa ia seorang kleptomania.
Pada akhirnya kepada keluarganya ia harus mengakui segala
kebohongan yang pernah dilakukannya, karena kebiasaan sejak
kecil dalam keluarga itu untuk berbicara tentang impian-impian
besar, bukannya kenyataan. Sebelum pergi dari rumahnya kembali,
setelah ia mencuri pulpen dari seorang kaya yang semula
diharapkannya memberi pinjaman duit, ia mengakui bahwa
pengembaraannya yang lalu bukan pengembaraan mencari nafkah,
tetapi dia telah disekap dalam penjara karena mencuri pakaian.
Happy (Eddy de Rounde) adik Biff juga tak dapat memenuhi lamunan
bapaknya (dan lamunannya sendiri) untuk menjadi pedagang besar.
Ia memang selalu mempunyai usul-usul yang besar. Tetapi anak
muda inipun seorang tukang mimpi kelas kakap yang sudah rela
menipu dirinya sendiri dalam pekerjaan dengan alasan untuk
sedikit memberikan hiburan pada harapan-harapan bapaknya. Dengan
berbohong tentang kedudukannya dalam perusahaan, ia pun tak
pernah bisa dekat dengan Willy, karena orang tua itu lebih
menganggapnya seorang pemalas daripada seorang yang malang.
Dua kakak beradik Happy dan Biff ini menjelang akhir kisah
diusir oleh Linda sang ibu (Ennie A Yusuf) karena dianggapnya
hanya tambah merusakkan Willy yang lebih dicintainya dari apa
saja di atas dunia. Dia tidak pernah tahu bahwa Willy pada suatu
saat pernah kepergok oleh Biff di Boston bersama-sama seorang
pelacur (Lena Simanjuntak) Kejadian tersebutlah yang awalnya
mematahkan semangat Biff untuk meneruskan pelajarannya ke
Universitas. Karena anak itu begitu terpukul melihat kenyataan
orang yang dipuja-pujanya itu.
Kocak
Sementara itu muncul pula tokoh Charley (Budi Setiawan), ayah
Bernard Ia orang yang kasar kocak tetapi baik hati. Tokoh yang
lebih sederhana dan tidak pernah bermimpi, sebagai warga yang
diperlukan oleh sebuah kota besar. Dia menempuh kehidupan
dengan mata terbuka dan berhasil seringkali menolong Willy pada
saat orang tua itu dipecat oleh majikannya Howard Wagner
(Afrizal Anoda) juga potret seorang pekerja yang sibuk.
Willy pada akhirnya tak dapat menguasai dirinya kembali. Ia
mulai mencoba untuk membunuh diri dan menyimpan sebuah pipa
dalam gudang yang kiranya hendak dipergunakannya untuk menghirup
gas manakala diperlukan. Dengan cara mati tabrakan ia boleh
mendatangkan duit tiba-tiba dari uang asuransi jiwanya. Tetapi
Linda memberitahukan bahwa perusahaan asuransi sudah mendapat
bukti-bukti bahwa ia melakukan hal tersebut dengan sengaja.
Tatkala pada akhirnya Willy membunuh diri dengan melarikan
mobilnya secara ngawur - puncak dari segalanya adalah tangis
keluarga itu di atas nisan. Tak seorang pun sahabatnya datang.
Lalu orang boleh teringat pada apa yang dikatakan Biff: "Willy
adalah orang yang tak pernah tahu siapa dia darl yang telah
membiarkan dirinya dimakan oleh impian-impian yang mustahil".
Naskah Arthur Miller yang terkemuka dalam khazanah pentas
Amerika ini memakan waktu lebih dari 4 jam Di bawah tangan
sutradara Sihombing, para mahasiswa Akademi Teater LPKI mencoba
menampilkannya di Teater Tertutup TIM untuk lima malam
pertunjukan (mulai 27 Nopember). Dengan penggarapan yang tak
tanggung-tanggung pada set -- untuk ukuran pementasan di TIM
pada masa ini -- Sihombing telah menunjukkan kerjanya yang lama
dipersiapkan dan bernafsu.
Tidak saja panggung dibuat menjadi interior rumah Willy yang
berloteng, tapi juga bahagian depan panggung yang bolong
ditutupi dengan level dan dipergunakan untuk melangsungkan
adegan-adegan flash back.
Sebagaimana diketahui Arthur Miller pernah membawa udara segar
dalam struktur penulisan naskah (pada masa itu) dengan caranya
yang lincah menyusun adegan-adegan, sehingga bingkai pentas
menjadi dinamis dalam dimensi waktu. Kadang-kadang ada adegan
yang saling menumpuk antara kenangan Willy pada Ben, dengan masa
kininya di mana ia sedang main kartu dengan Charley. Apalagi
sandiwara ini dimulai dengan suasana yang sudah memuncak,
tatkala Willy sudah mulai kehilangan akal menghadapi
kebangkrutannya.
Sebuah tragedi rumah tangga kecil yang hendak dikemukakan oleh
Arthur Miller ditangkap dengan baik oleh Hombing yang kelihatan
menguasai seluruh permainan para mahasiswanya. Dibandingkan
dengan penampilannya dahulu dalam Musuh Masyarakat, yang hanya
menonjolkan target membuat tempo permainan ketat, Hombing kali
ini lebih berhasil. Seluruh pemainnya tergarap merata dengan
kasting yang tepat, sehingga ada terasa suasana kompak yang
mengalir dalam seluruh pertunjukan. Warna dari masing-masing
pemain dibiarkan pula muncul, sehingga kita tidak terpaksa
melihat robot-robot.
Meskipun panggung selalu sibuk dengan perang mulut, toh beberapa
adegan sempat ditahan menjadi hening, sementara pemain Budi
Setiawan yang kocak dan potensiil berhasil memberikan
humor-humor yang segar.
Suka Mengeluh
Bambang B. Santoso sebagai Willy di samping memperlihatkan
ketekunan bermain mungkin mengalami keraguan apakah dia harus
memainkan Willy orang Amerika atau Willy pribumi. Keraguan yang
ternyata tidak diselesaikan oleh Hombing, tetapi diserahkan pada
para pemainnya sendiri. Di sini terjadi ketidak seragaman yang
membuat suasana tidak tergarap dengan teliti, sehingga akibatnya
yang lain adalah kekurang intiman dari pemainnya sendiri pada
"warna" tokoh-tokoh itu.
Hal ini selalu tidak dilewatkan oleh seorang Teguh Karya
misalnya. Mungkin sekali Hombing mengabaikan "warna" ini karena
menganggapnya tidak begitu perlu. Tetapi konsekwensinya kemudian
adalah bahwa kedua pemain wanitanya sebagai misal, Ennie A.
Yusuf (Linda) dan Lena Simanjuntak (pelacurl tak sempat hadir
dengan "akar" hidup tokoh yang hendak diungkapkannya.
Ennie misalnya hanya menunggu, meskipun ia telah bermain dengan
sungguh-sungguh serta memiliki stamina dan ekspresi yang baik.
Artinya ia hanya hidup pada saat berdialog, selepasnya tak ada
kehidupan lagi, sehingga terasa juga ada suasana untuk lebih
banyak menyelamatkan plot cerita bukan penampilan karakter
padahal ini drama kejiwaan.
Ini pula yang menyebabkan secara psikologis beberapa dialog yang
kesleo dari mulut beberapa pemain cepat-cepat diralat oleh
pemainnya dengan pengucapan yang benar - hal mana seharusnya
bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih pintar manakala ada
"akar" kehidupan peran sesudahnya berdialog.
Sebaliknya tokoh Biff misalnya yang disampaikan oleh Gandung
kadangkala menjadi terlalu dramatik karena perhatiannya hanya
tertuju pada analisa karakter yang pas, sementara Eddy (Happy)
berusaha bermain dengan wajar dan manis seringkali tersipu-sipu
sendiri. andung yang berusaha memberikan analisa yang baik pada
tokohnya jadi terlibat lebih banyak pada soal penyampaian
analisa itu secara fisik. Ini menyebabkan permainannya menjadi
kering. Tapi terlepas dari ini, Hombing telah memimpin anak
buahnya dengan baik, kendatipun pada malam ke-3 petugas lampu
sering ngawur.
Yang agak mengherankan adalah penonton. Kalau sering kita dengar
pertunjukan kontemporer alias absurd alias yang mengada-ada
alias yang eksperimen atau apa saja namanya kekurangan penonton,
mengapa pertunjukan yang realistis semacam ini, dengan tema
keluarga yang banyak juga hubungannya dengan kehidupan
sehari-hari di Jakarta mesti kekurangan penonton juga?
Barangkali publikasi kurang. Atau memang orang suka mengeluh
sekarang.
Putu Wijaya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini